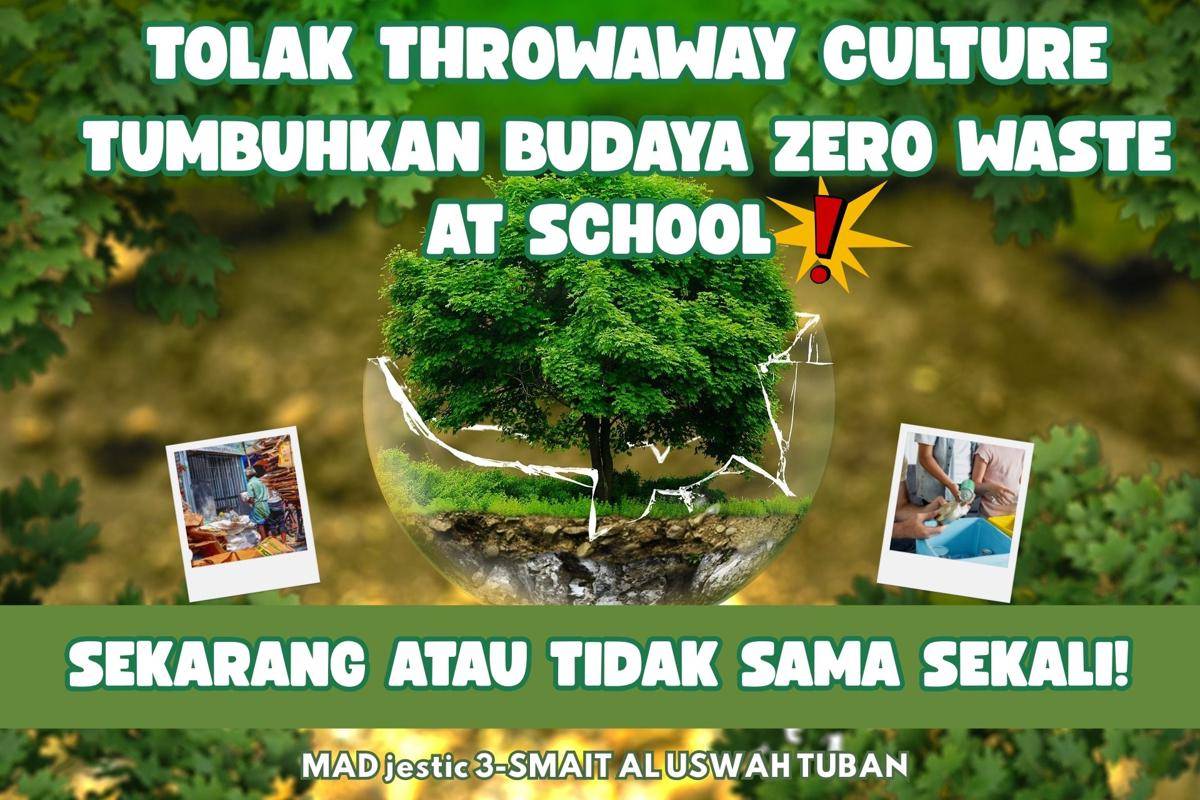IDN TIMES EXPLORE/MADJESTIC3_SMAIT Al Uswah Tuban
Berpaling dari Budaya Sekali Pakai: Peran Generasi Muda Menuju Zero Waste Melalui Teknologi dan Edukasi
Oleh: Shofi Ayu, Nasywa Laila
Pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya: ke mana perginya semua gelas kopi, kantong plastik, dan kemasan makanan yang kita gunakan setiap hari? Dalam hitungan menit, benda-benda itu berpindah dari tangan kita ke tempat sampah, lalu menghilang dari pandangan. Namun, kenyataannya, sampah tersebut tidak benar-benar menghilang tetapi ia terus berada di bumi, mencemari tanah, laut, bahkan udara yang kita hirup. Fenomena ini dikenal sebagai throwaway culture, budaya sekali pakai yang secara diam-diam namun pasti merusak ekosistem.
Budaya ini bukan sekadar kebiasaan buruk, melainkan pola pikir yang mengakar. “Kita tidak mewarisi bumi dari nenek moyang kita, kita meminjamnya dari anak cucu kita,” ujar pepatah kuno yang relevan hingga kini. Sayangnya, di tengah kemajuan teknologi, pola hidup konsumtif dan instan justru semakin kuat. Generasi muda, yang seharusnya menjadi motor perubahan, sering kali justru terjebak dalam kenyamanan budaya instan ini.
Pasca-pandemi COVID-19, fenomena fast living (gaya hidup cepat dan praktis yang semakin merajalela). Semua ingin serba instan seperti kopi takeaway, makanan dalam kemasan, belanja daring yang dikirim dalam bungkus berlapis-lapis. Di balik kemudahan ini, terkumpul timbunan sampah yang jumlahnya mengkhawatirkan.
Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK, 2023) mencatat Indonesia memproduksi 68,5 juta ton sampah setiap tahun. Dari jumlah tersebut, 17% adalah plastik sekali pakai seperti kantong plastik, sedotan, wadah makanan, dan kemasan sachet. Ironisnya, hanya 7% sampah yang berhasil didaur ulang secara formal. Sisanya berakhir di tempat pembuangan akhir (TPA), dibakar sehingga mencemari udara, atau hanyut ke sungai dan laut.
Situasi ini diperparah oleh tren fast fashion yang menghasilkan limbah tekstil dalam jumlah besar, serta budaya konsumsi cepat yang memicu peningkatan volume sampah. Laporan UNEP (2021) menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi digital mempercepat laju pertumbuhan sampah, karena memicu pola belanja dan konsumsi yang instan. Riset Jambeck (Science, 2015) bahkan menempatkan Indonesia sebagai penyumbang sampah plastik laut terbesar kedua di dunia, setelah Tiongkok.
Generasi muda urban memiliki akses teknologi dan informasi yang lebih luas dibanding generasi sebelumnya. Laporan Digital 2024 dari We Are Social menunjukkan bahwa 77% penduduk Indonesia terhubung ke internet, dengan mayoritas pengguna berasal dari kelompok usia muda. Namun, kemajuan ini belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk mendorong perubahan positif.
Alih-alih menjadi pusat gerakan keberlanjutan, sebagian anak muda justru terjebak dalam budaya instan yang mereka konsumsi sehari-hari. Media sosial lebih sering digunakan untuk hiburan viral ketimbang kampanye lingkungan. Padahal, teknologi digital memiliki potensi besar untuk membangun kesadaran kolektif dan mengubah perilaku konsumsi.
Generasi muda memegang posisi strategis dalam mengubah budaya sekali pakai menjadi budaya berkelanjutan. Dengan jumlah yang besar, energi kreatif, dan penguasaan teknologi, mereka memiliki modal sosial yang kuat untuk memimpin gerakan zero waste.
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS, 2023), 53% penduduk Indonesia berada pada kelompok usia produktif (15–39 tahun). Ini berarti mayoritas kekuatan sosial, ekonomi, dan budaya ada di tangan generasi muda. Mereka adalah pengguna media sosial paling aktif di Asia Tenggara, menghabiskan rata-rata 3 jam 11 menit per hari di platform seperti TikTok, Instagram, dan YouTube. Waktu ini seharusnya dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan edukasi lingkungan secara masif.
Kampanye digital yang kreatif telah membuktikan efektivitasnya. Misalnya, #HabiskanMakananmu yang digagas Zero Waste Indonesia berhasil mengajak ribuan pengguna media sosial mengurangi food waste. Gerakan #TukarBajuForBetter mendorong masyarakat mengurangi fast fashion melalui aksi tukar pakaian, menggabungkan aspek keberlanjutan dengan tren anak muda. Di lapangan, inisiatif generasi muda juga membuahkan hasil nyata. Komunitas Bye Bye Plastic Bags yang didirikan Melati dan Isabel Wijsen di Bali berhasil mendorong kebijakan larangan kantong plastik sekali pakai. Gerakan Youth for Climate Indonesia aktif mengedukasi publik tentang krisis iklim, termasuk isu pengelolaan sampah. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa generasi muda bukan sekadar penerima informasi, tetapi juga penggerak perubahan kebijakan.
Di sektor pendidikan, Program Sekolah Adiwiyata yang dibina KLHK telah melibatkan ribuan sekolah dalam pengelolaan lingkungan, mulai dari bank sampah hingga pengolahan kompos. Banyak dari program ini digerakkan oleh siswa yang memanfaatkan project-based learning untuk mencari solusi kreatif mengatasi masalah sampah di sekolah dan lingkungan sekitar. Pemanfaatan teknologi juga menciptakan peluang inovasi. Aplikasi seperti Rapel dan Gringgo, yang dikembangkan anak muda Indonesia untuk membantu masyarakat mengelola sampah dengan sistem digital, dimulai dari pengumpulan, pemilahan, hingga daur ulang. Inovasi ini membuktikan bahwa isu lingkungan dapat diintegrasikan dengan peluang ekonomi yang berkelanjutan.
Beberapa negara telah membuktikan bahwa perubahan budaya konsumsi dapat dilakukan dengan dukungan generasi muda. Di Jepang, kebiasaan memilah sampah menjadi standar hidup berkat edukasi lingkungan yang dimulai sejak sekolah dasar. Di Korea Selatan, generasi muda memelopori gerakan zero waste café yang kini menjamur di berbagai kota. Di Eropa, gerakan Fridays for Future yang dipelopori Greta Thunberg menunjukkan bagaimana aksi kolektif anak muda dapat menekan pemerintah membuat kebijakan lingkungan yang tegas.
Jika generasi muda di negara lain bisa mendorong perubahan sebesar itu, generasi muda Indonesia juga dapat melakukan hal yang sama bahkan lebih. Indonesia memiliki kekayaan budaya gotong royong yang dapat menjadi fondasi kuat untuk gerakan keberlanjutan.
Perubahan gaya hidup memang tidak terjadi secara instan, tetapi dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan konsisten. Membawa botol minum sendiri, menggunakan tas belanja kain, mengurangi belanja impulsif, atau memperbaiki pakaian lama adalah langkah awal yang sederhana namun berdampak besar.Kunci keberhasilan ada pada konsistensi dan penyebaran kesadaran kolektif. Generasi muda perlu melihat bahwa zero waste bukan sekadar tren, tetapi bentuk tanggung jawab terhadap bumi. Teknologi dan media sosial adalah alat yang bisa mempercepat penyebaran pesan ini, asalkan digunakan secara tepat.