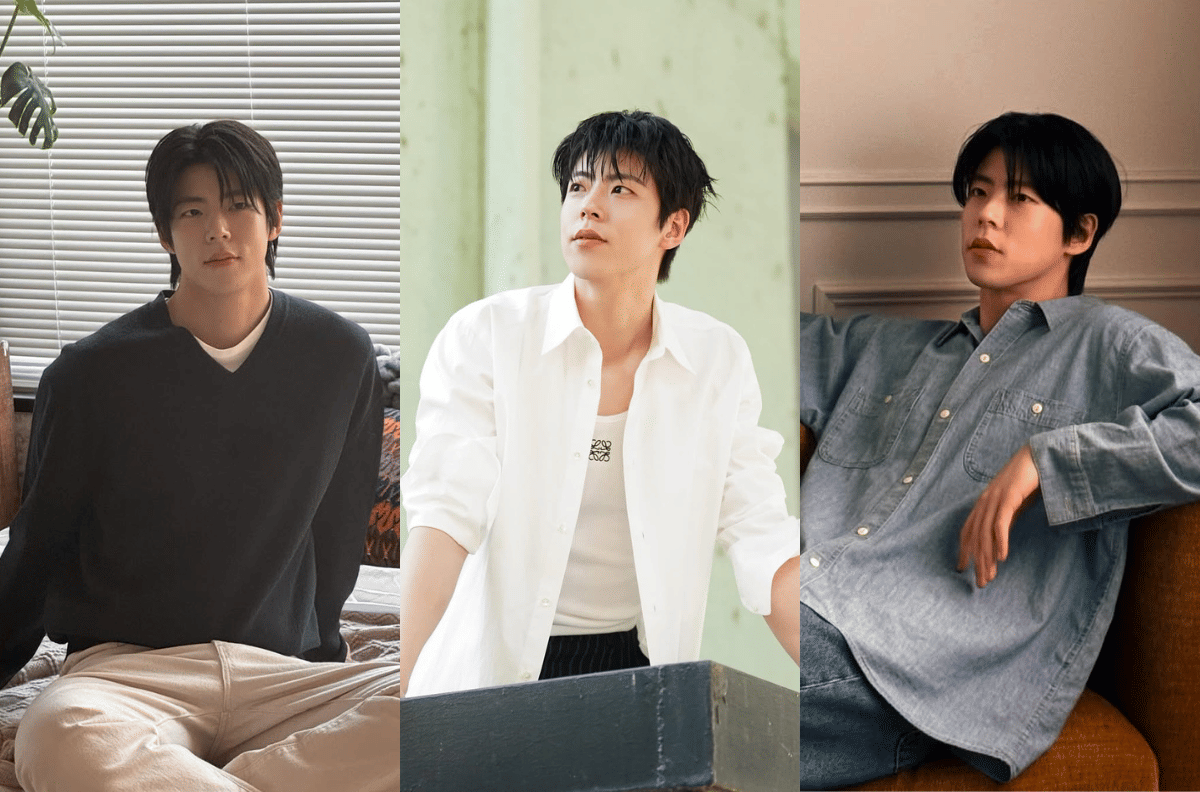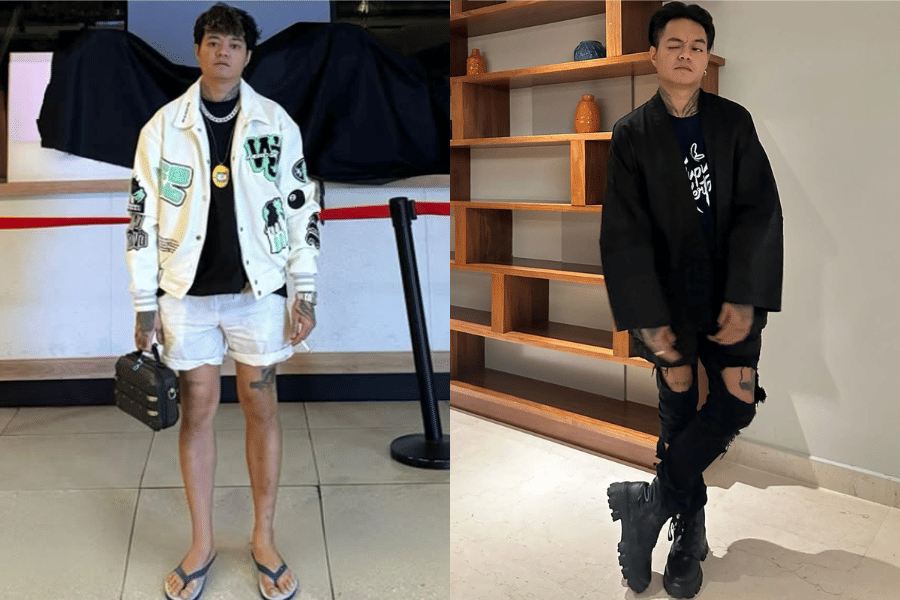7 Alasan Kenapa Kesehatan Mental Laki-laki Sering Diabaikan, Relate?

- Toxic masculinity menyebabkan laki-laki menahan emosi dan stres tanpa dukungan, berdampak pada kesehatan mental.
- Media sosial menciptakan tekanan untuk tampil sempurna, memperburuk kecemasan dan kesepian.
- Kurangnya representasi emosi lelaki dalam budaya populer dan kurangnya dukungan emosional meningkatkan stigma dan kesulitan meminta bantuan.
Banyak anggapan bahwa laki-laki harus selalu kuat, tegar, dan tahan banting dalam segala situasi. Stereotip ini membentuk ekspektasi sosial yang membungkam ekspresi emosional mereka. Akibatnya, banyak lelaki mengalami tekanan batin tanpa merasa aman untuk meminta bantuan. Padahal, seperti halnya perempuan, laki-laki juga berhak merasa lelah, bingung, takut, dan sedih. Tapi realitanya, kebutuhan emosional laki-laki sering dianggap kelemahan atau sesuatu yang harus disembunyikan.
Banyak laki-laki menyimpan luka di balik sikap tenang mereka. Mereka menanggung beban sosial, budaya, bahkan keluarga yang menuntut ketegaran tanpa ruang untuk rapuh. Berikut ini ada beberapa alasan utama kenapa kesehatan mental laki-laki sering kali diabaikan yang dampaknya sangat nyata. Dengan memahami penyebabnya, kita bisa mulai membangun empati dan membuka ruang diskusi bagi semua gender.
1. Toxic masculinity dalam kehidupan sehari-hari

Toxic masculinity adalah pola pikir dan perilaku yang mendorong laki-laki untuk selalu tampil dominan, kuat, dan tidak emosional. Dalam keseharian, lelaki yang menunjukkan emosi sering dianggap lemah. Hal ini menciptakan tekanan besar untuk menyembunyikan perasaan sebenarnya. Akibatnya, banyak dari mereka memendam stres, kecemasan, dan depresi tanpa pernah membicarakannya kepada siapa pun.
Jika hal ini terus dipelihara, laki-laki menjadi rentan terhadap gangguan mental karena tidak memiliki emosional yang sehat. Mereka lebih memilih diam daripada dicap “drama”. Padahal, memendam emosi dalam jangka panjang bisa berdampak serius pada kesehatan mental. Pergaulan yang sehat seharusnya mendukung ekspresi emosi, bukan malah menekannya. Mengubah pola pikir ini butuh kesadaran di semua kalangan.
2. Tekanan untuk sempurna dari media sosial

Media sosial mendorong citra sempurna yang sangat tidak realistis. Banyak laki-laki merasa tertekan untuk selalu terlihat sukses, produktif, dan kuat di hadapan publik. Mereka jarang memperlihatkan sisi rapuh karena takut dianggap gagal. Tekanan ini semakin memperparah kecemasan dan rasa tidak cukup, apalagi saat terus membandingkan diri dengan orang lain. Tanpa disadari, media sosial menjadi sumber stres yang tetap.
Algoritma media sosial juga memperkuat citra kesuksesan semu dan membentuk ekspektasi yang tidak manusiawi. Lelaki yang sedang berjuang merasa tidak punya ruang untuk jujur tentang kondisi mereka. Mereka merasa harus menjaga citra dan menyembunyikan kerentanan. Akibatnya, banyak yang berjuang sendiri tanpa dukungan yang memadai. Kesehatan mental pun akhirnya dikorbankan demi tampil sempurna di mata orang lain.
3. Kesepian akibat relasi emosional yang dangkal

Banyak laki-laki tumbuh tanpa membangun koneksi emosional yang dalam. Persahabatan antar lelaki sering kali terbatas pada obrolan ringan atau aktivitas bersama tanpa ruang untuk membahas perasaan secara terbuka. Hal ini membuat mereka kesulitan untuk mencari dukungan emosional saat benar-benar membutuhkan. Kesepian pun menjadi hal yang umum meskipun mereka dikelilingi banyak orang. Ironisnya, hal ini sering tak dikenali bahkan oleh diri mereka sendiri.
Tanpa relasi emosional yang kuat, laki-laki cenderung menyimpan masalahnya sendiri. Mereka merasa tidak punya tempat aman untuk berbicara tentang hal yang lebih dalam seperti trauma, ketakutan, atau tekanan hidup. Kondisi ini memperburuk kesehatan mental dan membuat pemulihan menjadi lebih sulit. Kita perlu mendorong budaya yang membuka ruang untuk kejujuran emosional, karena semua orang butuh didengar dan dimengerti.
4. Kurangnya representasi emosional lelaki dalam budaya populer

Media dan budaya populer jarang menampilkan lelaki yang sehat secara emosional. Sosok mereka dalam film, serial, atau iklan sering kali digambarkan sebagai pribadi yang dingin, kuat, dan tidak mudah goyah. Hal ini menciptakan gambaran keliru bahwa menjadi laki-laki sejati berarti harus tahan banting dan tidak boleh menunjukkan kelemahan. Representasi semacam ini memperkuat stigma bahwa ekspresi emosi bukan untuk pria.
Kurangnya representasi yang seimbang membuat banyak laki-laki merasa sendirian dalam berjuang. Mereka tak melihat contoh nyata dari tokoh yang bisa dijadikan panutan dalam mengelola emosi secara sehat. Ini menghambat proses validasi dan pemulihan diri. Media seharusnya ikut berperan dalam menampilkan laki-laki yang utuh secara emosional, bukan hanya tangguh secara fisik.
5. Luka batin dari ayah yang emosionalnya tertutup

Banyak lelaki tumbuh bersama figur ayah yang tak terbiasa mengekspresikan emosi. Hal ini kemudian menurunkan warisan emosional yang kaku dan tertutup. Mereka belajar bahwa menangis, curhat, atau mengeluh dianggap lemah dan tak diterima dalam keluarga. Akhirnya, saat dewasa mereka menciptakan siklus emosi yang tertekan dari generasi ke generasi. Luka batin ini kemudian berdampak besar pada kepercayaan diri dan kesehatan mental mereka.
Ketika hubungan emosional dengan ayah terasa jauh, laki-laki sulit membangun keintiman emosional dengan orang lain. Mereka kesulitan memaknai dan mengekspresikan perasaan karena tak pernah diajarkan bagaimana caranya. Situasi ini bisa menyebabkan kebingungan, rasa tidak aman, bahkan marah tanpa tahu sebabnya. Perlu keberanian dan kesadaran untuk memutus siklus ini dan mulai membangun hubungan emosional yang sehat.
6. Tidak dianggap sebagai korban kekerasan atau toxic relationship

Stereotip bahwa laki-laki selalu kuat dan dominan membuat mereka jarang dipandang sebagai korban kekerasan, baik fisik maupun emosional. Padahal, banyak lelaki mengalami toxic relationship, manipulasi, bahkan kekerasan verbal dari pasangan, teman, atau keluarga. Namun ketika mereka mencoba bercerita, sering kali tak dipercaya atau malah ditertawakan. Akibatnya, mereka memilih diam dan memendam trauma tersebut.
Minimnya dukungan pada mereka membuat pemulihan jadi sangat sulit. Layanan bantuan pun sering kali lebih berorientasi pada korban perempuan, membuat laki-laki ragu mencari pertolongan. Padahal semua korban berhak mendapatkan perlindungan dan bantuan. Kita perlu membangun pemahaman bahwa laki-laki juga bisa menjadi korban. Dukungan yang adil akan membantu lebih banyak orang pulih dari hubungan toksik.
7. Kurangnya edukasi dan dukungan emosional

Banyak lelaki tak pernah diajarkan cara mengenali dan mengelola emosi mereka sendiri. Pendidikan formal jarang membahas soal kesehatan mental secara terbuka, apalagi untuk laki-laki. Di rumah, pembicaraan soal perasaan pun sering dianggap tabu atau tidak penting. Akibatnya, mereka tak cukup memahami kondisi emosionalnya. Saat mengalami krisis, mereka pun bingung harus mulai dari mana untuk mencari bantuan.
Selain edukasi, lelaki juga membutuhkan dukungan emosional dari lingkungan sekitarnya. Validasi, ruang aman untuk bercerita, dan pemahaman tanpa menghakimi sangat dibutuhkan mereka. Kita perlu membangun budaya yang mendukung kesehatan mental untuk semua orang. Mulai dari keluarga, sekolah, hingga tempat kerja, semua bisa berkontribusi. Karena pemulihan butuh dukungan, bukan hanya keberanian.
Menganggap lelaki selalu kuat hanya akan membuat mereka terus memendam luka tanpa pernah disembuhkan. Hal ini menunjukkan bahwa tekanan sosial dan budaya memainkan peran besar dalam mengabaikan kesehatan mental laki-laki. Saatnya kita berhenti menuntut kekuatan dari laki-laki dan mulai membuka ruang untuk kerentanan mereka. Karena semua orang berhak didengar, dimengerti, dan disembuhkan.