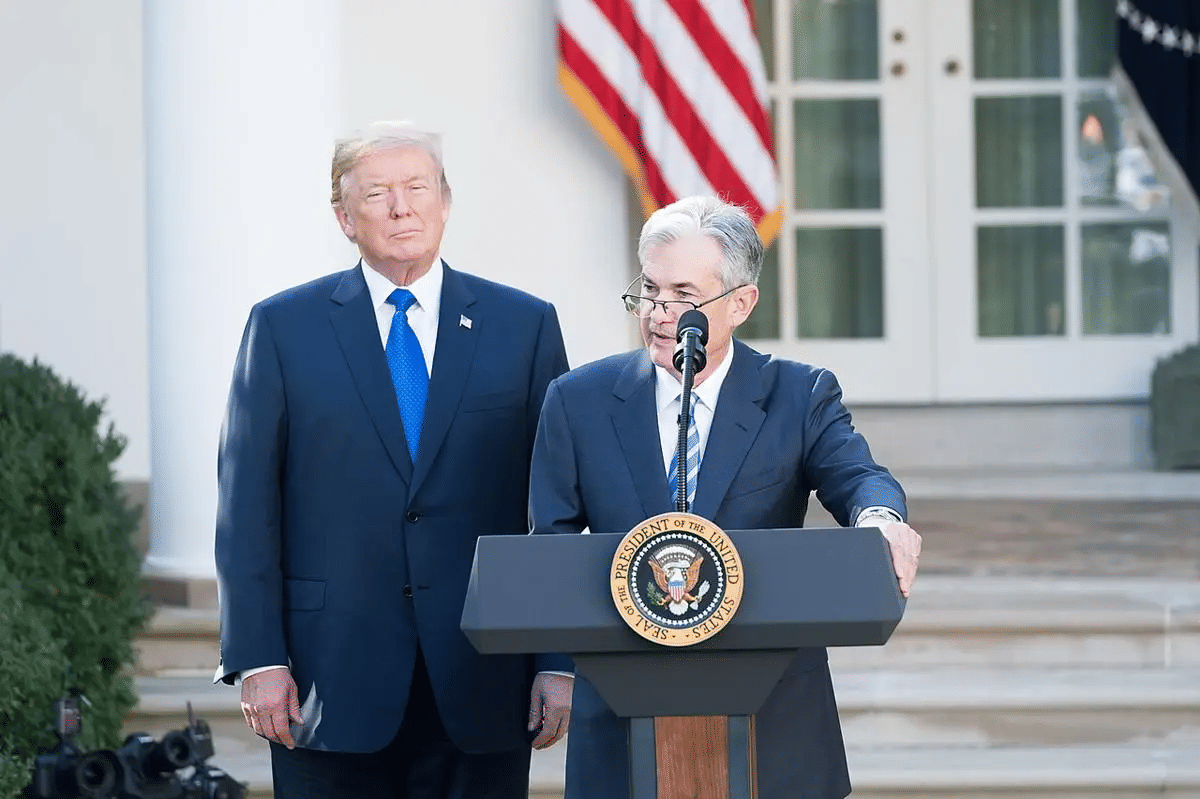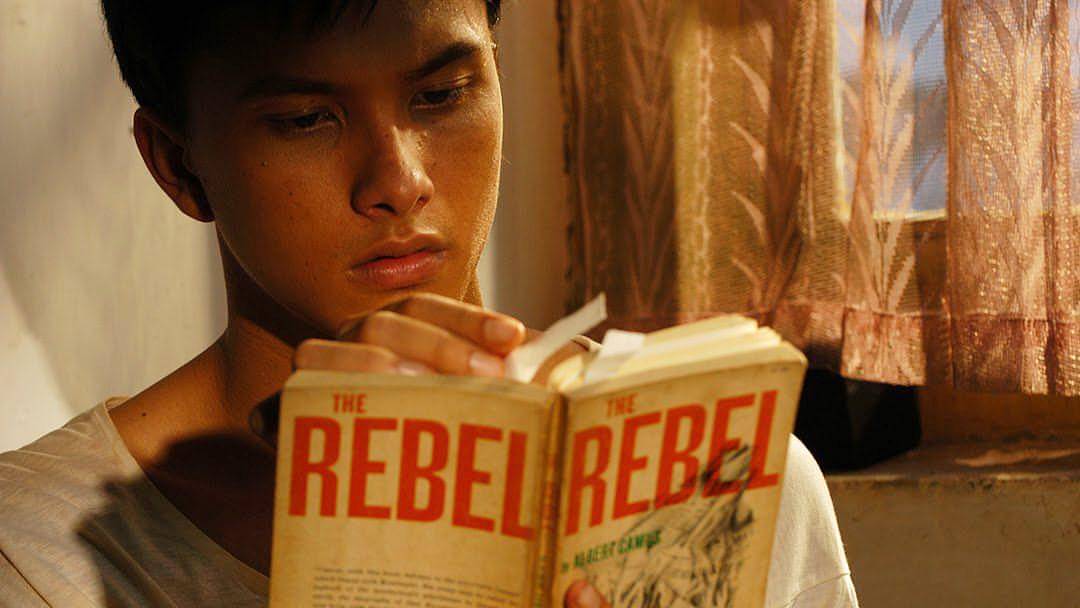Aku, Konsep Hidup Minimalis, dan Bisnis Susu

Pandemik COVID-19 menjadi pelajaran bagi setiap orang, begitu pula diriku. Namun aku benar-benar bersyukur tidak banyak hal buruk yang terjadi selama setahun ini, mungkin tidak ada yang benar-benar gawat. Memang kuakui perlu adaptasi yang tidak mudah dalam setahun terakhir. Tak bisa bertemu teman-teman, atau jarang, bekerja dari rumah dengan segala distraksinya, hingga kekhawatiran akan COVID-19 ini.
Aku justru belajar banyak hal baru setahun terakhir ini. Dua hal yang paling menggambarkan setahun terakhir ini adalah minimalisme dan bisnis susu. Pertemuanku dengan konsep minimalisme hingga bisnis susu yang sedang kujalani menjadi hal yang sangat berkesan dalam tahun yang penuh kesulitan ini.
Kedua hal yang terus aku jalankan dan kembangkan dan aku percaya akan menjadi besar beberapa tahun lagi. Dua hal yang aku percaya dan berkomitmen bahwa ini adalah jalan hidupku.
***
Kisah ini berawal pada Februari 2020 ketika aku tidak sengaja menonton A Day in the Life of a Minimalist-nya Matt D'Avella yang ada di timeline YouTube. "Hidup minimalis?" pikirku. Aku menonton video berdurasi 07:34 menit itu. Lalu berpikir "Ini orang gak ada kehidupan lain gitu? Gak main media sosial atau apa lah?"
Entah apa yang merasukiku pada Minggu, 8 Maret 2020 sore. Aku berbaring di atas kasur dan tidak mengerjakan apa-apa seharian. Hal paling bagus yang aku kerjakan di hari itu adalah mengantar ibuku membeli sarapan, menjenguk saudara, sudah.
Aku teringat video Matt. "Hidup minimalis?"
Aku membuka YouTube dan mengetik dua kata itu. Video pertama yang aku tonton adalah channel Satu Persen. Di sini lebih banyak bahas masalah distraksi ponsel dan media sosial. Benar. Aku banyak menghabiskan waktu membuka Facebook, Twitter, Instagram, Tokopedia, dan lain-lain. Seakan aku butuh afeksi dan ada kepuasan dari sana. Nyatanya, tidak.
Aku ingat dulu sempat detoks media sosial selama satu bulan. Yang akhirnya aku menyerah karena kepo sama urusan personal orang lain. Tapi dalam satu bulan itu aku cukup efektif dan produktif bekerja dan hal lainnya. Aku lebih fokus.
Aku candu sama media sosial. Aku juga boros karena sering memantau barang apa yang mau aku beli di Tokopedia dan Facebook. Parah.
Aku melanjutkan menonton video kedua, kali ini dari Narasi TV. Ini lebih bahas soal buku, yang akhirnya kupesan di Tokopedia untuk referensi hidup minimalis. Dua buku yang kubeli itu adalah Goodbye Things, Hidup Minimalis Ala Orang Jepang karya Fumio Sasaki dan Seni Hidup Minimalis karya Francine Jay.
Buku Fumio benar-benar memprovokasi hidup minimalis, yang menurutku sangat ekstrem. Aku menandai beberapa kalimat yang menghujam pemikiranku tentang benda dan kebahagiaan. Rasanya saat itu aku ingin langsung mengurangi banyak benda di kamarku.
Cuci otak buku Fumio itu berhasil. Aku lalu merenung menatap langit-langit kamar, melihat tumpukan komik, mainan dan barang-barang lain yang jadi koleksiku. “Haruskah semua ini aku jual? Setelah beberapa tahun mengoleksi ini semua?” tanyaku pada diri sendiri.
Lagi-lagi, provokasi buku Fumio dan Francine sangat berhasil. Belum lagi ditambah influencer hidup minimalis lain seperti The Minimalist dan Thoughtworthy. Aku semakin meyakini tidak ada gunanya terus membeli mainan, gim, sepatu, pakaian, dan benda-benda lainnya. Tidak akan ada habisnya kalau untuk sekadar cari kebahagiaan, yang ada semakin boros.
Dari SMA, aku selalu punya impian punya rumah sendiri. Impian yang lebih tepat disebut angan-angan karena hanya terus membayangkan dan tidak ada tindak nyata. Mulai dari rumah tipe country, mediteranian hingga smart living yang mengusung konsep SOHO, small office home office. Bisa dibilang karena waktu itu ayahku suka membeli majalah properti seperti Home. Aku mengamati desainnya yang menurutku menarik.
Impian itu muncul kembali, kali ini aku mengidamkan rumah minimalis. Yah terus aja ngimpi punya rumah, pikirku membantah angan-angan semu itu.
Tapi aku makin serius. Aku benar-benar menginginkan rumah sendiri dengan dengan konsep minimalis. “Eh tapi kan belum nikah, gimana mau beli rumah tapi biaya buat nikah aja belum ada?”
Pemikiran-pemikiran itu terus menghantuiku. Tapi semakin aku mengenal minimalisme, rasanya semua itu sangat mungkin terwujud.
Yah ngapain sih nikah sampai ngundang ratusan sampai ribuan orang? Nikah buat siapa? Cuma buang-buang duit buat resepsi yang seharusnya bisa disederhanakan. Mending uangnya buat beli rumah.
Aku lalu merencanakan hidupku, apa yang benar-benar aku inginkan, apa yang harus dibeli dan apa yang membuatku bahagia. Berapa sih pengeluaranku selama ini? Masih bisa nabung gak?
Rentetan pertanyaan dan jawaban yang kudapat lebih dulu, untuk membeli rumah dan menikah sesederhana mungkin akhirnya membuatku menjual seluruh koleksiku pada Juli 2020. Semuanya. Mulai dari mainan, pakaian, komik dan beberapa buku yang tidak kubaca.
“Lo ada masalah keuangan gara-gara corona sampai jual semua koleksi lo?” tanya salah seorang sahabat yang kaget dan mengomentari postingan koleksiku yang kujual itu.
“Enggak, emang mau gue jual dan setop koleksi mainan,” jawabku.
“Bohong lo, gak ada duit? Kena PHK? Gak sayang lo sama koleksi lo? Itu gak gampang loh carinya, lo pernah bilang salah satu mainan lo itu udah langka.”
“Buat modal nikah dan beli rumah,” jawabku asal agar tidak terus ditanya. Sayang, justru ucapan itu jadi bumerang buatku.
“Siapa emang pacar lo? Emang ada yang mau sama lo? Lo aja udah jomblo lama, coba sini kasih tahu gue kayak gimana rupa tuh cewek!”
Pertanyaan soal menikah memang bukan perkara mudah. Dalam dua-tiga tahun terakhir aku juga sering berdebat dengan ibuku untuk tidak mengundang banyak orang dalam resepsi pernikahan. Pernah satu hari ada sebuah berita yang sedang disaksikan ibuku. Berita itu tentang larangan menggelar resepi pernikahan dengan banyak orang saat pandemik.
“Tuh, udah benar kalau resepsi nikah gak perlu undang banyak orang. Makanya kalau aku minta nanti resepsiku gak usah banyak undangan jangan protes,” kataku kepada ibuku.
“Iya, kalau nikah sekarang. Kamu udah ada calonnya belum? Kalau udah ada ya gak apa nikah tanpa banyak undangan,” kata ibuku membalas yang tidak bisa kujawab lagi. Skakmat.
Terlepas dari itu semua, aku terus belajar hidup minimalis. Mengembangkannya menjadi sebuah kebiasaan meski tidak mudah. Perlahan, sifat konsumtifku berkurang, aku merasa tenang dan fokus dengan sedikit barang. Pun kebiasaan merokokku yang baru hilang dalam dua bulan terakhir ini.
Aku tidak lagi gampang tergiur dengan promo atau diskon. Bahkan aku menghapus banyak aplikasi di handphoneku. Dulunya aku punya banyak aplikasi e-commerce dan finansial seperti Akulaku, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, Shopee, GoJek, Grab, OVO, Dana, LinkAja, dan masih banyak lainnya. Sekarang aku hanya fokus di Tokopedia, Grab, GoJek, Paxel, OVO dan Mobile BCA.
***
Sementara, awal mula bisnis susuku terjadi sejak 2019 akhir. Tapi saat itu sebetulnya aku akan menginvestasikan uang untuk bisnis sapi potong. Aku dan ayahku sepakat berinvestasi pada sapi potong. Pertimbangannya karena keuntungan besar dan kepercayaan pada teman SMA-ku yang menjalankannya membuat kami pede berinvestasi.
Tapi pada pertengahan Maret 2020, semua berubah. Pandemik COVID-19 membuat kami batal berinvestasi sapi potong. Ayahku bilang kami harus menyimpan uang kami karena tidak tahu sampai kapan pandemik berlangsung.
Temanku lalu memintaku bersabar dan mengajak aku berdiskusi bisnis lainnya. Kali ini sapi perah. Ia memberikan perhitungan kasar modal dan keuntungan dari bisnis sapi perah. Ia juga mengajakku mengunjungi peternakan sapi di Batu, Blitar, dan Pasuruan.
Aku lalu mengunjungi Batu, Malang pada September 2020. Agak was-was karena COVID-19 cukup tinggi. Tapi aku berusaha ketat menjaga diri. Aku mengunjungi peternakan sapi perah di sana. Belajar dari peternak hingga alur produksi dan distribusinya.
Aku termasuk orang yang tidak terlalu suka susu. Kadang mual setelah minum susu full cream, sehingga hanya mengonsumsi susu yang manis seperti susu UHT pisang dan cokelat. Pandanganku ke susu kemudian tidak sama lagi ketika pada satu pagi di Batu disuguhkan susu segar yang baru diperah dan dimasak. Ya, itu kali pertama aku mencoba susu segar dari sapi.
Aku mengambil air putih hangat untuk berjaga-jaga jika perut mual setelah minum susu itu. Tapi susu sapi segar itu benar-benar berbeda. Aku sama sekali tidak mual, dan malah menyukainya. Temanku lalu meminta mencampur susu segar itu dengan teh, dan memintaku meminumnya. Kali ini rasanya sangat bisa diterima karena manis.
Dalam perjalanan pulang, kami mengevaluasi rencana yang sudah disusun. Untuk buat peternakan di Jakarta tentu saja sangat berat. Bukan cuma masalah sapi tapi kandang, lahan, pakan dan lain-lain. Kami belum sanggup. Ide yang muncul saat itu mengolah susu sapi dalam kemasan. Duh, baku hantam sama produk lain yang sudah punya nama dong.
“Susu pasteurisasi. Lo pelajari deh. Rasanya gak jauh beda sama yang lo minum di Batu itu,” kata temanku.
Aku mulai menggali soal susu pasteurisasi. Aku dan tiga orang temanku berkumpul. Mulai membahas rencana bisnis ini termasuk riset susu yang kami beli di salah satu peternakan di Jakarta sebagai supplier kami. Barulah pada Oktober 2020 untuk pertama kalinya kami berempat mulai memasarkan susu. Kami bilang, susu sapi ini segar dan murni, tidak bikin mual, dan tidak bau amis.
Namun kami hanya mendapat 20 liter di awal penjualan. Bahkan untuk membuat 20 liter susu pasteurisasi itu kami menghabiskan lebih dari lima jam. Kendala teknis, peralatan dan lain-lain membuat malam itu terasa panjang dan melelahkan.
Kami bertengkar, berbeda pendapat sampai ada keinginan untuk mengakhiri bisnis ini. Seorang teman bahkan pernah berkecil hati karena keuntungan yang kami dapatkan sangat kecil. Kami juga beberapa kali mengganti pekerja kami karena satu dan lain hal.
Tapi tiap minggu, jumlah pembeli susu kami makin bertambah seiring bertambahnya varian susu yang kami keluarkan. Keuntungan yang ada kami putar menjadi aset. Terus seperti itu. Rasanya kok mau menyerah, tapi sayang karena melihat antusiasme pelanggan kami yang percaya pada susu ini, serta harga diri kami yang sudah membangun dari nol. Kami tidak mau menyerah. Kami terus berjuang dengan keyakinan bahwa masyarakat bisa sehat dengan konsumsi susu yang segar ini, bukan sekadar cari untung.
Kami bersyukur bisa membantu memberi pekerjaan kepada dua orang teman kami yang membutuhkan. Apa yang kami berikan memang belum seberapa, tapi kedua teman kami itu yang membuat kami bisa sejauh ini. Bisnis susu ini kini terdiri dari tujuh orang inti yang di antaranya merupakan pendiri atau founder, dan tiga lainnya pekerja sambilan, semuanya adalah teman SMA dan kuliah.
Bagiku pribadi, kesenangan dalam menjalankan bisnis susu ini karena banyak orang yang suka dan mereka menilai susu pasteurisasi itu bermanfaat bagi mereka. Beberapa pelanggan kami kadang menuntut untuk kami lebih sering memproduksi susu dan menyediakan susu yang siap stok, ada juga yang meminta maaf karena belum memesan susu lagi meski baru 2-3 kali tidak memesan.
Kami masih terus berjuang, mengurus segala perizinan dan mengenalkan susu ini ke masyarakat yang lebih luas. Ah ya, nama susu pasteurisasi ini bernama Sukondang, susu seko kandang, bahasa Jawa yang artinya susu dari kandang.
#SatuTahunPandemik adalah refleksi dari personel IDN Times soal satu tahun virus corona menghantam kehidupan di Indonesia. Baca semua opini mereka di sini.