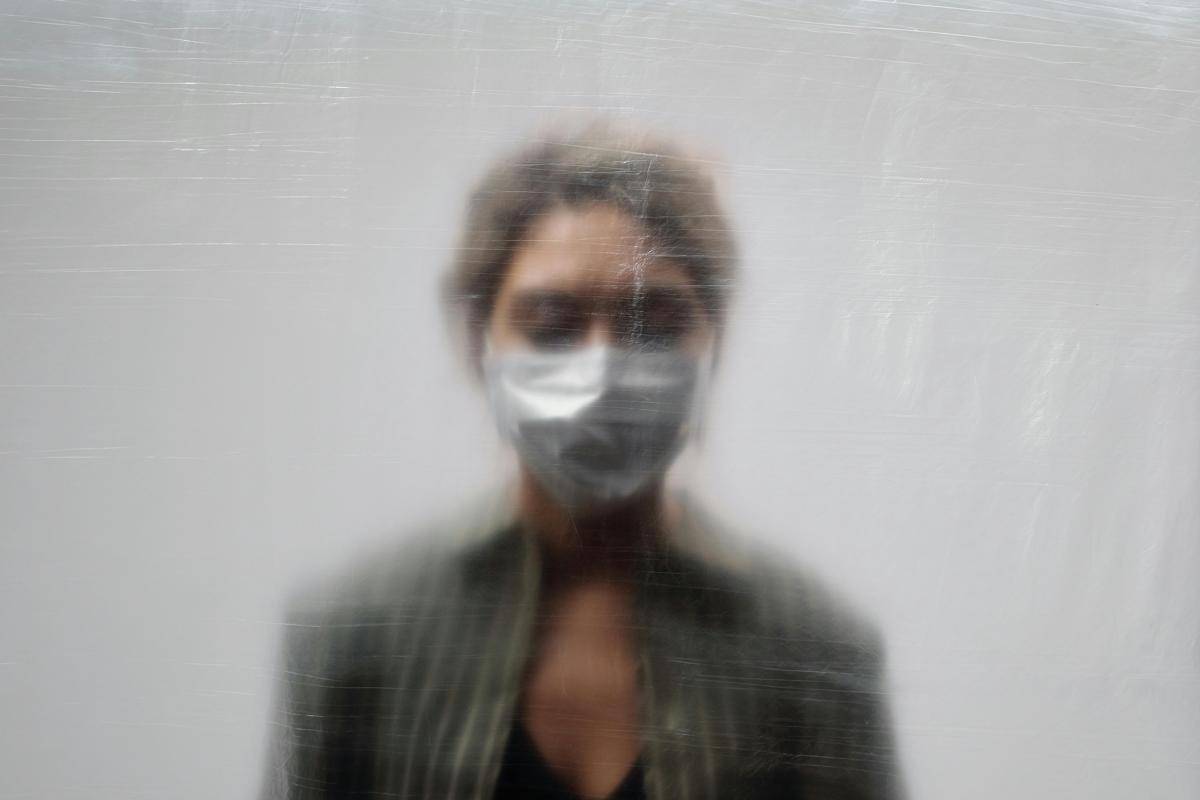Usiaku dua puluh delapan,
tapi luka-luka lamaku belum berubah alamat.
Ia masih tinggal di tubuh ini,
menyamar sebagai sabar,
bernafas pelan di sela kesibukan yang kuakali sebagai ‘tumbuh’.
Aku tak lagi berdarah,
tapi selalu ada bagian dari diriku
yang kembali membeku setiap kali disentuh.
Lelaki datang dan pergi,
situasi berubah,
tapi skenario selalu sama:
aku diam.
Aku paham peran korban lebih baik
daripada cara mencintai diriku sendiri.
Dulu kupikir ini nasib.
Tapi kini aku tahu: ini pola—
pola yang kubangun dari rasa bersalah,
dari cinta yang kupelajari lewat ketakutan,
dari rumah yang tak pernah mengajariku
cara merasa aman.
Aku menarik luka karena aku dilatih
untuk merasa nyaman di tempat yang menyakitiku.
Dan anak kecil di dalam dadaku,
masih berdiri di lorong itu,
mengira cinta datang dalam bentuk
yang membuatnya gemetar.
Tapi malam ini,
aku menutup pintu yang tak pernah kubuat sendiri.
Aku duduk dengan tubuh yang akhirnya jujur:
aku lelah mengulang cerita
di buku yang tak pernah kubolehkan kubakar.
Biar kali ini berbeda.
Biar tanganku yang menulis ulang—
meski dengan pena gemetar,
meski belum tahu ending-nya.
Yang kutahu:
aku tak mau jadi halaman yang terus mengulang luka
hanya karena aku takut membuka lembaran baru.