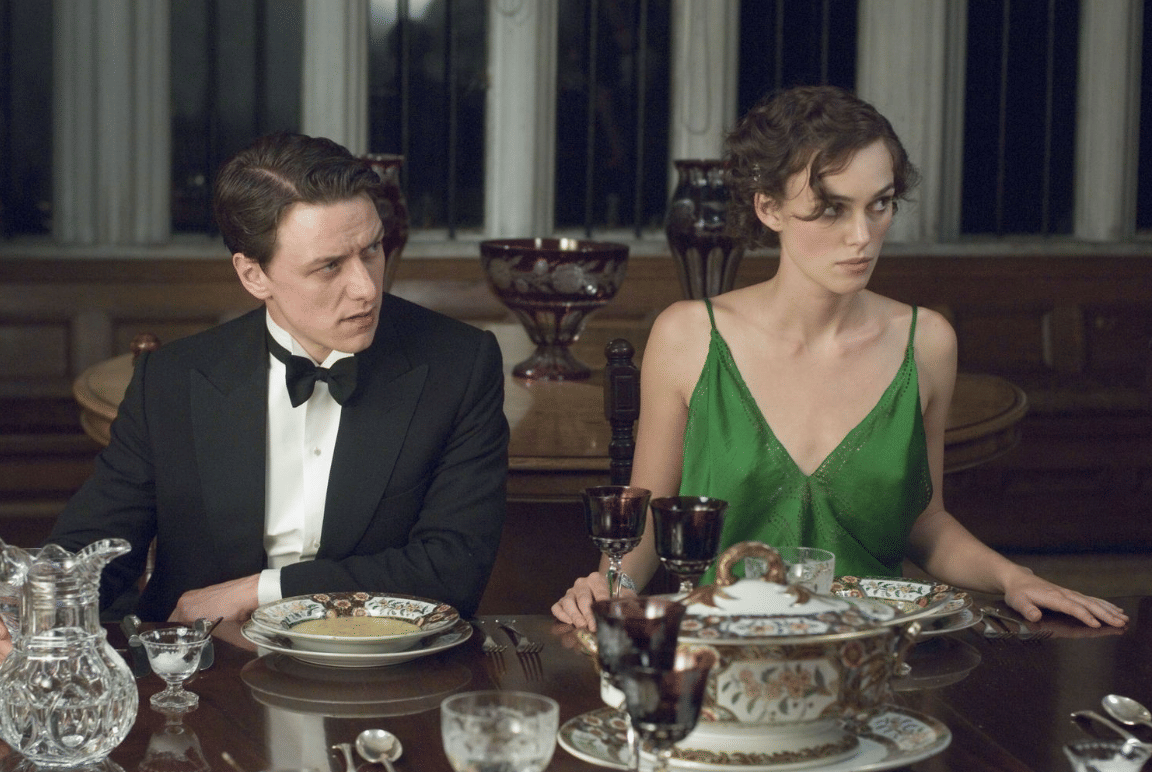5 Alasan Kenapa Kokuho Berhasil Jadi Film Non-Animasi Terlaris Jepang

- Kokuho menjadi film live-action Jepang terlaris sepanjang masa
- Sukses soroti keindahan Jepang lewat kesenian kabuki
- Naskah kuat dengan akting memikat dari pemainnya
Di dunia film, ada pepatah legendaris dari William Goldman: “Nobody knows anything.” Tak ada rumus pasti kenapa satu film meledak sementara yang lain tenggelam. Kokuho (2026) membuktikannya. Drama epik garapan Lee Sang Il ini melampaui segala logika pasar.
Durasinya hampir 3 jam, temanya berat, dan berpusat pada seni kabuki yang tergolong niche. Hasilnya? Ia justru menjadi film live-action Jepang terlaris sepanjang masa. Kokuho menghasilkan lebih dari 17,38 miliar Yen Jepang, secara resmi melampaui rekor sebelumnya sebesar 17,35 miliar Yen Jepang yang dicetak oleh Bayside Shakedown 2 (2003).
Berikut lima alasan kenapa Kokuho bisa mencetak sejarah, bahkan membuat banyak penonton rela nonton berkali-kali.
1. Sukses soroti keindahan Jepang lewat kesenian kabuki

Salah satu kekuatan terbesar Kokuho adalah caranya memperlakukan kabuki sebagai jiwa dari keseluruhan narasi. Film ini benar-benar mengajak kita masuk ke dunia seni pertunjukan tradisional Jepang yang selama ini terasa eksklusif dan tertutup. Setiap pementasan dilengkapi konteks cerita, kartu judul, dan simbol dramatik yang membantu penonton awam memahami makna adegan.
Pendekatan ini penting, karena kabuki sendiri sering dianggap terlalu "klasik" atau sulit diakses generasi muda. Lewat Kokuho, kabuki tampil sebagai sesuatu yang hidup, penuh konflik, ambisi, dan emosi manusia. Kita tak hanya melihat panggung, tetapi juga ikut masuk ke ruang ganti, lorong sempit teater, hingga napas para aktor sebelum naik pentas. Semua ini menciptakan pengalaman imersif yang jarang ditemui dalam film bertema seni tradisional.
Lebih jauh lagi, film ini memperlihatkan kabuki sebagai sistem sosial dengan hierarki ketat, diwariskan lintas generasi, dan sarat politik internal. Kita diajak memahami bahwa di balik kostum megah dan gerak elegan, ada latihan brutal, pengorbanan fisik, serta tekanan psikologis yang berlangsung puluhan tahun. Inilah yang membuat Kokuho bukan sekadar perayaan budaya, tapi juga potret jujur tentang harga yang harus dibayar demi menjaga tradisi tetap hidup.
2. Naskah kuat dengan akting memikat dari pemainnya

Dari sisi penulisan, naskah Kokuho berhasil memadatkan kisah lintas lima dekade sejak 1960-an menjadi rangkaian momen penting yang sarat makna. Alih-alih menjelaskan semuanya secara eksplisit, film ini memilih menampilkan turning point emosional yang saling terhubung sehingga penonton diharuskan aktif membaca gestur, tatapan, dan keheningan para karakter.
Penampilan Ryo Yoshizawa sebagai Kikuo dan Ryusei Yokohama sebagai Shunsuke menjadi tulang punggung film ini. Keduanya menjalani pelatihan kabuki berbulan-bulan sebelum syuting, dan hasilnya terasa nyata di layar. Gerakan tubuh mereka presisi, ekspresi wajah penuh kontrol, dan setiap adegan panggung terasa seperti pertunjukan kabuki sungguhan, bukan sekadar akting.
Yang menarik adalah, karakter Kikuo ditulis sebagai sosok ambigu: dingin, ambisius, tapi juga rapuh. Ia bukan protagonis yang bakal disukai, tetapi justru itu yang membuatnya kompleks. Sementara Shunsuke tampil lebih emosional dan manusiawi, mewakili sisi pewaris yang tertekan oleh ekspektasi keluarganya.
3. Angkat kisah relatable tentang perintis vs pewaris

Secara tematik, Kokuho berbicara tentang pertarungan klasik: bakat versus garis keturunan. Kikuo datang dari luar sistem, anak yakuza yang "tidak seharusnya" berada di dunia kabuki. Sebaliknya, Shunsuke adalah pewaris sah yang justru kehilangan arah. Konflik ini terasa sangat modern, terutama di era modern ketika isu privilege, kesempatan, dan meritokrasi makin sering dibicarakan.
Kokuho menunjukkan bahwa menjadi perintis berarti harus bekerja dua kali lebih keras, menanggung stigma, dan terus membuktikan diri. Namun menjadi pewaris pun bukan berarti lebih mudah, karena beban ekspektasi keluarga bisa sama beratnya. Keduanya sama-sama terjebak dalam sistem yang lebih besar dari diri mereka sendiri.
Relasi Kikuo dan Shunsuke pun berkembang seperti siklus: satu naik, yang lain jatuh, lalu berganti lagi. Pergulatan ini bukan sekadar rivalitas, melainkan refleksi tentang bagaimana manusia mendefinisikan nilai diri lewat pengakuan sosial. Inilah alasan kenapa penonton dari berbagai generasi bisa terhubung dengan ceritanya, meski latarnya adalah dunia kabuki yang sangat niche.
4. Pengambilan gambar dan make-up yang luar biasa

Secara visual, Kokuho tampil sangat ambisius. Kamera kerap naik ke atas panggung, merekam aktor dari jarak dekat, memperlihatkan detail riasan, keringat, bahkan getaran napas mereka. Desain kostum dan tata rias lintas usia juga menjadi elemen penting.
Perubahan fisik karakter dari remaja hingga usia lanjut ditampilkan halus, tanpa terasa artifisial. Setiap kostum kabuki dirancang bukan hanya indah, tetapi juga berfungsi sebagai bahasa visual yang mencerminkan kondisi batin karakter saat itu. Nominasi Oscar untuk Best Makeup and Hairstyling pun terasa layak didapatkan film ini.
Durasi hampir 3 jam yang biasanya menjadi "racun" box office justru terasa ringan berkat ritme visual yang konsisten. Banyak adegan dibuat seperti hipnosis pelan: kamera bergerak tenang, warna panggung kontras dengan dunia luar, dan komposisi frame terasa sangat terkurasi. Sinematografi mengalir dari Sofian El Fani (Blue Is the Warmest Color) menciptakan perspektif yang mustahil didapat penonton kabuki sungguhan, membuat pengalaman sinematiknya terasa eksklusif dan intim.
5. Mendapat sambutan positif di ajang penghargaan dunia

Dulu, perfilman Jepang memiliki genre yang disebut geidōmono atau "pertunjukan cerita," yang berlatar dunia seni pertunjukan tradisional seperti kabuki atau rakugo. Genre ini sempat menghilang sejak tahun 70-an, tapi kembali terangkat dewasa ini, salah satunya lewat Kokuho. Tak hanya hidup kembali di Jepang, genre ini pun kembali dikenalkan ke dunia.
Kokuho diputar di berbagai festival internasional, termasuk Cannes dan Toronto, serta dipilih sebagai kandidat Jepang untuk kategori Film Fitur Internasional di Oscar. Sambutan hangat dari kritikus luar negeri memperkuat posisinya sebagai karya yang mampu menembus batas budaya.
Yang lebih menarik, performa box office-nya justru meningkat setelah pekan pembukaan. Penonton datang kembali untuk menonton ulang, media sosial dipenuhi diskusi, dan demografi audiens meluas dari perempuan paruh baya ke generasi muda serta penonton pria. Fenomena ini menunjukkan bahwa film ini berhasil menjadi peristiwa sosial, bukan sekadar produk hiburan.
Kesuksesan tersebut juga menandai kebangkitan drama live-action Jepang di tengah dominasi anime seperti Demon Slayer. Kokuho membuktikan bahwa film lokal dengan tema berat pun bisa sukses besar jika digarap dengan visi kuat dan eksekusi total. Ia membuka kemungkinan baru bagi perfilman Jepang untuk kembali percaya diri membawa cerita budaya mereka ke panggung global.