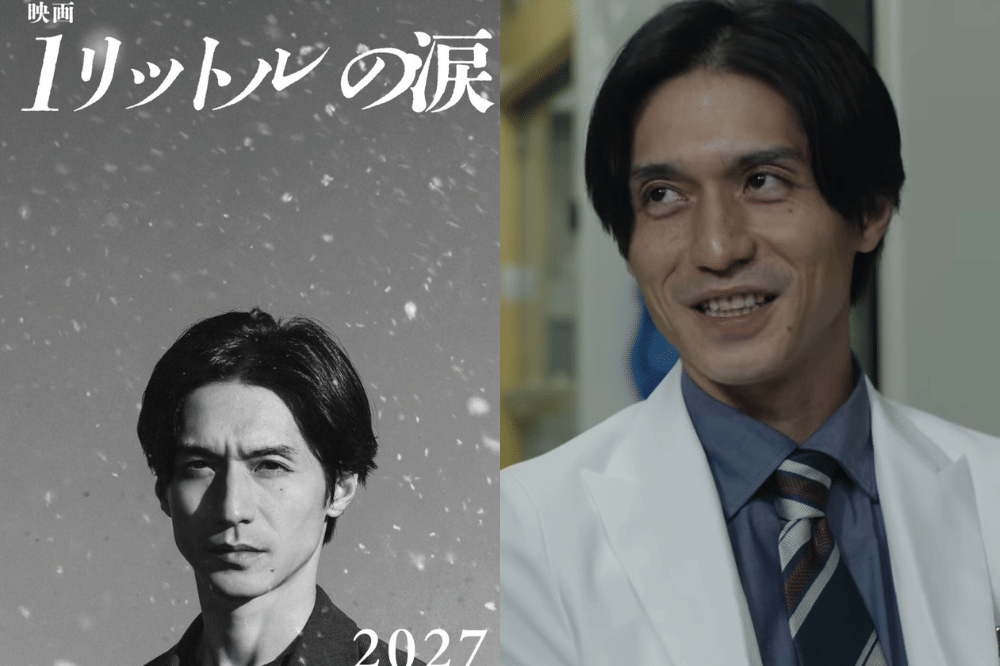Alasan Sinners Layak Pecahkan Rekor Nominasi Oscar Terbanyak, Sebagus Itu?

Setelah meraup lebih dari 368 juta dolar AS di box office global, Sinners (2025) karya Ryan Coogler berhasil mencetak sejarah. Berlatar di era Jim Crow, film ini resmi memecahkan rekor nominasi Oscar terbanyak sepanjang masa dengan 16 nominasi, melampaui rekor 14 nominasi yang sebelumnya dipegang All About Eve (1950), Titanic (1997), dan La La Land (2016).
Daftar nominasinya nyaris menyapu semua lini utama dan teknis: Film Terbaik, Sutradara Terbaik, Skenario Asli Terbaik, Aktor Terbaik (Michael B. Jordan), Aktris Pendukung Terbaik (Wunmi Mosaku), Aktor Pendukung Terbaik (Delroy Lindo), hingga Casting, Sinematografi, Musik Orisinal, Lagu Orisinal ("I Lied to You"), Penyuntingan, Tata Rias & Rambut, Suara, Efek Visual, Desain Produksi, dan Desain Kostum.
Banyak yang bertanya-tanya, mengapa Sinners bisa mendapat banyak nominasi Oscar? Berikut alasan mengapa pencapaian ini terasa pantas.
1. Penampilan terbaik Michael B. Jordan dan kejutan dari Miles Canton

Sinners terasa seperti panggung tempat Michael B. Jordan akhirnya benar-benar memeras seluruh spektrum kemampuannya sebagai aktor. Ini bukan performa heroik yang mengandalkan karisma fisik atau retorika lantang, melainkan akting yang dibangun dari tekanan internal. Karakternya (si kembar Smokestack) seolah selalu menahan sesuatu: kemarahan, ketakutan, dan keinginan untuk bertahan hidup tanpa kehilangan martabat.
Karakternya tidak selalu "benar," tidak selalu simpatik, dan justru sering tampak kelelahan secara moral. Inilah potret laki-laki kulit hitam di era Jim Crow yang jarang digambarkan secara utuh. Kamera kerap bertahan pada wajah Jordan lebih lama dari yang nyaman, membiarkan mikro-ekspresi bekerja. Oscar biasanya menyukai jenis keberanian sunyi seperti ini.
Kejutan datang dari Miles Canton, yang tidak diposisikan sebagai sekadar aktor muda potensial, tetapi sebagai kontrapung emosional. Jika Jordan adalah api yang tertahan, Canton adalah percikan yang belum tahu harus membakar atau padam. Permainannya mentah, nyaris tidak terlindungi, dan justru itu yang membuatnya efektif.
Dinamika keduanya bukan relasi mentor yang klise, melainkan benturan dua generasi trauma. Satu sudah belajar bertahan, yang lain masih mencoba memahami dunia yang tidak adil sejak awal. Kombinasi keduanya memberi Sinners denyut emosional yang sulit ditiru dan menjelaskan mengapa kategori akting mereka begitu kuat tahun ini.
2. Adegan "I Lied to You" dan gaung kejeniusannya

Adegan "I Lied to You" adalah alasan utama Sinners terasa lebih dari sekadar drama sejarah. Secara struktural, ini adalah momen di mana film menanggalkan realisme dan masuk ke wilayah psikologis yang hampir surealis. Musik tidak lagi menjadi ilustrasi emosi, melainkan alat naratif.
Keberanian adegan ini terletak pada cara ia memaksa penonton untuk "merasakan," bukan memahami. Seperti A Clockwork Orange (1971), adegan ini menolak empati yang nyaman. Ia justru memanipulasi ritme, warna, dan suara untuk menempatkan penonton di posisi karakter yang terperangkap. Bahwa Christopher Nolan memuji sekuens ini bukan hal mengejutkan, karena ini adalah sinema yang percaya pada bahasa visual, bukan dialog ekspositori.
Hal lain yang tak kalah paling penting adalah adegan ini bukan gimmick. Ia mengartikulasikan tema besar film tentang kebohongan yang diperlukan untuk bertahan hidup. "I Lied to You" bukan sekadar pengakuan personal, melainkan pernyataan eksistensial dari kelompok kulit hitam yang terus dipaksa berbohong tentang siapa mereka agar bisa selamat.
3. Genre-bending ambisius dalam format IMAX

Sinners adalah film yang secara sadar menolak dikurung dalam satu genre. Ia bergerak antara drama sejarah, thriller psikologis, musikal, bahkan horor sosial, tanpa pernah terasa terpecah. Kuncinya adalah kontrol tonal Coogler yang memahami bahwa genre hanyalah wadah, bukan tujuan.
Pilihan teknisnya memperkuat ambisi tersebut. Dengan memfilmkan Sinners secara simultan menggunakan Ultra Panavision 70 dan IMAX 65, Coogler tidak sekadar mengejar prestise teknis. Ia menggunakan skala visual untuk menegaskan ironi: tubuh-tubuh yang ditindas direkam dalam format paling megah yang dimiliki sinema. Dunia terlihat luas, tetapi ruang gerak karakter tetap sempit.
IMAX di sini bukan soal spektakel, melainkan soal kontras. Lanskap luas mempertegas keterkungkungan sosial. Ruang publik terasa megah, tetapi penuh ancaman. Pendekatan ini membuat Sinners terasa sinematik dalam arti klasik. Film ini memang dirancang untuk layar besar, bukan sekadar "konten" yang diperbesar.
4. Relevan secara budaya, tepat di zamannya

Ketika The Guardian menyebut Sinners sebagai "film yang paling relevan secara budaya tahun ini," penilaian itu tidak hanya bertumpu pada latar era Jim Crow atau kemarahan historis yang eksplisit. Kekuatan Sinners justru terletak pada cara Coogler memperluas perspektif tentang penindasan, tidak semata dari sudut pandang kulit hitam Amerika, tetapi juga melalui figur-figur pinggiran lain.
Di sinilah POV Remmick menjadi penting. Sebagai karakter keturunan Irlandia, Remmick membawa ingatan kolektif tentang bagaimana orang Irlandia juga pernah diposisikan sebagai "ras kelas dua" di dunia Anglo-Saxon.. Sinners dengan cerdas memanfaatkan irisan sejarah ini untuk menunjukkan bahwa rasisme bukan pengalaman tunggal, melainkan sistem hierarkis yang selalu membutuhkan kelompok untuk diinjak.
Namun film ini tidak menyederhanakan penderitaan sebagai kompetisi. Remmick tidak ditempatkan untuk "menyamai" penderitaan kulit hitam, melainkan untuk menunjukkan bagaimana orang-orang yang pernah tertindas bisa memilih dua jalan: membangun solidaritas, atau justru ikut menopang sistem penindasan demi rasa aman semu.
Film ini terasa seperti cermin yang dipoles rapi: memantulkan masa lalu sekaligus memaksa kita menatap masa kini. Relevansi inilah yang kerap dicari Oscar, dan Sinners menyajikannya tanpa kompromi artistik.
5. Original IP yang menantang dominasi blockbuster

Di era di mana Oscar kerap dituduh condong ke "prestise aman" atau waralaba besar, keberhasilan Sinners sebagai IP orisinal terasa hampir subversif. Dengan bujet sekitar 90–100 juta dolar AS dan pendapatan 368 juta dolar AS, film ini membuktikan bahwa penonton global masih lapar akan cerita baru, asal disampaikan dengan visi yang jelas.
Kesuksesan ini penting bukan hanya secara industri, tetapi juga simbolik. Sinners tidak bersandar pada nostalgia. Ia tidak mengadaptasi properti terkenal, dan tidak menjanjikan sekuel instan. Ia berdiri di atas kepercayaan pada penonton, bahwa audiens mampu mengikuti cerita kompleks, tema berat, dan struktur yang tidak selalu memanjakan.
Sinners bukan sekadar film bagus. Ia adalah pernyataan bahwa sinema orisinal masih relevan, laku, dan layak dirayakan. Dalam konteks rekor nominasi, pencapaian ini terasa seperti validasi kolektif bagi keberanian kreatif yang jarang diberi ruang sebesar ini. 16 nominasi Oscar adalah harga yang pantas didapatkan oleh film ini.
Singkatnya, Sinners mendapat banyak nominasi Oscar karena sukses menyatukan semuanya. Mulai dari akting, adegan ikonik, inovasi teknis, relevansi budaya, hingga keberanian IP orisinal. Jika ada film yang pantas memecahkan rekor nominasi Oscar tahun ini, jawabannya jelas: Sinners.