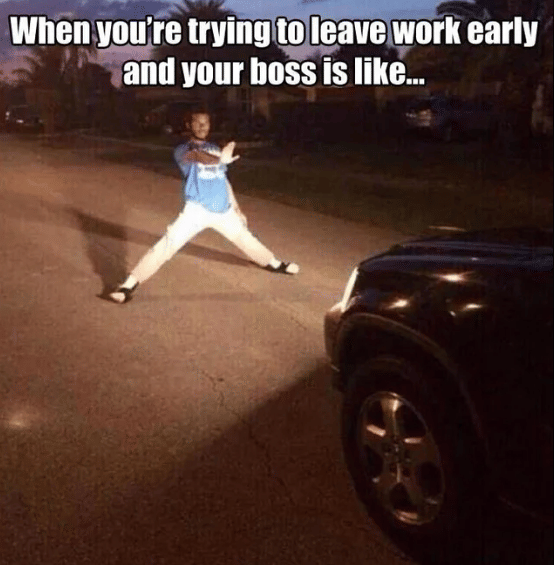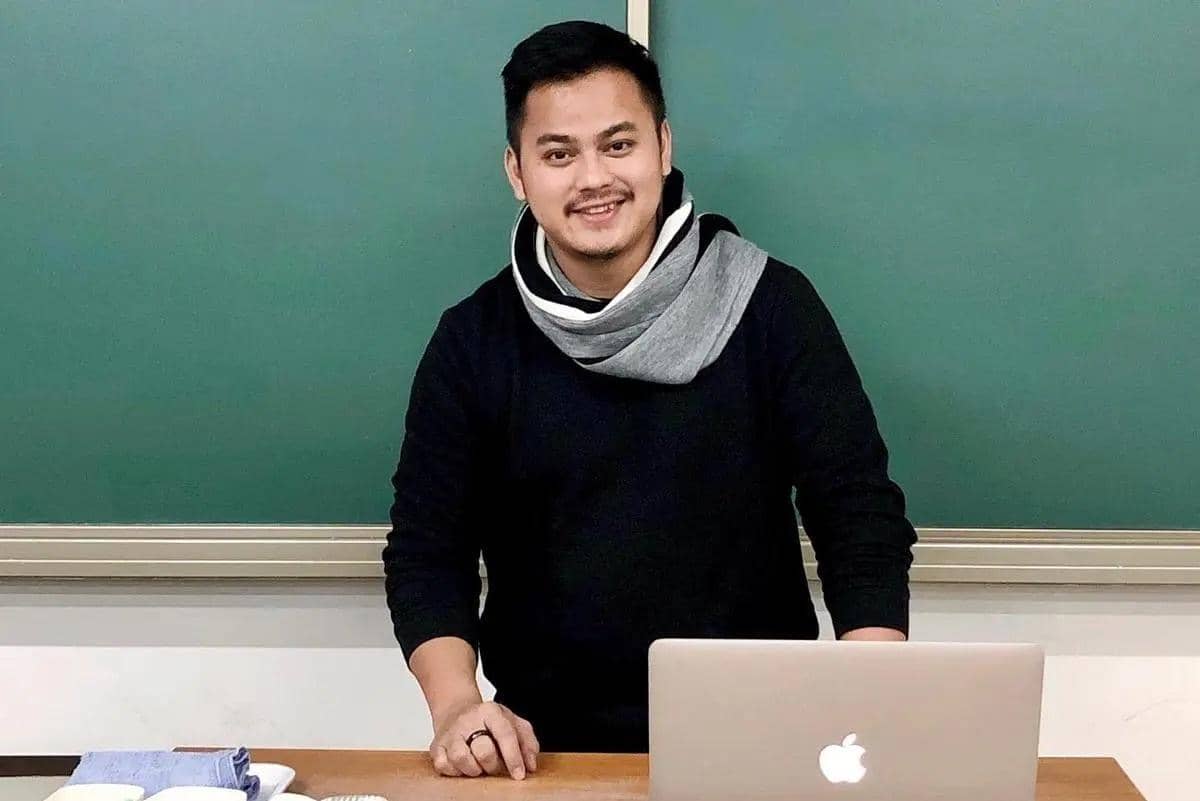Final Destination: Bloodlines, ketika Satu Keluarga Jadi Sasaran Maut

- Final Destination: Bloodlines berhasil membangun reputasi waralaba dengan rating tertinggi, 95% di Rotten Tomatoes.
- Kisah tentang mimpi yang menghantui sang protagonis membawa penonton pada perjalanan mencari jawaban di kampung halamannya.
- Bloodlines menyegarkan formula Final Destination dengan fokus pada dinamika keluarga inti, namun drama keluarga terasa kurang menyatu dengan tone filmnya yang cukup fun.
Awalnya ditulis sebagai episode serial legendaris The X-Files, Final Destination berkembang menjadi salah satu waralaba horor paling ikonis. Formula uniknya—tentang maut tak kasat mata yang memburu para penyintas kecelakaan tragis—menjadi ciri khas yang sulit dilupakan para penggemarnya. Lima film yang dirilis antara 2000—2011 berhasil membangun reputasi franchise ini sebagai pemicu paranoia paling efektif dari hal-hal sehari-hari.
Setelah vakum selama 14 tahun sejak Final Destination 5, waralaba ini akhirnya kembali lewat film terbarunya, Final Destination: Bloodlines, yang tayang di bioskop Indonesia sejak Rabu (14/5/2025). Film keenam ini membawa penyegaran lewat kisah tentang satu keluarga yang harus berjuang bertahan hidup dari kejaran maut. Tak disangka, pendekatan baru ini berbuah manis, terbukti dari pencapaiannya sebagai film Final Destination dengan rating tertinggi, yaitu 95 persen, di Rotten Tomatoes.
Penantian panjang tersebut tampaknya terbayar lunas dengan hadirnya Final Destination: Bloodlines yang dipuji banyak kritikus berkat eksekusi adegan kematiannya yang brilian dan sentuhan emosional yang tak terduga. Jadi, apakah Bloodlines benar-benar berhasil menghidupkan kembali franchise ini dengan gemilang? Untuk mengetahuinya, yuk, simak review film Final Destination: Bloodlines berikut ini!
1. Semua berawal dari mimpi yang mengerikan

Kata orang mimpi adalah bunga tidur. Namun, hal tersebut tampaknya tak berlaku bagi sang protagonis, Stefani Reyes (Kaitlyn Santa Juana). Selama berbulan-bulan, mahasiswi ini dihantui mimpi yang selalu sama: seorang gadis pirang bernama Iris (Brec Bassinger) bersama kekasihnya naik ke restoran menara pencakar langit Skyview pada 1968. Dalam mimpinya, menara itu hancur dalam kecelakaan mengerikan dan menewaskan seluruh pengunjungnya.
Yang mengejutkan, Iris bukanlah sosok asing. Ia adalah nama nenek Stefani yang keberadaannya entah di mana dan dianggap tak waras oleh keluarganya. Penasaran dan merasa ada sesuatu yang lebih besar di balik mimpi tersebut, Stefani memutuskan pulang ke kampung halamannya demi mencari jawaban.
Setibanya di rumah, Stefani disambut oleh ayahnya dan saudara laki-lakinya yang telah lama terpisah, Charlie (Teo Briones). Keduanya kemudian membawanya mengunjungi pamannya, Howard (Alex Zahara), dan keluarga besarnya. Ketegangan mulai muncul ketika Stefani menanyakan tentang Iris, dan perlahan misteri masa lalu keluarganya pun mulai terungkap satu per satu, termasuk bagaimana kegilaan Iris menyebabkan Darlene (Rya Kihlstedt), ibu Stefani dan Charlie, pergi meninggalkan mereka.
Dari surat-surat yang diberikan bibinya, Stefani akhirnya menemukan keberadaan Iris (Gabrielle Rose) yang ternyata tinggal di sebuah kabin terpencil di tengah hutan. Saat mereka bertemu, Iris mengungkapkan kebenaran mengejutkan bahwa ia pernah menggagalkan rencana kematian dengan menyelamatkan para tamu restoran setelah menerima "penglihatan" mengerikan. Dan kini, kematian pun datang untuk menuntut balas kepada mereka yang seharusnya tak pernah hidup.
2. Selipkan drama keluarga di tengah teror, efektifkah?

Selama ini, waralaba Final Destination dikenal lewat formula di mana sekelompok orang asing yang selamat dari bencana maut kemudian harus bekerja sama melawan takdir kematian. Seperti yang disinggung di atas, Final Destination: Bloodlines mencoba menyegarkan formula tersebut dengan mengalihkan sorotan utama pada dinamika sebuah keluarga inti. Tentu saja, saat fokusnya beralih ke hubungan darah, drama di antara mereka menjadi elemen sentral yang tak bisa dihindari dalam narasi.
Namun, kehadiran drama keluarga ini bak pisau bermata dua. Di satu sisi, ia berhasil membuat Bloodlines terasa lebih membumi dibanding pendahulunya. Menyoroti interaksi antara saudara kandung atau hubungan kompleks ibu dan anak memberi lapisan emosi yang lebih personal pada cerita. Alhasil, motivasi mereka untuk berjuang saling menyelamatkan satu sama lain di tengah ancaman kematian terasa jauh lebih meyakinkan.
Sayangnya, di sisi lain, paparan drama keluarga ini terasa kurang menyatu dengan tone filmnya yang secara mengejutkan cukup fun. Intensitas emosi yang seharusnya menguras air mata malah tenggelam dalam kekacauan ritme film yang serbacepat. Akibatnya, bagi sebagian penonton, bobot drama tersebut mungkin terasa kurang maksimal dalam menyentuh sisi emosional mereka.
Bicara soal sisi fun, Bloodlines memang tak ragu menyuntikkan elemen komedi. Sorotan utama jatuh pada Richard Harmon sebagai Erik, salah satu sepupu Stefani, yang menjadi comic relief dengan tingkahnya yang seenaknya sendiri dan celetukan kocaknya yang seolah mengolok-olok pakem franchise ini. Meski demikian, tentu saja kita semua tahu, dalam semesta Final Destination, karakter sekarismatik apa pun tak pernah benar-benar bisa "menang" melawan rancangan kematian yang keji.
3. Gore tetap jadi juara dalam Final Destination: Bloodlines

Selain selipan drama keluarga dan komedi, hal lain yang patut diapresiasi dari Final Destination: Bloodlines adalah kesediaannya untuk menyelami mitologi waralaba ini lebih dalam. Setelah memaparkan kisah Iris yang menjadi sumber dari semuanya, film ini tak hanya menyajikan aksi para keturunan Iris yang pontang-panting menghindari takdir. Sebaliknya, penonton justru diajak memahami logika kerja sang maut, dari aturan tak tertulisnya sampai celah-celah kemungkinan untuk lolos.
Kehadiran kembali Tony Todd sebagai William Bludworth, yang meski singkat, juga menjadi salah satu momen yang mencuri perhatian dalam film ini. Selain sebagai penghormatan pasca-kepergiannya, Bludworth menjadi kunci penting dalam merangkai benang merah dari semua film Final Destination. Lewat dialognya yang puitis dan penuh teka-teki, ia memberi clue yang memuaskan bagi penggemar lama maupun baru.
Seiring mitologinya dipaparkan dengan cerdas, duo sutradaranya, Zach Lipovsky dan Adam Stein (Freaks, Kim Possible), juga semakin leluasa menampilkan kreativitas dalam eksekusi kematian. Mulai dari insiden "sederhana" seperti kaki yang tertusuk pecahan kaca hingga skenario yang jauh lebih "rumit" seperti adegan yang melibatkan mesin MRI. Dengan timing dan sudut pengambilan gambar yang efektif, setiap kematian karakter tersaji secara brutal dan meninggalkan dampak.
Tak bisa dimungkiri, efek visual juga menjadi fondasi penting yang menopang seluruh keseruan "berdarah" dalam Bloodlines. Coba perhatikan bagaimana film ini membuka dan menutup kisahnya dalam skala yang luar biasa besar. Mungkin terlihat "over-the-top" atau berlebihan, tapi bukankah sensasi gore yang absurd, tapi menghibur inilah yang selalu dirindukan dari sebuah film Final Destination?
4. Apa yang akan terjadi di Final Destination 7?

Hingga kini, pembuatan Final Destination 7 memang belum dikonfirmasi secara resmi oleh New Line Cinema, selaku studio di balik waralaba ini. Namun, setelah keberhasilan Final Destination: Bloodlines yang mendapat respons positif dari penggemar dan kritikus, harapan untuk kelanjutannya tentu semakin besar. Apalagi film keenam ini bukan hanya menyajikan nostalgia, tetapi juga berhasil memperluas mitologi dengan elegan.
Jika penulis boleh berspekulasi, banyak kemungkinan menarik yang bisa digali untuk film ketujuh. Salah satunya adalah menghadirkan kembali Kimberly Corman (A. J. Cook), karakter dari Final Destination 2 (2003) yang masih bertahan hidup setelah berhasil mencurangi kematian. Ia selama ini menjadi ikon survivor paling misterius karena kisahnya belum benar-benar ditutup secara tuntas.
New Line Cinema juga bisa saja menggali semesta Final Destination lebih dalam melalui spin-off yang diangkat dari novelnya. Pilihan sumber cerita melimpah, termasuk novel Dead Reckoning yang menyoroti penyintas keruntuhan klub malam, atau Looks Could Kill yang mengisahkan model yang bekerja sama dengan kematian demi mengembalikan wajahnya. Tak hanya seru, kisah-kisah ini juga memberikan sudut pandang baru soal bagaimana manusia merespons takdir yang mengintai.
Lebih seru lagi jika New Line Cinema memilih meluaskan mitologi dari Bloodlines dan menyuguhkan kisah penglihatan awal lainnya yang tak kalah kelam dari insiden Skyview. Asumsi bahwa protagonis dari tiap film Final Destination adalah keturunan dari para pengunjung gedung pencakar langit di era 60-an membuka peluang narasi yang lebih masif dan terkoneksi. Bisa jadi, setelah "lingkaran Iris", akan ada "lingkaran" lainnya yang memicu siklus kematian dalam skala global!
Final Destination: Bloodlines membuktikan bahwa formula horor ikonis ini masih punya taring setelah sekian lama vakum. Perpaduan cerdas antara drama keluarga yang bikin haru, walau kurang maksimal, dengan adegan kematian over-the-top yang bikin meringis, ditambah penggalian mitologi yang lebih mendalam, sukses diracik jadi tontonan yang brutal sekaligus menghibur.
Jika ini adalah awal dari babak baru, maka "kematian" tampaknya belum selesai menulis takdirnya. Kini, pertanyaannya, siapkah kamu bertemu dengannya lagi di babak berikutnya?