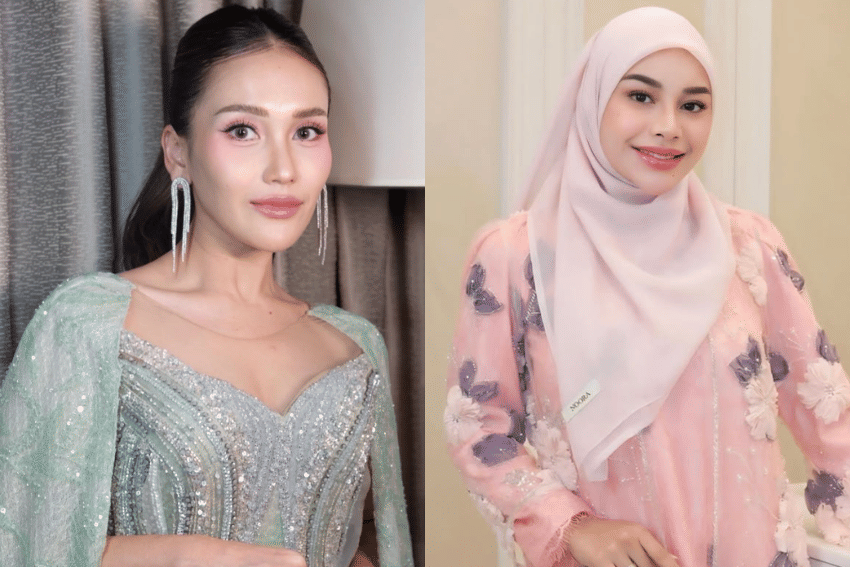Review Film Frankenstein (2025), Kisah Sang Monster yang Manusiawi

Membuat film memang tidak mudah. Namun, membuat film berdasarkan novel klasik yang sudah diadaptasi berkali-kali jauh lebih sulit. Lewat Frankenstein (2025), Guillermo del Toro membuktikan bahwa masih ada cara lain untuk menafsirkan kisah tentang penciptaan, kehilangan, dan kemanusiaan. Setelah mondar-mandir di festival film dan tayang terbatas di bioskop Amerika Serikat, Frankenstein akhirnya tayang di Netflix pada Jumat, 7 November 2025,
Dibintangi Oscar Isaac, Jacob Elordi, Mia Goth, dan Christoph Waltz, film ini membawa kisah sang monster ikonik yang tak hanya mengerikan, tapi juga menyentuh dan manusiawi. Sebagai seorang sineas yang selalu menemukan keindahan di tengah kegelapan, Del Toro kembali menunjukkan empatinya terhadap makhluk yang dianggap "asing" oleh dunia. Lalu, apa saja kelebihan dan kekurangannya? Mari simak ulasannya di bawah!
1. Sebuah adaptasi jujur dari novel Mary Shelley

Frankenstein versi Guillermo del Toro mengambil latar pada tahun 1857, dimulai dengan kisah Kapten Anderson (Lars Mikkelsen) yang menemukan Victor Frankenstein (Oscar Isaac) dalam keadaan sekarat di tengah badai Arktik. Namun, Victor tidak sendirian. Saat itu, ia tengah diburu oleh makhluk menyeramkan hasil ciptaannya sendiri (Jacob Elordi).
Melalui serangkaian kilas balik, penonton dibawa menyelami kisah perjalanan Victor, seorang ilmuwan ambisius yang terobsesi menaklukkan kematian setelah kehilangan ibunya. Obsesi itu mendorongnya melakukan eksperimen terlarang hingga akhirnya menciptakan "makhluk hidup" dari potongan tubuh manusia.
Sutradara yang akrab dipanggil GDT itu pun dengan cermat menghidupkan kembali semangat novel Mary Shelley. Ia membawa kisah tentang bermain Tuhan, tentang batas tipis antara cinta dan keangkuhan, antara hidup dan mati. Tidak, GDT tidak menakuti kita dengan teror berdarah atau jumpscare, melainkan dengan refleksi eksistensial: apa artinya menjadi manusia?
2. Penampilan memikat Jacob Elordi sebagai sang "monster"

Awalnya, peran makhluk ciptaan Victor Frankenstein ini hampir dimainkan oleh Andrew Garfield. Namun karena bentrokan jadwal, peran itu akhirnya jatuh ke tangan Jacob Elordi (Saltburn, Euphoria). Banyak yang meragukan kemampuan Elordi untuk menghidupkan sosok monster ikonik ini, hingga filmnya tayang.
Di luar dugaan, Elordi memberikan penampilan yang luar biasa sebagai Monster Frankenstein. Sosoknya tinggi menjulang tapi rapuh, brutal namun lembut. Ia sukses menampilkan monster yang baru lahir ke dunia. Ia belajar membaca, mencintai, dan bertanya siapa dirinya sebenarnya. Semuanya disampaikan dengan mimik dan gerak-gerik yang alami.
Chemistry-nya dengan Oscar Isaac pun begitu kuat. Hubungan mereka mencerminkan dinamika "ayah dan anak" yang penuh luka. Victor yang haus kontrol menciptakan kehidupan, tapi menolak untuk mencintai ciptaannya. GDT mengeksekusi hubungan ini sebagai bentuk daddy issues tragis yang membuat sang monster akhirnya menentang sang pencipta.
Adegan-adegan kecil, seperti saat sang monster mengelus tikus atau membaca kisah Adam dan Hawa bersama pria buta (David Bradley), menunjukkan sisi manusiawinya. Di sini, karakter Elordi benar-benar bersinar. Ia bukanlah monster, melainkan cermin dari kemurnian jiwa manusia.
3. Sinematografi dan scoring yang memanjakan indra

Secara visual, Frankenstein adalah salah satu karya terindah GDT. Sinematografer Dan Laustsen, yang sudah bekerja sama dalam Crimson Peak (2015), The Shape of Water (2017), dan Nightmare Alley (2021), kembali menyajikan visual yang magis. Permainan cahaya dan bayangan yang dramatis, warna hijau toska dan oranye yang membakar layar, serta tekstur detail dari setiap set periode Victoria terasa nyata.
Setiap bingkai terasa seperti lukisan gelap yang hidup. Dari laboratorium Victor yang remang-remang hingga lanskap bersalju di kutub utara, film ini menunjukkan kemewahan visual yang memukau. Tak ketinggalan, musik garapan Alexandre Desplat memberikan harmoni indah yang memperkuat emosi di setiap adegan. Scoring-nya terasa lembut, menghantui, sekaligus megah.
Berdurasi hampir 150 menit, tempo film terasa lambat di paruh kedua, tepatnya ketika fokus bergeser dari Victor ke makhluk ciptaannya. Namun, transisi ini justru memperdalam makna cerita ini: dari sains dan kesombongan manusia menuju pencarian eksistensi dan penerimaan diri.
4. Apakah Frankenstein (2025) recommended untuk ditonton?

Jawabannya sangat direkomendasikan, terutama bagimu yang menyukai drama filosofis dengan visual apik. Namun, jangan berharap film ini akan menakut-nakutimu seperti film GDT sebelumnya. Frankenstein versinya lebih berfokus pada drama eksistensial yang menyayat hati. Ia menampilkan monster bukan sebagai makhluk buas, tapi sebagai simbol kesepian, cinta, dan penolakan manusia di sekitarnya.
Dengan anggaran cukup besar, yang mencapai 120 juta dolar AS, film ini menjadi salah satu produksi Netflix paling megah tahun ini. Namun di balik megahnya visual dan efek prostetik yang dipakai GDT, kekuatan sejati Frankenstein justru ada pada pesan moralnya, bahwa terkadang makhluk yang disebut "monster" bisa jauh lebih manusiawi daripada penciptanya.
Guillermo del Toro sekali lagi berhasil mengisahkan dongeng kelam nan indah, sebuah ode bagi kemanusiaan di tengah gempuran AI. Jika kamu mencari tontonan yang tak hanya menggugah mata tapi juga pikiran, Frankenstein (2025) jelas layak masuk watchlist-mu di Netflix.