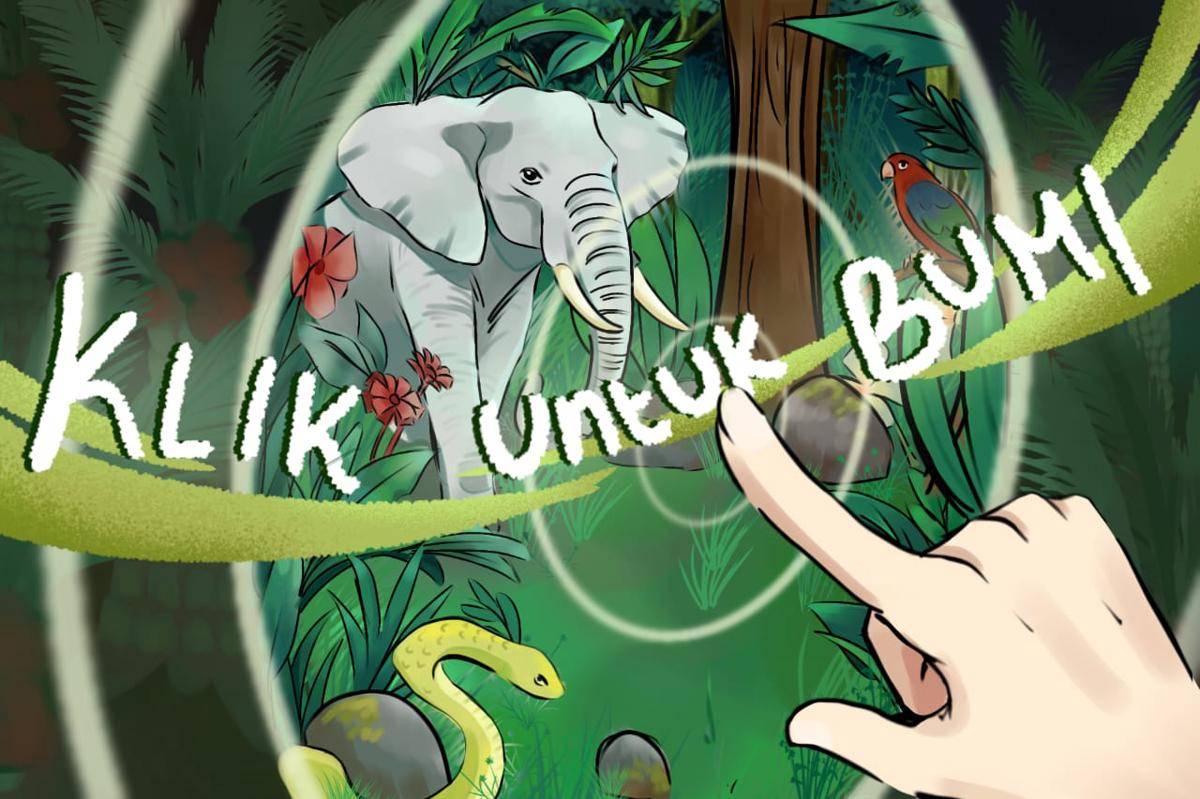IDN Times Xplore/Bumitra_SMAIT Al-Ittihad
Klik untuk Bumi: Generasi Muda Riau Lawan Sawit Lewat Edukasi dan Teknologi
Adat hidup memegang amanah
Tahu menjaga hutan dan tanah
Tahu menjaga bukit dan Lembah
(Tunjuk Ajar Melayu: Tenas Efendy)
Siapa yang tidak kenal kelapa sawit? Salah satu bahan baku industri yang berperan penting dalam perekonomian Indonesia. Namun, ada satu bayang hitam di balik ketenarannya sebagai duta perekonomian. Apakah itu?
Sawit sebagai komoditi ekspor Indonesia membutuhkan lahan penanaman yang luas. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 mencatat bahwa luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia mencapai 16,8 juta hektar. Angka yang fantastis jika dibandingkan dengan jumlah luas lahan tanaman perkebunan lain.
Pasalnya, kebutuhan akan lahan penanaman ini tentu tak akan tercukupi dengan area perkebunan biasa. Ke mana area tersebut diarahkan? Ya, sudah tentu hutan akan menjadi sasaran. Alih fungsi lahan hutan menjadi kebun sawit bukan cuma soal menggusur pohon tua. Ini tentang bagaimana satu ekosistem lengkap—yang seharusnya jadi rumah ribuan spesies, pengatur suhu, dan penyedia air bersih—dihancurkan dan diganti tanaman seragam. Dampaknya, perlahan kita akan menikmati punahnya keanekaragaman hayati, permasalahan udara, kualitas air yang buruk, dan permasalahan lingkungan lainnya.
Provinsi Riau dinobatkan sebagai daerah penyumbang sawit terbesar di Indonesia oleh BPS. Luas perkebunan kelapa sawit di Riau mencapai 2.741.621 hektar pada tahun 2021 dan produksinya mencapai 3.853.271 ton. Terbayang bagaimana tata kelola berhektar-hektar lahan ini. Sudah menjadi rahasia umum saat musim kemarau melanda, Riau menjadi daerah langganan kabut asap akibat aktivitas pembakaran lahan hutan. Uniknya, setelah proses tersebut mereda tumbuhlah tanaman-tanaman “asing” ini.
Kabut asap yang selalu datang di Riau kini seakan menjadi agenda. Seperti bukan hal yang aneh bahkan menjadi lumrah dianggap sebagai hal biasa. Bukan karena tidak pedauli, tetapi seperti sudah pasrah dengan kondisi. Semuanya terjadi perlahan, cara kita memandang alam ikut berubah. Kita terbiasa melihat sawit sebagai hal yang normal. Padahal, kebiasaan keliru bisa jadi akar krisis besar. Dan saat kerusakan dianggap wajar, di situlah bencana tumbuh dalam diam.
1. Ketergantungan pada Sawit: Antara Ekonomi dan Lingkungan
Sawit ibarat dua sisi mata uang: di satu sisi, ia jadi penyambung hidup banyak orang. Tapi di sisi lain, ia juga meninggalkan luka dalam bagi alam. Di Riau, sawit bukan cuma tanaman. Ia adalah tumpuan hidup ribuan orang. Tapi yang sering terlupa, sawit bisa tumbuh karena hutan yang ditebang. Artinya, sawit berdiri di atas jejak kehancuran.
Data dari WALHI Sumatera mencatat bahwa sepanjang 2023, sekitar 20 ribu hektare hutan di Riau lenyap. Ini baru masalah angka. Di baliknya ada pohon tumbang, sungai mengering, udara makin sesak, dan wilayah adat yang tergusur demi ekspansi industri.
Hampir 57% wilayah daratan Riau kini dikuasai industri dan perkebunan. Sawit jadi aktor utama. Bahkan ekspansi ini udah masuk ke kawasan yang seharusnya dilindungi. Dampaknya bukan cuma pohon yang hilang, tapi sistem ekologis yang rusak: air sulit diserap tanah, suhu makin ekstrem, dan hewan langka seperti harimau Sumatra serta gajah kehilangan habitatnya.
Fakta lebih jauh, sawit termasuk tanaman monokultur—artinya, cuma satu jenis tanaman hidup di area luas. Sawit membutuhkan banyak air, menyerap nutrisi, dan menyingkirkan tumbuhan lain. Akibatnya, tanah jadi tandus, air tanah surut, dan keanekaragaman hayati menghilang. Dalam jangka panjang, ini bukan cuma krisis lingkungan, tapi juga ancaman terhadap ketahanan pangan dan akses air bersih.
Tapi semua ini nggak bisa dilihat hitam-putih. Nggak semua orang yang menanam sawit itu salah. Banyak masyarakat Riau menggantungkan hidup dari sawit karena nggak punya pilihan lain. Mereka butuh makan, membayar sekolah anak, dan bertahan hidup.
Oleh karena itu, tantangan kita sekarang bukan hanya soal “lawan atau dukung.” Tapi, bagaimana mencari jalan tengah—bagaimana caranya tetap mendukung warga tanpa merusak alam. Solusi yang adil harus ada: bantu petani keluar dari ketergantungan tanpa meninggalkan jejak rusak pada lingkungan.
2. Menghadapi Tantangan: dari Pemahaman hingga Aksi Nyata
Masalah terbesar kita hari ini bukan karena kita tidak tahu, tapi karena kita belum memahami sepenuhnya. Kita lihat hutan terbakar, tapi berpikir itu karena cuaca. Saat melihat kabut asap, tanpa menyadari hasil pembakaran lahan. Ketika melihat kebun sawit, yang terpikir, “kan masih ijo.”
Padahal kenyataannya tak sesederhana itu. Hijaunya sawit masih menjadi misteri kelestarian alam. Tapi edukasi tentang sawit dan dampaknya sering kali disampaikan dengan cara yang terlalu teknis, berat, atau jauh dari kehidupan sehari-hari. Sedangkan yang kita butuh sekarang adalah edukasi yang relevan, mudah dicerna, dan sampai ke telinga anak muda dengan cata yang elegan.
Edukasi bisa datang dari mana aja: TikTok, thread X (Twitter), YouTube, atau obrolan santai di tongkrongan. Ketika kita paham, akan muncul kepedulian. Dan ketika peduli, kita akan bergerak. Tak perlu muluk-muluk. Mulai aja dari share info, bincang isu deforestasi di tongkrongan, atau tulis opini kecil di media sosial.
3. Teknologi: Senjata Digital Generasi Muda
Kita hidup di era digital. Satu unggahan bisa mengubah cara pandang ribuan orang. Karena itu, kami berkomitmen dengan membuat komunitas digital bertajuk Klik untuk Bumi—ruang edukatif di media sosial-- yang mengajak anak muda nggak hanya cuma tahu soal krisis lingkungan, tetapi juga aktif bersuara.
Lewat konten carousel, video pendek, dan storytelling yang gampang relate, kami tunjukin kalau isu sawit itu bukan sekadar soal “pro atau kontra.” Tapi tentang ketimpangan, kebijakan yang nggak adil, dan dampaknya buat generasi ke depan.
Media sosial tak hanya sebagai tempat viral-viralan. Tapi juga bisa jadi alat dorong perubahan. Kita bisa angkat suara soal kebijakan yang belum berpihak pada lingkungan, dukung petani yang mau beralih ke praktik berkelanjutan, atau membantu sounding program restorasi yang berdampak nyata. Dan yang paling penting: semua bisa terlibat. Nggak harus akademisi. Asalkan punya niat belajar dan nyali buat bersuara.