7 Rekomendasi Buku Nonfiksi untuk Pembaca Novel

Kamu salah satu pembaca yang kurang bisa menikmati buku nonfiksi? Coba, deh, sesekali keluar dari zona nyaman dan menantang diri. Bisa mulai dengan beberapa judul nonfiksi berikut. Memoar sampai kumpulan surat, semuanya emotif dan kaya deskripsi. Bakal bikin kamu terbawa dalam suasana sampai-sampai gak sadar kalau ini semua cerita nyata. Masih ragu? Elemen apa, sih, di tiap buku nonfiksi ini yang kiranya bisa memikat pecinta novel yang alergi buku self-help? Cari tahu lewat sinopsis dan ulasan singkatnya berikut!
1. Woman at Point Zero (Nawal As-Sa'dawi)
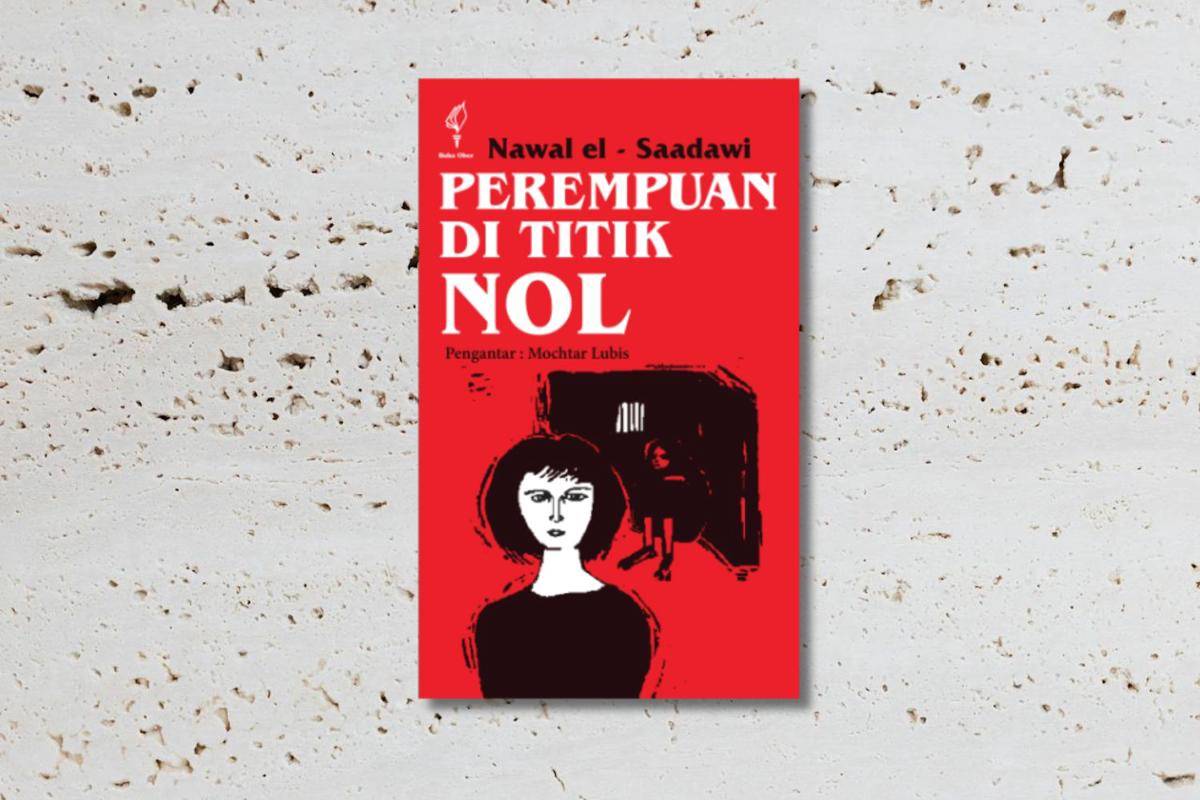
Woman at Point Zero atau yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul Perempuan Titik Nol sebenarnya adalah memoar yang ditulis wartawan perempuan Mesir. Bukan tentang dirinya, melainkan sosok bernama Firdaus, pekerja seks yang bakal menghadapi hukuman mati setelah terbukti membunuh muncikarinya. Ceritanya ditulis dengan kata ganti pertama oleh As-Sa’dawi yang membuat buku ini bak novel. Dengan gamblang Firdaus mengisahkan kisah hidupnya sekaligus proses sampai ia memutuskan untuk memonetisasi tubuhnya sendiri.
2. The Year of Magical Thinking (Joan Didion)
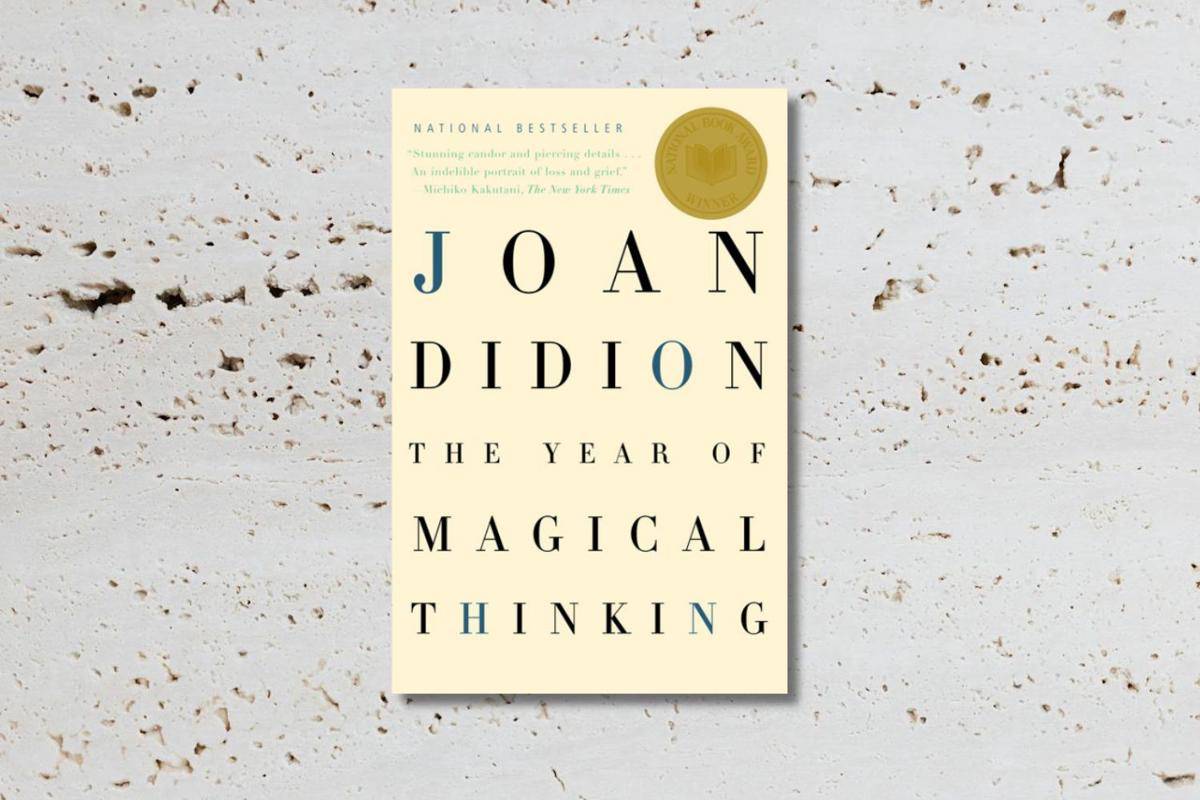
The Year of Magical Thinking berhasil bikin pembacanya merasa seperti dalam sebuah cerita fiksi. Bagaimana tidak, dalam waktu berdekatan, Didion harus menghadapi musibah bertubi-tubi. Dimulai dengan anaknya yang jatuh sakit, disusul kematian mendadak suaminya. Semua terjadi begitu cepat, bak film. Seolah tak ada waktu untuknya mencerna apa yang terjadi. Namun, tragedi itu pula yang mengubah pemikiran Joan Didion selamanya. Tak seperti memoar orang kelas atas yang biasanya tak menapak tanah, The Year of Magical Thinking cukup nyaman diikuti. Apa adanya hidup Didion yang memang datang dari kalangan atas Amerika Serikat.
3. Give Me My Father’s Body (Kenn Harper)
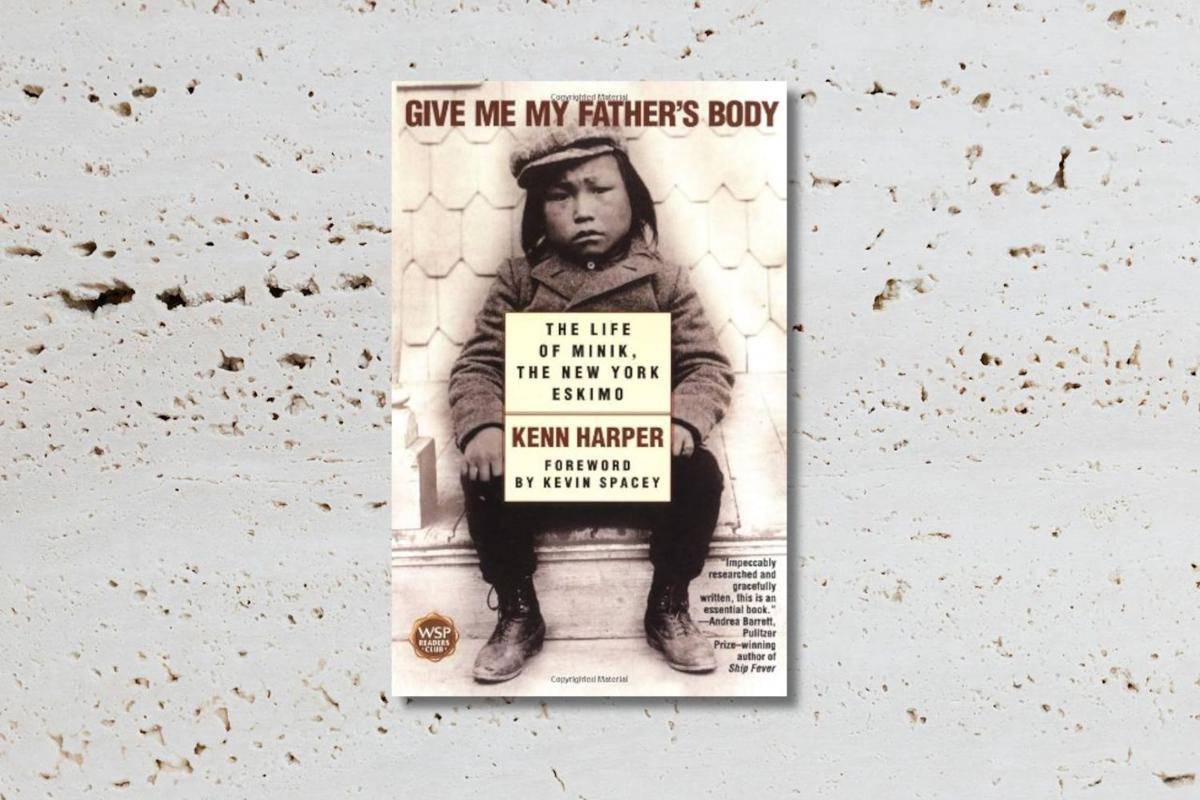
Give Me My Father’s Body adalah memoar lain yang sepertinya bakal bikin pembaca fiksi betah. Buku ini ditulis seorang pria Inuit yang dibawa bersama orangtuanya ke New York oleh seorang ilmuwan Amerika Serikat. Mereka dijadikan objek penelitian dan tontonan layaknya bukan manusia. Tanpa memikirkan kondisi biologis mereka yang biasa hidup di udara dingin ekstrem, banyak dari mereka yang jatuh sakit bahkan meninggal dunia di New York.
4. I’m Glad My Mom Died (Jennette McCurdy)
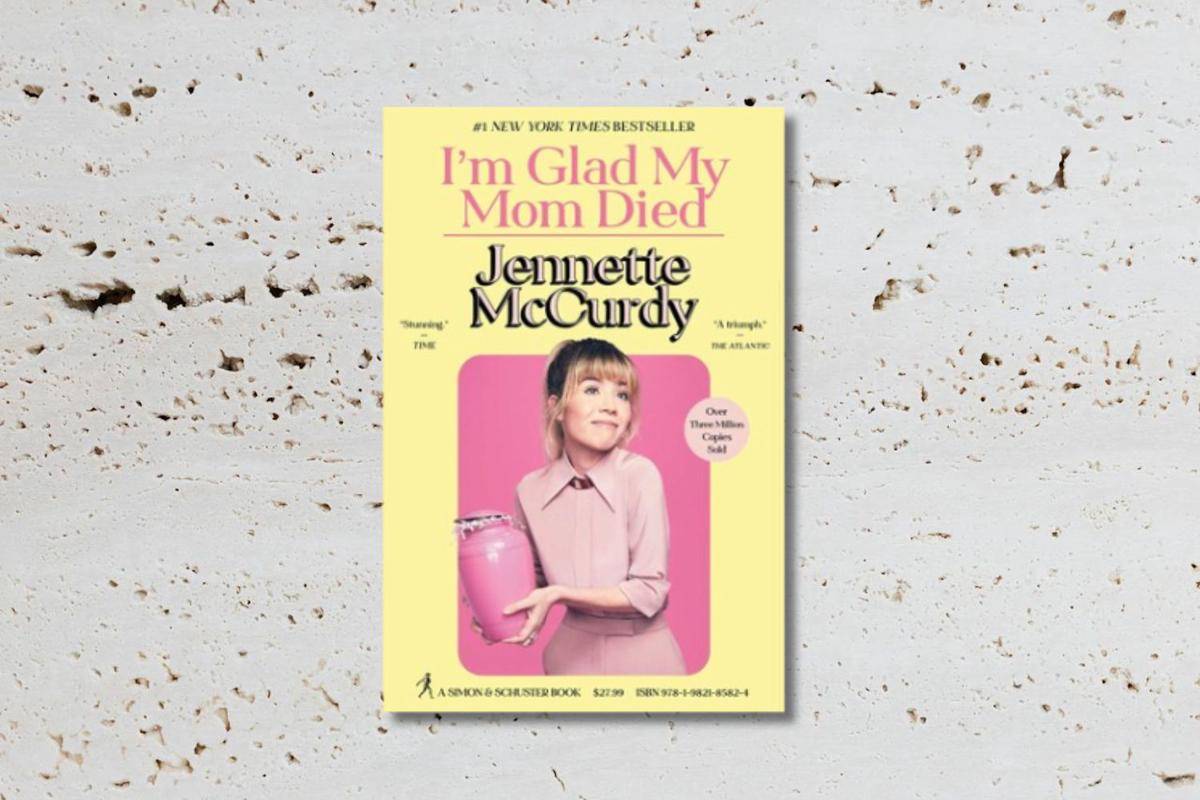
Jennette McCurdy adalah salah satu figur publik yang berhasil bikin memoar yang memikat. Memilih hengkang dari industri hiburan, McCurdy menjelaskan alasan kuat mengapa ia mengambil keputusan itu. Ternyata ada hubungan erat antara keputusannya dengan trauma yang ia alami selama ini. Bukan atas keinginan pribadinya, keterlibatannya jadi aktor cilik ternyata adalah ambisi sang ibu. Setelah ibunya meninggal, Jennette pun merasakan kelegaan yang mungkin dianggap aneh, tetapi bakal terasa wajar setelah kamu mendengar testimoninya di buku ini.
5. Letters to Young Poet (Rainer Maria Rilke)
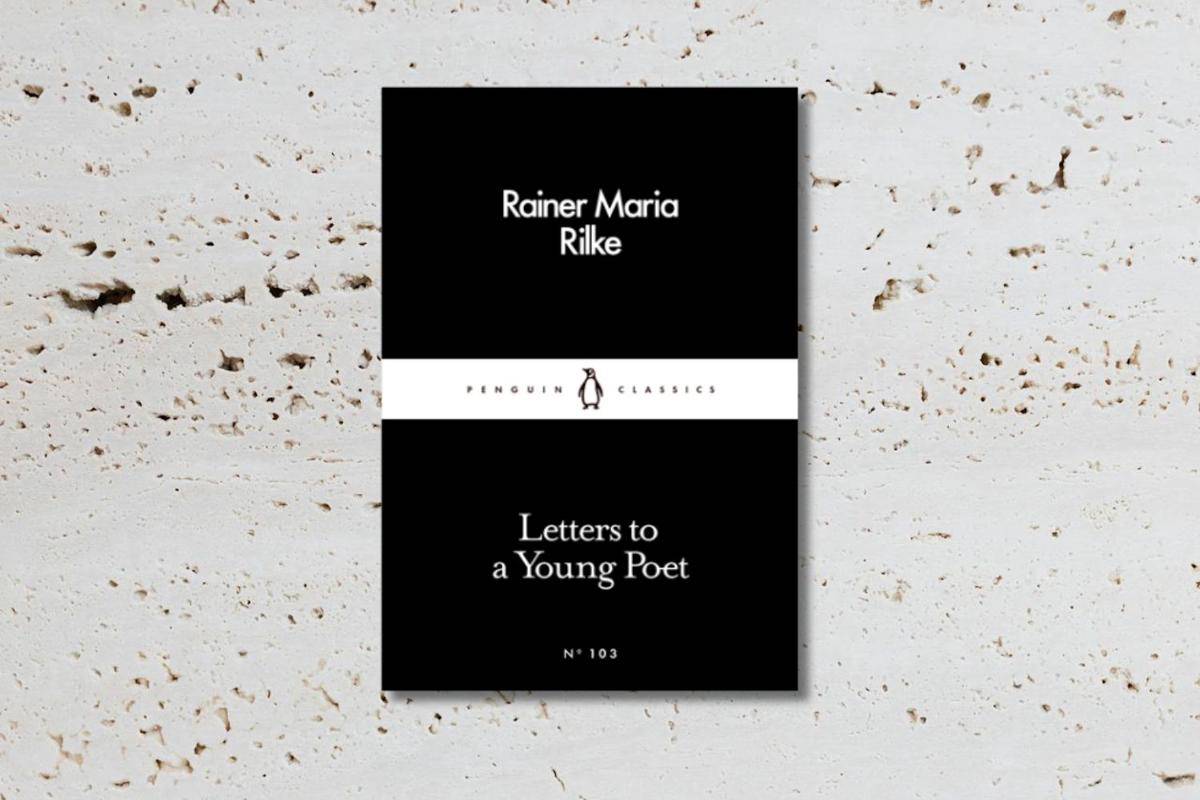
Tipis dan tak bertele-tele, buku nonfiksi ini adalah kumpulan surat yang ditulis penyair Austria Rilke untuk seorang tentara muda yang beraspirasi jadi seperti dirinya. Meski spesifik ditujukan untuk si perwira muda, secara umum surat-surat Rilke bisa dibaca siapa saja yang punya mimpi dan minat di bidang seni dan kepenulisan. Kamu yang biasa baca novel bakal terpukau dengan gaya penyampaian Rilke dan caranya memberi tips tanpa menggurui.
6. Cultish: The Language of Fanaticism (Amanda Montell)

Pembaca novel biasanya punya ketertarikan khusus di bidang bahasa. Cultish bisa jadi buku yang mengubah perspektifmu soal buku nonfiksi. Ia ditulis berdasar wawancara dan riset Amanda Montell dengan berbagai komunitas yang punya penggemar fanatik. Mulai dari komunitas agama, ideologi, sampai influencer. Ternyata ada pola yang bisa diamati dari mereka semua, yakni penggunaan jargon untuk memikat pengikut. Menariknya, hasil riset Montell ditulisnya seperti kumpulan cerpen.
7. The Monk Who Sold His Ferrari (Robin Sharma)
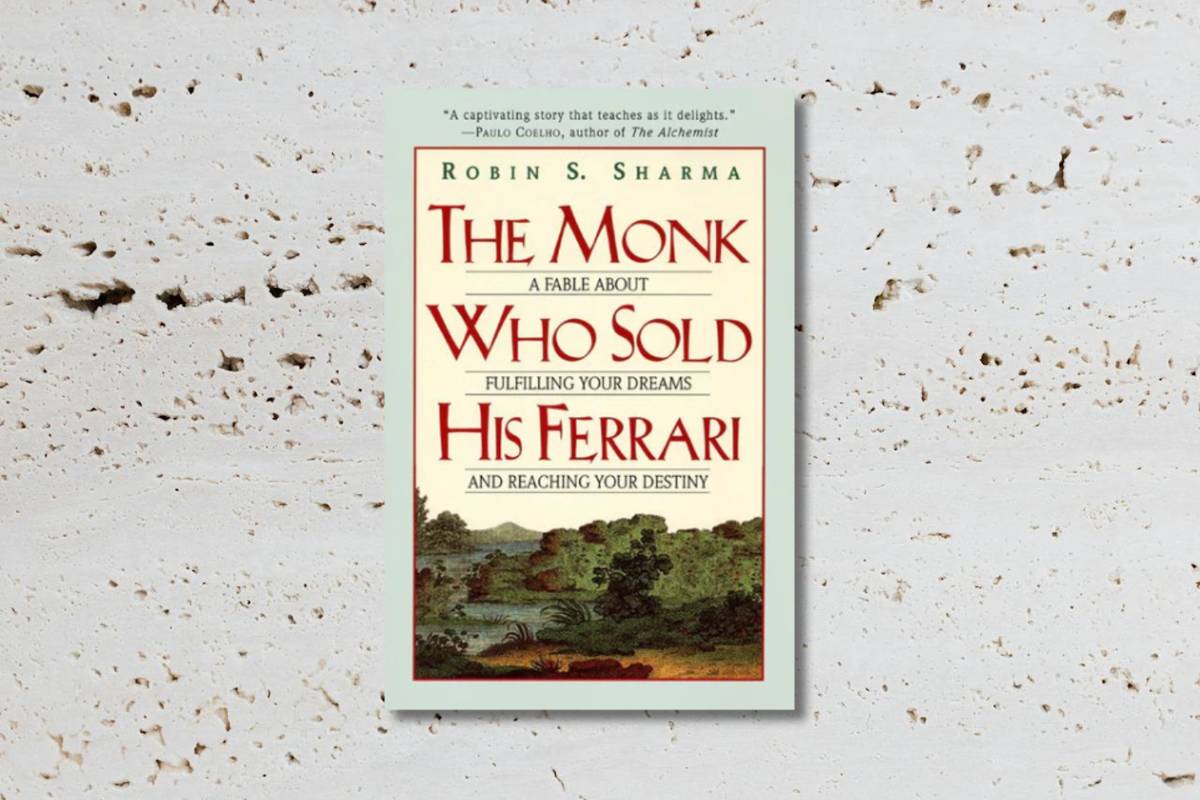
Robin Sharma adalah penulis buku-buku self-help. Namun, tidak seperti penulis nonfiksi yang saklek dan kadang terkesan menggurui, Sharma sering menyisipkan humor dan menggunakan bahasa sederhana untuk menyampaikan ide yang ia percaya. Lebih menarik lagi, dalam The Monk Who Sold His Ferrari, Sharma seperti mengajakmu masuk ke sebuah cerita fabel. Ada tokoh dan plot layaknya buku fiksi.
Lagi-lagi memilih bacaan itu hak prerogatif tiap orang dan pada akhirnya kamu bakal membangun preferensi spesifik sendiri. Namun, kalau ternyata kamu yang biasa baca novel ingin coba keluar dari zona nyaman, buku-buku nonfiksi tadi bisa, deh, jadi rujukan pertama. Siapa tahu ketagihan.













































