Ziarah Makam Leluhur saat Ramadan sebagai Amalan dari Sabda Nietzsche

Penghormatan kepada leluhur cukup lekat dengan budaya dan masyarakat Jawa. Masuknya Islam dalam sejarah rekonstruksi kepercayaan masyarakat Jawa pun tak membuat aktivitas tersebut ditinggalkan. Dewasa ini, kita masih bisa melihatnya dalam bentuk ziarah makam. Dari sudut pandang modern, budaya ini membuktikan bahwa akulturasi budaya yang terjadi mampu mengakomodir esensi dasar dari ziarah makam itu sendiri, yaitu menghormati leluhur.
Dalam skala ritus, aktivitas penghormatan leluhur itu masih bisa ditemui pada tradisi nyadran. Secara garis besar, tradisi yang masih populer tersebut menjadi salah satu sarana kolektif mendoakan leluhur yang telah meninggal dengan cara mengunjungi makam-makam. Perkembangan budaya akhirnya membuat tradisi turut memuat upacara-upacara adat dengan bumbu seni budaya yang lekat.
Jika diaplikasikan ke ranah lebih sempit dalam kehidupan bermasyarakat dan keluarga hari ini, masyarakat Jawa Timur dan sekitarnya mengenal aktivitas tersebut sebagai nyekar. Setidaknya, dalam ajaran turun-temurun keluarga saya, nyekar selalu dilakukan menjelang hari pertama Ramadan dan pada hari pertama Syawal dalam kalender Islam. Ritualnya pun lebih sederhana, yaitu membawakan bunga-bunga untuk ditabur sambil mengirimkan doa di makam-makam sanak saudara yang sudah berpulang.
Aktivitas nyekar ini sepertinya sudah saya lakukan sejak otak mulai bisa menyimpan memori karena memang sedari kecil sekali saya sudah dibiasakan untuk tidak melewatkan rutinitas tahunan ini. Makam pertama yang saya kunjungi dalam hidup adalah kuburan kakek. Letaknya ada di Kelurahan Mojolangu, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Beliau adalah bapaknya bapak saya, seorang masinis yang meninggal dunia ketika bapak saya masih berusia 18 tahun. Tentu saja saya tidak mengenal, apalagi mengingat, sosok beliau. Bahkan, mengetahui bagaimana parasnya saja saya tidak bisa karena tidak ada arsip foto tersimpan yang bisa diceritakan sebagai kenang-kenangan. Nukilan kisah hidupnya sesekali saya dengar ketika orang tua tengah menuturkan cerita-cerita masa lalu. Menariknya, bagaimana pun saya tidak mengenalinya, beliau tetaplah darah daging yang berperan dalam sejarah fisik soal bagaimana saya bisa ada di dunia.
Saat kecil itu, saya menemukan konsep penghormatan leluhur dengan cara berziarah makam seseorang yang tidak pernah saya kenali ini cukup unik. Apa yang ingin saya sampaikan dan doakan untuk kakek kalau saya tidak mengenalnya? Apakah selama hidupnya kakek adalah orang baik atau sebaliknya? Apa beliau membesarkan bapak saya dan memberi teladan cukup sebagai bekal yang diturunkan ke saya? Selain bunga yang dibeli oleh ibu, modal nyekar saya hanyalah hafalan surah Al-Fatihah yang belum genap. Sudah, itu saja.
Untuk ukuran kegiatan penghormatan kepada leluhur, modal cekak seperti itu terasa cukup menjengkelkan. Sudah tak pernah mengenal sosoknya selama hidup, saya tak tahu juga apa yang mau dibicarakan atau didoakan saat beliau sudah mati. Di sekolah pun seingat saya tak pernah ada pelajaran yang mengajarkan tentang hal ini.
Biar tak jengkel, tahun-tahun berikutnya saya ganti strategi. Kali ini, lebih baik saya saja sebagai yang masih hidup memperkenalkan dan mengisahkan diri ketika momen nyekar itu tiba. Mula-mula saya salam dan sapa kakek, lalu mulai monolog tentang apa saja yang telah saya lalui setahun ke belakang. Kemudian, selalu saya tutup dengan Al-Fatihah versi sudah lebih fasih plus bonus ayat kursi. Saya memberi hormat kepada beliau lewat kehidupan yang kini sedang saya miliki. Toh, intinya tetap sama-sama sebagai bentuk penghormatan.
Manusia sendiri adalah satu-satunya makhluk hidup yang mengenali konsep unik tentang kematian. Hewan tidak memiliki keistimewaan itu karena bagi mereka jasad hanyalah objek, bukan sisa-sisa kehidupan. Meski mungkin tampaknya memang ada beberapa mamalia yang secara biologis merasakan kehilangan dan kesedihan ketika ditinggalkan.
Nah, modal yang saya biasakan sejak kecil itu bikin saya sanggup memaknai momen nyekar sebagai sarana kontemplasi terbaik untuk mengingat mati dan menghidupi hidup sepenuhnya. Kalau kata Nietzsche, “fatum brutum amor fati” - tetap cintailah takdir meski takdir itu brutal. Apa yang saya percayai itu selaras dengan momentum waktu penghormatan dilaksanakan. Ia perlu ditunaikan sebelum bulan suci Ramadan sebagai pengingat bahwa kematian itu pasti. Leluhurmu adalah perantaramu untuk memaafkan diri sendiri sambil tetap mendoakan kehidupan menjadi lebih baik. Lalu, lakukan lagi ketika Hari Raya Idul Fitri tiba agar kamu tak lupa bahwa kehidupan ini adalah anugerah yang perlu dirayakan sepenuhnya.
Masalahnya, seiring tahun berganti, makam yang harus dikunjungi beranak menjadi lebih banyak dan lebih banyak lagi. Pada momen jelang Ramadan 2024 ini misalnya, saya perlu menemani ibu untuk mengunjungi deretan makam di tiga kecamatan berbeda! Beberapa di antara makam-makam itu mengukir memori indah semasa mereka hidup dalam sanubari. Ada sosok istimewa yang masih saya tangisi tiap kali menyapa sambil mengusap batu nisan berukirkan sebuah nama yang amat saya cintai. Ada juga yang patoknya sudah rusak sampai perlu menghabiskan waktu berputar-putar dulu di area kuburan sebelum makamnya berhasil ditemukan. Bahkan, ada yang dari ukiran nama pada batu nisan saja saya benar-benar tak tahu ia siapa. Eh, ternyata beliau adalah sahabat ibu semasa SMA. Ha!
Fakta itu sedikit banyak, kok, malah mendistorsi momen monolog indah ketika berziarah. Alih-alih berkontemplasi untuk mencapai makrifat, nyekar terasa makin menjadi rutinitas syariat yang sekadar bikin sungkan dan masygul kalau-kalau lupa ditunaikan. Gara-gara itu, saya jadi berpikir bahwa harusnya pertanyaan seperti berikut saja yang saya pikirkan saat kecil dulu, “Emangnya doa atau surah apa, sih, yang tepat dilafalkan ketika nyekar ke makam leluhur?”




























![[OPINI] Menakar Kelayakan Thomas Djiwandono Jadi Deputi BI](https://image.idntimes.com/post/20250115/sesi-1-sal02498-7b8580309183379b3c8eba91d7bc3c5b-273b07c328eb87f261cb80b9e2a0fd07_watermarked_idntimes-1.JPG)
![[OPINI] Apakah Perubahan Kemasan Produk Menjadi Saset Tanda Resesi?](https://image.idntimes.com/post/20260208/perubahan-ukuran-sachet-resesi-ekonomi_57b6ce7b-02bb-459b-b0d3-ce678054e335.JPG)
![[OPINI] Kenapa Tulisan yang Ditulis Sendiri Sering Dibilang Buatan AI?](https://image.idntimes.com/post/20260123/alasan-gak-semua-hal-layak-ditulis-menulis-berlebihan_d71a7bb9-f249-48fb-be75-26f38e13ac2f.jpeg)

![[OPINI] Relasi Epstein-Chomsky, dan Integritas Intelektual Kiri](https://image.idntimes.com/post/20260204/efta00003652-0_3909c293-079d-4870-ba54-8c60af9ef07b.jpg)
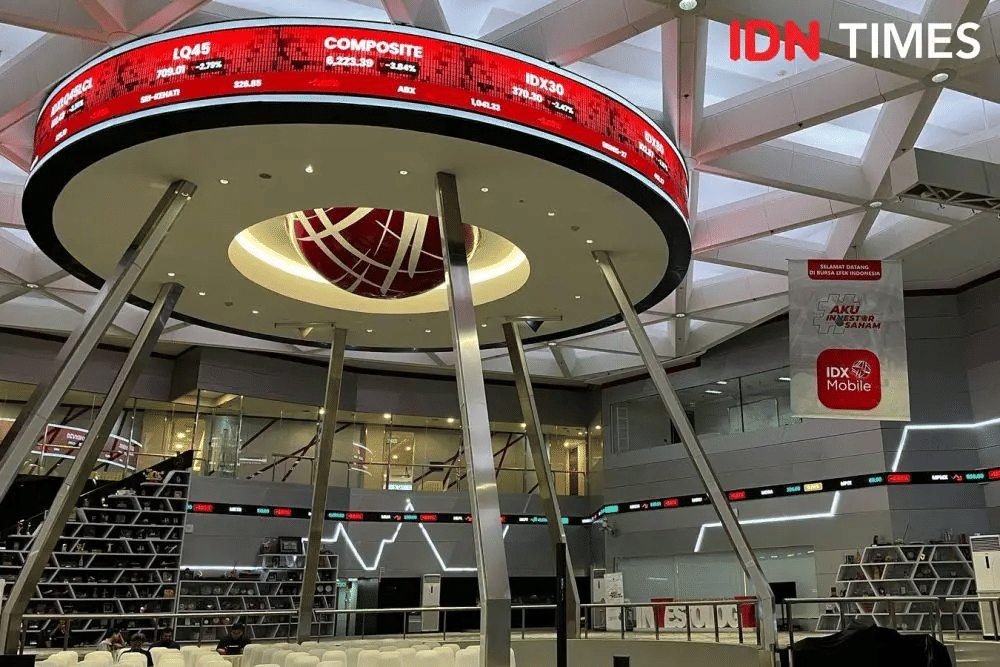


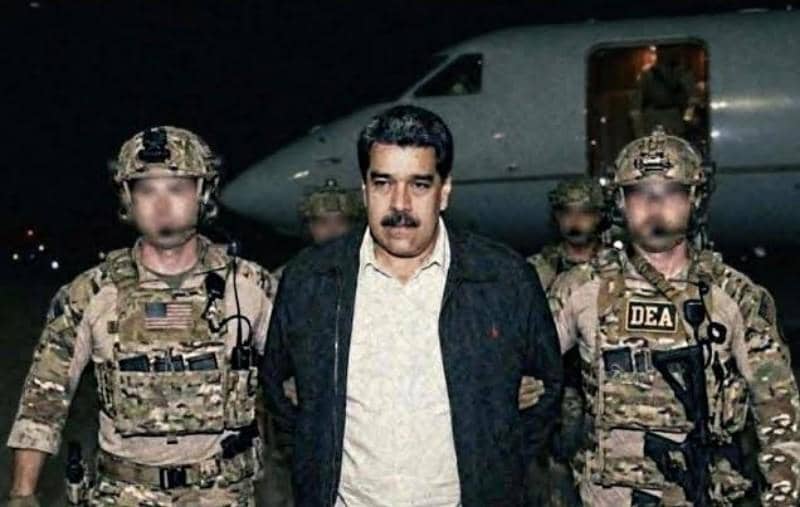


![[OPINI] Berhenti Berlindung di Balik Kalimat “Aku Orangnya Emang Begini”](https://image.idntimes.com/post/20251018/pexels-kampus-7555858_e0f0519c-fde0-4ab4-8965-0e12dabbd0b7.jpg)
![[OPINI] Peran Perempuan dalam Wujudkan Harmoni Sosial dan Lingkungan](https://image.idntimes.com/post/20250802/pexels-julia-m-cameron-8841582_4f4cbb51-bd42-46f6-ba78-fa42532e55a6.jpg)

![[OPINI] Setelah Chavez dan Castro: Ujian Revolusi Bolivarian](https://image.idntimes.com/post/20260108/upload_dd95bcd42f154a2960cdda3ed70e7109_4c8d29e1-0272-4459-9dbd-c40eeccc46c8.jpg)
![[OPINI] Nikah Muda: Alasan Kenapa Gak Semua Cerita Cinta Bisa Ditiru](https://image.idntimes.com/post/20260103/pexels-danu-hidayatur-rahman-1412074-2852135_2f19e731-6a9c-4db9-8adb-4642e15915d2.jpg)


