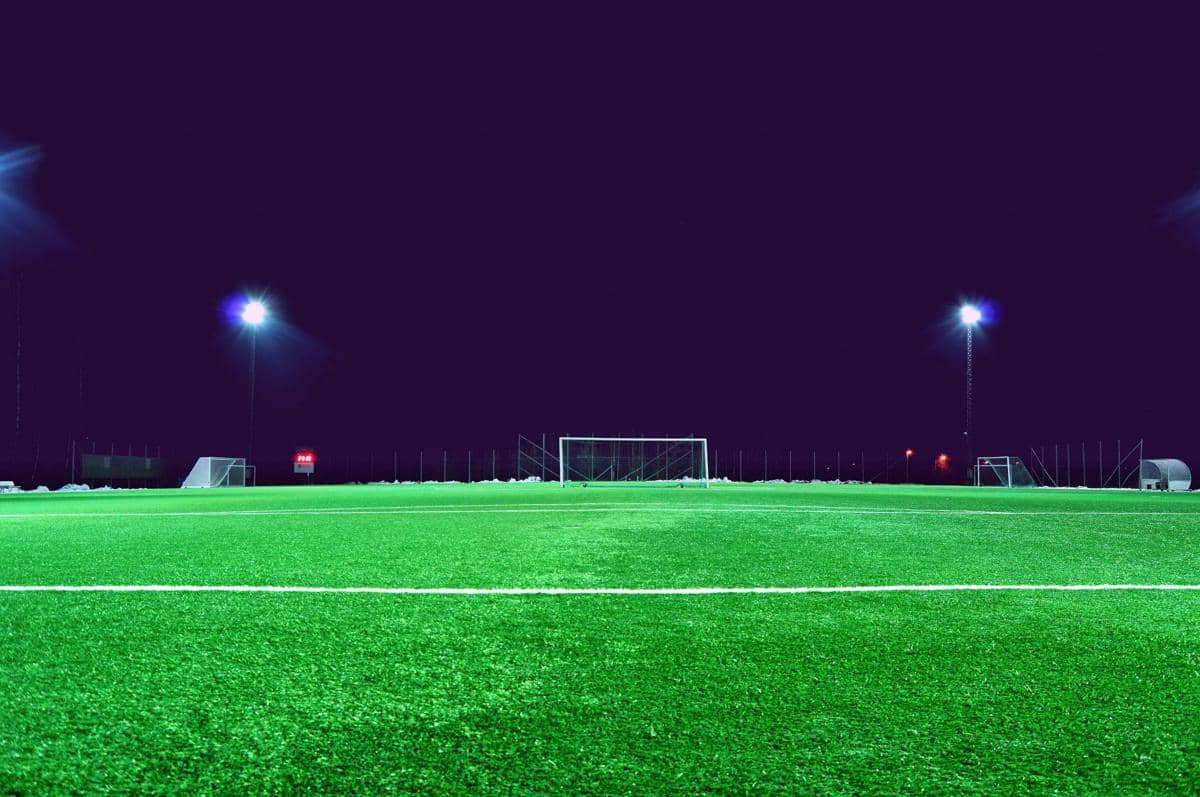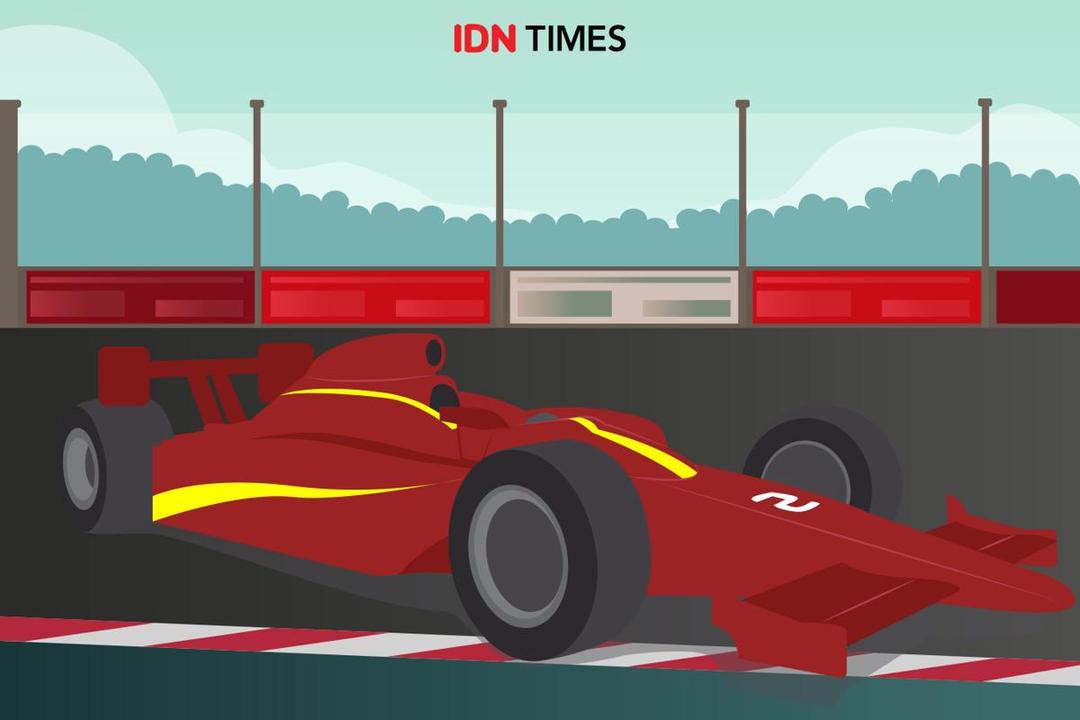Sejauh Mana Donald Trump Mempolitisasi Piala Dunia 2026?

Piala Dunia 2026 tinggal menghitung bulan, tetapi sudah menuai berbagai kritik. Selain soal harga tiket yang dianggap kelewat mahal, sorotan tajam juga mengarah pada meningkatnya irisan antara politik domestik Amerika Serikat dan turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut. Posisi Amerika Serikat selaku tuan rumah utama membuat kebijakan pemerintah federal sulit dipisahkan dari dinamika penyelenggaraan kompetisi.
Dalam hal ini, Donald Trump menjadi tokoh utama yang membuat campur tangan politik dalam Piala Dunia menguat. Orang nomor satu di Amerika Serikat ini seolah tak ingin melewatkan panggung olahraga internasional sebagai medium legitimasi kekuasaan, ruang pencitraan global, sekaligus perpanjangan dari agenda politik domestiknya. Lantas, sejauh mana Piala Dunia masih bisa dipertahankan sebagai ruang netral ketika ia dimanfaatkan sedemikian terbuka oleh kepentingan politik negara tuan rumah?
1. Larangan hadir terhadap suporter dari 12 negara menciderai nilai inklusivitas sepak bola
Kebijakan imigrasi Donald Trump menjadi salah satu titik krusial dalam politisasi Piala Dunia 2026. Pemerintah Amerika Serikat menerapkan larangan perjalanan terhadap 12 negara, termasuk bagi negara peserta seperti Iran, Senegal, Pantai Gading, dan Haiti dengan dalih keamanan nasional. Kebijakan tersebut berlaku bagi wisatawan dan pemegang visa kunjungan, kategori yang justru menjadi jalur utama bagi suporter internasional.
Pengecualian memang diberikan kepada atlet, staf tim, dan keluarga inti pemain. Namun, pengecualian itu tidak mencakup pendukung yang ingin hadir langsung di stadion. Oleh karena itu, negara-negara yang tim nasionalnya lolos ke Piala Dunia berpotensi tampil tanpa kehadiran suporternya di Amerika Serikat, kecuali pada laga yang digelar di Kanada atau Meksiko.
Situasi ini sudah pasti bertolak belakang dengan prinsip dasar FIFA. Dilansir The Athletic, pada 2017, Gianni Infantino pernah menegaskan, setiap tim yang lolos Piala Dunia, termasuk suporter dan ofisialnya, harus mendapat akses ke negara tuan rumah. Pernyataan tersebut kini terdengar seperti retorika kosong karena realitas kebijakan negara tuan rumah justru membatasi partisipasi publik global.
Pemerintah Amerika Serikat berdalih pada data overstay visa yang tinggi. Senegal dan Pantai Gading, misalnya, disebut memiliki tingkat overstay di atas 4 persen untuk visa wisata, sedangkan negara Haiti bahkan melampaui 30 persen. Narasi keamanan ini menjadi landasan resmi kebijakan, tetapi dampaknya secara langsung menggerus makna Piala Dunia sebagai perayaan inklusivitas.
Akibatnya, Piala Dunia 2026 bergerak menjauh dari karakter universalnya. Turnamen yang seharusnya netral dan inklusif justru tunduk pada logika politik domestik sehingga legitimasi moralnya ikut dipertanyakan. Sepak bola justru kehilangan salah satu fondasi globalnya ketika paspor dan kebijakan negara tuan rumah membatasi akses fans internasional.
2. Undian grup Piala Dunia 2026 digunakan Donald Trump untuk memoles citra globalnya
Politisasi Piala Dunia 2026 tidak berhenti pada tataran kebijakan. Donald Trump juga tampil dominan dalam simbolisme dan panggung resmi FIFA. Penyelenggaraan undian grup Piala Dunia di Washington D.C., tepatnya di Kennedy Center yang kini berada di bawah pengaruh politik Trump, menjadi bukti kuat arah tersebut.
Acara undian tersebut berlangsung dengan nuansa yang lebih menyerupai peristiwa geopolitik ketimbang seremoni olahraga. Trump tampil sebagai figur sentral, berdiri sejajar dengan pemimpin Kanada dan Meksiko, serta terlibat langsung dalam sesi simbolik pengundian. Kehadiran ini melampaui peran protokoler kepala negara tuan rumah.
Momen paling kontroversial terjadi ketika FIFA menganugerahkan FIFA Peace Prize perdana kepada Donald Trump. Tanpa proses nominasi terbuka, standar yang jelas, atau persetujuan Dewan FIFA, penghargaan itu diumumkan dan diserahkan di tengah acara undian. Infantino secara terbuka memuji Trump sebagai pemimpin yang membantu menciptakan perdamaian global.
Keputusan tersebut jelas memicu kritik luas. Human Rights Watch dan FairSquare menilai, penghargaan itu tidak memiliki legitimasi prosedural dan melanggar prinsip netralitas FIFA. Mereka juga menyoroti kedekatan personal Infantino dengan Trump yang sebelumnya bahkan secara terang-terangan melobi agar Trump menerima Nobel Perdamaian.
Simbolisme tersebut menegaskan bagaimana Piala Dunia dijadikan perpanjangan citra personal kekuasaan. FIFA tidak sekadar memberi ruang, tetapi secara aktif memfasilitasi satu figur politik untuk mengkapitalisasi panggung sepak bola dunia demi kepentingan narasinya sendiri. Akibatnya, batas antara diplomasi olahraga dan legitimasi politik pun menjadi kabur.
3. Kedekatan Gianni Infantino dengan Donald Trump membuat independensi FIFA dipertanyakan
Kedekatan antara FIFA dan Donald Trump memicu pertanyaan serius mengenai netralitas institusi tersebut. FairSquare secara resmi mengajukan keluhan kepada Komite Etik FIFA dengan menuduh Gianni Infantino melakukan pelanggaran berulang terhadap Pasal 15 Kode Etik FIFA yang mengatur kewajiban netralitas politik. Tuduhan itu mencakup dukungan publik terhadap agenda politik Trump dan penganugerahan FIFA Peace Prize.
Kritik juga datang dari kelompok suporter dan organisasi masyarakat sipil. Football Supporters Europe menyebut penghargaan tersebut sebagai aksi pencitraan yang tidak mewakili miliaran penggemar sepak bola. NAACP dan American Civil Liberties Union menilai kedekatan FIFA dengan Trump berpotensi menormalisasi kebijakan yang diskriminatif.
Risiko jangka panjangnya bersifat struktural. Jika FIFA membiarkan politisasi ini berlangsung, kredibilitasnya selaku badan pengelola sepak bola global akan terus terkikis. Turnamen internasional berpotensi dipersepsikan sebagai alat legitimasi kekuasaan daripada ruang persaingan yang adil dan inklusif.
Ketegangan ini juga berdampak pada hubungan antarnegara tuan rumah. Retorika Trump terhadap Kanada dan Meksiko, termasuk ancaman relokasi pertandingan dengan dalih keamanan kota-kota tertentu, menciptakan suasana penuh ketidakpastian yang bisa menimbulkan friksi diplomatik antara tuan rumah. Ancaman semacam ini belum pernah muncul dalam sejarah Piala Dunia modern, yang selama ini dibangun di atas prinsip koordinasi dan kepercayaan lintas negara.
Pada akhirnya, Piala Dunia 2026 tampil sebagai contoh betapa rapuhnya klaim independensi olahraga global. Turnamen ini seolah-olah menunjukkan, netralitas hanyalah janji kosong ketika sepak bola bergantung pada belas kasihan penguasa politik negara tuan rumah. Dalam hal ini, FIFA tengah diuji apakah masih layak dipercaya sebagai penjaga masa depan sepak bola internasional.
Piala Dunia 2026 memperlihatkan bagaimana olahraga dapat bergeser menjadi instrumen politik ketika institusi dan negara tuan rumah gagal menjaga jarak kekuasaan. Pertanyaannya kini bukan hanya tentang peran Donald Trump, melainkan tentang kemampuan FIFA mempertahankan otonomi moralnya di tengah tekanan politik global.