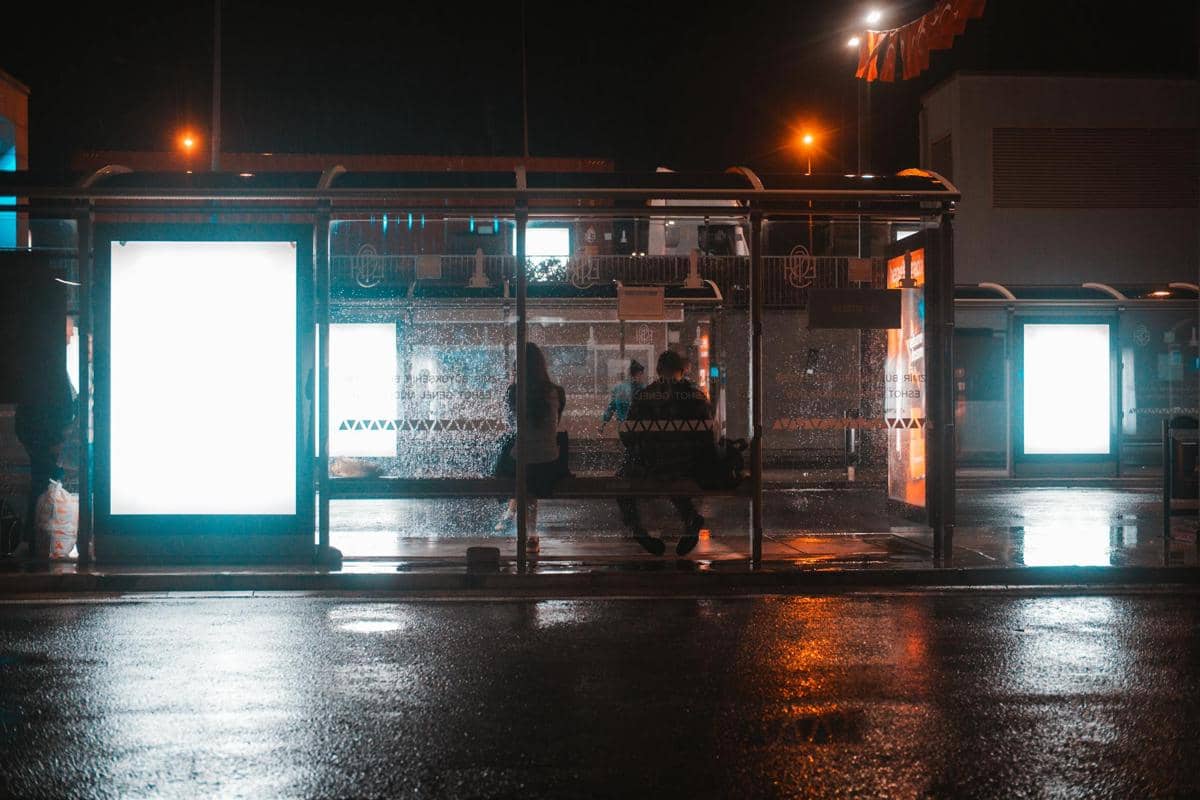- www.storial.co
- Facebook : Storial
- Instagram : storialco
- Twitter : StorialCo
- Youtube : Storial co
Rahasia Salinem - BAB 2
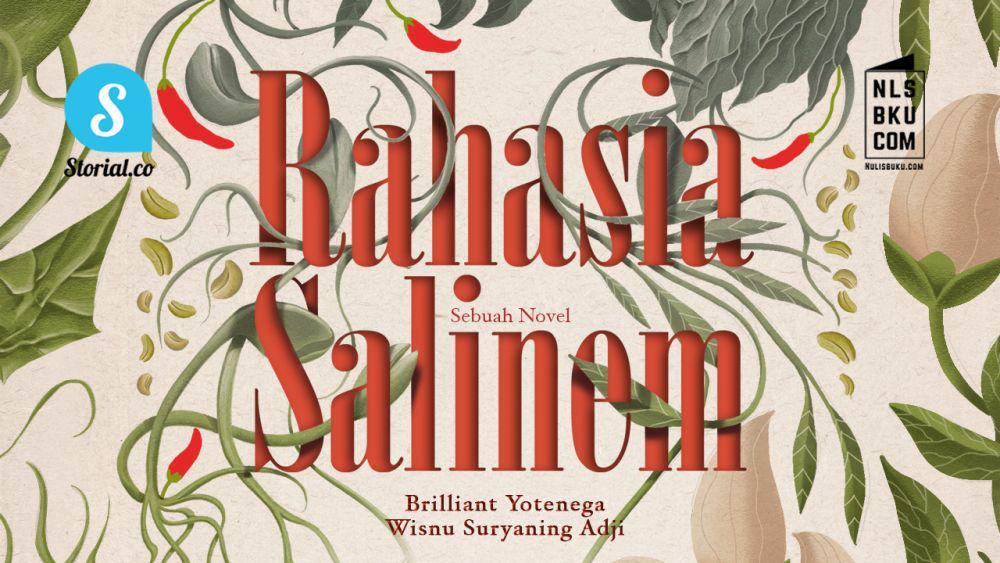
[2]
Sukoharjo, Pertengahan 1925
Laki-laki tua asing itu bilang: tak lama setelah kelahiran Salinem, Lasiyem meninggal karena pendarahan, hingga selama Salimun bekerja, Salinem harus dititip kepada bibinya— Daliyem, seorang pedagang pecel di pasar Sukoharjo.
Menjelang siang, pekerjaan para abdi dalem di rumah Gusti Wedana sudah berkurang, pun Daliyem harus mengurusi suami, dan anak-anaknya sendiri; jadilah, sepulang Daliyem dari pasar, Salinem harus pindah tangan lagi alias dititipkan kepada abdi dalem perempuan yang kerja di rumah Gusti Wedana. Tiap kali abdi dalem perempuan yang menjaga Salinem mendapat tugas dari Gusti Istri Wedana, ia akan menyerahkan Salinem pada orang lain lagi untuk diawasi. Sore menjelang malam, barulah Salinem tiba di tangan Salimun.
Salinem susah sekali disuruh tidur. Bocah kecil itu terlalu suka lari-lari, walau masih tertatih-tatih. Namun, Salimun tahu penawarnya. Salinem suka sama cerita. Kalau Salimun sudah mulai cerita, Salinem diam sampai ketiduran.
Keesokan paginya, Daliyem akan menjemput, membawa Salinem kembali ke pasar, menaruhnya di samping dagangan atau dititipkan ke teman-teman sesama pedagang. Sementara, Salimun—si kusir delman—mulai mempersiapkan pekerjaannya mengantar Gusti Wedana ke kantor. Begitu seterusnya, setiap hari sejak Salinem lahir.
“Bukannya kami ndak mau merawat Salinem, Mun. Kamu jangan tersinggung,” ujar Mbok Yah—seorang abdi dalem yang cukup senior—sambil membelai kepala Salinem yang sudah berusia satu setengah tahun, Salinem bergerak-gerak dalam gendongannya. “Sakjane, melas tenan [1] si Salinem pindah-pindah tangan terus. Mending kamu cari ibu untuk Salinem.”
Salimun belum berniat kawin lagi, walaupun rekan-rekannya di Kawedanan Sukoharjo memanas-manasi dia terus. Mereka bilang Salimun masih muda dan ganteng untuk bisa mendapat istri lagi dengan mudah. Sesungguhnya, Salimun iba kepada Salinem kecil yang sendirian, namun Salimun tak lagi selera menikah selepas kepergian Lasiyem. Biarlah begini dulu, ujarnya dalam hati.
“Kamu macam anak muda saja, masih milih-milih istri,” suara seorang temannya berkata ketika Salimun sedang membantu mengurus taman di kantor Gusti Wedana. “Pikirkan juga keadaan Salinem, Mun. Dia sudah satu setengah tahun.”
Salimun berpikir dan tenggorokannya terasa gatal, mungkin karena terlalu banyak pikiran. Ia terbatuk-batuk, kepalanya pening, kemudian Salimun menggeleng-geleng, lebih seperti hendak mengusir sakit kepalanya.
“Aku belum bisa menikah lagi, Mas,” ujar Salimun kepada rekannya itu.
“Sudah setahun lebih sejak Lasiyem meninggal. Ndak bisa lupa?”
Mungkin, dia pikir lupa itu gampang. Salimun terbatuk lagi, tidak menjawab pertanyaan itu. Ia tahu kalau Lasiyem sudah meninggal, namun bayangannya masih terasa hidup.
“Sudah, jangan melamun,” pungkas temannya. “Kamu sudah menyiapkan tempat dan rumput untuk kudanya Asisten Wedana baru itu?”
Salimun bergegas menuju ke belakang. Ia ingat perintah dari Gusti Wedana kemarin, Salimun harus mempersiapkan kedatangan Gusti Asisten baru. Katanya, Gusti Asisten baru itu akan bertugas di Tawangsari. Jaraknya tak terlalu jauh dari pusat Kawedanan Sukoharjo. Namun, sebelum itu, ia akan berkantor di sini sebentar, untuk meluruskan tugas-tugasnya. Jadi, Salimun perlu membereskan ruangan atau memastikan bahwa kudanya diberi makan dan minum.
Menjelang siang, sebuah delman bergerak memasuki kantor Wedana, tampak di dalamnya seorang laki-laki gagah duduk mengenakan beskap putih dan kain batik tulis yang membalut pinggang hingga ujung mata kakinya, selop hitam menutup telapaknya, selain rantai emas menjulur di dada, masuk ke dalam kantong beskapnya. Di sampingnya, duduk seorang perempuan cantik dengan sanggul berhias kuntum bunga dan kebaya panjang dengan bordiran senada. Di hadapan mereka terlihat dua orang: satu remaja laki-laki, dan satu anak perempuan yang kelihatannya berusia lima tahun lebih.
Dari Gusti Wedana, Salimun tahu bahwa laki-laki gagah itu adalah Gusti Asisten Wedana, dan duduk di samping adalah Istrinya—Raden Ayu Soemirah, sementara dua anak itu adalah adik istrinya, yaitu Raden Soekatmo dan Raden Ayu Soeratmi.
_
Daliyem baru tiba di pasar. Salinem sudah meronta-ronta minta turun. Pasar Sukoharjo adalah tempat yang di pagi hari selalu ramai, dan Daliyem sesungguhnya akan jadi sangat kerepotan jika saja teman-teman di pasar tidak membantunya mengawasi Salinem yang sudah satu tahun lebih. Bayi itu sudah bisa merayap-rayap sambil berpegang pada apa pun, sudah bisa melangkah kecil sendiri, lalu tiba-tiba berlari seperti layangan putus. Kalau Daliyem sedang melayani pelanggan, Salinem bisa hilang. Salinem senang berpetualang, bayi itu tak bisa diam.
Untunglah, tak jauh dari tempatnya berdagang ada pedagang kelontong yang baik hati. Ia punya anak laki-laki yang umurnya kira-kira lima tahun, namanya Giyo. Daliyem suka menitipkan Salinem pada Ibunya Giyo kalau pelanggan sedang ramai.
“Giyo jadi tenang kalau ada Salinem,” ujar perempuan itu. “Sudah seperti adiknya sendiri. Ke mana pun Salinem bergerak, dia ikuti.”
Daliyem bersyukur. Meski bukan anaknya, Daliyem sayang sama Salinem. Ada garis muka kakaknya tergurat di wajah bayi itu, dan ia ingat bagaimana Lasiyem selalu melindunginya saat mereka masih kecil. Daliyem selalu sedih jika teringat Lasiyem yang menurutnya terlalu cepat pergi.
“Biarkan aku yang merawatnya,” ujar Daliyem pada Salimun ketika Lasiyem meninggal satu setengah tahun lalu. Sesungguhnya, karena ia tidak rela kalau Salimun kawin lagi. Ia membayangkan bahwa Lasiyem akan sedih jika suaminya bersama perempuan lain. Namun, setelah setahun ini, Daliyem mulai berpikir ulang. Kesibukannya berdagang, juga suami, dan anak-anak, membuatnya tak bisa sepenuhnya merawat Salinem. Daliyem menduga kalau Lasiyem akan sedih jika mengetahui bayinya dirawat oleh banyak tangan yang semuanya bukan ibu.
Atau, mungkinkah Lasiyem gembira jika mengetahui anaknya disayangi semua orang? Ah, Daliyem bingung antara terus merawat Salinem dengan cara ini, atau meminta Salimun kawin lagi. Sejauh ini, Daliyem diam saja, berusaha merawat Salinem sebisanya. Melihat Giyo yang masih kecil menyayangi Salinem begitu rupa bisa sedikit menghibur Daliyem dari perasaan bersalah. Salinem punya kakak, walau tidak kandung.
Setiap Daliyem mengambil Salinem untuk dibawa lagi ke tempat tinggal Gusti Wedana, dia menyaksikan bagaimana wajah Giyo berubah sedih. Lalu, Daliyem sebentar membiarkan Giyo membelai-belai kepala Salinem sebelum membawanya pergi. Esok paginya, ketika Daliyem mulai menggelar dagangan, Giyo adalah bocah kecil yang pertama muncul. Salinem yang belum bisa bicara akan menyambut seperti kakaknya sendiri.
Awalnya, Daliyem takut waktu Giyo yang masih lima tahun itu mencoba menggendong Salinem, tapi anak itu ternyata kuat dan Salinem tak keberatan. Entah karena Salinem yang memang mudah akrab pada semua orang atau memang karena Salinem dengan segera menganggap Giyo sebagai kakaknya. Sungguh, bahkan sejak bayi, Salinem mengingatkan Daliyem pada Lasiyem yang ramah, mudah nempel sama orang.
Lalu, Daliyem akan meraih Salinem dan menggendongnya, membawanya ke toko kelontong tempat Ibu si Giyo berdagang dan Giyo akan berlari-lari mengikutinya, memandang dengan tatapan: Biarkan aku yang menggendongnya. Tentu saja, Daliyem takkan membiarkan Giyo menggendong Salinem lama-lama karena Giyo juga masih kecil. Ia tak mau Giyo menjatuhkan bayi itu ke lantai pasar yang becek.
_
Bau kayu bakar menyeruak bersama sisa embun. Salimun baru saja berpisah dengan Salinem. Daliyem menggendong bayi itu dengan selempang jarik batik di dadanya, sementara sebuah keranjang bambu berisi dagangan pecel menggantung di punggungnya. Lalu, Daliyem melanjutkan perjalanan ke Pasar Sukoharjo. Salimun tadi membantu mengangkat keranjang itu, dan seketika bisa membayangkan betapa berat perjalanan Daliyem untuk menuju pasar. Ia tak hanya membawa dagangan, tapi juga bayinya.
“Maafkan aku, Yem,” bisik Salimun. “Aku jadi merepotkanmu terus.”
“Ndak apa-apa, Mas. Salinem sudah seperti anakku sendiri,” Daliyem tersenyum, lalu mulai berjalan menjauh diiringi tatap mata Salimun yang segera berbalik, pekerjaannya sudah harus dimulai.
Ia menyikat punggung kuda, memastikan perut mereka terisi rumput segar. Lalu, mengukuhkan hewan itu dengan sabuk kulit bergesper ke delman. Tak lama Gusti Wedana akan muncul dari ambang pintu, dan sebelumnya Salimun harus memastikan bahwa semua peralatan yang Gusti Wedana butuhkan untuk bekerja sudah dibawa. Salimun juga bertugas macam asisten pribadi, memastikan ruangan kerja tersusun rapi, bebas dari debu, juga menyediakan semua kebutuhannya, termasuk kopi, dan teh hangat di meja saat bekerja di kantor. Di rumah, teh dan kopi dipersiapkan oleh Gusti Istri Wedana.
“Ayo, kita berangkat, Mun,” ujar Gusti Wedana.
“Nggih, Ndara [2],” jawab Salimun lalu berlari kecil menuju delman yang sudah dipersiapkan di depan tangga sambil membawa tas kulit berwarna hitam, dan meletakkannya di kursi sampingnya. Ia langsung duduk di kursi kusir, meraih tali kekang untuk menjaga agar kudanya tak bergerak-gerak karena Gusti Wedana akan naik dari belakang. Ia menengok, memastikan gustinya sudah duduk dengan baik, dan istrinya melambai.
“Ck. Ck,” Salimun berdecak sambil memecut pelan bokong kuda dengan sebuah pecut kecil, membuat mereka bergerak.
Perlahan-lahan delman keluar dari rumah, mulai menempuh perjalanan. Udara Sukoharjo masih sejuk walau sinar matahari menyorot. Salimun merasa pening, mungkin akibat tak bisa tidur semalaman. Sudah beberapa waktu ini, ia sakit kepala. Ia pikir karena kebanyakan pikiran.
“Kamu ndak mau ke mantri, Mun?” tanya Gusti Wedana, suaranya bercampur dengan derap kaki kuda.
“Ndak perlu, Ndara. Saya masih sehat.”
“Kalau kamu mau, biar kusiapkan.”
“Matur nuwun sanget, Ndara,” jawabnya lagi. “Saya ndak mau merepotkan.”
Gusti Wedana tak menjawab lagi, sementara Salimun terus memerhatikan jalan.
Delman terus berlari menuju Kantor Kawedanan. Orang-orang di pinggir jalan menghormat tiap berpapasan, dan Gustinya tersenyum membalas sapaan orang-orang. Sekitar dua puluh menit perjalanan, mereka tiba.
Gedung putih megah dengan empat tiang utama sudah muncul seperti kapal besar menyibak ombak. Derap kaki kuda melambat, menimbulkan kericik akibat ladam beradu dengan batu-batu yang menutupi pelataran. Di ujung tangga, dua arca Dwarapala berpijak. Setelahnya, dua tiang beton putih, dan di belakangnya terhampar pendopo yang atapnya disangga puluhan tiang besi. Seorang laki-laki sedang duduk di ujung tangga. Dia adalah kusirnya Gusti Asisten.
Asisten Wedana baru itu sungguh rajin, gumam Salimun dalam hati, ia sudah tiba lebih dulu sebelum gustinya. Delmannya parkir di sisi tangga. Salimun menarik kekangnya sendiri sampai delman berhenti. Gustinya turun, dan Asisten Wedana baru itu langsung muncul di pintu. Ia ternyata membawa kedua adik iparnya ke sana.
Salimun turun untuk membawa tas hitam kulit ke dalam. Ia cepat-cepat mengikuti langkah gustinya. Sampai di depan pintu kantor ia mendengar Gusti Asisten berkata pada Gusti Wedana, “Saya membawa adik ipar untuk membantu, Mas. Supaya dia belajar.”
“Bagus. Bagus,” jawab Gusti Wedana. “Kalau sudah belajar sejak muda, kelak kamu akan jadi pejabat yang baik,” ia menepuk-nepuk pundak Raden Soekatmo dengan senyum lebar, lalu memandang Raden Ayu Soeratmi yang berdiri diam di sampingnya sambil membawa sebuah boneka kain.
Gusti Soekatmo tersenyum lalu menyalami Gusti Wedana.
Pemuda itu memiliki mata tajam, dan garis rahang yang kuat.
Gusti Asisten melanjutkan, “Adiknya tetap ingin ikut kakaknya. Mereka dekat sekali.”
Gusti Wedana menganggukkan kepala, lalu menengok ke arah Salimun, “Mun, setelah ini beri tahu kusir Gusti Asisten tempat dia bisa mengurus kudanya, dan suruh salah satu abdi dalem untuk membantu mengurus Raden Ayu Soeratmi.”
“Nggih, Ndara,” Salimun masih berdiri di belakang gustinya, mengangguk, lalu mengikuti masuk dalam ruang kantornya, sementara Gusti Asisten, dan adik iparnya menuju ruangannya sendiri di sebelah.
Setelah meletakkan tas kulit di meja, Salimun minta izin untuk keluar, dan mengajak kusir Gusti Asisten Wedana untuk mengikutinya menuju istal. Saat itu, Salimun merasa kepalanya kembali diserang rasa sakit. Terlalu banyak berpikir, kiranya.
Esoknya, setelah seorang Belanda keluar dari Kawedanan, Raden Ayu Soemirah datang, menyusul suaminya yang sedang mengurus macam-macam surat atau entah apa di Kawedanan Sukoharjo sebelum pindah ke kantornya sendiri di Tawangsari.
Salimun jadi ingat mendiang istrinya. Pasangan yang belum punya anak selalu tampak menyenangkan, seperti selalu berkasih-kasihan saja. Raden Ayu Soemirah, dan suaminya tampak akrab, gemar bertukar senyum. Salimun baru saja berjalan ke belakang, duduk untuk mengusir pening yang selalu datang bolak-balik ketika ia mendengar suara seseorang memanggil. “Mun! Kamu di mana? Gusti Wedana mencarimu.”
Salimun segera mendekat, “Ada apa?”
“Ndak tahu.”
Salimun bergegas ke depan. Sering, Gusti memintanya mengantar ke suatu tempat, atau menemaninya memeriksa sawah atau kebun tebu, mengawasi hasil panen dan memperhatikan apakah ada hama. Tapi, kali ini ia memanggilnya bukan untuk itu.
“Mun, tolong antarkan Raden Ayu Soemirah ke Pasar Sukoharjo,” ucapnya. “Sekalian, ia ingin melihat-lihat kota ini.”
Gusti Soemirah berdiri tetap dengan senyumnya, dan Salimun membungkuk. “Nggih, Ndara. Sebentar, saya persiapkan delmannya.”
“Pakai delmanku saja, Mun,” tambah Gusti Wedana.
“Nggih, Ndara.”
Salimun berbalik menuju istal. Tak memakan waktu lama, delman, dan kudanya telah tiba di ujung tangga Kawedanan. Namun, mereka tak kunjung naik perkara Gusti Soeratmi menangis, ia tak mau berangkat tanpa boneka kain kesayangannya. Dicari-carinya boneka itu, dan akhirnya ditemukan juga di bawah kursi tamu di dalam kantor Asisten. Gusti Soekatmo menghapus air mata adiknya kemudian gadis kecil itu memelesat ke luar menuju kakaknya—satu lagi—yang sudah menunggu.
Gusti Soemirah dan adiknya langsung naik ke delman yang lanjut bergerak pelan menyusuri jalanan Sukoharjo. Beberapa orang yang berpapasan tampak membungkuk, namun menatap menyelidik setelahnya, agaknya karena putri yang sekarang duduk di delman sama sekali belum dikenal. Gusti Soemirah seperti memang selalu tersenyum, sibuk melihat-lihat pemandangan kota, sementara Gusti Soeratmi tetap sibuk menimang-nimang bonekanya.
Sukoharjo hitungannya kota kecil, namun tetap lebih besar dibanding Klaten, daerah asalnya. Ke mana-mana saja terasa dekat. Tak memakan waktu lama, mereka tiba di Pasar Sukoharjo. Seorang petugas pasar yang melihat delman Gusti Wedana langsung menyambut. Delman berhenti. Salimun bergegas turun lalu melangkah cepat menuju belakang delman, membantu Gusti Soemirah. Gusti Soeratmi menyusulnya. Udara sudah mulai panas. Putri bangsawan ini tampak mengembuskan napas sambil menggoyang-goyangkan kipas di tangannya.
“Sapa kuwi?” bisik seorang petugas pasar.
“Itu istri Asisten Wedana Tawangsari yang baru. Gusti Soemirah.”
“Ayu tenan, ya,” decaknya kagum. “Kuwi putrine?”
“Bukan. Itu adiknya. Gusti Soeratmi,” jawab Salimun. “Sudah, jangan banyak omong. Bantu aku mengikat delman ini, aku harus segera menyusul.”
Petugas pasar itu segera menarik tali kekang, menuntun delman agar berhenti di tempat seharusnya lalu Salimun setengah berlari menyusul Gusti Soemirah dan adiknya yang sudah berjalan masuk ke pasar. Pasar langsung heboh, jarang-jarang ada bangsawan masuk ke sana.
Ratusan mata berebutan melihat, jadi semacam tontonan. Toh, dua putri bangsawan ini tampak tenang saja dan sibuk mengedarkan pandangan ke sepenjuruan. Setiap mereka melangkah, orang-orang menyibak, lalu memberi hormat. Gusti Soemirah selalu membalas dengan senyum ramah.
“Saya mau beli jajan pasar, Pak Mun,” ujar Gusti Soemirah sambil menggandeng adiknya. “Antarkan saya ke sana.”
“Di Kantor Wedana sudah disediakan penganan kecil, Ndara,” jawab Salimun.
“Aku ingin tahu rasa jajanan dari sini, Pak Mun.”
“Nggih, Ndara. Mangga kula dherekaken.3”
Salimun segera mendahului berjalan, mengarahkannya makin jauh ke tengah pasar. Salimun sebenarnya khawatir karena pasar ini becek, putri-putri bangsawan bukan jenis manusia yang terbiasa berada di tempat-tempat seperti ini, tapi keduanya tidak tampak keberatan.
Salimun berjalan di depan sambil sesekali menengok, memastikan dua putri itu masih mengikutinya. Tiba-tiba, ada sesuatu yang memberatkan kakinya, ia menengok ke bawah. Lah? Salinem kini menggelayuti kakinya. Tergopoh-gopoh Daliyem menyusul di belakangnya dan langsung meminta maaf pada Gusti Soemirah.
“Anaknya, Pak Mun?” Gusti Soemirah langsung bertanya. “Nggih, Ndara. Namanya Salinem.”
“Ibu, istrinya?” Gusti Soemirah beralih pada Daliyem.
Sambil agak membungkuk, Daliyem menjawab, “Sanes [4], Ndara. Saya Daliyem, adik iparnya.”
“Istri saya sudah meninggal pas melahirkan Salinem, Ndara,” tambah Salimun.
“Oh, mohon maaf, Pak Mun,” Gusti Soemirah memandang Salinem yang terus bertahan di kaki Salimun sementara Gusti Soeratmi nanar memandangi adegan itu.
“Ndak apa, Ndara. Justru saya yang harus minta maaf.”
“Mau mampir ke tempat saya, Ndara?” tawar Daliyem.
“Ibu dagang apa?”
“Pecel, Ndara.”
“Oh, boleh. Ayo.”
Daliyem meraih Salinem dengan cepat, menggendongnya, lalu berbalik masih dengan gerakan membungkuk-bungkuk. Gusti Soemirah dan Gusti Soeratmi mengikutinya dan Salimun membuntuti mereka dari belakang. Tak lama mereka di sana, dan ketika Daliyem menolak dibayar, Gusti Soemirah tetap memaksa, “Ndak boleh gratisan. Ibu sedang dagang. Masak saya minta.”
Daliyem menyerah dengan wajah kagum dan menerima uang dari Gusti Soemirah. Salimun meneruskan menemani mereka dan mencari jajan pasar.
Di perjalanan pulang, Gusti Soemirah bertanya, “Pak Mun, kenapa anaknya tak dibawa ke Kawedanan saja?”
“Takut jadi merepotkan, Ndara. Kawedanan tempat orang bekerja.”
Gusti Soemirah mengangguk-angguk dan sampai di kantor Kawedanan Gusti Soemirah segera mencicipi pecel itu dan berkata, “Enak sekali, Pak Mun. Kapan-kapan, saya minta tolong untuk dibawakan kemari pagi-pagi.”
_
Salinem jarang sakit, kalaupun sakit tak pernah seberapa parah. Siang itu, waktu Salinem dipindahtangankan oleh Daliyem kepada abdi dalem di rumah Gusti Wedana, ia baik-baik saja. Begitu yang didengar Salimun. Namun, ketika sore Salinem pindah ke tangannya, ia melihat bayinya itu tak seperti biasanya. Salinem jadi tak mengeluarkan suara, kecuali tangis. Makin malam, tubuhnya makin panas dan ia menolak makan.
Wajah bayinya terus memucat dan Salimun tak bisa tidur. Ia menyuapkan bubur ke mulut anaknya, tapi Salinem meronta-ronta. Salimun mencoba memaksa dan yang terjadi berikutnya Salinem muntah. Salimun berjalan bolak-balik, bingung ke mana ia hendak mencari kain untuk menyeka sisa muntahan.
Sebelum Salimun menemukan apa pun, Salinem muntah lagi. Salimun menepuk-nepuk pipi bayinya yang terkulai lemas, mencoba memanggil nama anaknya berulang-ulang, Salinem seperti tak mendengarnya. Salimun makin panik dan mulai menangis walau ia tahu bahwa tangisan tidak akan bisa menolong putrinya. Tubuh putrinya seperti mengandung tungku yang berisi kayu bakar, mulai mengejang-ngejang. Tubuhnya terlalu panas. Salimun benar-benar menangis.
“Nem ..., Nem ....”
Salinem tak membalas apa-apa, terus mengelejat dan Salimun tak punya pilihan. Dengan jantung sempit, dan Salinem tegang di dadanya, ia berlari menuju bangsal tempat tinggal abdi dalem perempuan. Sekuat-kuatnya, Salimun menggedor-gedor pintu dan Mbok Yah muncul.
“Mbok, Salinem kejang-kejang.”
“Haduh, Mun. Kenapa tidak kamu bawa dari tadi?” Mbok Yah langsung merebut Salinem dari pelukannya. Tubuh besarnya terguncang-guncang. “Ambil air di belakang. Salinem dikompres dulu.”
Mbok Yah langsung mengikat rambutnya yang panjang mengilat seperti kebanyakan minyak, tangannya menyentuh dahi Salinem yang matanya masih membelalak. Ia menggeleng-geleng. Salimun jadi tambah khawatir. Seiring itu, Salimun memelesat menuju padasan dan menampung air dalam baskom, berlari lagi ke dalam, dan ketika ia tiba, Mbok Yah sedang memarut bawang merah, mencampurnya dengan minyak kelapa.
“Taruh di situ,” ia menunjuk sisi ranjang. “Sekarang kamu ke belakang, panaskan air. Buat kopi, jangan pakai gula.”
“Buat apa?”
“Sudah buat saja,” putus Mbok Yah. “Habis itu kamu ke kebun belakang, cari tanaman binahong. Petik daunnya yang banyak.”
“Binahong kayak apa bentuknya?”
“Pohonnya merambat, daunnya bulat-bulat. Jangan tertukar dengan daun Cau.”
Salimun berlari lagi ke belakang, tertatih-tatih ke dalam pawon, meraba-raba dalam gelap, menyalakan lampu sentir, dan cahaya kecil menyeruak membuat dapur berisi cahaya jingga dan bayangan-bayangan hitam besar memancang di dinding. Api tungku sudah menyala, Salimun menjerang air dalam panci, dan langsung meninggalkannya, berlari ke luar sambil merintih dalam hati: Kalau sampai Salinem menyusul ibunya, lebih baik aku mati.
Gelap. Di bagian belakang rumah Gusti Wedana ada sepetak kebun. Purnama sedang moncer menuju puncak langit, sedikit membantu penglihatan. Duh, Gusti. Tersuruk-suruk Salimun masuk ke dalam kebun, mencari tanaman yang dimaksud. Bukan hanya binahong dan cau, ada banyak tanaman lain. Yang mana ini?
Rasanya waktu bisa memadat hingga cuma jadi sekepalan tangan. Ia petik semua daun tanaman merambat banyak-banyak, ada yang tercabut sampai akarnya. Ia tak peduli. Kalau besok ia dimarahi Pak Kebon, yang penting Salinem hidup.
Ia kembali ke dapur dan air sudah mendidih. Entah berapa takarannya, ia memasukkan saja kopi ke gelas dan menyeduhnya. Segenap tenaga, ia kembali ke kamar Mbok Yah.
“Ya, Gusti. Kamu bawa apa, Mun?” omelnya. “Kamu mau memindahkan kebun kemari?”
“Aku tidak tahu binahong yang mana, Mbok.”
“Sudah, sini semuanya.”
Salimun menyodorkan kopi, dan meletakkan semak-semak itu di samping Mbok Yah. Mbok Yah memilih beberapa lembar daun dan mengunyahnya. Oh, itu binahong, gumam Salimun. Sambil itu, Mbok Yah menyuapkan kopi sesendok demi sesendok ke mulut Salinem, lalu ia membalurkan kunyahan daun binahong bercampur liur di dahi anaknya. Salimun menyentuh lengan bayinya, bahkan lengannya terasa mendidih. Gusti, jangan biarkan Salinem menyusul ibunya.
“Ndak guna kamu bengong di situ, Mun!” bentak Mbok Yah. “Kamu sekarang liwet nasi, ambil air tajinnya saja. Kalau nanti Salinem sudah tenang, biar makan itu dulu,” Mbok Yah masih mengunyah-ngunyah binahong dan menempelkannya ke leher Salinem, kemudian memutar kepalanya ke arah Salimun, “Apa maneh? Mau anakmu mati?”
Mendengar ucapan Mbok Yah, Salimun berlari balik ke pawon, dan memasukkan blarak5 dan kayu ke dalam tungku yang masih bersisa bara. Sekejap, api membesar lagi, kembali membuat bayangan. Las, maafkan, maafkan aku, rintih Salimun sambil menatap jilatan-jilatan api, aku gagal menjaga putrimu. Las, kalau kamu masih di sini, Salinem takkan begini. Las, apakah aku berkhianat padamu jika kawin lagi? Aku kangen kamu, Las. Mengapa kamu begitu cepat pergi?
_
Salimun tak tahu bagaimana cara berterima kasih pada Mbok Yah karena sudah menyelamatkan nyawa Salinem. Tanpa dia, Salinem mungkin sudah hilang dari pelukannya. Keberadaan Mbok Yah di rumah Gusti Wedana bisa mengurangi rasa waswasnya.
“Tapi, mulai besok, aku ndak di sini lagi, Mun,” ucap Mbok Yah.
“Mbok Yah mau ke mana?”
“Sementara, aku disuruh pindah sama Gusti Wedana.”
“Ke mana?”
“Ke tempat Gusti Asisten.”
“Kok, isa?”
“Embannya Gusti Soeratmi pulang ke Solo, orang tuanya sakit. Ndak tahu kapan balik, bisa ndak balik.”
“Mbok Yah disuruh menggantikan?”
“Iya,” jawabnya lagi, “tapi kamu ndak usah khawatir.”
Berbunyi di benak Salimun: Rasa aman memang tak pernah tinggal lama, bisa hilang dalam sesaat.
“Ndak khawatir bagaimana, Mbok?” Salimun membayangkan apa yang harus ia lakukan kalau Salinem kejang-kejang lagi.
“Tugasku sama seperti emban yang dulu. Nemani Gusti Soeratmi kalau sedang ikut ke Kawedanan,” lanjutnya. “Jadi, kalau ada apa-apa sama Salinem, kamu masih bisa tanya.”
Salimun mengangguk, dan membantah dalam hati. Gusti Asisten takkan lama di Sukoharjo dan bagaimana kalau Salinem sakit tengah malam? Tidak ada lagi abdi dalem sepengalaman Mbok Yah. Yang bisa menggantikannya hanya Lasiyem.
Duh, Las.
Sekarang, Salimun cuma bisa ketemu Mbok Yah di kantor Kawedanan. Gusti Wedana menyuruh Mbok Yah untuk segera pindah ke tempat Gusti Asisten. Hampir tiap pagi putri kecil itu ikut; naik delman atau sepeda berdua dengan Gusti Soekatmo. Kadang, dilihatnya Gusti Soeratmi duduk di pangkuan kakaknya, dan remaja laki-laki itu mencubit-cubit pipi adiknya.
Raden Soekatmo, dan adiknya itu memang seperti tak bisa dipisahkan. Gusti Soeratmi selalu mengikuti ke mana pun kakaknya berjalan, tetap dengan membawa bonekanya. Kadang, kalau kakaknya sibuk, ia menjauh lalu main-main sendiri. Salimun jadi kasihan, beberapa kali ia mencoba mendekati putri kecil itu, tapi ia begitu pendiam, susah diajak bicara. Wajahnya yang masih bulat kanak-kanak jarang tersenyum. Kalau dilihat, bocah itu membawa bakat jadi galak.
Soeratmi baru bisa pisah dari kakaknya, ya, setelah Mbok Yah rutin mengasuhnya. Dan, benarlah kecurigaan Salimun. Begitu Gusti Asisten, dan istrinya pindah ke Tawangsari, Mbok Yah dibawa serta. Gusti Wedana menempatkannya jadi pengasuh tetap untuk Soeratmi. Salimun jadi jeri, dan berpikir mungkin benar kalau ia harus mulai mencari istri. Tidak mungkin terus-menerus tergantung pada bantuan orang lain.
Namun, belum sempat Salimun ketemu calon istri, Mbok Yah balik lagi ke kantor Gusti Wedana. Bukan bagaimana-bagaimana, Gusti Soekatmo ternyata mengajukan diri untuk membantu jadi juru tulis Gusti Wedana sekalian belajar macam-macam.
Tentu saja, Gusti Wedana senang hati menerimanya, bahkan ia bilang: Kamu hebat, mau melakukan pekerjaan remeh semacam ini. Memang, biasanya yang jadi juru tulis bukan anak-anak bergelar Raden. Toh, Gusti Soekatmo niat belajarnya memang tinggi. Bukan cuma membantu menulis ini-itu, ia juga membantu Gusti Wedana jadi sejenis asisten pribadinya. Tangannya terampil, sepeda saja bisa ia perbaiki.
Tentu saja, Soeratmi memilih untuk mengekor kakaknya. Kadang, mereka tinggal di Tawangsari, namun tak jarang Gusti Soekatmo, dan adiknya itu menginap di rumah Gusti Wedana terutama jika ada pekerjaan yang memaksanya kerja sampai malam. Kalau mereka menginap, Salimun lega karena artinya Mbok Yah juga menginap. Lama-lama, Gusti Soekatmo, dan adiknya itu lebih sering menginap di Sukoharjo. Gusti Soeratmi juga sekolah di sana.
Salimun jadi ingat Salinem, anaknya sendiri, umurnya sudah dekat dua tahun, dan meski baru bisa bicara sepatah-sepatah, Salinem mudah akrab bahkan sama orang asing; kata-katanya mulai bisa ditangkap, mungkin karena selalu bergaul dengan banyak orang di pasar, sering dengar orang bicara.
Gusti Soeratmi nyaris tak punya teman, kecuali kakaknya—yang selalu sibuk membantu Gusti Wedana. Tentu saja, itu membuat Gusti Soeratmi setelah pulang sekolah lebih sering main-main sendirian, dengan Mbok Yah yang cuma mengikutinya ke mana-mana. Salimun merasa kasihan, namun nasib anaknya sama saja.
Hari ini pekerjaan sedang banyak. Selain membereskan kantor Gusti Wedana yang lebih berantakan dari biasanya, siang tadi Salimun harus mengantar gustinya, dan Gusti Soekatmo ke daerah-daerah pertanian di pinggir Sukoharjo. Sawah-sawah hampir panen, bulir-bulir padi menghampar, menguning seperti permadani emas. Panen tebu akan menyusul.
“Syukurlah, tidak ada hama tahun ini ya, Mun,” ujar Gusti Wedana.
“Nggih, Gusti. Berkat usaha keras dan doa semua penduduk Sukoharjo.”
“Omong-omong, kamu ndak pernah ingin pulang ke Klaten, Mun?”
“Tidak, Gusti. Keluarga sudah tidak ada yang di sana. Yah, saya anggap saja Sukoharjo adalah kampung saya. Salinem juga sudah jadi orang Sukoharjo.”
Gusti Wedana menatapi pinggiran sawah, “Mun, selama ini anakmu siapa yang urus?”
“Kalau pagi, adik ipar saya yang mengurusnya sambil dagang di pasar, Ndara. Kalau siang, dibawa pulang ke rumah.”
“Kenapa tidak kamu bawa anakmu ke Kawedanan saja? Sekalian, bisa jadi teman Soeratmi. Kasihan, dia selalu main sendirian.”
Raden Soekatmo tak memberi komentar apa pun.
“Nanti malah merepotkan, Ndara,” jawab Salimun dengan perasaan heran. Di tengah kesibukannya, Gusti Wedana sempat memperhatikan hal itu. Apakah Gusti Soemirah atau Gusti Soekatmo menyampaikannya?
“Ah, tidak merepotkan. Di belakang ada satu kamar kosong. Nanti kusuruh orang untuk menyiapkan buat tempat Soeratmi. Anakmu bisa menumpang di sana. Lagipula, jadi ada yang mengawasi anakmu.”
“Nggih, Ndara.”
“Pikirkan, ya, Mun.”
“Nggih, Ndara.”
_
Daliyem sudah curiga waktu magrib-magrib itu Salimun datang membawa jajanan dari rumah Gusti Wedana. Tak biasanya Salimun repot-repot ke rumahnya. Jelas, Salimun bukan sedang menyuruh Salinem menginap. Dan, benarlah.
“Kenapa, Mas?” mata Daliyem menajam. “Apakah aku tidak becus mengurus Salinem?”
“Bukan, Yem. Bukan,” Salimun menyanggah. “Aku sangat berterima kasih karena kamu sudah merawat Salinem sebaik itu.”
“Apakah karena sakitnya dulu itu?” tuduh Daliyem.
“Bukan, Nem,” Salimun menyanggah lagi. “Gusti Wedana yang memintaku membawa Salinem ke sana untuk jadi teman Gusti Soeratmi.”
Mata Daliyem jadi melunak, namun menyelidik, “Benarkah?”
Salimun mengangguk, “Benar. Sudah hampir satu setengah tahun ini Gusti Soeratmi selalu main sendirian. Salinem juga sudah hampir tiga tahun.”
Daliyem sadar betul kalau keputusan ini tidak terletak di tangannya, namun ia ragu.
“Kita coba saja. Siapa tahu, Salinem jadi lebih baik di Kawedanan,” Salimun sepertinya melihat keraguan itu. “Kalau Salinem ndak suka, kamu bisa membawanya ke pasar lagi, Yem.”
Daliyem langsung membayangkan si Giyo, bocah itu pasti sedih. Ia masih ragu tapi ia tetap berkata, “Benar, Mas. Memang lebih baik Salinem di Kawedanan. Ia akan lebih terjamin daripada berkeliaran di pasar.” Padahal, Daliyem merasa ini tidak adil; tidak seharusnya Salinem direbut dari tangannya. Tapi, menahan Salinem di pasar sama dengan menahan masa depannya.
_
Pagi itu, hari terakhir Salinem ikut ke pasar. Besok, Salinem sudah akan pindah ke Kawedanan. Daliyem ingin memperlambat semua kejadian, dan menggendong Salinem lebih lama. Ia memandang Salinem yang sudah tertawa-tawa saja. Daliyem jadi membenarkan bahwa cinta memang sering baru ternyatakan saat hampir hilang.
Di tengah perjalanan menuju pasar, Daliyem berbisik pada Salinem meski meragukan kalau anak itu sudah bisa mengerti, “Nem, nanti kalau sudah pindah ke Kawedanan, sering-sering tengok Bulik, ya?”
Sekarang, ia memikirkan bagaimana cara memberi tahu Giyo kalau adik angkatnya ini takkan muncul di pasar, tak bisa jadi kawan mainnya lagi.
_
Salimun bahagia karena ia jadi sering melihat Salinem. Dari jarak yang masih bisa terdengar suara, Salimun memandang dua bocah itu. Salinem yang kurus kecil duduk di hadapan Soeratmi. Selisih umur mereka empat tahun, tapi bisa begitu akrab, macam kakak-adik saja.
Salimun berdiri di balik pintu, dua bocah itu ndeprok6 di teras. Gelas kopi yang hendak ia antar ke ruangan Gusti Wedana masih bertahan di tangannya. Rasa penasaran merebut perhatian. Pelan, ia bergerak ke sela pintu, mengintip permainan mereka. Ia cukup terkejut, boneka kain itu ada di tangan Salinem, dibanting-banting ke lantai.
Herannya, Gusti Soeratmi tidak marah padahal itu boneka kesayangan yang hampir tak pernah berpisah dengannya. Ia cuma berkata, “Tidak boleh begitu. Kasihan, nanti dia sakit.” Salinem menatapi Gusti Soeratmi yang lantas membuai-buai boneka kain sambil berkata, “Begini caranya.”
Tak lama, Salinem sudah mengikuti gerakannya. Rambut Salinem yang tipis terikat rapih ke belakang. Pasti Soeratmi yang membantunya. Salimun berjalan masuk ke dalam ruang Gusti Wedana.
Pintu berderit pelan, namun Gusti wedana sama sekali tak menengok; sedang sibuk, berhadapan dengan lembaran-lembaran kertas. Meja ukiran besar jadi seperti terlalu kecil untuk tubuhnya yang tambun.
“Ndara,” ucap Salimun sambil meletakkan gelas kopi di meja.
“Iya, Mun.”
“Terima kasih banyak, Ndara.”
“Buat apa?”
“Sudah mengizinkan Salinem ada di sini.”
Gusti Wedana menghentikan gerakan tangannya, wajah bulatnya tersenyum memandang Salimun. “Aku juga senang, Mun.”
“Saya tidak tahu bagaimana bisa lebih berterima kasih, Ndara.”
“Jangan berlebihan, Mun,” Gusti Wedana kembali pada tumpukan kertasnya. “Apa lagi?”
“Itu saja, Ndara.”
Gusti Wedana tidak menjawab lagi, dan Salimun mafhum benar bahwa itu artinya ia harus segera keluar ruangan. Ia merasa melihat Lasiyem sedang tersenyum.
_
Waktu berjalan terus. Tahu-tahu sudah 1929. Salinem sudah lima tahun saja, namun sakitnya Salinem waktu itu benar-benar membuat Salimun kapok. Ia khawatir kalau Salinem menyusul ibunya. Anak itu satu-satunya alasan Salimun hidup, dan ia belum mau pisah sama anak itu. Tapi, perpisahan kerap tak bisa direncanakan.
Gusti Soekatmo yang biasanya menginap di Sukoharjo, malam ini pulang ke Tawangsari, di rumah Gusti Asisten. Mbok Yah dan Gusti Soeratmi ikut.
Sudah dua malam sakit kepala Salimun tak reda-reda. Ia sudah minum obat yang dibeli dari warung, namun sakit kepala ini tak menyerah, malah membuat kakinya kesemutan. Salimun memijat kepalanya sendiri, seperti ada tawon mengamuk di sana. Menyengat. Merambat. Ujung-ujung jarinya terasa dingin, mati rasa.
Ia duduk di dipan tidurnya, Salinem tidur tenang di seberangnya. Salimun menarik napas. Duh, Gusti, jangan bikin hamba mati dulu, desisnya, Salinem masih kecil. Kepanikan lain menjulur dari ujung-ujung ibu jari kakinya, melumpuhkan lututnya. Telinganya berdenging, mengalir ke leher, membuatnya kaku, mengeras. Salimun mencoba bangun, merangkak keluar. Sakit luar biasa melumpuhkan tapi ia harus melawan. Ia terus merangkak ke depan kamar Mbok Yah. Bukankah Mbok Yah sedang tak di sana? Hatinya tersayat membayangkan Salinem, dan bayangan Lasiyem menembus kelopak matanya. Lasiyem, aku belum mau ketemu kamu. Apa pun, tolong sampaikan.
Entah siapa yang kini tidur di dalam kamar itu, namun sebelum kepalan tangannya sempat menggedor pintu, Salimun jatuh dipeluk kegelapan. Ia tak sanggup lagi melawan. Kesadaran terakhirnya berkata: Las, akhirnya kita ketemu juga.
_
1 Sebenarnya, kasihan sekali
2 Tuan
3 Mari saya antarkan.
4 Bukan
5 Daun kelapa kering.
6 Duduk di lantai.
**
Baca ribuan cerita seru dan tuliskan ceritamu sendiri di Storial!