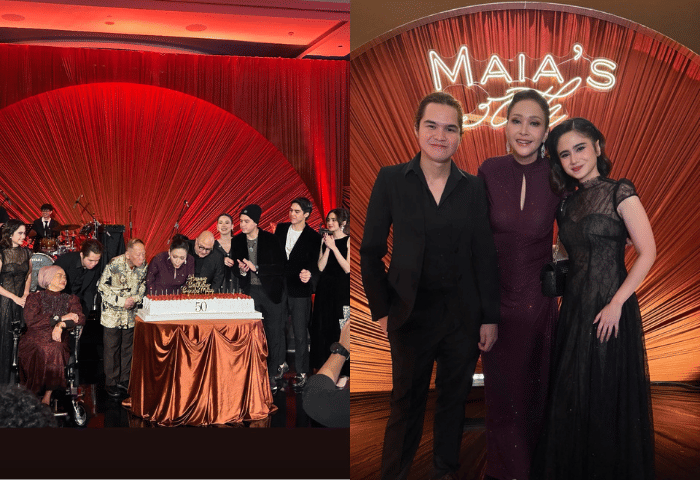Kenapa Body Positivity Sering Disalahartikan Jadi Malas Jaga Diri?

- Publik salah paham akan makna menerima diri. Menerima diri bukan berarti berhenti berkembang, tetapi memperlakukan tubuh dengan baik.
- Media sosial mengaburkan batasan positif dan menjadi toksik. Konten body positivity sering mendorong pola pikir permisif yang salah arah.
- Individu menggunakan body positivity sebagai alasan untuk menghindari perubahan. Masyarakat terjebak pada label tanpa memahami esensinya.
Gerakan body positivity awalnya muncul sebagai bentuk perlawanan terhadap standar kecantikan yang dianggap masih terlalu sempit dan diskriminatif. Tujuannya sederhana agar setiap orang bisa menerima tubuhnya sendiri tanpa tekanan sosial untuk terlihat ideal. Dalam konteks ini, menerima tubuh bukan berarti menolak perawatan diri, melainkan memberi ruang untuk mencintai diri sendiri tanpa syarat.
Namun, makna dari body positivity kini sering melenceng. Banyak orang menggunakannya sebagai pembenaran untuk berhenti menjaga kesehatan, baik fisik maupun mental. Isu ini jadi penting karena pemahaman yang keliru bisa memicu dampak serius dalam kehidupan sehari-hari. Berikut lima hal yang menjelaskan kenapa body positivity bisa disalahartikan dan bagaimana sebaiknya melihatnya secara lebih bijak.
1. Publik salah paham akan makna menerima diri

Banyak yang mengira bahwa menerima diri berarti tidak perlu berubah sama sekali. Padahal, penerimaan diri adalah titik awal untuk mencintai diri sendiri secara utuh, bukan alasan untuk berhenti berkembang. Kalau konteksnya dimaknai hanya sebagai “terima saja apa adanya tanpa usaha,” maka yang muncul bukan lagi penghargaan, melainkan penyangkalan terhadap kebutuhan dasar tubuh.
Sikap semacam ini dapat membuat seseorang abai terhadap sinyal tubuh yang butuh perhatian. Misalnya, malas berolahraga karena merasa tubuhnya “sudah cukup baik” padahal gampang lelah atau sering sakit. Dalam jangka panjang, sikap pasif ini justru merugikan kesehatan. Body positivity semestinya jadi alasan untuk memperlakukan tubuh dengan baik, bukan membiarkannya tanpa perawatan sama sekali.
2. Media sosial mengaburkan batasan positif dan menjadi toksik

Konten bertema self love dan body positivity sering viral, tapi tidak semuanya menyampaikan pesan yang sehat. Beberapa unggahan justru mendorong normalisasi gaya hidup yang tidak seimbang atas nama penerimaan diri. Ketika pesan-pesan itu dikonsumsi tanpa refleksi, publik bisa terjebak dalam pola pikir permisif yang salah arah.
Misalnya, seseorang merasa tidak perlu tidur cukup atau menjaga pola makan karena ingin bebas aturan, padahal, tubuh tetap punya kebutuhan biologis yang tidak bisa diabaikan. Kalau media sosial menjadi satu-satunya referensi, nilai-nilai kesehatan bisa tergeser oleh tren konten yang belum tentu akurat. Body positivity jadi kabur maknanya karena lebih sering dikaitkan dengan kenyamanan instan dibanding keberlanjutan hidup sehat.
3. Individu menggunakan body positivity sebagai alasan untuk menghindari perubahan

Bentuk tubuh, kondisi kulit, atau ukuran berat memang tidak seharusnya jadi sumber rasa malu. Namun, ada kalanya orang menggunakan dalih body positivity untuk menghindari perubahan yang sebenarnya dibutuhkan. Ini bukan soal memaksakan standar tertentu, melainkan menyadari ketika tubuh memberi tanda-tanda ketidakseimbangan.
Contohnya, seseorang tahu kadar kolesterolnya tinggi, tapi malah memilih mengabaikannya karena merasa harus mencintai diri sendiri apa adanya. Ini berbahaya karena mencintai diri bukan berarti menolak perbaikan, tapi justru aktif menjaga kesejahteraan diri. Menghindari perubahan karena takut dianggap tidak body positivity hanya akan menciptakan kebingungan antara penerimaan dan pengabaian.
4. Masyarakat terjebak pada label tanpa memahami esensinya

Label body positivity kini sering digunakan sebagai identitas, tapi sayangnya tanpa pemahaman mendalam. Sering kali, orang merasa cukup dengan menyebut dirinya pro terhadap gerakan ini tanpa benar-benar memahami nilai yang dibawanya. Padahal, konsep ini seharusnya menekankan inklusivitas, kesadaran diri, dan keseimbangan antara penerimaan dan perawatan.
Ketika label menjadi fokus utama, esensinya justru tertinggal. Banyak yang akhirnya terjebak pada pembenaran perilaku tanpa mempertanyakan apakah itu benar membawa kebaikan jangka panjang. Misalnya, tidak memeriksakan diri ke dokter karena khawatir dianggap tidak menerima tubuh. Padahal, perhatian semacam itu adalah bentuk cinta pada diri sendiri yang justru mendalam.
5. Kebiasaan malas dirasionalisasi dengan istilah positif

Tidak sedikit orang yang mulai melabeli kebiasaan tidak sehat sebagai bentuk penerimaan diri. Malas bergerak, konsumsi berlebih, atau tidur tidak teratur kadang dikemas dengan istilah positif seperti me time, self love, atau acceptance. Rasionalisasi ini terlihat menarik, apalagi jika dikaitkan dengan gerakan body positivity yang tengah populer.
Tapi, ketika kebiasaan tidak sehat dirayakan dengan dalih mencintai diri, yang sebenarnya terjadi adalah penolakan tanggung jawab. Menerima diri bukan berarti tidak punya batas. Justru karena mencintai diri, seseorang seharusnya mampu membedakan mana yang menyehatkan dan mana yang hanya memberi kenyamanan sesaat. Jika tidak, maka body positivity hanya akan jadi tameng untuk tetap berada di zona nyaman yang merugikan.
Body positivity bukan alasan untuk berhenti merawat diri, melainkan dorongan agar kamu bisa mencintai tubuh tanpa tekanan sosial yang sempit. Tapi, cinta pada diri juga perlu disertai tanggung jawab dan kesadaran bahwa tubuh butuh dijaga. Memahami makna body positivity secara utuh bisa menjadi kunci agar gerakan ini tidak melenceng dari tujuan awalnya.