Menilik Lebih Dalam Legalitas Pernikahan Beda Agama di Indonesia

Seiring dengan perkembangan zaman dan waktu serta dengan bergeraknya roda globalisasi yang semakin masif, membuat permasalahan masyarakat Indonesia yang juga semakin kompleks, termasuk kompleksitas masalah pada perkawinan. Muncul berbagai jenis ataupun kasus perkawinan di Indonesia yang layak untuk didiskusikan dan diperbincangkan, karena perkawinan merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan sebab akibat antara pasangan yang melakukan perkawinan, salah satunya perkawinan beda agama yang akhir-akhir ini menjadi fenomena di Indonesia.
Perkawinan beda agama memang bukan merupakan hal yang baru bagi masyarakat Indonesia yang multikultural. Namun demikian, tidak berarti bahwa persoalan perkawinan beda agama tidak dipermasalahkan, bahkan cenderung selalu menuai kontroversi di kalangan masyarakat. Oleh sebab itu, perkawinan beda agama adalah perkawinan yang sangat sulit diterima bagi kalangan masyarakat multikultral yang agamis seperti di Indonesia, karena perkawinan merupakan ikatan yang sangat dalam dan kuat sebagai penghubung antara seorang pria dengan seorang wanita dalam membentuk suatu keluarga.
Penyatuan antara seorang pria dengan wanita ini jelas memiliki konsekuensi yaitu akibat hukum. Maka dari itu, diperlukan adanya norma hukum yang jelas dan pasti, dan sejauh ini perkawinan di indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP). Dalam Pasal 1 UUP menyebutkan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Jika ditafsirkan secara gramatikal, maka perkawinan tersebut harus dilaksanakan berdasarkan “prinsip agama” sebagaimana yang dituangkan dalam Pasal 2 ayat (1) UUP.
Namun dari pada itu, sebenarnya dalam UUP mengenal frasa “perkawinan campur” yang diatur dalam Pasal 57 UUP, tetapi perkawinan campur yang dimaksud dalam Pasal 57 UUP adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaran, bukan karena perbedaan agama. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa indonesia tidak mengadopsi perkawinan yang berbesik beda agama, karena dalam UU tersebut mendelegasikan bahwa negara mengesahkan perkawinan itu selama agama membolehkan dan mengesahkan perkawinan yang dilakukan.
Ditambah lagi, Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan No. 68/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Materil Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam putusanya Mahkamah berpendapat bahwa “Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, agama menjadi landasan dan negara mempunyai kepentingan dalam hal perkawinan.
Agama menjadi landasan bagi komunitas individu yang menjadi wadah kebersamaan pribadi-pribadi dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa serta turut bertanggung jawab terwujudnya kehendak Tuhan Yang Maha Esa untuk meneruskan dan menjamin keberlangsungan hidup manusia. Agama menetapkan tentang keabsahan perkawinan, sedangkan Undang-Undang menetapkan keabsahan administratif yang dilakukan oleh negara.” Dengan adanya tafsir dalam putusan tersebut, MK menolak permohonan pemohon Judicial Review, dan semakin menguatkan larangan untuk dilaksanakanya pernikahan beda agama karena putusan MK bersifat final dan mengikat.
Namun walaupun UUP telah mengatur larangan perkawinan beda agama dengan tegas, serta juga diperkuat dengan adanya putusan MK yang semakin mengunci untuk tidak dilakukanya perkawinan beda agama, tapi dalam pelaksanaanya tetap ada perkawinan beda agama yang dapat dilaksanakan, bahkan diizinkan oleh pengadilan melalui penetapan pengadilan. Hal ini tentu menimbulkan kerancuan hukum, sebab ada perangkat hukum yang melarang, tapi larangan itu tetap dilakukan bahkan disahkan melalui penetapan pengadilan.
Hal itu dapat terjadi karena berdasarkan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam UU tersebut tersirat bahwa “Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan”. Ini dapat dilihat pada penjelasan Pasal 35 huruf a dimana dijelaskan bahwa maksud dari Pasal 35 huruf a adalah perkawinan yang dilakukan antar umat penganut beda agama. Dan dalam pelaksanaan, penetapan pengadilan tersebut juga mengizinkan untuk dilaksanakanya perkawinan beda agama. Jadi perkawinan beda agama dapat dilaksanakan apabila sudah ada sumber hukum yaitu penetapan pengadilan yang mengizinkan untuk dilaksanakanya perkawinan beda agama.
Ada beberapa penetapan pengadilan yang penulis jadikan bahan rujukan sebagai contoh penetapan pengadilan yang mengizinkan untuk dilakukanya perkawinan beda agama, seperti Penetapan Pengadilan No. 186/Pdt.P/2018/Pn.Skt., Penetapan No. 220/Pdt.P/2020/PN Bpp., Penetapan No. 959/Pdt.P/2020/PN.Bdg., Penetapan No.12/Pdt.P/2022/PN.Ptk, Penetapan No. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby., dan Penetapan No. 512/Pdt.P/2022PNJkt.Tim. Penetapan-penetapan tersebut ditetapkan dengan dasar hukum Putusan Mahkamah Agung (MA) No. 1400 K/Pdt/1986 yang di dalamnya mengindahkan untuk dilakukanya perkawinan beda agama.
Namun yang menjadi pertanyaan, apakah Putusan MA masih dapat menjadi sumber hukum sebagai pembuatan penetapan pengadilan? Padahal sudah ada Putusan MK yang mengunci untuk tidaK dilaksanakanya perkawinan beda agama. Yang jelas penetapan-penetapan yang mengizinkan untuk dilakukanya perkawinan beda agama tersebut hanya bersumber kepada putusan MA No. 1400 K/Pdt/1986 yang bertentangan dengan UUP yang melarang perkawinan beda agama yang juga diperkuat dengan Putusan MK No. 68/PUU-XII/2014. Hal ini tentu menimbulkan ketidakpastian hukum, sebab sebenarnya sumber hukum yang mana yang harus digunakan dalam membuat penetapan pengadilan terkait perizinan pelaksanaan perkawinan beda agama.
Sebagai sebuah putusan yang memiliki fungsi perundang-undangan (negative legislator), sifat putusan MK yang final tersebut mengikat semua pihak baik warga negara ataupun lembaga-lembaga negara, termasuk MA dan badan peradilan yang ada di bawahnya. Oleh karenanya, semua organ penegak hukum, terutama pengadilan terikat untuk tidak lagi menerapkan hukum yang telah dibatalkan. Putusan tersebut mesti dijadikan acuan atau rujukan dalam memperlakukan hak dan kewenangannya. Hans Kelsen juga mengemukakan MA merupakan institusi atau organ negara yang terikat pada hasil pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar oleh MK.
Pun demikian, walapun Putusan MA No. 1400 K/Pdt/1986 mempertimbangkan dengan objek Konstitusi pada UUP, tetapi hal tersebut sekarang menjadi kewenangan MK. Maka dari itu, apabila ada pertentangan antar putusan MA dan putusan MK, yang harus diikuti dan ditaati sebagai sumber hukum adalah putusan MK karena secara tidak langsung MK membatalkan putusan MA No.1400 K/Pdt/1986, kemudian sesuai juga dengan asas Lex posterior derogat legi priori karena putusan pengadilan juga merupakan sumber hukum yang mengikat.
Sejalan dengan itu, Saldi Isra, berpendapat bahwa perbedaan penafsiran antara dua lembaga ini apabila perbedaan penafsiran terhadap undang-undang tersebut benar-benar terjadi, maka yang semestinya diikuti adalah penafsiran yang dilakukan oleh MK. Maka dari itu MA tunduk pada penafsiran yang dilakukan MK terhadap UUD 1945 dalam menilai dan menafsirkan sebuah atau bagian undang-undang tertentu.
Oleh sebab itu, Penetapan pengadilan yang dibuat setelah adanya Putusan MK No. 68/PUU-XII/2014 tidak boleh bertentangan dengan putusan MK, dan semestinya dalam membuat penetapan pengadilan harusnya bersumber pada putusan MK bukan Putusan MA, termasuk dalam pembuatan penetapan pengadilan terkait perizinan pelaksanaan perkawinan beda agama, guna mengharmonisasikan yurisprudensi yang menjadi sumber hukum untuk membuat penetapan atau putusan pengadilan yang lebih berkepastian hukum.
Jika hal yang telah penulis paparkan dijalani secara konsisten oleh pengadilan di bawah MA, maka sampai sekarang tidak mungkin masih ada perdebatan apakah perkawinan beda agama boleh dilaksanakan atau tidak boleh dilaksanakan. Kedua-dua hal tersebut dalam pelaksanaan masih dapat mungkin terjadi, karena kedua hal tersebut masih memiliki sumber hukum dan masih dapat dilaksanakan. Penulis hanya berpendapat bahwa harusnya MA menjalani putusan MK agar terciptanya kepastian hukum. Sebab baik secara yuridis maupun teoritis, keputusan MA yang tidak menaati dan tidak menjalani putusan MK secara konsisten adalah perbuatan tidak taat hukum.




























![[OPINI] Menakar Kelayakan Thomas Djiwandono Jadi Deputi BI](https://image.idntimes.com/post/20250115/sesi-1-sal02498-7b8580309183379b3c8eba91d7bc3c5b-273b07c328eb87f261cb80b9e2a0fd07_watermarked_idntimes-1.JPG)
![[OPINI] Apakah Perubahan Kemasan Produk Menjadi Saset Tanda Resesi?](https://image.idntimes.com/post/20260208/perubahan-ukuran-sachet-resesi-ekonomi_57b6ce7b-02bb-459b-b0d3-ce678054e335.JPG)
![[OPINI] Kenapa Tulisan yang Ditulis Sendiri Sering Dibilang Buatan AI?](https://image.idntimes.com/post/20260123/alasan-gak-semua-hal-layak-ditulis-menulis-berlebihan_d71a7bb9-f249-48fb-be75-26f38e13ac2f.jpeg)

![[OPINI] Relasi Epstein-Chomsky, dan Integritas Intelektual Kiri](https://image.idntimes.com/post/20260204/efta00003652-0_3909c293-079d-4870-ba54-8c60af9ef07b.jpg)
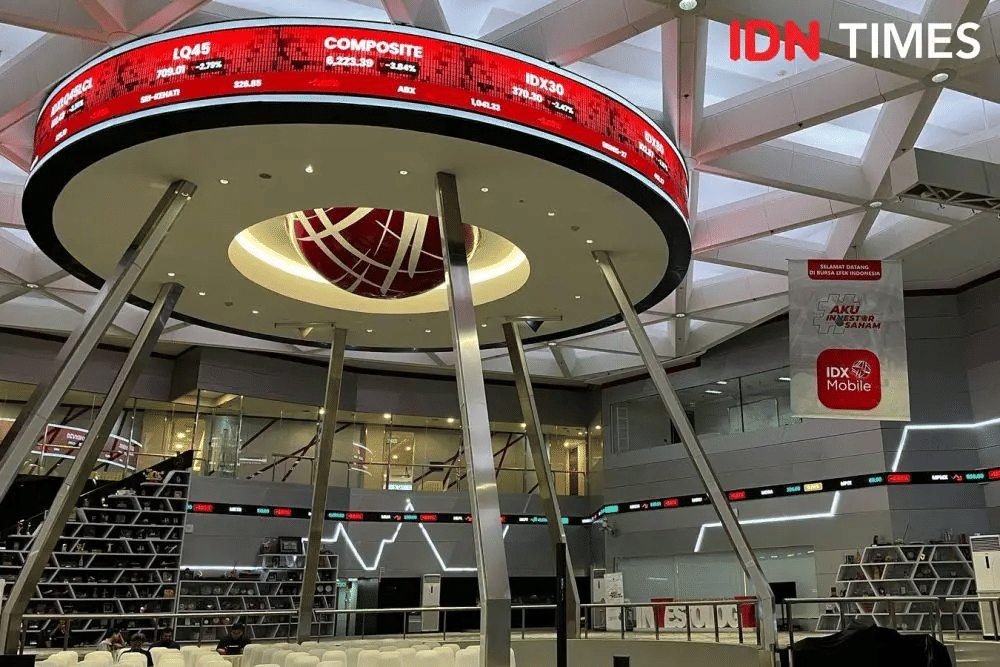


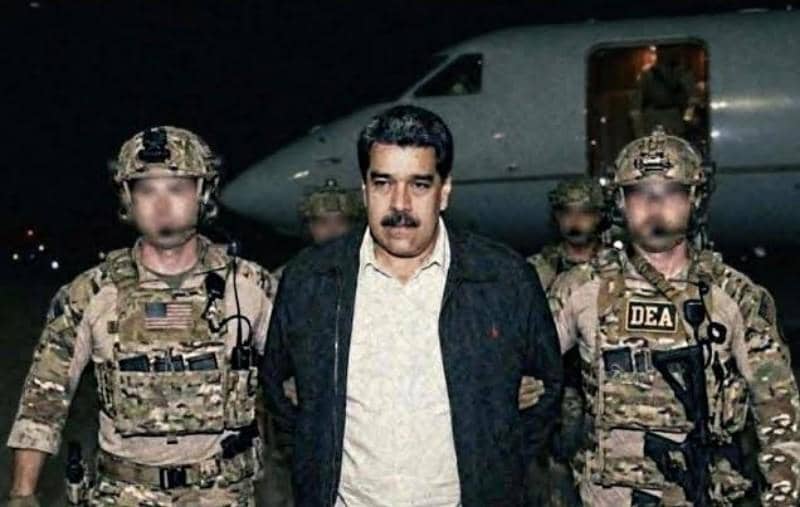


![[OPINI] Berhenti Berlindung di Balik Kalimat “Aku Orangnya Emang Begini”](https://image.idntimes.com/post/20251018/pexels-kampus-7555858_e0f0519c-fde0-4ab4-8965-0e12dabbd0b7.jpg)
![[OPINI] Peran Perempuan dalam Wujudkan Harmoni Sosial dan Lingkungan](https://image.idntimes.com/post/20250802/pexels-julia-m-cameron-8841582_4f4cbb51-bd42-46f6-ba78-fa42532e55a6.jpg)

![[OPINI] Setelah Chavez dan Castro: Ujian Revolusi Bolivarian](https://image.idntimes.com/post/20260108/upload_dd95bcd42f154a2960cdda3ed70e7109_4c8d29e1-0272-4459-9dbd-c40eeccc46c8.jpg)
![[OPINI] Nikah Muda: Alasan Kenapa Gak Semua Cerita Cinta Bisa Ditiru](https://image.idntimes.com/post/20260103/pexels-danu-hidayatur-rahman-1412074-2852135_2f19e731-6a9c-4db9-8adb-4642e15915d2.jpg)


