Bagaimana Media Sosial Bisa Jadi Lahan Subur Online Child Grooming?

Child grooming adalah isu serius yang masih kerap luput dari perhatian publik
Media sosial menjadi ruang subur bagi praktik child grooming, terutama di kalangan anak dan remaja
Pencegahan child grooming memerlukan kolaborasi antara regulasi, teknologi, dan edukasi
Isu child grooming kembali ramai diperbincangkan setelah Aurelie Moeremans membagikan pengalaman traumatisnya melalui memoar berjudul Broken Strings. Buku tersebut memicu beragam respons dari publik, mulai dari komunitas bookstagram, pegiat literasi, hingga kreator konten di media sosial. Aurelie juga menyampaikan kisah ini melalui akun media sosial pribadinya, @aurelie.
Dalam Broken Strings, Aurelie mengungkap bahwa ia mengalami child grooming saat berusia 15 tahun oleh seseorang yang usianya hampir dua kali lipat dari dirinya. Kisah ini ditulis sepenuhnya dari sudut pandang korban, tanpa romantisasi, dan menyoroti proses manipulasi yang ia alami. Pendekatan tersebut membuat buku ini tidak hanya bersifat personal, tetapi juga edukatif bagi pembaca.
Keberanian Aurelie untuk speak up turut menyadarkan publik bahwa child grooming merupakan isu serius yang masih kerap luput dari perhatian. Media sosial yang tampak ramah, terbuka, dan akrab ternyata menyimpan celah yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan seksual. Selain child grooming, perilaku ini juga berkembang ke dalam bentuk lain yakni online child grooming, di mana teknologi dan ruang digital digunakan sebagai sarana utama pendekatan terhadap anak. Anak dan remaja menjadi kelompok paling rentan karena intensitas interaksi mereka di dunia maya. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana media sosial bisa menjadi ruang subur bagi praktik child grooming, sekaligus menyadari perlunya perlindungan dan literasi digital yang lebih kuat.
1. Apa itu Child Grooming dan mengapa penting?

Sebelum membahas fenomena child grooming, terlebih dahulu kita perlu tahu tentang definisi anak. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan. Definisi ini menegaskan bahwa anak memiliki hak yang harus dilindungi secara khusus oleh negara, keluarga, dan masyarakat. Dalam konteks hukum, anak dipandang sebagai individu yang memerlukan perlindungan ekstra karena keterbatasan kapasitasnya.
Penelitian Marhayani et al. tahun 2024 yang dimuat dalam Jurnal Legalitas menambahkan bahwa anak merupakan subjek hukum yang belum cakap hukum secara penuh. Oleh karena itu, orang tua atau wali memiliki kewajiban untuk menjaga, membimbing, dan melindungi anak, mengingat mereka telah memiliki kecakapan hukum. Posisi anak yang belum mandiri secara hukum ini menjadikannya kelompok yang rentan terhadap berbagai bentuk pelanggaran hak, termasuk eksploitasi dan kekerasan seksual. Seiring meningkatnya kasus eksploitasi anak dan remaja, khususnya terhadap remaja perempuan, isu child grooming pun semakin mendapat perhatian publik.
Ditinjau dari aspek perkembangan psikologis, anak yang berada pada rentang usia 12–18 tahun termasuk dalam fase remaja, yaitu masa transisi dari kanak-kanak menuju dewasa. Fase ini ditandai dengan proses pencarian jati diri, kebutuhan tinggi akan pengakuan sosial, dan keinginan untuk mendapatkan kasih sayang dan penerimaan. Pada saat yang sama, kematangan emosional remaja masih belum terbentuk secara utuh. Kondisi tersebut menjadikan remaja, terutama remaja perempuan, lebih rentan terhadap manipulasi emosional yang kerap digunakan dalam praktik child grooming.
Kerentanan ini semakin diperkuat oleh adanya relasi yang tidak setara antara anak dan pihak yang memiliki otoritas. Formas Juitan Lase et al., dalam temuan yang dipublikasikan di Jurnal Comita Servizio menjelaskan bahwa child grooming kerap terjadi dalam hubungan yang timpang, seperti antara anak dengan orang tua, guru, atau pemuka agama. Anak memandang figur-figur tersebut sebagai pihak yang memiliki kekuasaan dan otoritas lebih tinggi, sehingga tidak pantas untuk dibantah atau dilawan. Pola relasi semacam ini telah terbentuk sejak dini dan tertanam kuat dalam proses sosialisasi anak.
Akibatnya, ketika kekerasan seksual terjadi dalam relasi yang tidak setara tersebut, anak sering kali tidak memiliki kemampuan maupun keberanian untuk melawan. Dalam banyak kasus, anak justru cenderung menerima perlakuan tersebut atau memilih untuk menutupinya. Kondisi ini menunjukkan bahwa child grooming tidak hanya berkaitan dengan niat jahat pelaku, tetapi juga dipengaruhi oleh struktur relasi sosial dan budaya yang menempatkan anak pada posisi subordinat. Oleh karena itu, pemahaman terhadap aspek hukum, psikologis, dan relasi kuasa menjadi krusial dalam upaya pencegahan dan penanganan child grooming.
2. Bagaimana child grooming terjadi di media sosial?

Di era digital saat ini, fenomena child grooming semakin mudah terjadi seiring masifnya penggunaan media sosial di kalangan remaja. Platform seperti Instagram, WhatsApp, TikTok, hingga gim daring menyediakan ruang interaksi yang luas dan mudah diakses. Melalui media sosial, pelaku dapat dengan cepat mengamati aktivitas korban, mengumpulkan informasi pribadi, dan memulai komunikasi tanpa perlu bertemu secara langsung.
Media sosial juga memungkinkan pelaku grooming menyamarkan identitas dan berpura-pura menjadi teman sebaya korban. Pelaku memberikan perhatian, empati, dan dukungan emosional secara bertahap untuk membangun kedekatan. Karena proses ini berlangsung di balik layar dan menyerupai interaksi sehari-hari, banyak remaja perempuan tidak menyadari bahwa mereka sedang dimanipulasi. Kesadaran baru sering muncul ketika relasi tersebut berkembang menjadi kontrol, tekanan seksual, atau bentuk kekerasan lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa media sosial dapat menjadi pintu masuk yang sangat efektif bagi praktik child grooming.
Di sisi lain, peran orang tua menjadi semakin krusial menghadapi risiko ini. Sayangnya, masih banyak orang tua belum melakukan pengawasan optimal terhadap aktivitas digital anak. Hal ini terutama terjadi pada orang tua generasi X atau Y yang kurang akrab terhadap teknologi dan fitur keamanan media sosial. Ketidakpahaman tersebut membuat orang tua kesulitan mengenali tanda-tanda risiko, seperti pertemanan mencurigakan, pesan dari orang asing, atau pola interaksi tidak sehat. Akibatnya, anak menjadi lebih rentan terpapar praktik grooming karena pengawasan digital tidak berjalan maksimal.
Berdasarkan CATAHU (Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan) 2024 yang dirilis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), tercatat 1.791 kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) dilaporkan ke Komnas Perempuan sepanjang 2024. Angka tersebut mengalami kenaikan 40,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini tidak hanya menunjukkan bertambahnya kesadaran korban untuk melapor, tetapi juga mengindikasikan bahwa kasus kekerasan di ruang digital memang semakin meningkat.
Menariknya, data tersebut mencatat pelaku terbanyak di ranah publik berasal dari teman di media sosial yang mencapai 515 kasus. Temuan ini menegaskan bahwa ruang digital kini menjadi medium semakin rawan bagi terjadinya kekerasan, khususnya terhadap perempuan dan remaja. Pelaku memanfaatkan perkembangan teknologi untuk melakukan berbagai bentuk kekerasan, mulai dari intimidasi, pemerasan, penyebaran konten pribadi, hingga praktik child grooming.
3. Media sosial sebagai ruang interaksi berisiko

Media sosial pada dasarnya dirancang sebagai ruang interaksi yang terbuka, cepat, dan personal, terutama melalui fitur seperti direct message, komentar, dan grup privat. Bagi anak dan remaja, ruang ini sering dipersepsikan sebagai lingkungan yang aman karena digunakan untuk bersosialisasi sehari-hari. Namun, karakter media sosial yang minim pengawasan langsung membuatnya rentan dimanfaatkan oleh pelaku child grooming. Interaksi yang awalnya tampak wajar dan ramah dapat berkembang menjadi relasi manipulatif tanpa disadari korban.
Pelaku grooming kerap memanfaatkan sifat media sosial yang mendorong kedekatan emosional dan intensitas komunikasi. Hubungan dapat dibangun secara bertahap melalui percakapan rutin, perhatian personal, dan validasi emosional yang konsisten. Dalam banyak kasus, komunikasi berlangsung di ruang privat yang tidak terlihat oleh orang tua atau pihak lain. Kondisi ini menjadikan media sosial sebagai medium yang efektif bagi pelaku untuk membangun kepercayaan dan mengisolasi korban secara psikologis.
Risiko tersebut diperparah oleh anonimitas identitas dan kemudahan membuat akun palsu di berbagai platform. Pelaku dapat menyamar sebagai teman sebaya, figur pendukung, atau bahkan mentor, sehingga sulit dikenali oleh korban. Anak sering kali tidak memiliki cukup pengalaman untuk membedakan interaksi sehat dan manipulatif di ruang online. Akibatnya, relasi yang berbahaya bisa berlangsung dalam waktu lama tanpa terdeteksi.
4. Upaya pencegahan child grooming di media sosial

Meningkatnya kasus child grooming yang berujung pada kekerasan seksual terhadap remaja perempuan menunjukkan pentingnya upaya pencegahan yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari keluarga, sekolah, masyarakat, hingga negara. Salah satu langkah awal yang krusial adalah memberikan pemahaman tentang batasan tubuh (body boundaries), yaitu pengetahuan mengenai bagian tubuh yang boleh dan tidak boleh disentuh oleh orang lain. Edukasi ini idealnya mulai diperkenalkan sejak anak berusia 4–6 tahun sebagai fondasi perlindungan diri. Selain berfungsi mencegah potensi pelecehan, pengenalan body boundaries juga berperan dalam membangun rasa percaya diri anak serta menanamkan kesadaran bahwa tubuh mereka berharga dan layak dihormati. Peran orang tua menjadi kunci dalam tahap awal ini, yang kemudian diperkuat oleh guru ketika anak mulai memasuki jenjang pendidikan formal, termasuk saat anak menghadapi perubahan fisik dan emosional di masa pubertas.
Selain edukasi dasar, dukungan sosial dan emosional yang konsisten dari orang tua juga memiliki peran penting dalam pencegahan child grooming. Anak yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang penuh kasih, kepercayaan, dan keterbukaan cenderung memiliki kemampuan lebih baik untuk mengenali perhatian yang tulus dan membedakannya dari manipulasi. Komunikasi yang hangat dan tidak menghakimi membuat anak merasa aman untuk berbagi pengalaman, termasuk ketika menghadapi situasi yang membingungkan atau tidak nyaman. Melalui mendengarkan dan menghargai cerita anak, orang tua membantu membangun kepercayaan diri, kemampuan menilai risiko, serta keberanian anak untuk mencari bantuan ketika menghadapi potensi kekerasan atau grooming.
Upaya pencegahan juga perlu diperkuat melalui edukasi tentang tanda-tanda child grooming, baik yang terjadi secara langsung maupun melalui media digital. Orang tua perlu menyadari bahwa media sosial memiliki potensi risiko selain manfaat, sehingga diperlukan aturan yang jelas terkait penggunaan gawai dan platform daring. Pembatasan waktu layar, pengawasan aplikasi yang digunakan, serta kesepakatan untuk berdiskusi ketika anak menerima pesan dari orang tidak dikenal merupakan langkah preventif yang penting. Di lingkungan sekolah, peran guru dan pendidik juga tidak kalah krusial melalui pendidikan kesehatan dan pendidikan seksual yang dirancang untuk meningkatkan kesadaran serta kemampuan anak melindungi diri. Edukasi yang berkelanjutan menggunakan metode dan materi yang sesuai usia, dapat mendorong perubahan perilaku positif dan memperkuat ketahanan anak terhadap berbagai bentuk kekerasan seksual, termasuk child grooming.
5. Upaya perlindungan hukum terhadap child grooming di media sosial

Selain peran orang tua dan guru, pemerintah juga memiliki tanggung jawab penting dalam mencegah terjadinya child grooming di ruang digital. Upaya tersebut diwujudkan melalui berbagai perangkat hukum yang bertujuan melindungi anak sebagai kelompok rentan sekaligus memberikan efek jera kepada pelaku. Regulasi ini menjadi landasan hukum untuk menindak praktik eksploitasi seksual terhadap anak, termasuk yang terjadi melalui media sosial dan platform digital.
Salah satu dasar hukum yang relevan adalah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Dalam Pasal 29, diatur bahwa setiap orang yang memproduksi, memperbanyak, menyebarluaskan, menyiarkan, memperjualbelikan, atau menyediakan materi pornografi dapat dikenai sanksi pidana. Ancaman hukuman yang ditetapkan cukup berat, yakni pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 tahun, serta denda minimal Rp250 juta hingga maksimal Rp6 miliar. Ketentuan ini mencakup pula konten pornografi yang melibatkan anak.
Selain itu, perlindungan anak juga diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam konteks online child grooming, perbuatan pelaku sering kali dilakukan melalui tipu muslihat, bujuk rayu, atau manipulasi emosional terhadap korban. Tindakan tersebut dapat dijerat melalui Pasal 76E juncto Pasal 82 ayat (1), yang melarang setiap orang melakukan kekerasan, ancaman, paksaan, kebohongan, atau bujukan terhadap anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Pelanggaran terhadap pasal ini diancam pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun, serta denda hingga Rp5 miliar.
Dalam kasus penyebaran atau transmisi konten pornografi anak melalui media elektronik, seperti jual beli video atau gambar di platform media sosial, pelaku juga dapat dijerat melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Ketentuan Pasal 45 ayat (1) juncto Pasal 52 ayat (1) mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan konten bermuatan kesusilaan dapat dipidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda hingga Rp1 miliar. Jika perbuatan tersebut melibatkan eksploitasi seksual anak, sanksi pidana dapat diperberat sepertiga dari ancaman pokok.
Rangkaian aturan hukum ini menunjukkan bahwa negara tidak memandang child grooming sebagai persoalan sepele, melainkan sebagai kejahatan serius yang membutuhkan penanganan tegas. Namun, keberadaan regulasi saja tidak cukup jika tidak diiringi pemahaman yang memadai tentang cara kerja media sosial dan teknologi digital. Media sosial bukanlah ruang yang sepenuhnya aman dan netral, melainkan ekosistem dengan risiko yang perlu disadari bersama.
Ke depan, pencegahan child grooming menuntut kolaborasi antara regulasi, teknologi, dan edukasi. Orang tua, pendidik, serta pengelola platform digital perlu memiliki kesadaran yang sama mengenai potensi risiko interaksi daring. Literasi digital anak tidak cukup hanya mengajarkan cara menggunakan teknologi, tetapi juga membekali mereka kemampuan mengenali relasi yang manipulatif dan tidak sehat. Dari berbagai pengalaman yang muncul ke ruang publik, masyarakat diingatkan bahwa perlindungan anak di dunia digital merupakan tanggung jawab bersama.































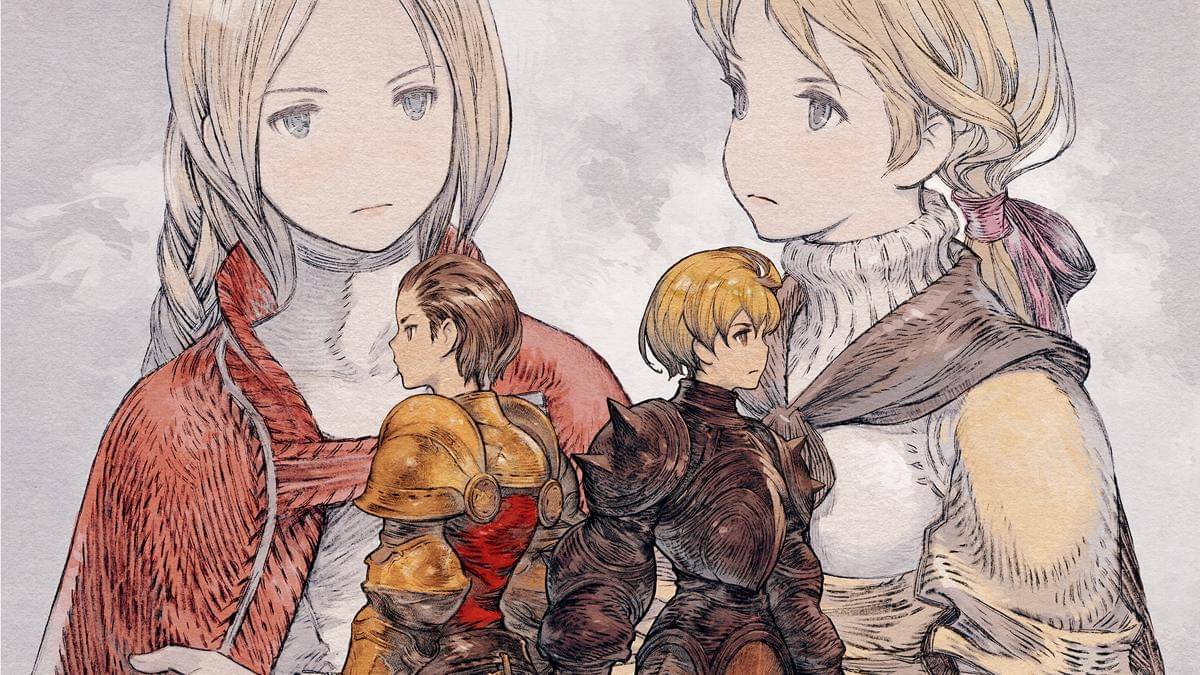



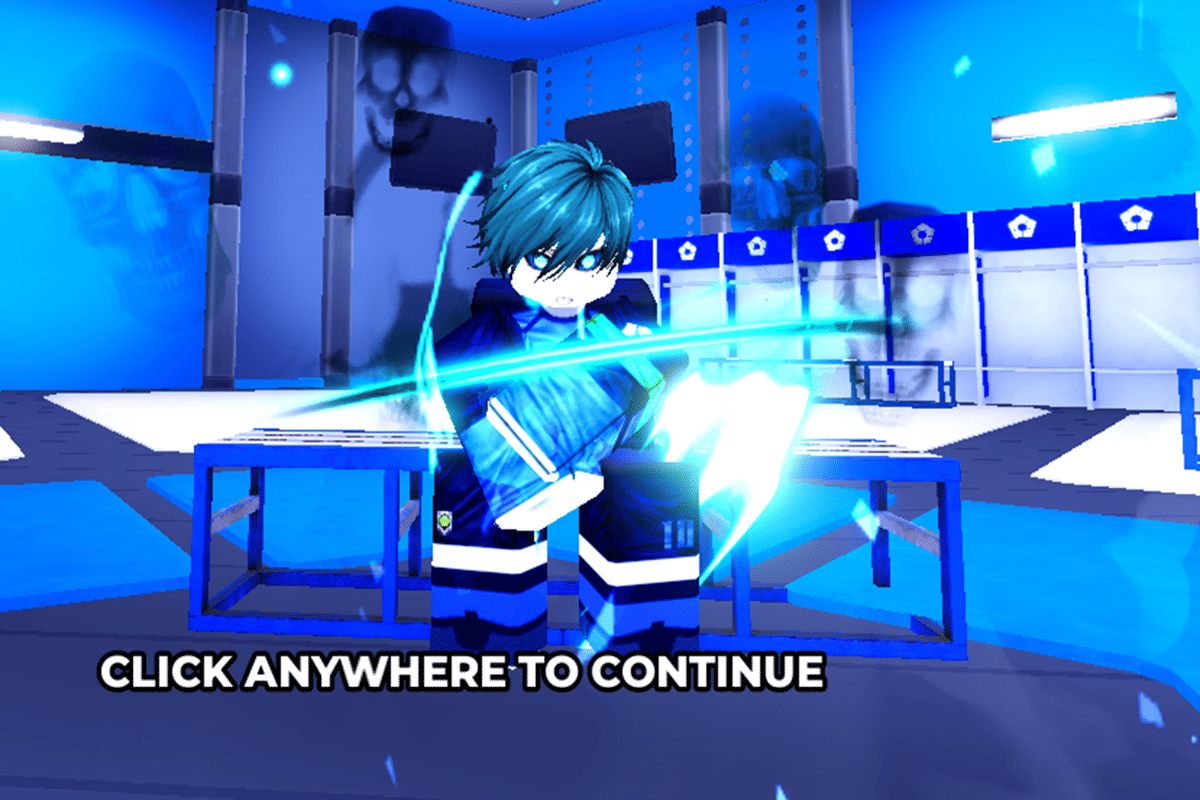


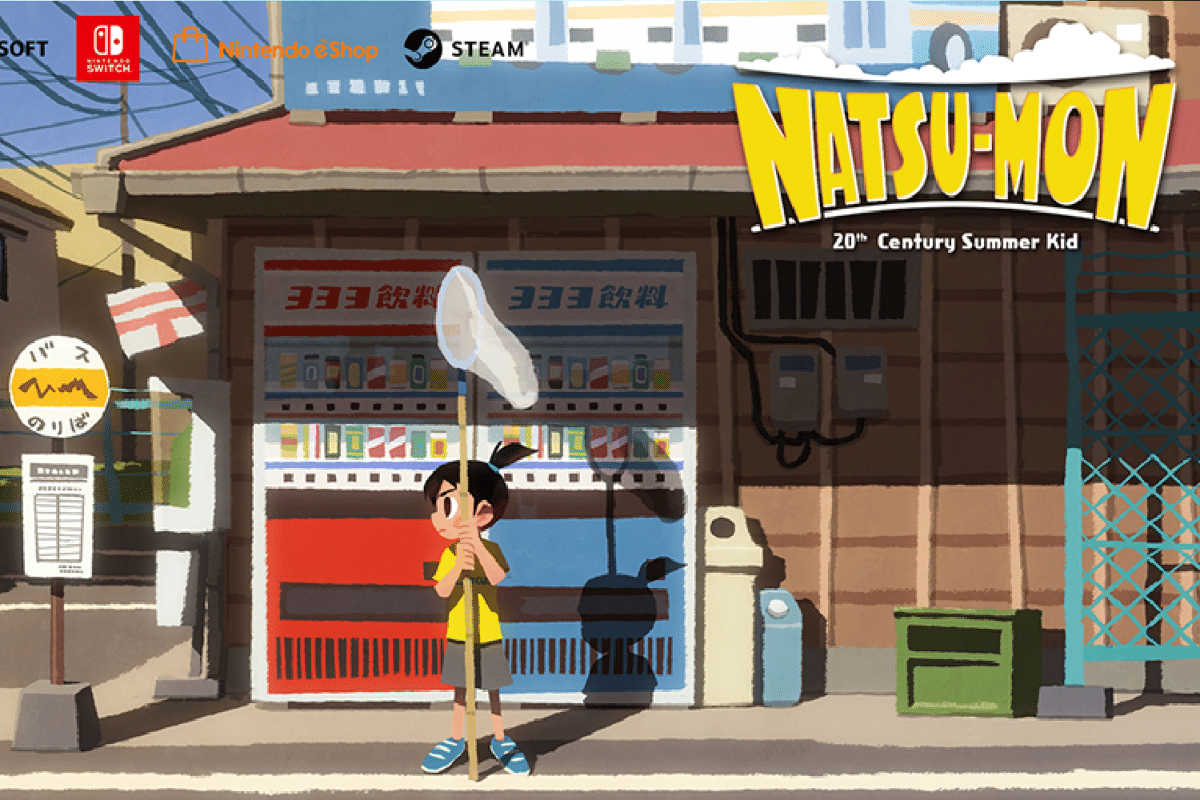




![[QUIZ] Reaksi Kamu Saat Internet Lemot Ungkap Gaya Menghadapi Tekanan](https://image.idntimes.com/post/20240306/hal-sepele-yang-bisa-memancing-emosi-apa-saja-hal-sepele-yang-bisa-bikin-emosi-internet-lemot-9cde86371d7fc78c91ae80a6ffab250e-118c8610674753f052efac2a0a377ed3.jpeg)


