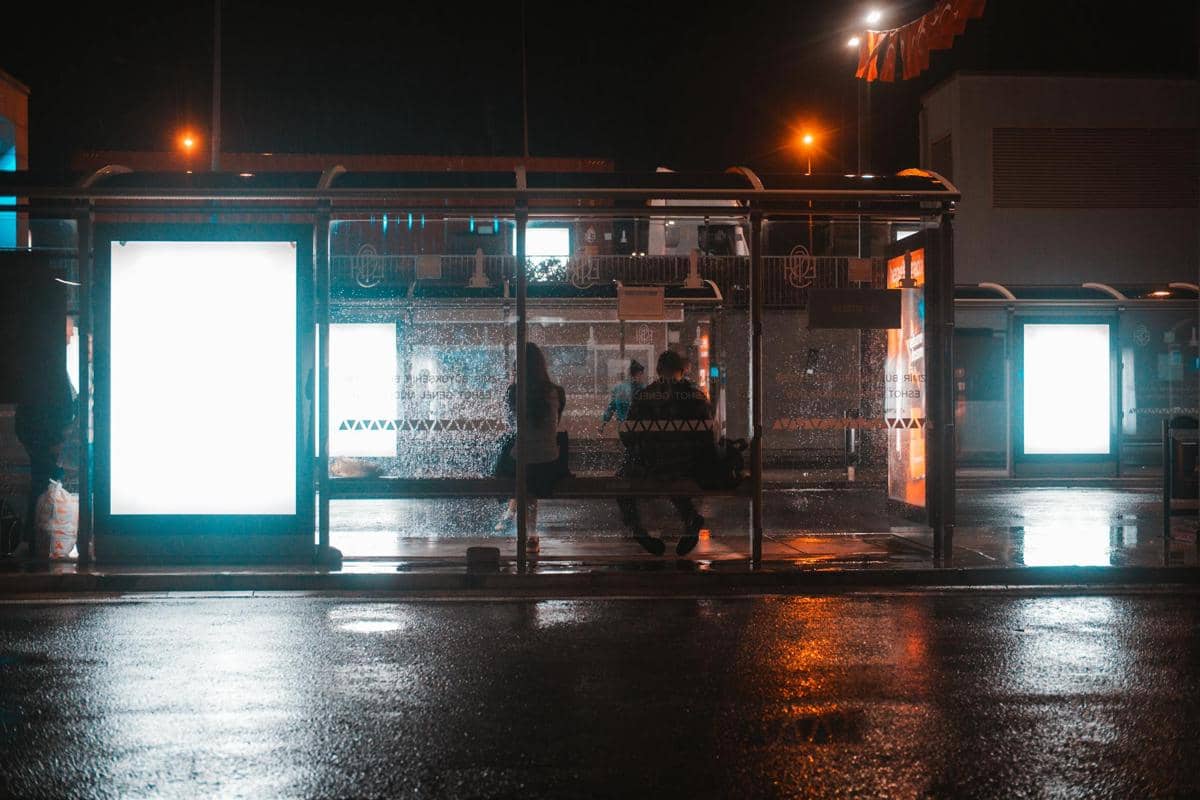- www.storial.co
- Facebook : Storial
- Instagram : storialco
- Twitter : StorialCo
- Youtube : Storial co
Rahasia Salinem - BAB 4
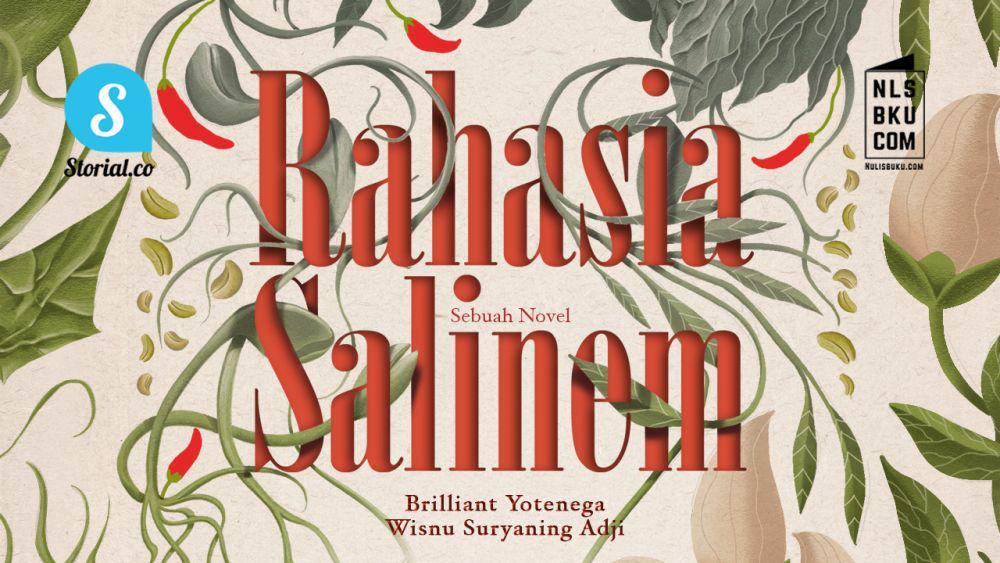
[4]
Mulai 1930
Mbok Yah memandang Salinem yang tengah bermain dengan Gusti Soeratmi. Kamu sial tapi beruntung, Nduk, ujarnya dalam hati. Di usia sekecil itu, Salinem harus memahami rasanya kehilangan orang tua. Walau, Salinem juga beruntung bisa bertemu dengan keluarga-keluarga terpandang yang hatinya luas macam Gusti Wedana dan Gusti Asisten. Entah akan seperti apa nasibmu, Nduk, kalau mereka bukan orang baik.
Mbok Yah memegang dua piring secara bergantian. Satu piring untuk Gusti Soeratmi dan satu lagi untuk Salinem. Setiap salah satu dari mereka selesai melempar bola, mereka berlari ke arahnya sambil menganga dan Mbok Yah akan memasukkan sendok ke sana.
Kalau tidak ada Gusti Soeratmi, Mbok Yah tidak tahu bagaimana cara menjelaskan pada Salinem bahwa ayahnya takkan kembali dari kuburan. Bukannya Gusti Soeratmi bisa menjelaskan, melainkan Gusti Soeratmi bisa menegaskan kalau Salinem tidak sendirian. Dua gadis itu terus saja bermain-main seakan-akan permainan adalah satu-satunya hal yang bisa terjadi pada hidup.
“Bukan begitu, Nem,” ujar Gusti Soeratmi, “tapi begini.” Gusti Soeratmi menunjukkan bagaimana cara melempar bola karet, lalu membolak-balik biji tembaga. Salinem yang baru lewat lima tahun memerhatikan benar-benar. Mbok Yah ingat kalau tadi pagi Daliyem mengatakan, “Semalam, Salinem bertanya dan aku tak bisa menjawabnya, Mbok.”
“Bertanya apa dia?”
“Dia tanya mengapa bapaknya belum pulang dari Klaten?”
“Dari Klaten, piye ta, Yem? Bapaknya wis seda.”
“Aku pernah bilang kalau bapaknya pergi ke Klaten habis dari kuburan,” Daliyem menunduk.
“Duh, Yem ..., jangan pernah bohong sama anak kecil. Kamu kira mereka ndak bisa mikir?”
“Iya, Mbok. Lantas, sekarang, piye?” raut Daliyem sudah seperti cucian kotor. “Salinem ndak tahu kalau bapaknya sudah mati, Mbok,” Daliyem merintih, “dan itu artinya bapaknya tidak akan kembali. Aku harus jawab apa?”
Mbok Yah menggeleng, “Aku juga ndak tahu,” sambil menatap Salinem yang berlari masuk ke Kawedanan akibat melihat Gusti Soeratmi yang sudah jadi sahabat barunya muncul. “Lalu, semalam, kamu jawab apa?”
“Aku ndak jawab apa-apa. Aku cuma menyuruhnya tidur saja. Aku ndak tahu bagaimana menjelaskan ‘mati’ pada anak seumur itu.”
“Memangnya, orang tua kita pernah menjelaskan kematian, Yem?” Mbok Yah menggeleng. “Ndak usah terlampau khawatir. Dia akan ngerti sendiri, seperti kita dulu.”
“Aku takut kalau nanti malam dia bertanya lagi. Anak-anak tak pernah berhenti bertanya sampai dapat jawaban, bukan?”
“Ya, sudahlah, Yem. Berdoa saja supaya nanti malam dia tidak bertanya.”
“Semoga, ya, Mbok. Aku tidak tahu harus beralasan apa lagi kalau dia masih bertanya,” Daliyem mengembuskan napas berat. “Wis, Mbok. Aku mangkat sik,” ucapnya sambil mengangkat keranjang bambu ke punggungnya.
Tubuh Daliyem yang mungil terus mengecil sampai kemudian hilang ketika ia berbelok. Lantas, Mbok Yah menutup pagar samping Kantor Kawedanan. Dari pintu kecil itulah Daliyem selalu mengantar Salinem ke sana. Mungkin, memang nasibmu selalu pindah-pindah tangan, ya, Ndhuk, bisik Mbok Yah dalam hati. Miris. Tapi, dia juga tak tahu harus berbuat apa.
Semenjak kematian Salimun, Salinem tinggal bersama bibinya itu dan tiap pagi diantar menuju Kawedanan untuk jadi teman main Gusti Soeratmi. Menjelang sore, Daliyem akan menjemputnya dan membawanya pulang.
“Mbok Yah,” tiba-tiba suara Gusti Soeratmi memanggil.
“Nggih, Ndara.”
“Bolanya sudah tidak membal lagi.”
“Ooh. Ayo, ke dapur. Bolanya sudah perlu direndam minyak tanah lagi,” lanjut Mbok Yah. “Tapi, habiskan dulu sarapannya.”
Kini Salinem dan Soeratmi berbaris berdampingan sambil menganga seperti dua ekor ikan yang minta diberi makan. Mbok Yah tersenyum lalu menyuapkan makanan secara bergantian ke mulut mereka. Keduanya mengunyah cepat-cepat kemudian berlari-lari ke dapur belakang. Mbok Yah mengikuti sambil terus tersenyum.
Sore harinya Gusti Wedana menghampiri Mbok Yah dan mengatakan, “Mbok, kalau besok bibinya Salinem datang, suruh tunggu aku. Aku ingin bicara.”
“Nggih, Ndara.”
“Ada apa, Yem?” selidik Mbok Yah habis Daliyem selesai bicara dengan Gusti Wedana. Ia sempat ingin menguping, tapi tidak jadi karena dua bocah itu terus berlari ke sana kemari dan ia harus mengikuti ke mana mereka pergi.
“Aku ndak tahu harus jawab apa, Mbok.”
“Memangnya, Gusti Wedana bilang apa?”
“Gusti Wedana mau Salinem sekalian pindah saja ke rumahnya daripada tiap hari bolak-balik terus.”
“Loh? Kenapa bingung? Malah bagus, ta?”
Suara Daliyem menegang, “Tapi, aku sayang sama Salinem, Mbok. Kalau dia diambil lagi, aku ....”
“Pikirkan yang baik untuk Salinem, Yem.” Mbok Yah memotong. “Di rumah Gusti Wedana, Salinem bisa lebih terjamin. Bukan aku bilang kalau kamu ndak bisa menjaminnya, ya, Yem. Aku cuma mau bilang kalau kondisinya akan lebih baik untuk masa depan Salinem.”
“Iya, Mbok,” ucap Daliyem dengan suara pelan. “Aku paham.” Daliyem kembali mengangkut bakul bambu ke punggungnya.
Mungkin ia kesal hingga terlihat seperti sedang melontarkan benda berat itu ke belakang dan Mbok Yah langsung sigap membantunya mengikat dengan kain. Bakul itu membuatnya tampak kedodoran. Orang kecil malah sering harus bawa beban berat, batin Mbok Yah sambil memandangi punggung Daliyem yang menjauh, mengecil, lalu hilang karena jalan menikung.
Mbok Yah langsung berjalan masuk ke Kawedanan dan melihat kalau Gusti Soeratmi dan Salinem sudah main bersama lagi.
Bocah memang tak pernah bosan, ada saja yang mereka lakukan. Mbok Yah juga pernah jadi bocah, tapi tidak ingat tentang bagaimana caranya melihat kehidupan waktu itu. Sepertinya, dirinya memang menganggap kehidupan adalah sebuah tempat tanpa kematian, kegembiraan tanpa kesedihan.
Rasanya, kematian tak bisa memberatkan hati anak-anak sampai, pelan-pelan, semua diperkenalkan. Anak-anak akan tumbuh dewasa dan menyadari bahwa kehilangan terus terjadi. Bahwa, semua perkara dunia selalu memiliki hal di baliknya yang bisa saja tak terlihat. Salinem sudah melihatnya. Ia tidak mengerti, tapi ia melihatnya.
Salinem diperkenalkan terlalu dini pada kematian, desisnya. Pohon Duwet rimbun di pelataran. Di bawahnya, butir-butir buahnya yang ungu berjatuhan. Mbok Yah terus melangkah naik ke teras. Baru beberapa langkah, Mata Mbok Yah tertumbuk pada Salinem dan Soeratmi bertepatan dengan ucapan Gusti Soeratmi pada Salinem, “Begini tulisan namamu, Nem. Sa ..., li ..., nem ....”
s l i n e m \
Gusti Soeratmi lantas menyodorkan pensil itu pada Salinem. Mbok Yah tertegun. Salinem menirunya. Untuk kali pertama dalam hidupnya, Salinem menulis namanya sendiri.
_
Daliyem ini mengherankan, begitu pikir Mbok Yah. Seharusnya, dia senang kalau Salinem dibesarkan bersama-sama Gusti Soeratmi, tapi sepertinya Daliyem enggan berpisah dengan bocah itu. Sebenarnya sama saja seperti keadaan sebelum Salimun meninggal. Daliyem tetap bisa bertemu Salinem, meski situasinya memang agak berbeda. Kalau dulu Salinem yang dibawa ke pasar, sekarang Daliyem yang harus datang ke Kawedanan untuk melihat Salinem. Sekali-sekalinya Daliyem tak bisa bertemu Salinem adalah kalau Gusti Soekatmo dan Gusti Soeratmi pulang ke tempat Gusti Asisten di Tawangsari, itu pun jarang-jarang.
“Mbok, Salinem mana?”
Mbok Yah bergegas memanggil Salinem yang berlari-lari menyambut bibinya itu. Anak kecil sepertinya memang tak lama bersedih pada perpisahan. Bocah itu langsung memeluk bibinya yang juga merangkulnya seperti dia akan pergi jauh.
“Nem, ini pecel untuk kamu,” sodor Daliyem. “Satu lagi untuk Gusti Soeratmi.”
“Terima kasih, Bulik,” balas Salinem sambil menerima dua bungkus pecel itu dengan bungah1. Mbok Yah langsung membantunya membawa dua bungkusan itu karena dua tangan kurus Salinem tampak kerepotan.
Daliyem menengok pada Mbok Yah dan berkata dengan senyum lebar, “Belum seberapa lama ia tinggal di rumah Gusti Wedana, tapi cara bicaranya sudah seperti anak keraton saja.”
“Anak-anak,” jelas Mbok Yah, “mudah diajari, ndak seperti kita yang mengingat saja sudah susah.”
“Bulik, lihat!” seru Salinem sambil menarik-narik jarik yang dikenakan Daliyem, menyodor-nyodorkan kertas di tangannya, ada huruf meliuk-liuk di sana. “Ini namaku. Sa ..., li ..., nem ....”
Daliyem terpaku, matanya seperti kosong, menerawangi Salinem yang terus memandang Daliyem dengan bening. Sejurus kemudian, Daliyem malah berkaca-kaca, “Kamu bisa nulis, Nem?”
“Gusti Soeratmi yang mengajariku nulis, Bulik.”
“Bagus. Bagus, Nem,” Daliyem memeluk bahu sempit bocah itu. “Kamu harus jadi pintar.” Daliyem memandang Mbok Yah yang terus memandangi mereka berdua entah dengan perasaan apa. Daliyem berbisik, “Keputusan yang tepat, ya, Mbok.”
Mbok Yah mengangguk.
Dan esok-esok harinya, Daliyem terus datang membawakan pecel. Entah di kali yang ke berapa, Daliyem tak hanya membawa pecel. Ia membawa seorang bocah laki-laki berkulit kuning. Garis mukanya lembut, cocok dengan rambutnya yang sedikit ikal dan hitam legam. Seorang perempuan asing berdiri di belakangnya, mengenakan kebaya katun berwarna biru dan jarik yang sederhana. Cepol kecil menggantung di tengkuknya.
“Ini Giyo, Mbok,” ucap Daliyem. “Salinem tumbuh bareng anak ini. Sekarang, tiap hari ia merengek minta ketemu Salinem. Ini ibunya.” Daliyem menunjuk perempuan asing itu.
“Maafkan saya, Bu,” ujar perempuan itu. “Anak saya jadi merepotkan.”
“Oh. Ndak apa-apa,” jawab Mbok Yah.
Bocah laki-laki itu tak memandang ke arah Mbok Yah, matanya yang sayu menembus pagar samping Kawedanan, lurus menghadap langsung ke teras gedung itu. Di sana, ia melihat Salinem dan Gusti Soeratmi sedang bermain-main. Mbok Yah menduga kalau anak itu hendak lari ke sana tapi kakinya menancap saja. Sampai, tiba-tiba senyumnya melebar.
Mbok Yah menengok dan melihat Salinem berdiri kaku di sana, matanya lurus seperti hendak memastikan orang yang sedang dilihatnya. Pelan serupa terbit fajar, senyum Salinem memecah bayangan pohon duwet raksasa. Gusti Soeratmi terdiam ketika melihat Salinem menghambur begitu saja. Giyo tetap berdiri diam di tempatnya, tapi senyumnya makin tegas. Salinem berlari seperti hendak menubruknya, dan berhenti mendadak tepat di hadapan Giyo.
Mata mereka beradu dan Mbok Yah terpana saat melihat tangan Giyo menepuk-nepuk puncak kepala Salinem. Bocah itu tersenyum. Tanpa bisa dihalangi, Salinem menarik tangan Giyo, nyaris seperti sedang menyeretnya ke hadapan Gusti Soeratmi. Mbok Yah ikut tersenyum. Cuma butuh beberapa menit untuk membuat mereka bertiga sudah main bersama.
Dan, itulah yang kemudian terjadi hingga empat tahun kemudian. Giyo, Salinem, dan Gusti Soeratmi jadi teman sepermainan. Giyo datang nyaris setiap hari. Awalnya diantar Daliyem siang hari dan dijemput ibunya sore hari, namun lama-lama, Giyo sudah bisa datang dan pergi sendiri. Salinem dan Gusti Soeratmi akan menunggunya datang di balik pagar samping.
Hingga pada tahun 1933, Salinem menyadari bahwa semua yang datang harus pergi. Ia baru sembilan tahun, tubuhnya sudah lebih tinggi walau tetap saja kurus kecil seperti mudah sakit. Tapi, jangan salah, Salinem memang hampir tak pernah sakit lagi. Entahlah, apakah hati anak-anak bisa sakit atau tidak. Bisa jadi, ia belum benar-benar menyadari tentang kehilangan ayah-ibu yang ia alami, tapi ia tahu bahwa di pertengahan tahun itu ia harus kehilangan Giyo.
Raden Soekatmo dan Raden Ayu Soeratmi—yang sudah berusia 13 tahun—harus kembali ke rumah orang tua mereka di Solo. Gusti Soekatmo ada rencana dengan keluarganya dan Soeratmi hendak melanjutkan sekolah di Solo—bersama anak-anak Belanda. Cocok. Gusti Soekatmo makin jelas gagahnya, bahunya lebar dan tubuhnya cukup tinggi. Sementara, Soeratmi tumbuh jadi gadis remaja bertubuh sintal dan matanya tajam kalau menatap orang. Salinem ikut bersama mereka. Daliyem sedih karena terpisah makin jauh, tapi ia merelakannya.
Mbok Yah berkata dalam kepalanya sendiri: Mungkin memang nasibmu terus pindah-pindah, ya, Nduk; dan Giyo menahan tangis karena—kata Salinem—Giyo sudah seperti orang dewasa dan orang dewasa tidak boleh menangis. Giyo memang hampir dewasa, usianya tak jauh dari Gusti Soeratmi, jadi ia mengerti apa yang dimaksud Salinem ketika berpesan sebelum berpisah: Aku akan tulis surat. Kamu harus membalasnya.
Dari pelataran, setelah Soekatmo pamit pada Gusti Wedana,
Gusti Soemirah melambai pada dua adiknya yang bergerak perlahan di atas delman, kuda terus menariknya, menjauh dari Kawedanan Sukoharjo. Giyo berlari di belakangnya sampai delman yang membawa mereka benar-benar hilang karena Giyo kehabisan napas mengejarnya. Buat Giyo, Salinem menghilang dari pandangannya. Dan, buat Salinem sebaliknya.
_
Salinem belum pernah ke Solo sebelumnya, namun Gusti Soeratmi memang berasal dari sini. Waktu tahun 1932, Gusti Soeratmi sempat pulang kampung ke Solo. Sekembalinya ke Sukoharjo, ia langsung cerita-cerita. Salinem tak terlalu ingat apa isi cerita itu, kurang lebih Gusti Wedana dan Asisten Wedana diundang pihak Keraton untuk hadir dalam sebuah acara peresmian di keraton.
“Keraton itu besar sekali, Nem,” ujar Gusti Soeratmi waktu itu. “Lebih besar dari Kawedanan ini. Raja tinggal di sana.”
Buat Salinem, apa pun yang lebih besar dari rumah Bulik Daliyem adalah besar sekali. Apa pun yang diukur pakai tubuh Salinem memang jadi tampak kebesaran. Jadi, kalau keraton lebih besar dari Kawedanan, artinya tempat itu luar biasa besar. Artinya, rumah Bulik Daliyem luar biasa kecil. Cuma orang besar yang tinggal di sebuah rumah luar biasa besar, dan orang itu seorang Raja. Jadi, Raja luar biasa besar.
Buat Salinem, kata “raja, sultan, atau adipati” bukan cuma besar, tapi juga jauh. Terdengar seperti Brahma, Siwa, atau Wisnu yang suka dicerita-ceritakan Mbok Yah sebelum Salinem dan Gusti Soeratmi tidur siang. Atau, Gatotkaca yang menurut cerita bisa terbang. Mungkin, Raja adalah semacam dewa atau sejenis Gatotkaca yang bisa terbang, pikir Salinem kecil.
Salinem memang masih kecil, tapi ia sudah bisa tahu bahwa hidup selalu berubah, membelokkan nasib nyaris ke arah manasuka, dan tak jarang menyisakan perasaan kehilangan.
Hal lain yang disadari Salinem, makin dewasa, perasaan kehilangan juga jadi makin susah hilang. Usia adalah obat pengawet untuk perasaan kehilangan itu. Ada yang hilang ketika Salinem pindah dari Sukoharjo ke Solo. Perihal-perihal yang awalnya ada di bawah kesadaran, seiring bertambahnya umur semakin tersadari keberadaannya. Salinem sudah sadar kalau dirinya tak punya ayah-ibu, membuatnya merasa makin kecil.
Solo adalah kota besar dan Sukoharjo kota kecil. Dibanding Solo, Sukoharjo seperti desa sepi. Solo ramai dan banyak orang Belandanya. Banyak orang penting di sini. Gaya berpakaiannya saja sudah beda. Banyak perempuan tak pakai kain, mereka pakai rok.
Satu hal yang kemudian disadari oleh Salinem remaja: Solo mengandung ketegangan. Mungkin perkara di Solo banyak penggede. Mulai dari nama-nama tak dikenal; Adipati di Mangkunegaran; sampai Sunan yang bertahta di Keraton Pakubuwana.
Terlebih ketika memasuki tahun 1937, Salinem sudah mulai bisa menyimpulkan ketegangan-ketegangan yang muncul walau ketegangan itu belum meluas. Entah dapat berita dari mana, ada segelintir pedagang Cina yang membicarakannya.
Katanya Jepang menyerang Cina. Salinem tidak tahu Jepang ada di mana, katanya muka mereka mirip orang Cina. Kalau mirip bukannya bersaudara? Kenapa mereka saling serang? Salinem tidak paham.
Di Solo banyak orang Cina, tapi yang diserang bukan mereka, mereka tetap asik berdagang. Cina yang diserang adalah negara asal orang-orang Cina di sini. Pantas, di pasar mereka membicarakannya dengan muka masam. Mereka takut perang menyebar sampai kemari. Salinem setuju dengan mereka, seharusnya tidak perlu perang. Ia tidak tahu kenapa orang harus berperang. Siapa yang mengharuskan mereka berperang?
Usia Salinem sudah tiga belas tahun, sudah bisa menguping saat membawa cangkir teh ke meja depan. Mendengar pembicaraan Gusti Asisten dengan ayah Soeratmi. Katanya, Belanda terlibat perang di suatu tempat jauh.
Salinem membenak, kalau Keraton saja terasa jauh, berarti Belanda lebih jauh lagi. Kalau keraton isinya dewa, mungkin Belanda isinya dewanya dewa. Mungkin, itu yang bikin kulit mereka beda (seperti hantu lejas, menurut Salinem) dan badannya besar-besar. Tiap kali melihat orang Belanda, ia laiknya sedang memandang raksasa. Mungkin, mereka adalah anak buah Rahwana yang juga pernah diceritakan Mbok Yah.
Ketegangan makin bertambah pada tahun 1939. Katanya, Belanda tidak mau perang. Dekat pertengahan 1940, suasana makin tegang. Katanya, Belanda yang tidak mau perang itu kalah perang. Kalau tidak mau, kenapa tetap berperang? Salinem bingung. Kalau begitu, pada akhirnya Belanda perang juga. Percuma menolak perang kalau buntut-buntutnya tetap diserang.
Untunglah, cuma ketegangannya yang terbawa kemari, karena situasi nyatanya belum banyak berubah. Paling tidak, Surakarta masih terasa baik-baik saja. Sambil meletakkan teko keramik berisi teh hangat dan sepiring nagasari, Salinem berpikir: Kalau dewanya dewa bisa kalah, berarti yang menang adalah dewa dari dewanya dewa.
Salinem mulai berpikir bahwa cerita-cerita perang itu sama saja seperti cerita wayang yang disampaikan Mbok Yah. Kalaupun benar-benar terjadi, pengaruhnya tidak terasa. Kalaupun terasa hanya ketegangannya saja, sama seperti ketika Mbok Yah bercerita bagaimana Gatotkaca gugur akibat lesatan senjata konta yang diluncurkan Adipati Karna. Salinem merasa tegang mendengarnya.
Selama tinggal di Sukoharjo Salinem tidak pernah mendengar cerita-cerita perang yang menegangkan. Di Solo, cerita-cerita perang—yang ia pikir cuma ada dalam kisah Baratayuda—jadi terasa dekat. Namun, di antara periode-periode itu, ada juga yang membuat Salinem bahagia di Solo. Walaupun ia sempat tidak senang.
Gara-gara surat.
Salinem sudah mengirimkan beberapa surat buat Giyo lewat kusir Gusti Asisten yang sedang sowan, tapi tak kunjung dibalas. Pertamanya, Salinem pikir Giyo tak sempat membalas, atau lupa mengantarnya ke Pak Kusir. Tapi, kalau sampai delapan kali tidak dibalas juga, Salinem curiga, jangan-jangan Giyo memang tak mau membalasnya. Padahal, bukankah dulu Giyo berjanji membalas surat-suratnya?
Baru di surat kesembilan ada jawaban, kira-kira sudah tahun 1936, Salinem nyaris menyerah dan tidak mau mengirimkan surat lagi. Jadi, ketika akhirnya balasan datang, Salinem membuka surat itu dengan semangat berkobar-kobar, semacam orang sedang sakit perut dan harus menunggu orang dalam jamban yang tak keluar-keluar.
Salinem lari ke kamar dengan surat di tangannya. Suratnya cuma berupa lipatan kertas tanpa amplop dan di depan lipatan Salinem menemukan tulisan nama “Soegiyo” dalam aksara Hanacaraka. Berarti, surat ini benar dari Giyo. Ia membukanya perlahan-lahan seakan-akan kalau ia melakukan dengan gerakan lebih cepat huruf-huruf itu bisa tumpah berantakan. Salinem diam. Senyumnya hilang. Ia membalik kertas itu. Membaliknya lagi. Bolak. Balik. Bolak. Balik. Bolak-balik.
Ini kertas kosong!
Kenapa Giyo cuma mengirim kertas berisi namanya? Salinem tidak bisa menyebut kertas bertuliskan nama saja sebagai “surat”, bukan?
Salinem kesal. Nyaris membuntal-buntal kertas itu dan melemparkannya ke luar. Tapi, urung. Ia tetap melipatnya dengan rapih lalu menyimpannya. Sialnya, hatinya yang sekarang jadi berantakan.
Salinem memutuskan untuk tak sudi mengirim surat lagi. Ia marah.
Untungnya, tahun 1937 keadaan berubah. Kusir Gusti Asisten berganti orang. Dan orang itu: Giyo.
Salinem sudah merencanakan untuk marah besar ketika melihat Giyo datang mengantar Gusti Asisten, tapi melihat rautnya yang saat itu sudah 16 tahun, rencana itu bubar. Kulit Giyo memang tambah gelap, mungkin karena bekerja jadi kusir, tapi matanya, kenapa jadi bening begitu? Rambutnya yang bergelombang sudah lebih panjang, muncul dari balik ikat kepala batiknya, sedikit menutup tengkuknya yang kekar.
Salinem nyaris tak berani menengok lagi, takut tertangkap basah saat mukanya jadi aneh. Adegan ini seperti masa kecil, tapi kali ini bikin jantung Salinem pindah ke perut. Duduk di samping lengan Giyo membuat Salinem ciut jadi liliput. Gusti, siapa yang mengubah Giyo hingga serupa ini? Makan apa dia?
“Kamu sehat-sehat saja, Nem?”
“Sehat, Mas.”
Dalam kepalanya tebersit kata-kata: Mengapa Mas Giyo tega membalas suratku cuma dengan kertas kosong? Kamu jahat! Aku tidak mau ketemu kamu lagi! Salinem menajamkan matanya, menatap Giyo yang terus menggoyang-goyangkan kaki ke depan dan ke belakang. Salinem merapal ulang kata-kata barusan dalam kepalanya. Kemudian, sepenuh kemarahan, ia membuka mulutnya. Dan, meluncurlah (pakai acara senyum segala): “Mas Giyo sehat? Sudah makan?”
Mulut bodoh!
Giyo membalas senyumnya, “Sehat dan sudah makan. Kamu sehat?”
“Tadi, Mas Giyo sudah tanya itu.”
“Oh? Benarkah?”
“Benar, Mas.”
Lalu, mereka berdua diam sampai diam itu terasa janggal. Sampai Giyo pulang dari rumah orang tua Soeratmi, mereka cuma diam dan lebih seperti saling menghindar.
Kesimpulannya, jangankan marah besar, marah saja memang tidak bisa direncanakan, Salinem membatin.
“Kamu kenapa, Nem?” tanya Gusti Soeratmi.
“Tidak kenapa-kenapa, Gusti.”
Tapi, dalam hati, Salinem merasa bodoh. Ah, ndak apa-apa. Orang bodoh gampang senangnya. Salinem tersenyum.
Sejak 1937 itu, Giyo berkali-kali bertandang ke rumah orang tua Gusti Soeratmi karena Gusti Asisten dan Istrinya datang menjenguk. Pembicaraan terbaik yang bisa Salinem dan Giyo lakukan adalah: Apa kabar? Sehat? Sudah makan? Dan sebaik-baiknya: Kapan datang? Seburuk-buruknya: Kapan pulang? Karena, Salinem sebenarnya tak mau Giyo pulang. Toh, ia tetap pulang.
“Setiap kakakku habis datang dari Tawangsari, kenapa kamu jadi aneh, Nem?” suatu ketika Gusti Soeratmi bertanya.
“Benarkah?”
“Iya. Kamu jadi lebih pendiam tapi belingsatan.”
“Mungkin capek saja, Gusti, karena harus masak,” dalihnya.
“Mana ada orang capek belingsatan.”
“Mungkin, karena ndak terlalu capek.”
“Ah? Piye? Kamu capek, atau ndak capek? Kok, aku jadi ndak ngerti?”
“Pokoknya, begitu, Gusti.”
“Kamu sehat?”
“Sehat, Gusti.”
“Ah, sak karepmu,” Gusti Soeratmi menggeleng. “Oh, iya. Besok, temani aku ke rumah Kartinah, ya, Nem.”
Kartinah adalah teman baik Gusti Soeratmi—sama-sama belajar di sekolah Belanda itu. Walau begitu, Salinem tidak terlalu kenal siapa Gusti Kartinah. Sejak pindah ke Solo, Salinem jadi paham kalau Raden Soekatmo teman Belandanya juga banyak. Berkali-kali Belanda-Belanda itu datang ke rumah. Salinem ndak ngerti mereka bicara apa—mereka bicara pakai bahasa aneh yang terdengar macam orang sedang kumur-kumur. Kadang, mereka tertawa-tawa. Di lain waktu, mereka berdebat. Sering juga mereka nyanyi-nyanyi dengan diiringi biola. Salinem juga baru tahu kalau Raden Soekatmo pandai main biola.
Raden Soekatmo sering datang ke rumah Gusti Kartinah dan minta Soeratmi menemaninya. Soeratmi kini meminta Salinem menemaninya.
“Aku ingin kita bertiga bisa berteman baik,” ungkap Gusti Soeratmi.
Salinem hanya mengangguk.
Esoknya, dengan delman yang dikendarai seorang kusir tua, mereka bertiga berangkat ke rumah orang tua Kartinah. Kejadian ini berlangsung sekitar awal tahun 1937, sebelum balasan surat dari Giyo diterima Salinem. Ia menduga kalau Raden Soekatmo naksir Raden Nganten Kartinah. Kata Soeratmi, kali pertama Soekatmo bertemu Kartinah adalah di peresmian sesuatu di keraton pada 1932, lima tahun sebelumnya.
Raden Soekatmo benar-benar niat untuk mendekati sahabat adiknya itu. Ia pergi membawa bingkisan buah-buahan segar: sawo, jambu darsana, pisang raja, nanas, dan mangga harum manis.
Saat bertemu, barulah Salinem paham. Pantaslah Gusti Soekatmo rajin bawa bingkisan, Gusti Kartinah memang ayu. Sepertinya, Gusti Kartinah adalah jenis orang yang tak bisa marah. Wajahnya bulat telur dan matanya seperti selalu tersenyum. Iya, yang tersenyum matanya, sementara bibirnya yang tipis seperti hanya menambah warna di wajahnya. Pas senyum, tak pernah lebar-lebar, seperti cuma dikulum.
Kalau duduk, pahamya selalu dimiringkan dengan lutut rapat, membuat bentuk pinggulnya jadi jelas. Mungkin, karena ia dididik di sekolah Belanda yang tak luput mengajar tata krama. Suaranya halus macam kain beledu (beda jauh sama Soeratmi yang meledak-ledak). Jadi, walau anak bangsawan Jawa, jangan heran kalau Kartinah lebih sering mengenakan rok; jarik dan kebaya dipakai sekali-sekali saja. Kalau sedang pakai jarik, tubuhnya yang mungil berisi jadi singset.
Salinem senang bicara dengan Raden Nganten Kartinah karena ia tak pernah memotong orang lain bicara. Gusti Soekatmo pantas jatuh cinta pada Kartinah, dan mau repot-repot. Salinem tak berharap Giyo melakukan hal yang sama. Lah wong, membalas surat saja ia enggan. Jangan berharap jauh-jauh, bisik Salinem pada dirinya sendiri.
Salinem sebenarnya heran, jarak rumah Gusti Soekatmo dan Gusti Kartinah tak lebih dari sepuluh menit, itu pun kalau berjalan kaki. Naik delman malah bisa jadi lebih lama, kalau dihitung dengan waktu mempersiapkannya. Lebih praktis jalan kaki. Namun, orang jatuh cinta memang gemar melakukan hal-hal merepotkan.
Gusti Soeratmi dan Salinem berkali-kali diajak ke sana. Salinem mulai curiga bahwa sebenarnya Gusti Soekatmo menjadikan Soeratmi sebagai tameng, supaya gampang mendekati orang tua Kartinah. Toh, yang disebut gampang itu ternyata tidak gampang juga. Hampir dua tahun mereka bertiga melakukan kegiatan itu, sampai-sampai yang menjadi lebih dekat malah Soeratmi, Kartinah, dan Salinem. Gusti Soekatmo jadi serupa tukang antar.
Tak cuma sekali dua, bukannya Gusti Soekatmo yang dapat kesempatan, malah Soeratmi dan Salinem yang berjalan-jalan dengan Kartinah mencari jajanan di pasar Gede. Gusti Soekatmo ditinggalkan saja di rumah Kartinah. Gusti Soekatmo pasti kesal. Atau, jangan-jangan malah senang karena jadi akrab dengan orang tuanya? Entahlah. Bisa jadi semua itu memang muslihat. Salinem suka geli sendiri jika mengingat ini.
Merepotkan, memang.
Cinta selalu merepotkan dan di saat yang sama membuat orang yang jatuh cinta bersedia dibuat repot. Toh, kerepotan itu berbuah hasil. Akhir 1939, lamaran Gusti Soekatmo diterima oleh Gusti Kartinah dan kedua orang tuanya.
Pemenang selalu tertawa belakangan.
_
1 Gembira.
**
Baca ribuan cerita seru dan tuliskan ceritamu sendiri di Storial!