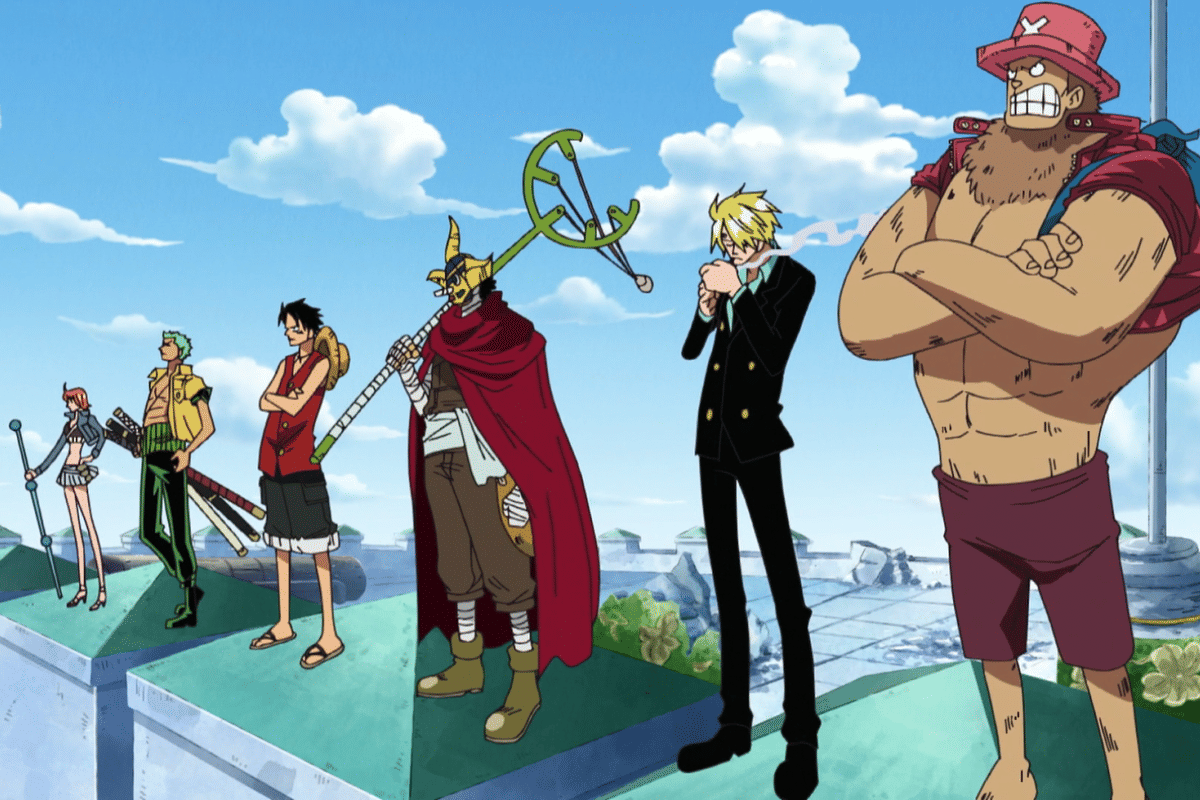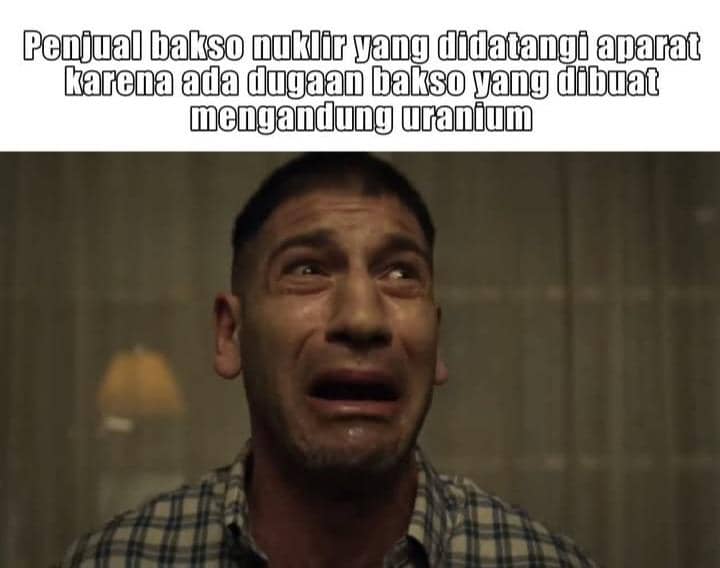Review Film Wuthering Heights, Terlalu Fokus pada Romansa Panas

- Wuthering Heights (2026) bukan adaptasi langsung dari novel Emily Brontë, lebih menekankan hubungan romantis dan keindahan visual.
- Film ini memukau secara visual, tetapi dangkal secara naratif dengan fokus pada estetika dan erotisme daripada eksplorasi sosial dan psikologis.
- Penyederhanaan karakter kunci dan casting yang tidak tepat membuat film ini kehilangan lapisan penting dalam dinamika cerita aslinya.
Satu lagi karya klasik sastra Inggris kembali dihidupkan ke layar lebar. Wuthering Heights, novel legendaris karya Emily Brontë, telah diadaptasi lebih dari 30 kali dalam bentuk film dan serial televisi. Versi terbaru datang dari tangan Emerald Fennell, sineas yang dikenal gemar memicu perdebatan lewat karya-karyanya.
Setelah Promising Young Woman (2020) dan Saltburn (2023), Fennell kembali menantang ekspektasi publik dengan menggaet Margot Robbie dan Jacob Elordi sebagai Catherine dan Heathcliff. Hasilnya adalah film yang memikat secara visual, provokatif secara sensual, namun terus memancing pertanyaan besar: apakah ini masih Wuthering Heights atau sekadar fantasi romantis versi Fennell? Berikut penjelasannya!
Sinopsis Wuthering Heights (2026)
Di Wuthering Heights, hiduplah Catherine "Cathy" Earnshaw, gadis riang yang tumbuh bersama ayahnya yang kasar dan pecandu alkohol, serta sahabatnya, Lady Nelly. Kehidupan mereka berubah ketika seorang anak yatim piatu tanpa nama dibawa pulang oleh Tuan Earnshaw. Catherine menamainya Heathcliff dan menjadikannya sahabat dekat, meski ia diperlakukan tak lebih dari penjaga kuda.
Saat dewasa, hubungan Catherine dan Heathcliff berkembang menjadi ikatan obsesif yang sarat hasrat, rasa cemburu, dan permainan psikologis. Ketika Edgar Linton dan Isabella memasuki hidup Catherine, pilihan kelas sosial dan kenyamanan material mendorong Catherine menjauh dari Heathcliff. Kepergian Heathcliff, kepulangannya 5 tahun kemudian dengan kekayaan (dan dendam), serta perselingkuhan terlarang yang menyusul, menjadi pemantik tragedi yang berlapis dalam kisah ini.
| Producer | Emerald Fennell, Josey McNamara, Margot Robbie |
| Writer | Emerald Fennell (naskah), Emily Brontë (novel) |
| Age Rating | D17 |
| Genre | Romantic, drama |
| Duration | 136 Minutes |
| Release Date | 11 Februari |
| Theme | Steamy Romance |
| Production House | MRC, Warner Bros. Pictures |
| Where to Watch | Bioskop |
| Cast | Margot Robbie, Jacob Elordi, Hong Chau, Shazad Latif, Alison Oliver, Martin Clunes, Ewan Mitchell, Owen Cooper |
Trailer Wuthering Heights (2026)
Cuplikan film Wuthering Heights (2026)
1. Bukan adaptasi langsung dari novel Emily Brontë
Sejak awal, Wuthering Heights (2026) menegaskan dirinya bukan adaptasi harfiah dari novel Brontë. Wuthering Heights di novel aslinya adalah kisah tentang rasisme, siklus kekerasan, trauma antar generasi, dan kelas sosial, dengan dua narator yang tidak dapat dipercaya. Film ini memilih jalur lain, mereduksi kompleksitas itu menjadi kisah dua insan yang saling terobsesi lewat pendekatan yang seksi dan melodramatis.
Fennell sendiri mengakui bahwa interpretasinya didasarkan pada kesannya saat membaca novel tersebut di usia 14 tahun. Sayangnya, pendekatan ini terasa seperti membaca ulang buku klasik dari kacamata remaja yang hanya menangkap romantisasi hubungan toksik, tanpa menggali lapisan sosial dan psikologis yang membuat novel Brontë bertahan lintas zaman hingga hari ini.
Jika judul dan nama karakternya dihapus, film ini nyaris kehilangan identitas Brontë sepenuhnya. Sisanya hanyalah melodrama penuh gairah tentang cinta terlarang, alih-alih eksplorasi tentang kekerasan struktural dan luka yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
2. Memukau secara visual, tetapi dangkal secara naratif
Secara visual, film ini sulit dibantah keindahannya. Sinematografi Linus Sandgren berhasil menangkap Yorkshire Moors sebagai lanskap yang liar, berangin, dan terus-menerus diselimuti hujan. Alam menjadi metafora emosi para karakter yang dingin, keras, dan tak kenal ampun. Namun, kemegahan visual ini sering kali terasa menutupi kekosongan naratif.
Adegan hujan, angin, dan tubuh-tubuh yang saling mendekat diulang berkali-kali tanpa pengembangan dramatik yang sepadan. Desain produksi Thrushcross Grange bahkan terasa anakronistis alias tak sezaman, lebih mirip rumah impian gotik ala Barbie yang terlalu mengilap dibanding ruang hidup yang mewakili hierarki kelas abad ke-19.
Ditambah dengan musik orisinal Charli XCX dan skor Anthony Willis yang bombastis, dunia film ini terasa "bising" secara estetika. Alih-alih memperdalam emosi, elemen-elemen tersebut justru kerap mengalihkan perhatian dari konflik batin para karakternya.
Jika kamu mencari film dengan suguhan visual + musik yang berani dengan cerita yang layak untuk direnungkan, tontonlah Crimson Peak (2015) karya Guillermo del Toro sebagai gantinya.
3. Terlalu fokus ke steamy romance, melupakan rasisme dan trauma antar generasi
Dari adegan erotis eksplisit hingga simbol-simbol seksual yang tersebar lewat detail kecil, Wuthering Heights versi Fennell menempatkan seksualitas sebagai pusat narasi. Bahkan sebelum film benar-benar dimulai, terdapat adegan yang sangat sensual dan hampir obsesif terhadap hawa nafsu. Ketika karakter tidak sedang bercinta, erotisme tetap hadir dalam gestur-gestur yang dibingkai dengan intensitas berlebihan.
Masalahnya, fokus ini datang dengan harga mahal. Tema rasisme yang tersirat kuat dalam novel, terutama melalui sosok Heathcliff sebagai "orang luar" (beberapa menyebutnya keturunan Romani/Gypsy), hampir sepenuhnya terhapus. Trauma antar-generasi dan kekerasan dalam rumah tangga pun hanya muncul sebagai latar, bukan konflik utama yang dieksplorasi secara kritis.
Wuthering Heights pun terasa seperti tragedi romantis ala novel Harlequin yang diadaptasi ke layar lebar, bukan refleksi sosial yang menggugah. Relasi toksik Catherine dan Heathcliff memang ditampilkan secara brutal dan manipulatif. Namun tanpa konteks sosial yang pas, semuanya terasa kosong dan nirmakna.
4. Casting yang tidak tepat dan hilangnya beberapa tokoh penting
Pemilihan Jacob Elordi sebagai Heathcliff memicu kontroversi tersendiri. Dalam novel, Heathcliff sangat tersirat sebagai karakter non-kulit putih atau setidaknya "asing" secara ras dan kelas. Dengan memilih aktor kulit putih, film ini kehilangan salah satu lapisan terpenting dalam dinamika cerita. Begitu pun karakter Mr. Linton yang diperankan oleh Shazad Latif.
Ironisnya, karakter pendukung seperti Nelly (Hong Chau) dan Isabella (Alison Oliver) justru tampil lebih hidup. Nelly, yang diubah latar belakangnya, menjadi saksi emosional yang kuat atas kehancuran hubungan utama. Isabella bahkan diberi nuansa menyimpang yang menarik, meski perannya tetap dipinggirkan.
Penghilangan atau penyederhanaan sejumlah karakter kunci membuat dunia Wuthering Heights terasa sempit. Kisah ini seharusnya tentang ekosistem sosial yang rusak, bukan hanya dua individu yang saling menghancurkan satu sama lain.
5. Apakah Wuthering Heights versi Fennell layak ditonton?
Sebagai adaptasi sastra, film ini jelas mengecewakan. Ia gagal menangkap kompleksitas dan relevansi novel Brontë. Namun, sebagai ekspresi artistik murni dari Emerald Fennell, film ini justru terasa jujur terhadap obsesinya pada estetika, erotisme, dan provokasi emosional.
Jika kamu mencari adaptasi Wuthering Heights yang setia pada buku, film ini bukan jawabannya. Tapi jika kamu penasaran melihat bagaimana seorang sineas kontroversial membedah kisah klasik lewat lensa personal yang berani dan tidak kompromis, versi ini tetap menarik untuk disimak.
Pada akhirnya, Wuthering Heights karya Fennell adalah film yang akan memecah penonton menjadi dua kubu. Suka atau benci, ia setidaknya berani berdiri tegak sebagai karya yang dibuat sepenuhnya sesuai kehendak pembuatnya. Tinggal satu pertanyaan, apakah keberanian itu cukup untuk menutupi kekosongan maknanya? Wuthering Heights tayang di bioskop Indonesia mulai 11 Februari 2026.