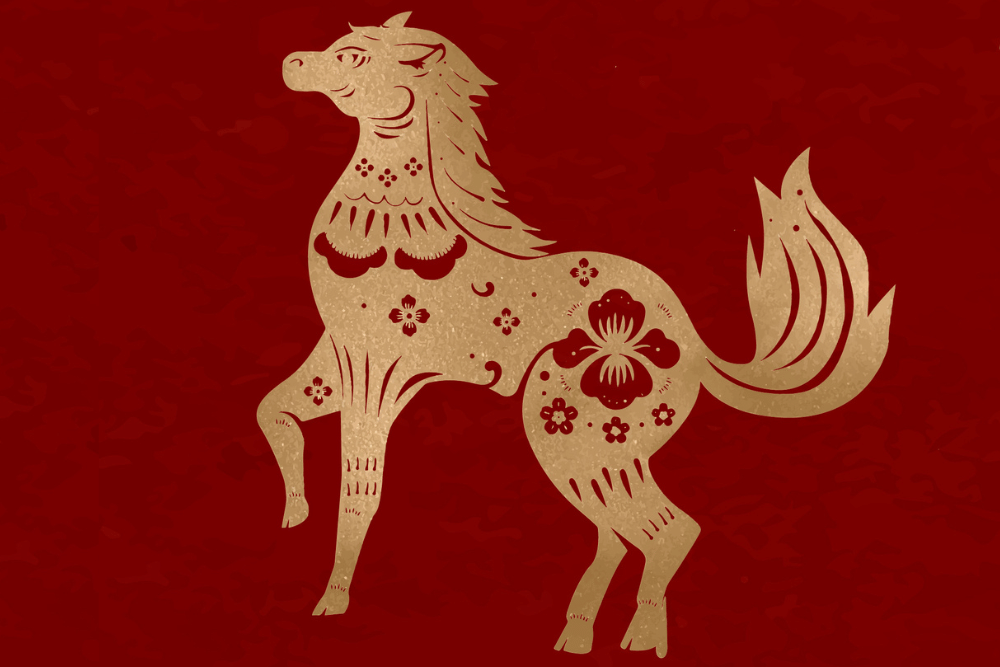5 Alasan Tren Slow Living Makin Susah Diterapkan di Kota Besar

Belakangan ini tren slow living makin sering muncul di media sosial. Feeds dipenuhi pagi yang tenang, kopi hangat, rumah estetik ala cottagecore, dan hidup yang katanya lebih mindful. Sekilas terlihat sederhana dan menenangkan. Tapi kalau kamu tinggal di kota besar, rasanya tidak sesederhana itu.
Gaya hidup lambat terdengar seperti jawaban dari tekanan hidup kota besar yang serba cepat. Banyak orang ingin keluar dari ritme kerja yang melelahkan dan tuntutan produktivitas tanpa henti. Namun realita hidup di kota besar sering kali tidak memberi banyak pilihan. Yuk simak lima alasan kenapa tren slow living terasa makin susah diterapkan.
1. Biaya hidup yang terus meningkat

Slow living sering digambarkan dengan aktivitas sederhana seperti berkebun, memasak sendiri, atau menikmati waktu senggang. Namun semua itu tetap butuh waktu dan biaya yang tidak sedikit. Di kota besar, sebagian besar energi sudah habis untuk membayar sewa, transportasi, dan kebutuhan pokok. Ruang untuk hidup santai jadi terasa seperti kemewahan.
Ketika pengeluaran bulanan saja sudah bikin cemas, fokus utama tentu bertahan hidup. Banyak orang harus bekerja lebih lama demi stabilitas finansial. Dalam kondisi seperti ini, gaya hidup lambat bukan prioritas. Privilege gaya hidup sangat berperan dalam menentukan siapa yang bisa benar-benar melambat.
2. Budaya hustle yang masih kuat

Meski narasi self-care makin populer, budaya kerja keras tanpa henti belum benar-benar hilang. Di kota besar, sibuk sering dianggap sebagai simbol sukses. Orang yang terlihat santai justru dicurigai kurang ambisius. Tekanan sosial ini membuat tren slow living terasa kontradiktif.
Kamu mungkin ingin pulang tepat waktu dan menikmati sore dengan tenang. Namun notifikasi kerja terus berdatangan bahkan setelah jam kantor. Lingkungan yang kompetitif membuat banyak orang takut tertinggal. Akhirnya, gaya hidup lambat kalah oleh tuntutan untuk selalu produktif.
3. Waktu tempuh yang menguras energi

Realita hidup di kota besar sering dimulai dan diakhiri di jalan. Perjalanan panjang menuju kantor menyita waktu berharga setiap hari. Energi sudah terkuras bahkan sebelum pekerjaan dimulai. Dalam kondisi ini, meluangkan waktu untuk hidup lebih pelan terasa sulit.
Slow living butuh ruang jeda yang konsisten. Namun jika dua sampai tiga jam habis di transportasi, sisa waktu hanya cukup untuk istirahat. Kamu mungkin ingin membaca buku atau memasak dengan tenang. Sayangnya, tubuh sudah terlalu lelah untuk itu.
4. Ruang tinggal yang terbatas

Cottagecore sering menampilkan rumah luas dengan taman hijau. Kenyataannya, banyak orang kota tinggal di apartemen kecil atau kos sederhana. Ruang yang terbatas membuat aktivitas seperti berkebun atau membuat ruang hobi jadi tidak mudah. Konsep hidup tenang terasa tidak relevan dengan kondisi hunian.
Keterbatasan ruang juga memengaruhi kualitas istirahat. Suara kendaraan dan kepadatan lingkungan sulit dihindari. Situasi ini membuat ketenangan terasa mahal. Lagi-lagi, privilege gaya hidup menentukan akses terhadap kenyamanan dasar.
5. Slow living yang terkesan estetika semata

Di media sosial, gaya hidup lambat sering terlihat sebagai visual yang cantik. Padahal esensinya bukan soal pakaian linen atau dapur estetik. Slow living seharusnya tentang kesadaran mengatur ritme hidup. Sayangnya, banyak yang berhenti di permukaan.
Ketika hanya jadi tren, slow living mudah berbenturan dengan realitas. Kamu mungkin bisa membuat pagi lebih tenang, tapi tetap dikejar target kerja setelahnya. Tanpa perubahan sistem kerja dan lingkungan, melambat hanya jadi momen sesaat. Bukan perubahan yang berkelanjutan.
Bukan berarti tren slow living sepenuhnya mustahil di kota besar. Namun kamu perlu melihatnya dengan realistis, bukan sekadar ikut visual yang menenangkan. Hidup lebih pelan itu baik, tapi harus disesuaikan dengan realita dan kemampuanmu. Yuk, mulai temukan ritme yang masuk akal di tengah tekanan hidup kota besar.