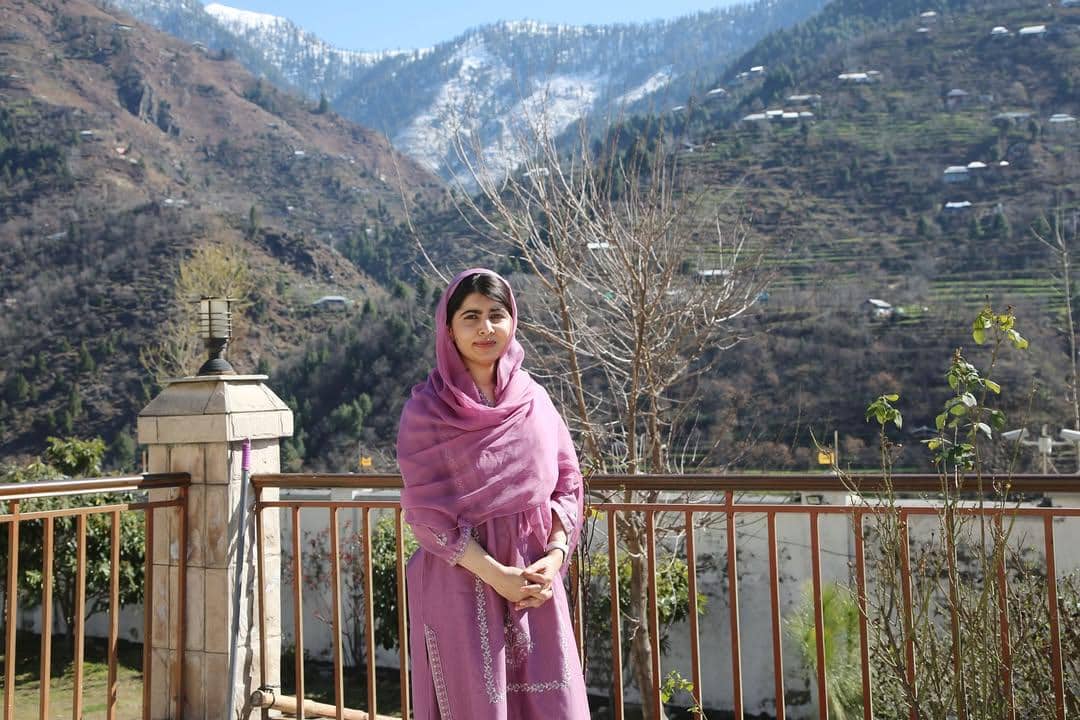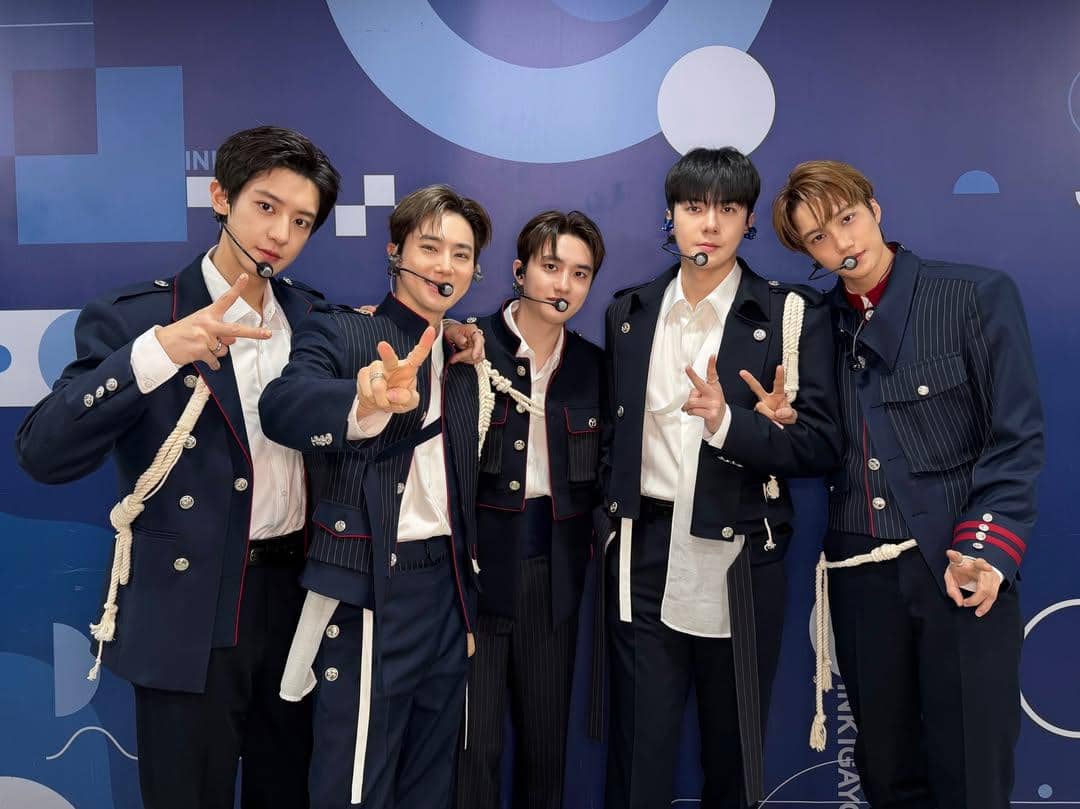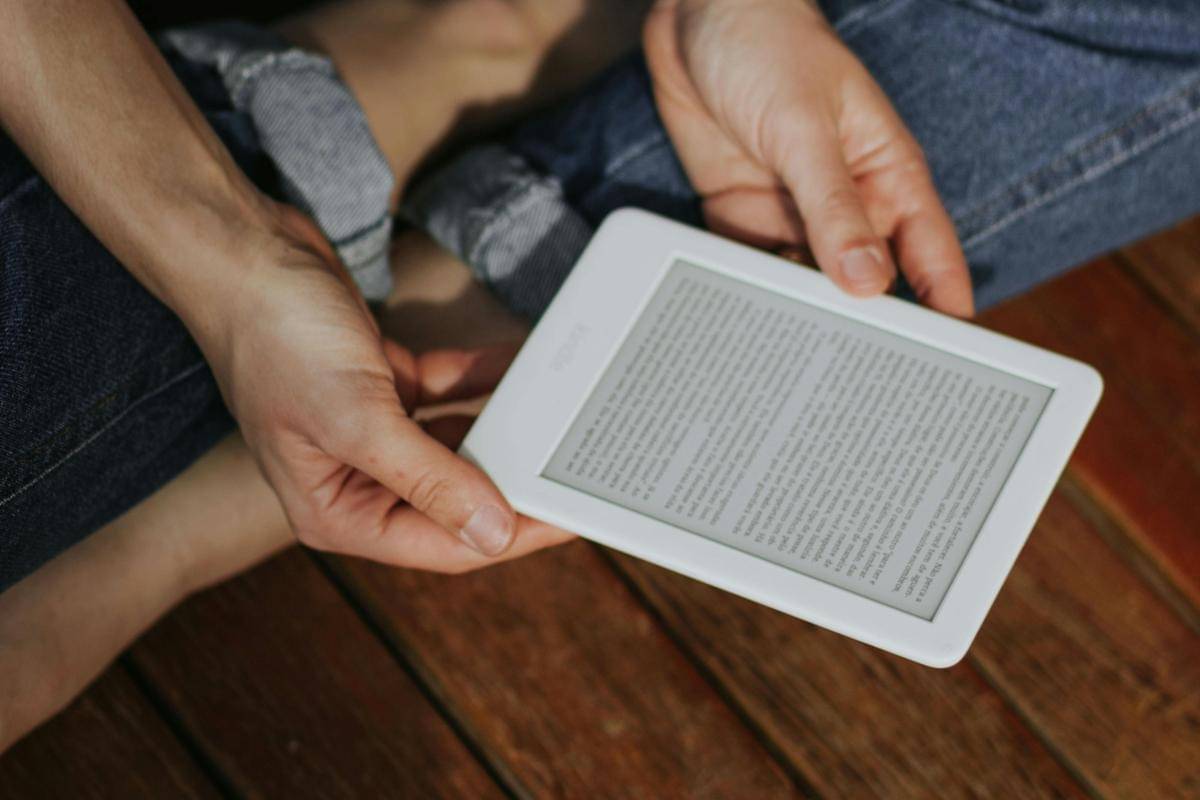Kuliah Jurusan Sastra Bukan untuk Penulis, Ini 7 Alasannya!
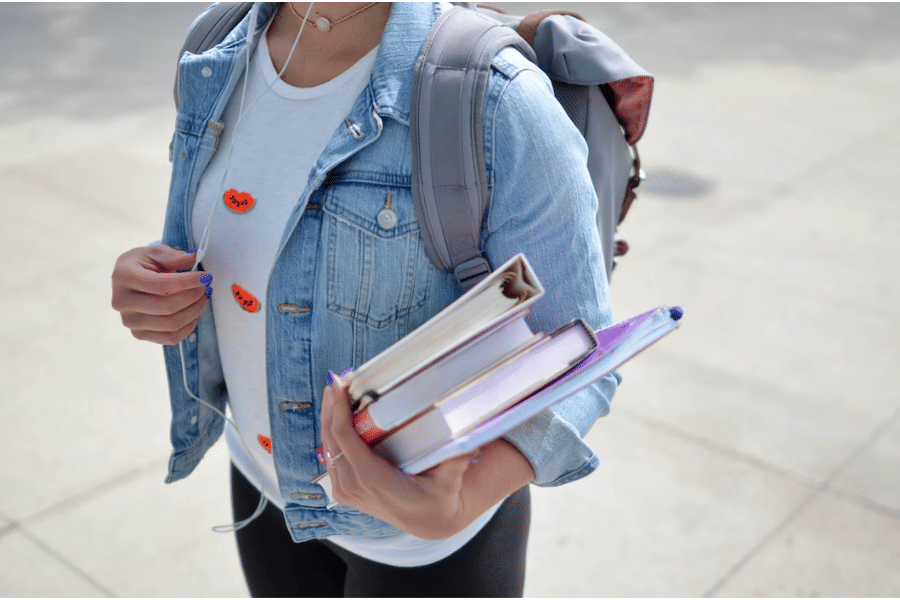
Orang awam mengira bahwa kuliah sastra bisa menjadikan mereka penulis profesional. Lantas banyak yang berbondong-bondong masuk jurusan tersebut, tapi kemudian kecewa karena realita yang mereka dapatkan jauh berbeda dari harapan. Itu sebabnya kalian perlu tahu beberapa fakta mengenai jurusan atau program studi sastra, khususnya Sastra Indonesia.
Jangan sampai kamu menjadi orang kesekian yang memiliki penyesalan seumur hidup karena salah pilih jurusan. Mengapa kuliah di jurusan sastra memang bukan untuk penulis? Yuk, simak uraiannya!
1. Tidak ada mata kuliah yang mempelajarii secara detail proses berkarya

Beberapa universitas menyisipkan matkul (mata kuliah) seperti penulisan kreatif, tapi materinya hampir seumum yang telah dipelajari di jenjang sekolah sebelumnya. Terkadang prodi (program studi) berkenan memberi effort untuk menghadirkan praktisi. Sayangnya jika tidak karena keterbatasan waktu, sering kali pemateri yang dipilih terlalu genius untuk memaparkan proses berkaryanya. Alih-alih mendapatkan gambaran terstruktur yang konkret dan aplikatif, kemungkinan peserta hanya mendapat tambahan motivasi untuk terus berkarya. Mungkin hal ini akan bekerja pada penulis pantser (tipe penulis bebas), tetapi jelas tidak bekerja untuk tipe penulis plotter (tipe penulis terencana) seperti kebanyakan mahasiswa yang terbiasa menulis secara sistematis dan metodologis.
Di beberapa universitas lain bahkan sama sekali tidak memberi porsi untuk matkul terkait kreativitas berkarya. Mereka justru secara vokal menyatakan jurusan sastra tidak untuk menciptakan penulis melainkan peneliti dan kritikus sastra. Cukup disayangkan, tapi begitulah kenyataannya. Jurusan sastra seringnya lebih fokus pada pembelajaran terkait teori, analisis, dan sejarah sastra daripada aspek praktis menulis.
2. Minimnya umpan balik yang mendalam

Meskipun prodi sastra juga terkenal akan matkul kritik sastranya, sayangnya dalam proses pembelajaran sangat minim ruang untuk mendapatkan umpan balik yang mendalam. Tugas penulisan karya sastra (bahkan termasuk kebanyakan tugas yang telah dikumpulkan), jarang sekali diberi kritik langsung ataupun umpan balik yang membangun. Kalau tidak benar-benar tanpa komentar, paling jauh hanya sekilas disampaikan secara umum di depan kelas.
Satu-satunya kemewahan mendapat koreksi yang mendetail dan memungkinkan dialog, umumnya hanya saat mahasiswa tengah melakukan pendampingan skripsi. Itu pun jika cukup beruntung bertemu dosen pembimbing yang rajin, baik hati, dan tidak sibuk. Jadi jika ingin jadi penulis, lebih baik pakai waktu kalian untuk terjun langsung ke industri. Atau pakai uang kalian mengikuti pelatihan-pelatihan privat yang diadakan mantan atau pelaku aktif di industri yang menyediakan ruang untuk melakukan umpan balik secara rinci disertai diskusi. Itu akan menghemat banyak waktu serta biaya yang diperlukan.
3. Tidak ada atau rendahnya kerja sama dengan industri

Ternyata kebanyakan kampus tidak punya pengaruh atau koneksi sekuat itu dengan industri. Mungkin mereka punya beberapa koneksi dengan karyawan yang merupakan alumnus dari kampus mereka, tapi tidak terlalu banyak yang bisa dilakukan jika prodi sendiri tidak memiliki penawaran yang dibutuhkan perusahaan. Mahasiswa tetap akan dituntut berjuang seorang diri untuk bisa bersaing dengan mahasiswa kampus lain bahkan dari prodi yang berbeda.
Privilese yang mungkin didapatkan mahasiswa sebatas adanya peluang semacam program merdeka belajar dari kurikulum kampus merdeka. Namun seperti kebanyakan kurikulum yang lekas berganti, kita tidak tahu sampai kapan program tersebut bertahan. Belum lagi, kita juga perlu berhati-hati memilih perusahaan yang benar-benar menjalankan program sesuai semangat pembelajaran dan bukannya perbudakan terselubung yang dilegalkan.
4. Mudah minder karena terbiasa menganalisis dan mengkritik karya tersohor
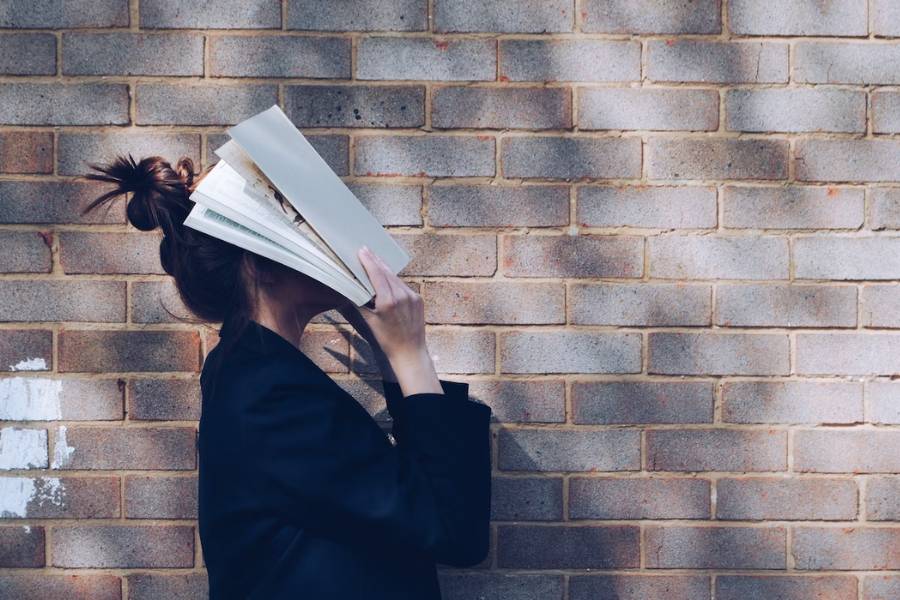
Hal umum yang sering ditemui pada calon penulis yang akhirnya masuk jurusan sastra adalah fenomena berhenti menulis. Ternyata setelah lebih banyak membaca karya dan membedah naskah, banyak calon penulis di jurusan sastra justru menjadi minder dengan karyanya. Sebab, karya tersohor saja bisa mereka temukan kekurangannya, apalagi saat melihat karya mentah mereka sendiri. Bisa dibayangkan berapa banyak kritik yang bisa mereka lemparkan pada diri sendiri.
Hal yang patut disayangkan, tidak ada pembelajaran yang membahas mengenai developmental editing secara memadai. Umumnya pembelajaran dalam matkul semacam penyuntingan bahasa akan lebih fokus pada masalah line editing yang kadang bahkan kekurangan jam terbang dan harus mahasiswa upayakan sendiri di luar kelas. Itu sebabnya meski tahu karyanya masih banyak kekurangan, mereka kadang tidak yakin cara memperbaikinya.
5. Terbatasnya peluang kerja yang relevan

Blak-blakan saja, peluang kerja dunia penulisan yang hanya mengandalkan pembelajaran dari kurikulum program studi sangatlah kecil. Sangat tidak berimbang antara permintaan pasar serta tersedianya jumlah lulusan sastra. Kalaupun banyak yang mengklaim peluang dunia penulisan sangat besar, penulisan tersebut pastilah bukan yang spesifik masalah sastra.
Dunia penulisan itu cukup luas dan kurikulum kampus seringnya berada satu langkah di belakang perkembangan pasar. Jadi selain memang sulit mengejar perubahan, banyak sekali pasar penulisan yang membutuhkan lintas studi. Jadi jika sebagai calon penulis kamu hanya membekali diri dengan ilmu sastra, tentunya peluangmu mendapatkan pekerjaan akan semakin kecil. Percaya tidak percaya, penulis yang adaptif memiliki peluang lebih besar daripada penulis ideologis yang hanya mau berkubang pada zona nyamannya.
6. Ketatnya persaingan di lapangan

Masih berkaitan dengan poin sebelumnya, karena terbatasnya peluang, maka semakin ketat pula persaingan di lapangan. Itu sebabnya mereka yang punya nilai lebih akan berpeluang lebih besar. Masalah lain kemudian muncul di titik ini. Ternyata banyak orang dari program studi lain juga tertarik menjadikan dunia penulisan sebagai prospek karier mereka.
Kasus yang kemudian muncul, jika pasar membutuhkan buku mengenai bisnis dan mereka dihadapkan pada dua pilihan. Seorang lulusan prodi bisnis yang bisa menulis atau seorang lulusan sastra yang bisa menuliskan masalah bisnis dari hasil riset dan wawancara, menurutmu mana yang punya kredibilitas lebih kuat? Sepertinya perumpamaan ini sudah bisa membuatmu membayangkan dan menilai sendiri situasi-situasi serupa lainnya.
7. Kurangnya apresiasi

Mungkin karena sastra merupakan salah satu bidang tersier dan bukannya primer, apresiasi terkait bidang tersebut lumayan minim. Imbasnya kamu yang akan menjadi penulis dengan latar belakang sastra tidak terlalu punya nilai lebih dibandingkan penulis dari latar belakang lain. Mungkin pernyataan tersebut terdengar picik, tapi memangnya kenapa jika kita juga memperhitungkan keuntungan?
Kenapa sastra seakan-akan elit dan bernilai tinggi jika menjadi tumpangan ideologi dan alat pedagogis tetapi menjadi tabu jika jadi komoditas untuk menghidupi pelakunya? Bukankah justru karena pandangan kaku tersebut masyarakat luas merasa tak perlu memberi apresiasi? "Toh pengarang sudah mendapatkan kepuasan tersendiri dalam proses berkaryanya." Gimana perasaan kamu yang sumber pendapatan utamanya dari menulis saat mendengar pemikiran semacam itu?
Secara umum prodi atau jurusan sastra memang bisa memberikan banyak manfaat seperti membuka wawasan baru, memperkaya keterampilan berpikir kritis, memperluas kemampuan analisis sastra, dan memberikan dasar pengetahuan yang luas dalam berbagai tema serta gaya penulisan.
Akan tetapi, jika tujuan utama kamu adalah menjadi seorang penulis yang mendapatkan pemasukan utama dari pekerjaan tersebut, dalam banyak kasus, masuk ke jurusan sastra mungkin tidak memberikan keuntungan langsung atau praktis. Masih tetap ingin kuliah sastra? Maka risetlah secara mendalam karena prodi sastra di tiap-tiap kampus punya kebijakan dan mata kuliah yang berbeda.