5 Kebiasaan Kecil agar Kamu Tak Jadi Orang yang Mudah Menghakimi

- Penilaian berdasarkan tampilan fisik memperkuat diskriminasi struktural dalam akses pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, bahkan pelayanan publik di Indonesia.
- Konsep attribution bias membuat kita lebih mudah mencap seseorang malas saat melihatnya gagal tanpa menyadari adanya kemungkinan tekanan mental atau hambatan sistemik lainnya.
- Budaya menghakimi kehidupan pribadi orang lain merupakan warisan masyarakat yang merusak nilai kebebasan sipil dan martabat manusia.
Masyarakat adil dan berkelanjutan tidak akan tercipta hanya dari pembangunan infrastruktur yang megah atau bahkan melalui kebijakan makro pemerintah, melainkan tumbuh dari konsistensi kebiasaan kecil yang berlangsung di kehidupan sehari-hari di masyarakat. Salah satu kebiasaan kecil yang paling merusak masyarakat apalagi kalau bukan kecenderungan untuk menghakimi orang lain. Kebiasaan semacam ini bukan sekadar sikap tidak sopan, melainkan akar dari banyak konflik sosial, kesenjangan gender, polarisasi digital, bahkan kegagalan advokasi pada lingkungan hidup.
Di negara majemuk seperti Indonesia, yang dihuni oleh lebih dari 1,3 ribu suku bangsa dan 300 kelompok etnis, berbagai agama, status ekonomi, hingga identitas gender dan kemampuan yang beragam, kemampuan menunda penilaian dan memberi ruang terhadap keberagaman bisa menjadi bentuk tertinggi dari peradaban. Bila pembangunan sumber daya manusia, kesehatan, sains, teknologi, pendidikan, hingga kesetaraan seperti halnya yang tercantum dalam Asta Cita ingin segera diwujudkan, maka reformasi cara berpikir dan empati warga negara Indonesia harus dimulai dari kebiasaan terkecil yakni berhenti menghakimi orang lain. Lantas bagaimana caranya? Mari cari tahu bersama-sama!
1. Hentikan penilaian berdasarkan tampilan fisik

Penelitian dalam bidang neurologi sosial menunjukkan bahwa otak manusia secara otomatis membentuk impresi dalam waktu kurang lebih 100 milidetik terhadap wajah atau penampilan seseorang. Dr. Alexander Todorov dari Princeton University juga menyebut bahwa proses ini dipengaruhi oleh stereotipe yang tertanam secara budaya dan berlangsung tanpa disadari. Di Indonesia, contoh paling nyata bisa dilihat dari prasangka yang diberikan kepada perempuan berhijab yang diasumsikan sebagai sosok konservatif, laki-laki bertato yang dianggap berandalan, atau bahkan penyandang disabilitas yang seringkali dianggap sebagai individu yang kurang produktif, tidak berguna dan butuh dikasihani.
Penilaian berdasarkan tampilan seseorang semacam ini bukan hanya tidak akurat, tetapi juga memperkuat diskriminasi struktural dalam akses pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, bahkan pelayanan publik di Indonesia. Maka menghentikan penilaian dari atribut visual tidak bisa dianggap sebagai isu etika semata, melainkan sebagai prasyarat bagi masyarakat yang ingin berbasis ilmu pengetahuan, data, dan rasionalitas. Literasi visual dan pelatihan kesadaran terhadap bias kognitif harus menjadi bagian kurikulum pendidikan agar generasi masa depan mampu membedakan antara penampilan seseorang dan kapasitas sesungguhnya yang mereka miliki.
2. Ubah asumsi negatif menjadi kemungkinan yang positif

Konsep attribution bias menjelaskan bahwa manusia cenderung menyalahkan karakter atau sifat orang lain atas kegagalan mereka, tetapi menyalahkan keadaan eksternal ketika kegagalan itu terjadi pada dirinya sendiri. Bias ini membuat kita lebih mudah mencap seseorang malas saat melihatnya gagal, tanpa menyadari adanya kemungkinan tekanan mental, trauma, kurangnya dukungan infrastruktur, atau hambatan sistemik lainnya yang tidak terlihat secara kasat mata. Perubahan cara berpikir dari "kenapa sih dia begitu?" menjadi "mungkin dia sedang berjuang menghadapi sesuatu" menjadi salah satu bentuk kematangan kognitif yang harus dilatih sejak dini melalui pendidikan karakter dan pengalaman sosial lintas latar.
Dalam pelayanan publik, perspektif ini akan meningkatkan kualitas hubungan antara guru dan murid, dokter dan pasien, atau pimpinan dan staf. Dalam ekosistem kerja maupun lingkungan komunitas, asumsi positif akan memperkuat rasa percaya, mempercepat kolaborasi, dan mempermudah adopsi inovasi. Bahkan dalam gerakan lingkungan, sikap ini penting untuk memahami gaya hidup seperti veganisme, zero-waste, atau konservasi adat yang sering kali disalahpahami karena tidak mengikuti arus utama.
3. Sadari bahwa kehidupan orang lain tidak layak untuk kita hakimi
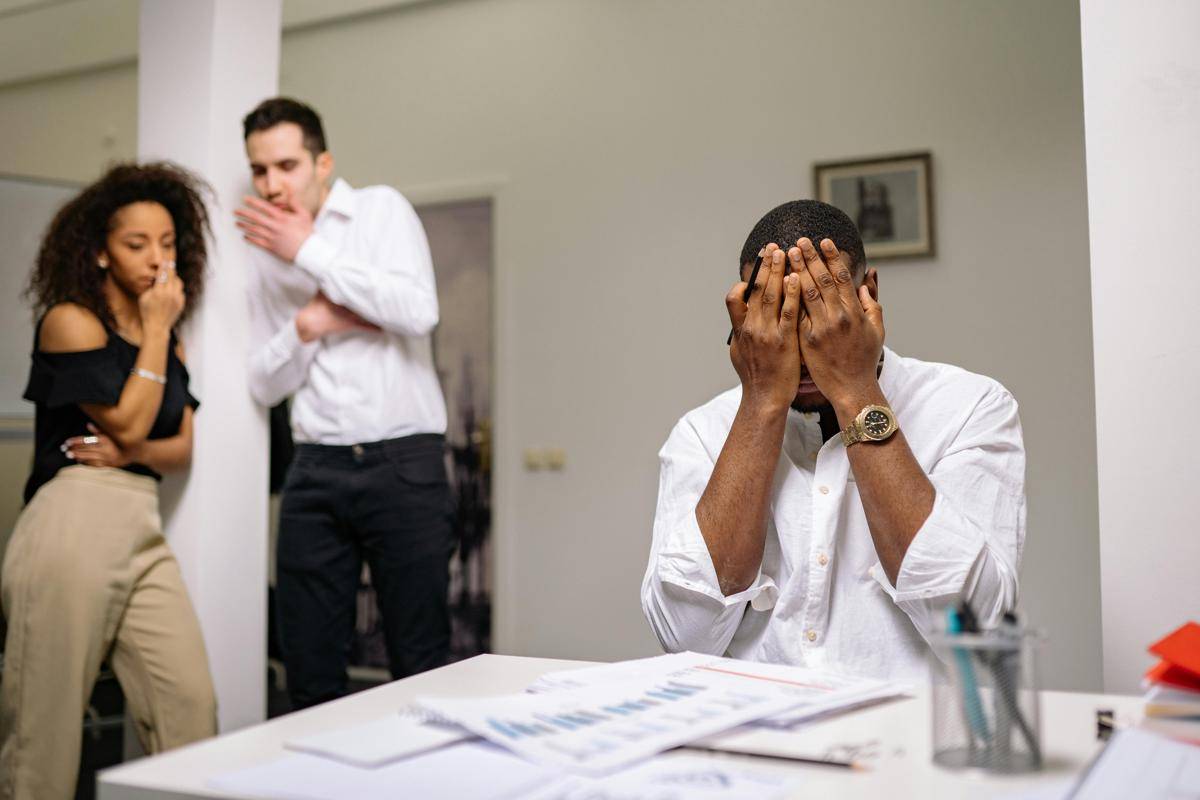
Budaya menghakimi kehidupan pribadi orang lain merupakan warisan masyarakat yang merusak nilai kebebasan sipil dan martabat manusia. Pada era digital yang masif seperti saat ini, fenomena menghakimi orang lain diperparah oleh media sosial yang menjadikan opini publik sebagai alat untuk memvonis orang hanya berdasarkan potongan informasi. Kelompok rentan seperti perempuan, pemuda desa, penyintas kekerasan, penyandang disabilitas, dan komunitas adat sering kali menjadi korban utama narasi tunggal dan persepsi yang menyudutkan.
Kebebasan berpikir dan pilihan hidup harus dipandang sebagai ekspresi valid dari keberagaman pengalaman manusia. Pendidikan empatik dan nilai non-intervensi harus ditanamkan sejak dini agar warga negara memahami bahwa setiap individu memiliki cerita, konteks, dan latar belakang yang tidak bisa disederhanakan. Dalam konteks Asta Cita, penguatan peran perempuan dan penyandang disabilitas tidak akan berhasil jika masyarakat Indonesia terus memaksakan satu ukuran untuk semua, atau menilai mereka berdasarkan standar yang tidak adil. Ruang publik yang aman hanya dapat terbentuk jika warga saling menghormati pilihan hidup satu sama lain tanpa merasa lebih benar.
4. Latih diri untuk mendengarkan tanpa menyela dan membentuk kesimpulan

Active listening merupakan sebuah kemampuan mendengarkan yang dimiliki seseorang untuk memahami, bukan sekadar hanya untuk menanggapi saja. Dalam laporan McKinsey & Company, disebutkan bahwa tim yang memiliki budaya mendengar aktif mampu meningkatkan efektivitas proyek hingga 38 persen lebih tinggi dibanding tim dengan komunikasi satu arah. Ini secara tidak langsung bisa membuktikan bahwa kemampuan mendengarkan bukan sekadar kesantunan, tetapi juga instrumen kerja yang produktif.
Dalam tataran sosial, kemampuan ini menjadi jembatan yang memungkinkan lahirnya pemahaman antarkelompok, baik dalam relasi mayoritas-minoritas, antaragama, maupun antara generasi. Ketika masyarakat bersedia mendengar perempuan yang bicara tentang pelecehan, pemuda yang menyuarakan ide segar, atau atlet disabilitas yang berbagi metode latihan dan tantangannya, maka kebijakan dan sistem yang lahir akan lebih inklusif dan efektif. Mendengarkan secara aktif adalah bentuk toleransi mikro yang bisa menciptakan perubahan makro. Dalam olahraga, misalnya, mendengar kebutuhan atlet muda dari daerah tertinggal bisa menjadi titik awal lahirnya pusat pelatihan berbasis lokal yang unggul.
5. Mulai untuk mempelajari perspektif dari mereka yang hidupnya tak sama dengan kita

Sosiolog asal Prancis, Pierre Bourdieu menyebutkan bahwa untuk memahami struktur sosial, seseorang harus keluar dari titik referensi pribadinya melalui reflexive sociology. Artinya, kita tidak bisa memahami realitas masyarakat hanya dengan berkaca pada pengalaman sendiri. Sayangnya, dalam masyarakat yang homogen secara referensi, empati sering kali hanya berbentuk slogan karena tidak dibangun dari pengalaman lintas perspektif.
Memperluas cakrawala empati bisa dilakukan melalui membaca literatur dari suara marjinal, menonton film dokumenter tentang komunitas adat, terlibat dalam forum lintas identitas, atau mendatangi langsung komunitas lingkungan yang terdampak perubahan iklim. Dari sana, terbentuk keberanian berpikir di luar norma yang biasa, membuka ruang bagi ide kebijakan, inovasi teknologi, serta pendekatan sosial yang benar-benar kontekstual. Bahkan dalam dunia sains dan teknologi, banyak penemuan lahir dari ketidakbiasaan dan keberanian melihat dari sudut yang berbeda. Maka, belajar dari yang berbeda bukan sekadar tugas moral, tapi investasi peradaban.
Toleransi sejati tidak bisa dibentuk lewat regulasi, melainkan dibangun melalui kebiasaan sehari-hari yang menjunjung nilai hormat, pengertian, dan empati. Di tengah gempuran teknologi yang memungkinkan kita menilai cepat tapi memahami lambat, kemampuan untuk menahan diri dari menghakimi menjadi kekuatan paling langka sekaligus paling krusial bagi masa depan bangsa. Tanpa reformasi cara berpikir warga, pembangunan sekuat apa pun akan mudah runtuh karena retaknya kepercayaan sosial. Lima kebiasaan kecil ini bisa jadi fondasi yang akan menentukan seberapa jauh bangsa ini mampu menjadi rumah bersama yang aman, adil, inklusif, dan lestari. Jika kebiasaan menghakimi bisa kita tinggalkan, maka jalan menuju masyarakat harmonis tak lagi menjadi cita-cita, tapi realitas yang bisa kita wujudkan bersama.














































