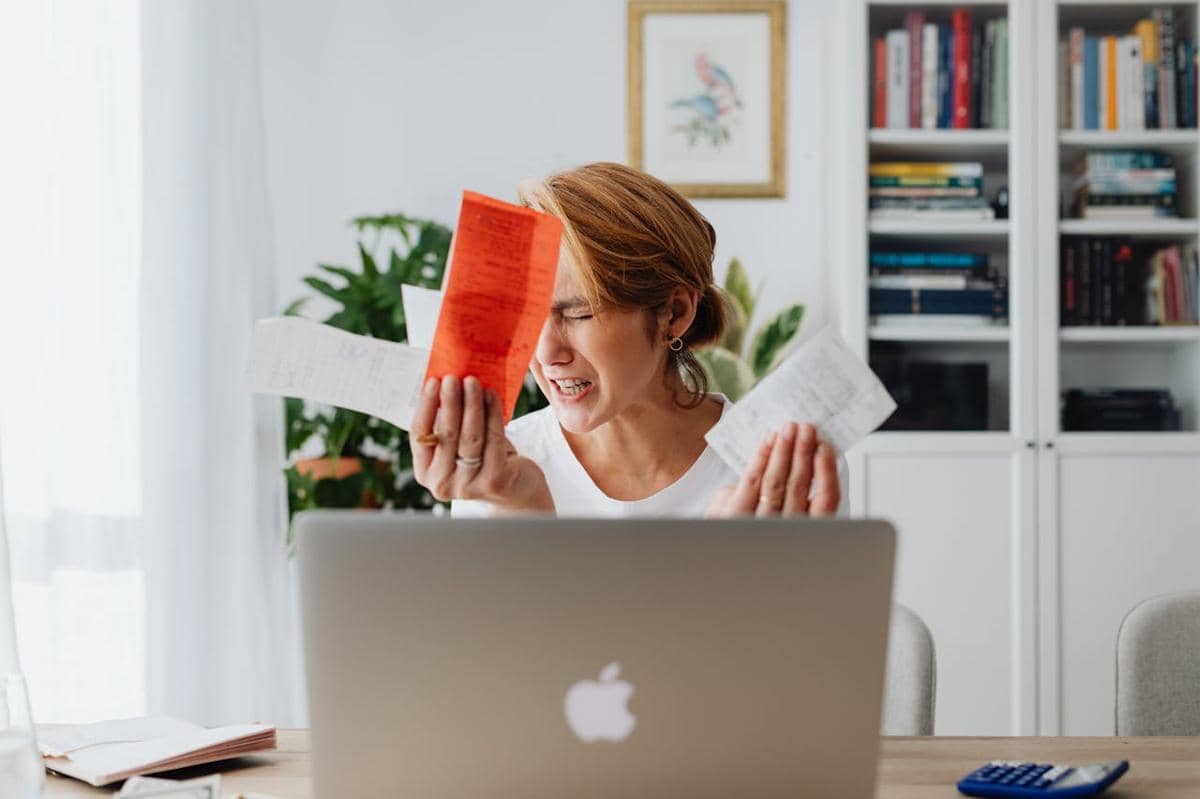“Akhirnya aku stres, terus banyak pikiran, terus aku sampai pengin b*n*h diri.”
[INFOGRAFIS] Sisi Gelap Gen Z dan Milenial: Bullying Masih Eksis?

- Perundungan masih eksis di berbagai kalangan, menimbulkan dampak serius bagi kesehatan mental.
- Bullying tidak hanya menyakiti secara fisik, tetapi juga dapat berdampak pada aspek emosional, sosial, dan psikologis korban.
- Korban perundungan mengalami gangguan hubungan sosial, penurunan motivasi belajar, meningkatnya kecemasan sosial, dan penurunan nilai diri.
Linimasa media sosial penuh sesak dengan berita-berita perundungan yang tak kunjung usai. Tak jarang menimbulkan keinginan untuk mengakhiri hidup. Nyatanya, praktik bullying masih saja eksis di berbagai kalangan, menunjukkan bahwa masalah ini tidak mengenal zaman.
Perilaku ini merajalela baik di dunia nyata maupun digital hingga menimbulkan dampak serius bagi kesehatan mental. Komentar merendahkan, body shaming, hingga cancel culture bisa meninggalkan luka psikologis yang dalam, seperti kecemasan, depresi, bahkan keinginan untuk mengisolasi diri.
Meski berkedok "candaan", bullying kerap meninggalkan trauma dan memori buruk dalam kehidupan korban. Hal membuktikan bahwa generasi muda pun masih punya sisi gelap yang perlu diwaspadai.
Pandangan Gen Z dan Milenial terhadap kasus perundungan telah IDN Times himpun melalui survei yang dilakukan sejak Januari hingga April 2025. Dari 285 responden, sebanyak 56,5 persen menyatakan diri sebagai korban perundungan. Lantas, mengapa bullying masih eksis hingga kini? Seberapa besar efek bullying?
1. Sebagian besar Gen Z dan Milenial pernah menjadi korban bullying
![[INFOGRAFIS] Sisi Gelap Gen Z dan Milenial. (IDN Times/Aditya Pratama)](https://image.idntimes.com/post/20250429/sisi-gelap-gen-z-dan-milenial-bullying-masih-eksis-01-large-4bc36ae0be6faf9947789644fbe1bd02.jpeg)
Perundungan atau bullying merupakan bentuk perilaku agresif yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang memiliki kekuasaan lebih terhadap pihak lain yang dianggap lebih lemah. Menurut Centers for Disease Control and Prevention (CDC) dan US Department of Education, dalam “Preventing Bullying through Science, Policy, and Practice” bullying tidak hanya menyakiti secara fisik, tetapi juga dapat berdampak pada aspek emosional, sosial, dan psikologis korban. Tindakan ini biasanya terjadi secara berulang atau memiliki potensi untuk terulang kembali, menjadikannya masalah serius yang dapat berdampak jangka panjang pada kehidupan korban.
Meski definisi perundungan dapat berbeda-beda tergantung sudut pandang dan konteks sosial budaya, ada satu benang merah yang menyatukannya: bullying selalu melibatkan ketidakseimbangan kekuasaan. Ketidakseimbangan ini membuat korban sulit membela diri dan memperparah luka yang ditimbulkan. Oleh karena itu, memahami esensi dari perilaku ini sangat penting agar kita dapat mengenali, mencegah, dan mengambil langkah tepat dalam menanggulanginya.
IDN Times berhasil menghimpun 285 responden yang didominasi oleh jenis kelamin perempuan (61,4 persen) dan laki-laki sebanyak (38,6 persen). Mayoritas partisipan berdomisili di Pulau Jawa (80,7 persen), Pulau Sumatera (8,8 persen), dan sisanya terbagi di berbagai pulau seperti Sulawesi, Kalimantan, Kepulauan Nusa Tenggara, Bali, hingga luar negeri.
Kasus perundungan jadi konflik yang dialami oleh berbagai kalangan. Informan yang terlibat dalam survei ini terbagi dalam tiga kelompok usia, didominasi oleh generasi Z berusia 15-26 tahun (55,4 persen), generasi milenial berusia 27-40 tahun (36,5 persen), dan baby boomer dari usia di atas 40 tahun (8,1 persen).
Perundungan menjadi isu serius yang terjadi pada berbagai lapisan usia. Fenomena ini ditemui oleh sebagian besar informan yang mengaku pernah jadi korban perundungan (56,5 persen). Meskipun 30,2 persen responden mengaku tidak pernah terlibat dalam konflik agresif ini, namun masih ada 11,6 persen yang mengaku pernah ikut melakukan perundungan sekaligus menjadi korban.
Seiring dengan tingginya keterlibatan individu terhadap kasus perundungan yang terjadi di sekitar mereka, sejumlah pihak merespons dengan cara berbeda ketika melihat tindakan kasar tersebut. Gen Z dan Milenial berupaya membantu menghentikan perundungan (45,6) ketika kekerasan terjadi. Selain itu, informan mengaku berempati dan memberikan dukungan emosional pada korban, kesadaran ini dilakukan oleh sebagian partisipan (28,1 persen).
Sayangnya, tingkat pelaporan tergolong rendah (17,2 persen), bahkan masih ada yang diam atau pura-pura tidak tahu ketika mengetahui adanya perundungan. Menurut Psikolog Arfilla Ahad Dori, bystander effect ini turut memberikan dampak negatif. Mereka yang bersikap diam dan tidak berbuat apa pun ketika melihat perundungan, bisa merasa bersalah, mengalami trauma, atau bahkan muncul desensitisasi terhadap kekerasan (tidak lagi sensitif dan biasa aja lihat tindak kekerasan).
2. Perundungan berdasarkan gender dan usia: perempuan jadi pihak paling rentan bullying
![[INFOGRAFIS] Sisi Gelap Gen Z dan Milenial. (IDN Times/Aditya Pratama)](https://image.idntimes.com/post/20250429/sisi-gelap-gen-z-dan-milenial-bullying-masih-eksis-02-large-0316236a23cec70c053e6620c60daf5e.jpeg)
Aspek internal individu memegang peran penting terhadap perilaku dan niat untuk melakukan perundungan. Faktor seperti usia, gender, kepribadian, dan status sosial jadi hal yang esensial untuk memahami perilaku agresif terhadap perundung. Hal ini dipaparkan dalam publikasi The National Academy of Sciences berjudul “Preventing Bullying through Science, Policy, and Practice”.
Perempuan jadi kelompok paling rentan dalam kasus perundungan, 2 dari 3 perempuan pernah menjadi korban atas tindakan agresif tersebut. Berdasarkan data yang dihimpun oleh IDN Times, pihak terbanyak yang jadi korban bullying adalah perempuan dengan angka mencapai 66,5 persen, sementara laki-laki menduduki posisi kedua dengan persentase 33,5 persen.
Menariknya, proporsi pelaku perundungan oleh perempuan juga menunjukkan tren yang cukup dominan. Sebagian besar perempuan tercatat pernah melakukan perundungan (60 persen) padahal tidak pernah jadi korban, sementara laki-laki menampilkan rasio yang lebih kecil (40 persen). Pemaparan ini menunjukkan perempuan jadi golongan yang paling banyak berurusan dengan kasus perundungan, baik sebagai korban maupun pelaku.
IDN Times menemukan, fenomena perundungan marak terjadi pada individu dengan rentang usia 17-26 tahun. Partisipan survei mengaku pernah menjadi korban bullying ketika menginjak usia remaja hingga dewasa muda (54,6 persen) dan sebagian lainnya menjadi pelaku (60,6 persen) saat menginjak periode usia tersebut.
3. Pelaku bullying tumbuh dari keluarga yang otoriter, benarkah demikian?

Perundungan menjadi masalah serius bagi anak-anak usia sekolah hingga orang dewasa. Perilaku agresif yang banyak menyasar individu atau kelompok yang dianggap lemah ini, pada dasarnya muncul akibat dorongan internal maupun eksternal.
Berdasarkan data yang dihimpun IDN Times, sebagian besar pelaku perundungan (40 persen) mengaku terdorong untuk bertindak agresif akibat pengaruh lingkungan sekitar. Di sisi lain, mereka juga mengungkapkan bahwa tindakan perundungan kerap dilatarbelakangi oleh keinginan untuk balas dendam, menunjukkan dominasi, atau melampiaskan emosi yang tidak tersalurkan.
Sejalan dengan fenomena tersebut, Psikolog Arfilla menegaskan, “Yang pasti, gak ada faktor tunggal yang jadi penyebab seseorang melakukan bullying. Perilaku bullying muncul sebagai hasil dari interaksi banyak faktor yang kompleks.”
Arfilla mengungkapkan bahwa tindakan provokatif kerap dipicu oleh dorongan individu untuk berkuasa dan mengendalikan orang lain, harga diri yang rendah, serta keterampilan sosial yang kurang berkembang. Selain itu, faktor lingkungan juga berperan penting, seperti pola asuh yang otoriter, banyaknya contoh perilaku agresif di sekitar, lemahnya penegakan aturan, serta tekanan dari peer group.
“Anak belajar banyak sekali dari melihat dan memperhatikan lingkungan sekitarnya. Apa yang ditunjukkan lingkungan, itulah yang anak serap. Jika terus berulang, akan terinternalisasi jadi value anak,” tambah Arfilla.
Menurutnya, lingkungan pertama yang memengaruhi kecenderungan sikap agresif anak adalah pola asuh keluarga. Anak yang mendapati perilaku kekerasan dan diabaikan emosinya oleh orang terdekat, akan kesulitan berempati belajar bahwa menyakiti orang lain merupakan tindakan wajar. Lingkungan sosial juga memperkuat perilaku tersebut. Misalnya, dengan menormalisasi perundungan dan menganggap wajar hinaan yang merendahkan orang lain.
Selain pola asuh, kekurangan kasih sayang dalam keluarga merupakan salah satu penyebab munculnya bibit perundungan. Hal ini diutarakan Co-Founder sekaligus Executive Principal dari Playhouse Academy, Dr. Astrid HW-Levi, Ed.D. kepada IDN Times pada Februari 2024 silam. Ketika seorang anak kekurangan kasih sayang, hal ini memungkinkannya mencari kasih sayang dengan cara yang kurang tepat.
Sebagai kepala sekolah, Astrid mengatakan banyak faktor yang melatarbelakangi mengapa perundungan kerap terjadi di sekolah. Untuk itu, anak yang melakukan perundungan secara berulang perlu memerlukan bantuan dari profesional.
“Kalau anak sudah mem-bully dan dia lakukan terus-menerus, harus dibawa ke psikolog. Harus dicari tahu root of the problem-nya itu apa,” kata Astrid.
Pola asuh tertentu jadi salah satu faktor utama timbulnya perilaku konfrontatif. Perspektif ini diperkuat oleh pemaparan ahli dalam jurnal “The Relation between Harsh Parenting and Bullying Involvement and The Moderating Role of Child Inhibitory Control: A Population‐based Study” yang menyatakan harsh parenting atau pengasuhan keras meningkatkan kemungkinan seseorang untuk terlibat dalam peran perundungan (baik sebagai pelaku, korban, maupun keduanya).
Karakteristik pola pengasuhan yang turut berkontribusi pada perilaku perundungan mencakup pengasuhan otoriter yang keras, terlalu mengontrol, dan minim empati. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan ini, cenderung tidak belajar menghadapi konflik dengan cara sehat dan lebih memilih menyelesaikannya dengan kekerasan. Sementara itu, pola pengasuhan permisif di mana orangtua memberikan kebebasan tanpa batasan jelas, dapat menumbuhkan perilaku anak yang enggan menerima aturan dan merasa selalu benar.
“Bullying semakin masif terjadi. Sayangnya, kepedulian orang juga semakin berkurang atau bahkan gak sadar kalau perilaku itu adalah bullying. Bahkan terkadang, banyak yang merasa mem-bully itu tanda lebih hebat. Sebenarnya akarnya cuma satu, yakni kurangnya pendidikan moral. Segala bentuk perilaku bullying bisa dihindari kalau kita manusia yang bermoral dan moral pertama kali diajarkan lewat sekolah terkecil, yakni keluarga. Jadi, sebenarnya orangtua bertanggung jawab penuh membentuk anak yang bermoral dan budaya berperilaku baik,” responden survei berinisial IS asal Pulau Sumatera memberikan tanggapannya terkait kasus perundungan.
Pembuli menargetkan korban karena menilai anak-anak memiliki karakter yang tidak tegas, tidak aman secara emosional, dan ditolak oleh kelompok sebaya. Viktimisasi dilakukan oleh pelaku untuk meningkatkan status dirinya. Hal ini dijelaskan dalam jurnal “Bullying in Schools: The State of Knowledge and Effective Interventions”.
“Kultur mem-bully sudah menjadi permasalahan umum di society kita. Di setiap generasi akan ada dan memiliki ciri khas mereka sendiri walau mungkin saja pengaplikasiannya berbeda. Perilaku menyimpang ini selalu memiliki pola yang sama. Sang pelaku tidak beraksi sendirian dan korban merupakan seseorang yg lemah secara psikis maupun emosional,” komentar responden berinisial IT yang berdomisili di Pulau Jawa.
Menariknya, jika menilik dari sudut pandang pelaku perundungan, mayoritas partisipan mengaku tidak pernah memikirkan dampak jangka panjang dari apa yang dilakukannya (60 persen). Mereka cenderung fokus pada kepuasan pribadi (60 persen) dibanding perasaan bersalah ketika melakukan penindasan. Akan tetapi, setelah melalui periode tersebut, pelaku cenderung menyesali perbuatannya (60 persen).
4. Mengulik sisi gelap Gen Z dan Milenial: bullying masih eksis sampai picu keinginan bunuh diri
![[INFOGRAFIS] Sisi Gelap Gen Z dan Milenial. (IDN Times/Aditya Pratama)](https://image.idntimes.com/post/20250429/sisi-gelap-gen-z-dan-milenial-bullying-masih-eksis-04-large-d3db901a605191f9482c499e5faa28d7.jpeg)
Kasus perundungan mampu mengubah kondisi psikologis seseorang secara signifikan. Tindakan ini tidak hanya menyasar mental individu, namun juga memengaruhi keseharian hingga penurunan potensi akademik.
Mawar (bukan nama sebenarnya) bercerita tentang perundungan yang dialaminya saat masih duduk di bangku SMP. Remaja berusia 15 tahun tersebut mengaku dirundung oleh teman sebayanya dalam bentuk verbal. Hal ini membuat Mawar merasa sedih, marah, dan muncul keinginan untuk mengakhiri hidup.
Ia membagikan kisahnya, “Selain sedih, aku merasa marah, kayak merasa gak adil aja karena mereka mementingkan beauty privilege. Yang cantik diutamakan. Dari situ, aku sering disindir-sindir di sosial media. Akhirnya aku stres, terus banyak pikiran, terus aku sampai pengin bunuh diri.”
“Udah jauh dari keluarga, terus gak punya teman, di rumah juga sendiri, mau cerita ke orangtua gak mungkin. Ya udah, jadi apa-apa aku memendam sendiri,” tambahnya.
Menariknya, kisah Mawar telah marak terjadi. Hampir seluruh responden (88,3 persen) mengungkapkan bahwa mereka pernah menjadi korban perundungan dari teman-temannya. Bentuk perundungan yang paling sering terjadi adalah kekerasan verbal (83,3 persen), diikuti dengan penindasan fisik (27,8 persen), dan cyberbullying (27,8 persen). Tidak mengherankan, sekolah (84 persen) dan lingkungan pertemanan (37 persen) jadi tempat-tempat di mana perundungan paling sering terjadi.
Riset yang dilakukan oleh IDN Times semakin memperkuat pandangan bahwa perundungan bisa menimpa siapa saja dan dilakukan oleh siapa saja. Menariknya, kasus perundungan yang muncul akibat pola perilaku agresif justru paling sering terjadi di tempat yang seharusnya menjadi ruang aman bagi anak, yaitu sekolah.
Responden berinisial NN (25 tahun) mengalami perundungan oleh senior di sekolah. Ia mengalami pemerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang. “Dampaknya jadi holding grudge against those people (menyimpan dendam terhadap orang-orang itu) dan jadi males aktif ekskul. Terus karena pemalakan itu udah jadi tradisi dan budaya selama belasan tahun di sekolah, somehow jadi tertanam juga kalau kegiatan kayak gitu tuh normal (which is not), dan merasa perlu melakukan hal yang sama ke adik kelas nanti,” akunya.
Kerap kali, kita melihat perundungan sebagai tindakan normal yang wajar menjadi bagian dari kehidupan. Mirisnya, perundungan justru menyebabkan gangguan serius secara psikologis, menurunnya kemampuan kognitif, serta timbulnya masalah self-regulation dan gangguan kesehatan fisik, seperti dikutip dari jurnal “Preventing Bullying through Science, Policy, and Practice”.
Konsekuensi serius dari perundungan juga dikonfirmasi oleh mayoritas responden survei yang kehilangan rasa percaya diri akibat menjadi korban bullying (75,3 persen). Efek negatifnya bisa bersifat jangka panjang karena munculnya ketidakpercayaan atau trust issue pada orang lain. Ironisnya, perundungan dapat mengakibatkan seseorang mengalami trauma (50 persen). Korban cenderung rentan mengalami gangguan mental (46,3 persen) dan merasa terisolasi (42,6 persen).
Informan berinisial SW asal Makassar membagikan pengalaman saat alami perundungan, “Aku pernah mengalami bullying saat bersekolah di salah satu SMA negeri yang cukup terkenal di Makassar. Rasanya benar-benar tidak enak. Hidupku terasa hampa, aku kehilangan semangat untuk pergi ke sekolah. Mereka mem-bully-ku lewat ucapan, menertawakanku, dan sering memanggil namaku dengan sebutan aneh yang bukan nama asliku. Akibatnya, aku kehilangan semangat untuk belajar, bahkan sekadar berangkat ke sekolah pun terasa berat. Aku sering menangis diam-diam setelah sampai di rumah. Saat itu, momen paling membahagiakan bagiku justru ketika tidak perlu masuk sekolah.”
Akibat psikologis yang dirasakan SW dianggap valid oleh mayoritas informan. Mereka juga mengaku dominan mengalami ketidakstabilan emosi saat menghadapi perundungan. Perasaan tidak nyaman seperti hilangnya rasa percaya diri (74,1 persen), anxiety (66,7 persen), serta marah dan frustasi (49,4 persen), menghantui kehidupan mereka selama periode perundungan.
Dinamika emosi yang dialami oleh korban memengaruhi bagaimana mereka merespons tindakan tersebut. Perasaan atau dampak negatif membuat korban cenderung insecure, menarik diri, hingga tidak berani mengungkapkan hal yang sebenarnya terjadi.
Hal itu dinyatakan melalui jurnal “Shutting-up or Speaking-up: Navigating the Invisible Line between Voice and Silence in Workplace Bullying (2017)” bahwa rasa malu dan takut dicap buruk jadi alasan mengapa para pekerja yang mengalami perundungan memilih diam dan tidak melaporkan tindakan bullying tersebut. Paparan dalam jurnal tersebut menyatakan bahwa korban perundungan kerap berpikir bahwa tidak akan ada yang percaya. Mereka memilih ketakutan terhadap labelling dari orang lain sehingga memilih menghindar dan tidak berbagi informasi.
Slonje dan Smith dalam jurnal “The Impact of Cyberbullying on Adolescent Health” juga menyatakan 50 persen korban cyberbullying tidak memberitahu siapa pun tentang pengalaman perundungan mereka. Daripada memberi tahu orang dewasa, 35,4 persen informan dalam riset tersebut lebih memilih mengutarakan pengalaman cyberbullying kepada teman.
Kondisi serupa juga dialami oleh masyarakat Indonesia. Riset IDN Times memaparkan bahwa ada 2 dari 3 generasi muda yang menjadi korban perundungan lebih banyak menjauh atau menghindar saat berjuang mengatasi kasus tersebut. Sejalan dengan tingkat pelaporan yang terbilang rendah (22,8 persen), responden juga mencatat lebih memilih untuk memendam atau menyimpan krisis yang dialaminya (48,1 persen).
“First thing first, kalau aku pribadi, aku memilih untuk menjauhkan diri dan menghindarkan diri aku dari tempat itu. Aku pribadi memilih untuk menjauhkan diri untuk menghindari tempat itu dan juga aku lebih menutup diri buat gak main sama anak-anak (yang pernah merundung). Aku gak mau ketemu lagi biar kasarnya aku membiarkan waktu yang menyembuhkan. Aku berharap aja semua orang lupa sama momen itu karena aku main dewasa kan, gak sama kayak waktu aku kecil. Jadi, harusnya orang-orang lupa, udah gak inget sama kejadian itu," ujar JT (24 tahun) yang dirundung oleh orang asing di ruang publik.
Menariknya, Gen Z dan Milenial berupaya untuk lepas dari kasus perundungan dengan keluar dari lingkungan toxic yang merugikannya (40,7 persen). Sementara, masih banyak korban yang menunjukkan keberaniannya dengan melawan (26,5 persen). Di sisi lain, Gen Z dan Milenial juga menggalakkan tindakan preventif dengan menyebarkan awareness (mendukung korban, memberi pemahaman tentang bullying, memberi contoh perilaku yang baik).
“Pandangan saya mengenai perundungan adalah suatu hal yang sangat penting untuk kita lawan dan jauhi. Pem-bully-an adalah sikap yang menunjukkan ketidakdewasaan seseorang dalam berpikir karena ia merasa lebih baik dari orang lain atau mungkin jika ia hanya sekedar ikut-ikutan, maka semakin jelek lagi perilakunya dan menunjukkan bahwa pelakunya adalah orang yang bodoh secara logika. Akan tetapi, kita juga harus mempertimbangkan alasan mereka melakukan pem-bully-an di media sosial karena bisa saja ia adalah seseorang yang menjadi korban pem-bully-an di real life,” tulis IN, remaja perempuan berdomisili di Pulau Sumatera.
5. Perundungan di sekolah: ruang aman yang mengancam anak-anak
![[INFOGRAFIS] Sisi Gelap Gen Z dan Milenial. (IDN Times/Aditya Pratama)](https://image.idntimes.com/post/20250429/sisi-gelap-gen-z-dan-milenial-bullying-masih-eksis-05-large-2d2a06afa7cbdb5a53ed9e05b93f8360.jpeg)
Sekolah sudah sepatutnya menghadirkan tempat yang nyaman bagi individu untuk mengeksplorasi dan mengembangkan potensi diri. Ironisnya, lingkungan pendidikan yang seharusnya jadi ruang aman bagi anak-anak, justru menorehkan luka dan trauma akibat kasus perundungan. Pemaparan di atas membuktikan, hampir seluruh kasus perundungan terjadi di sekolah, terutama dilakukan oleh teman.
Arfilla membagikan pandangannya sebagai profesional, “Sekolah adalah tempat dengan tekanan yang tinggi bagi anak, baik tekanan akademik (target belajar, kompetisi, dan lain-lain) juga tekanan sosial dari peer-group. Di usia anak sekolah, faktor teman dan image (pencapaian prestasi) memberi pengaruh besar sekali ke anak.”
Arfilla juga menyebutkan bahwa sekolah jadi tempat anak berkumpul dari latar belakang yang beragam dalam rentan waktu tertentu, sehingga benturan antar berbagai konflik dan kepentingan kerap kali tak bisa dihindarkan. Permasalahan kian kompleks apabila pihak sekolah gagal memediasi konflik yang terjadi dan tidak dapat mengajarkan nilai-nilai seperti empati, manajemen emosi, toleransi dan lain-lain.
Korban perundungan dan penurunan prestasi akademik, ternyata memiliki korelasi yang kuat. Korban perundungan cenderung memiliki skor yang rendah terhadap kemampuan kognitif dan motivasi sekolah sebab kurangnya fokus, motivasi belajar yang rendah, dan perasaan tidak mampu menyelesaikan studi.
Dengan kata lain, perundungan memengaruhi cara seseorang berpikir dan merasa tentang diri mereka sendiri serta menentukan kemampuan mereka. Pada akhirnya, itu juga mengurangi motivasi dan kinerja akademik. Pemaparan ini berdasarkan riset dalam “How Can Bullying Victimisation Lead to Lower Academic Achievement? A Systematic Review and Meta-Analysis of the Mediating Role of Cognitive-Motivational Factors”.
“Bullying yang tidak segera ditangani atau dihentikan dapat berdampak besar pada akademik korban, seperti konsentrasi dan fokus belajar menurun karena mereka merasa cemas, takut, dan tertekan di sekolah sehingga lebih sering ada di fase survival mode. Otak fokus mencari cara untuk yang penting bisa bertahan,” ujar Arfilla.
Persoalan perundungan dapat dicegah dengan langkah preventif yang diterapkan secara konsisten. Arfilla menggarisbawahi respons yang bisa dilakukan oleh sekolah untuk menangani kasus bullying, seperti keberpihakan pada korban tanpa menyudutkan, memberikan sanksi tegas kepada pelaku sesuai SOP dan aturan yang berlaku, hingga menyediakan pendampingan psikologis bagi pihak yang terlibat.
Selain itu, apabila terlibat dalam kasus perundungan, dapat melaporkan kepada pihak berwenang jika diperlukan. Keterbukaan dalam penyelesaian kasus bullying jadi aspek penting, mengingat siswa lain dan orang tua juga berhak mengetahui perkembangan kasus yang dapat berdampak pada keselamatan dan kenyamanan.
“Sekolah harus mengembangkan sistem nilai yang dianut sekolah dan semua praktik sekolah sehari-hari harus selaras dengan ini. Misal, sekolah gencar mengedukasi anak tidak boleh melakukan bullying, maka perilaku sekolah pun harus sesuai. Jangan sampai menyuruh siswa jangan bullying, tapi sehari-hari gurunya sering berkata kasar, merendahkan siswa, atau bahkan menggunakan kekerasan,” imbuh Arfilla.
6. Cyberbullying menjerat generasi muda, salah kaprah bermedia sosial bisa berakhir cancel culture

Era teknologi yang berkembang begitu dinamis, memungkinkan seseorang melakukan perundungan secara digital. Hal ini disetujui oleh mayoritas responden (60 persen) yang lebih banyak melakukan cyberbullying dibanding kekerasan fisik atau verbal secara langsung. Sosial media dan anonimitas membuka celah bagi pengguna untuk melemparkan pandangan pribadi secara bebas.
Fenomena perundungan daring atau yang lebih dikenal dengan cyberbullying, merupakan tindakan agresif yang kerap terjadi di media sosial. Bentuk perundungan seperti hate comments, penyebaran rumor, penghinaan, hingga ancaman virtual yang menyasar pihak tertentu, dapat menimbulkan ketidaknyamanan. Selain itu, tindakan cyberbullying berpotensi mengganggu kesejahteraan psikologis seseorang dan merusak kehidupan individu secara drastis.
Kerentanan media sosial dinilai psikolog Faza Maulida sebagai permasalahan yang serius, “Jadi, yang namanya kita itu sedang bermedia sosial, kita cenderung memiliki anonimitas. Kita bisa saja mengungkapkan hal-hal yang mungkin itu too harsh, tanpa orang itu jadinya tahu sebenarnya siapa sih di balik akun itu. Jadi, gara-gara itu, makanya orang itu jadi lebih mudah untuk mengatakan hal-hal atau mengucapkan kalimat-kalimat yang itu menyakiti orang lain, yang pada akhirnya itu lead into bullying. Jadinya, memang ketika kita bermedia sosial, jelas menjadi lebih rentan.”
Pola perundungan di media sosial dipicu oleh kebebasan penuh yang dimiliki seseorang untuk mengungkapkan isi pikiran dan perasaannya, tanpa mempertimbangkan pihak lawan. Faza menerangkan, interaksi di media sosial membuat adanya less empathetic interaction, artinya seseorang cenderung sulit berempati terhadap kondisi atau situasi orang lain. Perilaku ini yang kemudian mendorong sikap agresif.
Berkat adanya anonimitas, proses ini terasa lebih ‘aman’, sehingga pengguna merasa tidak perlu mempertanggung jawabkan ujaran yang dilemparkan pada jejaring sosial di dunia maya. Akibatnya, media sosial menjadi wadah yang rentan terhadap perundungan.
“Pandangan saya untuk perundungan dan hate comments memang tidak etis karena itu bisa menyakiti perasaan orang tersebut dan membuat mental mereka down,” tulis perempuan berinisial AD yang berdomisili di Pulau Jawa.
Menurutnya, perundungan di media sosial dapat dipicu hate comments yang digunakan sebagai sarana untuk melampiaskan emosi sesaat. Selain itu, AD juga menggarisbawahi rendahnya kemampuan literasi pengguna media sosial sehingga mudah untuk melakukan tindakan agresif di dunia maya.
Korban perundungan mengakui munculnya gangguan hubungan sosial, terutama pada remaja. Secara spesifik, cybervictimization atau korban perundungan siber merasa kesepian, penurunan motivasi belajar, meningkatnya kecemasan sosial, dan penurunan nilai diri. Riset ini dipaparkan oleh jurnal “The Impact of Cyberbullying on Adolescent Health”.
Informan survei dengan inisial nama FK, yang berdomisili di Pulau Jawa, berpendapat bahwa perundungan kerap muncul karena tindakan negatif yang dapat mengganggu kondisi mental seseorang. Menurutnya, “Bullying di media sosial, termasuk hate comments dan ujaran kebencian, adalah masalah serius yang dapat memiliki dampak negatif pada kesehatan mental dan emosional seseorang.”
Faza menilai cyberbullying menjadi tindakan yang kompleks, terutama bagi remaja. Pasalnya, pada fase peralihan antara masa kanak-kanak dan dewasa, seorang remaja cenderung menutup diri sehingga tidak memiliki cara coping yang baik.
Ditanya seberapa besar dampak bullying di media sosial, Faza menilai tindakan ini akan memengaruhi banyak aspek kehidupan dalam jangka panjang. “Kerentanannya itu akan menjadi sangat-sangat panjang kalau misalnya kasus yang dialami itu tidak teratasi dengan baik atau gangguan psikologis yang dialami itu tidak ditangani dengan baik,” kata dia.
Menurut teori transaksional tentang stres dan coping dalam jurnal “The Impact of Cyberbullying on Adolescent Health” oleh Medical Research terkait Adolescent Health, Medicine and Therapeutics, dampak cyberbullying tidak hanya bergantung pada peristiwa itu sendiri, tetapi juga pada bagaimana remaja merespons situasi tersebut.
“Kasus bullying atau cyberbullying, bentuk intervensinya itu gak bisa kalau hanya dilakukan secara individual. Jadi memang harus bentuknya itu adalah intervensi secara komunitas sehingga nanti bisa memunculkan yang namanya resiliensi kolektif. Memang semua faktor-faktor atau semua aspek-aspek yang ada dalam kehidupan dari komunitas terkecil, yaitu keluarga sampai dari jenjang kebijakan atau pemerintah itu, sebenarnya harus turut serta mengatasi hal ini,” tegas Faza.
Langkah kolektif yang dilakukan oleh individu dan masyarakat harus saling bersinergi untuk menciptakan ruang aman bermedia sosial. Kesadaran bahwa keamanan digital adalah tanggung jawab bersama menjadi fondasi utama dalam membangun ekosistem online yang lebih positif.
“Jadi, yang bisa kita lakukan itu adalah sebisa mungkin kita menciptakan perubahan digital yang aman. Sebisa mungkin kita juga menahan diri supaya diri kita itu tidak menjadi seorang pelaku atau kita itu harus memiliki kontrol diri yang sebaik mungkin supaya bisa menahan diri dari mengetik atau mengungkapkan hal yang sebenarnya itu menyakiti orang lain dan kemudian lead to bullying tadi,” ujar Faza.
Isu cyberbullying erat kaitannya dengan fenomena cancel culture atau budaya penghapusan popularitas seseorang. Kultur ini muncul sebagai konsekuensi atas perbuatan individu atau sekelompok orang yang dinilai kurang sesuai dengan norma yang berlaku. Hukuman yang diterima oleh individu atau sekelompok orang berupa kritik dan pemboikotan berdasarkan pandangan kolektif masyarakat di internet.
“Secara psikologi, cancel culture lebih kayak bentuk aksi-reaksi gitu lho. Misalnya, seseorang melakukan sesuatu yang mungkin itu di luar norma masyarakat pada umumnya, kemudian tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut sama masyarakat itu, kemudian kan orang-orang jadi meng-cancel dia gitu,” terang Faza sembari menambahkan bahwa cancel culture dapat menjadi perbuatan yang kurang objektif lantaran dapat muncul kecenderungan seseorang kurang memahami pokok permasalahan yang diangkat.
Pandangan tersebut sejalan dengan perspektif responden berinisial ER. Perempuan yang berdomisili di Pulau Sumatera tersebut mengungkapkan, “Cancel culture juga sering kali menjadi pisau bermata dua—awalnya bertujuan untuk meminta pertanggungjawaban seseorang atas kesalahannya, tetapi dalam banyak kasus justru berubah menjadi perundungan massal yang tidak memberikan kesempatan bagi seseorang untuk memperbaiki diri. Dampaknya bisa sangat besar, baik secara psikologis maupun sosial. Korban bisa mengalami gangguan mental, kehilangan reputasi, bahkan kesulitan dalam kehidupan profesional dan sosialnya.”
Kesadaran tentang pentingnya etika digital serta bagaimana bermedia sosial secara bertanggung jawab, ditekankan oleh ER dalam kasus ini. Sejumlah responden sepakat bahwa anonimitas dan ruang untuk melemparkan ujaran kebencian seperti hate comments memudahkan seseorang untuk melakukan perundungan maupun menjadi pihak yang ditindas.
Informan berinisial NAW, menyebutkan, “Bullying di media sosial, termasuk hate comments dan cancel culture, menunjukkan kegagalan kolektif kita dalam memanfaatkan teknologi secara bertanggung jawab.”
“Ini adalah cerminan dari literasi digital yang rendah, kurangnya empati, dan obsesi untuk mencari kesalahan sebagai hiburan kolektif. Jika dibiarkan, budaya ini akan menciptakan masyarakat yang semakin tidak toleran, penuh ketakutan, dan kehilangan ruang untuk diskusi kritis yang sehat. Kita membutuhkan reformasi menyeluruh—dari regulasi platform hingga pendidikan moral digital—agar kebebasan berpendapat tidak menjadi pembenaran untuk melukai orang lain,” tambahnya.
7. Gen Z dan Milenial percaya bullying adalah lingkaran setan. Meski demikian, masih banyak generasi muda yang melakukannya
![[INFOGRAFIS] Sisi Gelap Gen Z dan Milenial. (IDN Times/Aditya Pratama)](https://image.idntimes.com/post/20250429/sisi-gelap-gen-z-dan-milenial-bullying-masih-eksis-03-large-3236dad89a701ac35b1e61b4ef0d82b7.jpeg)
IDN Times menghimpun data dengan melemparkan pernyataan kepada responden terkait perundungan untuk menggali perspektif mereka. Berikut adalah rangkuman hasil pandangan Gen Z dan Milenial yang disepakati oleh informan dan berhasil terhimpun.
Perundungan menjadi luka yang sulit disembuhkan bagi Gen Z dan Milenial. Tak memungkiri, aksi agresif ini bak trauma sepanjang hidup bagi generasi muda, yang sulit dihapuskan.
Bagi generasi muda, belum adanya solusi konkret untuk menuntaskan perundungan masih menjadi akar permasalahan yang membuat kasus ini tak terselesaikan secara tuntas. Mereka juga setuju, korban bullying rentan menjadi pelaku di masa depan, sehingga menciptakan ‘lingkaran setan’ yang tak berujung.
Perspektif ini sejalan dengan pernyataan psikolog pendidikan Putri Sari, “Kalau di psikologi, kita bisa bilang ada yang namanya trauma atau emosi yang dipendam. Nah, kalau misalnya si emosi ini dipendam ketika kecil, terus ada sesuatu yang nanti men-trigger emosi ini untuk muncul, bisa aja (terjadi bullying).”
Kasus perundungan kian pelik, menurut mayoritas Gen Z dan Milenial, berkat budaya atau kebiasaan dalam masyarakat. Kasus bullying kerap kali terjadi berkat adanya perpeloncoan, senioritas yang banyak terjadi di lingkup sekolah dan masyarakat.
Terlebih berkat adanya kemudahan teknologi, kesempatan bagi generasi muda untuk melakukan perundungan dan mendapatkan penindasan di ruang siber atau cyberbullying kian masif. Fenomena ini kian meluas seiring berkembangnya teknologi digital.
“Kita harus menjaga mental kita sendiri. Kalau memang kita merasa bahwa kita lagi gak oke, ya jangan buka hal-hal yang membuat kita menjadi semakin gak oke. Jadi, memang kesadaran diri kita itu pada akhirnya akan sangat-sangat penting supaya kita juga jadi orang yang gak gegabah (dalam bermain media sosial),” ungkap Psikolog Faza Maulida.
8. Fakta menarik seputar bullying
![[INFOGRAFIS] Sisi Gelap Gen Z dan Milenial. (IDN Times/Aditya Pratama)](https://image.idntimes.com/post/20250429/sisi-gelap-gen-z-dan-milenial-bullying-masih-eksis-06-large-3773b4638b579fd0a41e0ff30a447405.jpeg)
Bayangan kelam bernama perundungan masih menyelimuti kehidupan Gen Z dan Milenial. Perundungan bukan sekadar fisik dan verbal saja, media sosial juga membuka peluang besar terjadinya cyberbullying.
Data IDN Times memaparkan sebagian besar informan (56,5 persen) pernah jadi korban. Hal ini menjadi bukti bahwa kasus perundungan di Indonesia gak bisa dianggap sepele. Korban perundungan mengakui bahwa tindakan tersebut sangat mempengaruhi kondisi psikis.
Bak lingkaran setan yang berputar tanpa henti, kasus perundungan nyatanya dialami oleh banyak pihak, khususnya perempuan yang rentan jadi sasaran (66,5 persen). Sayangnya, banyak pelaku mengaku tak sadar akan luka jangka panjang yang mereka tinggalkan dan baru menyesal saat semuanya telah terlambat. Bahkan lebih banyak informan yang mengaku sudah memikirkan dampak yang mungkin terjadi akibat bullying dan tetap melakukannya.
Sayangnya, hanya ada 17,2 persen yang berupaya melaporkan tindakan bullying. Data survei juga menjelaskan bahwa korban selama ini cenderung menjauh dan menghindar ketika mendapatkan perlakuan tersebut. Artinya, masyarakat masih membutuhkan awareness untuk mau dan berani speak up agar tidak ada lagi korban perundungan lainnya.
Perihal mengatasi dan mencegah perundungan bukanlah perkara yang mudah. Faza sebagai profesional, menyebut kasus bullying, khususnya cyberbullying, memerlukan intervensi secara komunitas mencakup semua aspek kehidupan dari keluarga, sekolah, bahkan pemerintah.
Secara preventif, Faza mengatakan, “Paling penting dan paling utama adalah mencanangkan atau mengedukasi anak terkait emosi. Ketika anak sudah mulai memahami sekitar, dia boleh banget diajarkan terkait penanaman nilai-nilai dan emosi sehingga orangtua perlu membangun pola komunikasi yang hangat dan terbuka kepada anak.”
Ketika anak merasakan emosi yang membuatnya gak nyaman, anak akan paham bahwa mereka punya ruang aman seperti keluarga untuk bisa mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi baik di kehidupan sehari-hari maupun media sosial. Terkait cyberbullying, Faza menekankan pentingnya pendampingan orangtua terhadap akses remaja ke media sosial. Tujuannya agar anak juga tahu mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan.
Sekolah menduduki peringkat teratas terjadinya perilaku perundungan. Untuk itu, pihak sekolah pun perlu menerapkan tindakan preventif dan represif. Menurut Faza, sekolah perlu menyediakan ruang aman supaya siswa bisa melaporkan apabila terjadi kasus perundungan.
Arfilla juga menuturkan, “Jika anak jadi pelaku, maka tidak defensif. Bertanggung jawab sepenuhnya, baik pada proses penegakan aturan di sekolah maupun secara hukum. Bicara dari hati ke hati dengan anak agar paham konteks kejadian dan motif anak melakukan hal tersebut, termasuk apa yang anak rasakan selama ini terhadap diri dan orang tuanya.”
Dari sisi sekolah, Astrid menyarankan agar sekolah juga membuka ruang dialog antara korban, pelaku, maupun orangtua. Terkait tindakan represif, sekolah bisa mendiskusikan hal tersebut kepada orangtua dan bersama-sama mencari solusinya.
Tindak preventif sejatinya dibangun sejak dini. Hal ini berkaitan dengan pola asuh yang sehat, perilaku ber-value positif, serta melengkapi diri dengan pemahaman tentang bullying secara menyeluruh. Bagi mereka yang menjadi korban, pastikan ada dukungan psikologis yang sehat baik dari sisi keluarga maupun lingkungan. Kalau bukan kita yang memulai, siapa lagi?
Referensi:
- Menestrel, S. L. (2020). Preventing Bullying: Consequences, Prevention, and intervention. Journal of Youth Development, 15(3), 8–26. https://doi.org/10.5195/jyd.2020.945.
- Samara, M., Da Silva Nascimento, B., El-Asam, A., Hammuda, S., & Khattab, N. (2021). How can bullying victimisation lead to lower academic achievement? A Systematic Review and Meta-Analysis of the Mediating Role of Cognitive-Motivational Factors. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(5), 2209. https://doi.org/10.3390/ijerph18052209.
- Hogye, S. I., Jansen, P. W., Lucassen, N., & Keizer, R. (2021). The relation between harsh parenting and bullying involvement and the moderating role of child inhibitory control: A population‐based study. Aggressive Behavior, 48(2), 141–151. https://doi.org/10.1002/ab.22014.
- Easteal, P., & Ballard, A. J. (2017). Shutting-up or speaking-up: Navigating the invisible line between voice and silence in workplace bullying. Alternative Law Journal, 42(1), 47–54. https://doi.org/10.1177/1037969x17694793.
- Nixon, C. (2014). Current perspectives: the impact of cyberbullying on adolescent health. Adolescent Health Medicine and Therapeutics, 143. https://doi.org/10.2147/ahmt.s36456.
- Menesini, E., & Salmivalli, C. (2017). Bullying in schools: the state of knowledge and effective interventions. Psychology Health & Medicine, 22(sup1), 240–253. https://doi.org/10.1080/13548506.2017.1279740
Penulis:
Dina Fadillah Salma
Adyaning Raras Anggita Kumara
Grafis:
Aditya Pratama
Editor:
Pinka Tsarina Wima
Febriyanti Revitasari
Muhammad Tarmizi Murdianto