Mengapa Barang Thrifting Harganya makin Melambung?

Penjual membentuk nilai lewat kurasi dan branding
Tren media sosial mendorong permintaan
Kualitas sering disejajarkan dengan barang baru
Fenomena thrifting di Indonesia awalnya dikenal sebagai cara hemat untuk mendapatkan pakaian layak pakai dengan harga ramah di dompet. Namun, beberapa tahun terakhir, citra itu mulai berubah. Barang-barang yang seharusnya identik dengan murah justru dijual dengan harga yang cukup tinggi, bahkan kadang menyaingi produk baru di mal. Kondisi ini menimbulkan tanda tanya bagi banyak orang yang merasa nilai thrifting sudah jauh bergeser dari konsep awalnya.
Ada yang menilai hal ini wajar karena faktor kurasi dan tren, ada pula yang merasa pasar sengaja dimanipulasi demi keuntungan. Situasi tersebut memunculkan perdebatan soal batas wajar harga yang pantas untuk pakaian bekas. Apalagi, setiap orang punya standar berbeda tentang apa itu murah dan apa itu mahal. Berikut beberapa hal yang patut diperhatikan untuk memahami mengapa thrifting harganya makin melambung.
1. Penjual membentuk nilai lewat kurasi dan branding

Banyak penjual kini tidak sekadar menjajakan pakaian bekas apa adanya, melainkan melakukan kurasi. Mereka memilih potongan yang dianggap estetik, mengikuti tren, atau berasal dari label populer. Proses ini tentu memakan waktu, tenaga, bahkan biaya tambahan. Dari sudut pandang penjual, wajar jika harga dinaikkan karena mereka menjual “nilai tambah” berupa gaya dan identitas, bukan sekadar kain bekas.
Namun, di sisi pembeli, kondisi ini sering memicu perasaan harga tidak masuk akal. Barang yang dulunya bisa dibeli puluhan ribu rupiah kini ditawarkan ratusan ribu hanya karena diberi label “rare” atau “vintage”. Branding yang diciptakan penjual membuat pakaian biasa terlihat eksklusif, sehingga pembeli merasa terdorong membeli bukan karena kebutuhan, melainkan citra sosial. Inilah awal mula harga barang thrifting jadi terasa melambung tinggi.
2. Tren media sosial mendorong permintaan
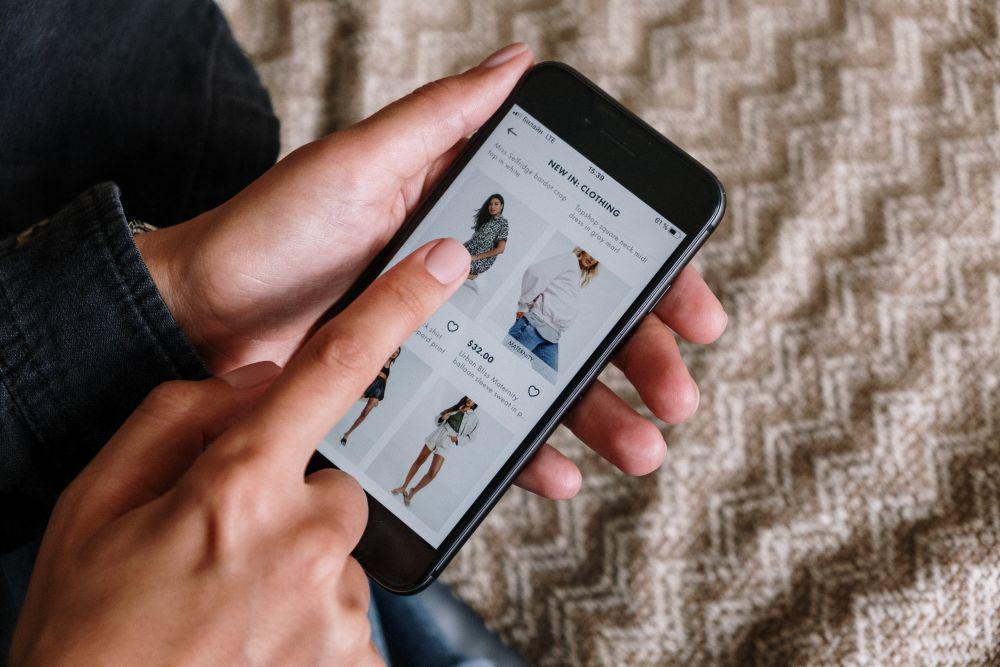
Tidak bisa dimungkiri, media sosial punya peran besar dalam memengaruhi perilaku belanja. Foto atau video seseorang yang tampak modis dengan pakaian thrift membuat orang lain ingin tampil serupa. Padahal, jika ditarik ke belakang, gaya itu sebenarnya terbentuk bukan dari mahalnya barang, melainkan cara memadukannya. Ketika permintaan meningkat pesat, penjual melihat peluang untuk mengerek harga.
Di sisi lain, tren ini juga menumbuhkan semacam standar gaya yang membebani sebagian orang. Mereka merasa tertinggal jika tidak ikut berbelanja di toko thrifting populer. Akibatnya, nilai barang bekas tidak lagi ditakar dari kualitas fisik, melainkan dari seberapa “Instagramable” ia terlihat. Permintaan yang tidak rasional inilah yang akhirnya memperkuat alasan harga naik.
3. Kualitas sering disejajarkan dengan barang baru

Sebagian besar pembeli thrifting kini menuntut kualitas yang nyaris setara dengan barang baru. Pakaian yang bebas noda, tidak pudar, hingga berasal dari merek internasional dianggap lebih layak dihargai tinggi. Penjual pun menjadikan kualitas sebagai justifikasi untuk menaikkan harga, dengan alasan bahwa barang baru di mal bisa lebih mahal berkali lipat.
Masalahnya, anggapan ini membuat batas murah dan mahal jadi kabur. Apakah baju thrift seharga 50 ribu masih disebut murah, atau sudah mahal karena bekas? Sering kali, pembeli tidak lagi menimbang dari fungsi pakaian, tetapi dari gengsi yang melekat. Kualitas memang penting, tapi logika perbandingan dengan barang baru tidak bisa sepenuhnya dipaksakan pada pasar barang bekas.
4. Risiko barang palsu dan label manipulatif

Fenomena lain yang tidak kalah penting adalah maraknya barang palsu yang diselipkan di pasar thrifting. Ada penjual yang mengaku menjual “barang branded asli” padahal kualitasnya KW. Pembeli awam sulit membedakan, apalagi jika tidak paham detail produk asli. Situasi ini membuat harga thrifting semakin tidak konsisten dan rentan menipu.
Lebih jauh, label “rare”, “limited”, atau “vintage” sering dipakai sebagai strategi pemasaran semata. Tidak jarang barang biasa pun dilekatkan dengan istilah itu demi membenarkan harga yang lebih tinggi. Hal ini menimbulkan dilema apakah pembeli membayar nilai autentik, atau sekadar ilusi eksklusivitas yang dibentuk penjual? Dari sinilah muncul kekecewaan dan rasa ragu terhadap wajar tidaknya harga yang ditawarkan.
5. Perubahan cara pandang konsumen

Pada akhirnya, lonjakan harga juga dipengaruhi cara pandang konsumen sendiri. Ada kelompok yang rela membayar mahal karena melihat thrifting sebagai gaya hidup ramah lingkungan. Mereka merasa uang yang dikeluarkan sepadan dengan ide keberlanjutan. Di sisi lain, ada pula yang melihatnya sebatas tren sementara, sehingga merasa harga sekarang jauh melampaui logika.
Dua pandangan ini membuat pasar thrifting terbagi. Sebagian orang semakin menganggap pakaian bekas bernilai tinggi, sementara sebagian lain merasa dipermainkan. Bagi konsumen yang berpenghasilan terbatas, kondisi ini justru menyingkirkan esensi awal thrifting sebagai solusi belanja murah. Maka, harga “selangit” sebetulnya lebih banyak mencerminkan pergeseran persepsi ketimbang kebutuhan nyata.
Fenomena thrifting harganya makin melambung memperlihatkan bagaimana pasar, tren, dan persepsi saling memengaruhi. Bagi sebagian orang, harga tersebut masuk akal karena alasan kurasi dan kualitas, tetapi bagi yang lain, justru terasa tidak wajar. Pada akhirnya, kembali pada konsumen sendiri apakah membeli barang thrift untuk fungsi, gaya, atau sekadar citra?


























