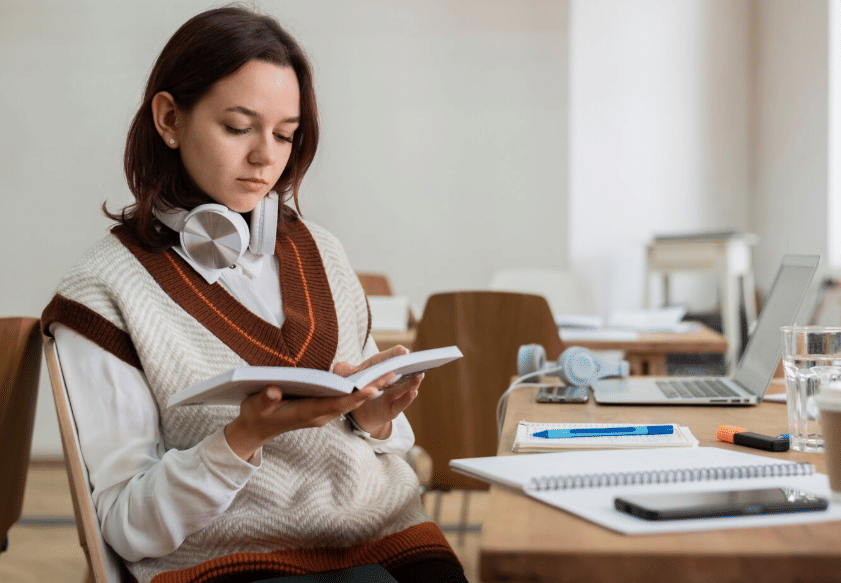Andil Perempuan Andal dalam Menjaga Masa Depan Plasma Nutfah

- Perempuan sebagai penjaga plasma nutfah di pedesaan menyumbang hingga 90 persen benih dan germplasm yang digunakan petani.
- Peran perempuan dalam pertanian modern dapat diperkuat melalui integrasi sains dan teknologi untuk meningkatkan efisiensi serta produktivitas.
- Pelestarian plasma nutfah memerlukan harmoni sosial, struktur kelembagaan yang mendukung, dan praktik agribisnis berkelanjutan.
Jalinan antara keharmonisan sosial dengan lingkungan dapat diwujudkan melalui konsep pertanian berkelanjutan. Pertanian berlanjut adalah sistem pengelolaan lahan, tanaman, dan sumber daya alam yang mengintegrasikan aspek ekonomi, ekologi, serta sosial secara seimbang. Sistem ini bertujuan memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang. Prinsip-prinsipnya meliputi menjaga produktivitas lahan, meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan, dan menjamin keadilan serta kesejahteraan bagi seluruh pelaku dalam rantai pertanian, termasuk petani kecil, perempuan, maupun kelompok rentan lainnya.
Salah satu pilar utama pertanian berlanjut ialah perlindungan dan pemanfaatan plasma nutfah. Plasma nutfah adalah sumber daya genetik dari berbagai spesies tumbuhan dan hewan yang menjadi bahan dasar pemuliaan tanaman, perbaikan varietas, serta ketahanan pangan jangka panjang. Keberadaan plasma nutfah sangat menentukan kemampuan adaptasi pertanian terhadap perubahan iklim, hama, dan penyakit.
Di pedesaan, perempuan memegang peran vital dalam menjaga, memelihara, dan mengembangkan plasma nutfah ini, terutama melalui praktik tradisional, seperti menyimpan benih, memilih varietas lokal, dan mempertahankan pola tanam beragam. Dengan demikian, plasma nutfah tidak hanya menjadi penyangga ketahanan pangan, tetapi juga penopang keberlanjutan ekosistem di tengah tekanan modernisasi pertanian. Lalu, seperti apa andil perempuan dalam menjaga pelestarian plasma nutfah? Berikut penjelasannya!
1. Perempuan sebagai penjaga plasma nutfah yang tak tergantikan di komunitas pedesaan

Menyimpan benih merupakan langkah awal yang krusial dalam mewujudkan ketahanan pangan masyarakat. Keberadaan benih lokal membantu petani untuk mengelola pertanian secara mandiri, berbeda dengan benih hibrida yang tidak dapat menghasilkan benih berkualitas untuk penanaman berikutnya. Selain itu, benih hibrida merupakan produk pertanian industri yang terkait erat melalui penggunaan agrokimia dalam skala besar sehingga membuat petani bergantung pada benih yang dijual di pasaran.
Perempuan dalam komunitas pedesaan memegang peran sentral menjaga plasma nutfah, yaitu benih lokal yang diwariskan secara turun-temurun sebagai fondasi ketahanan pangan lokal. Mereka tidak hanya bertanggung jawab memilih benih yang paling tahan dan berkualitas, tetapi juga menyimpan serta memperbanyaknya dengan penuh ketelitian. Sayangnya, kontribusi mereka sering terabaikan akibat dominasi benih komersial dan minimnya perhatian kebijakan. Namun, melalui praktik tersebut, perempuan menjadi pilar penting dalam menjaga keberagaman genetik sekaligus identitas lokal.
Temuan dari Food and Agriculture Organization (FAO) menyatakan bahwa perempuan menyumbang hingga 90 persen benih dan germplasm yang digunakan petani. Hal ini menegaskan betapa besar peran mereka dalam melestarikan keanekaragaman hayati lokal. Peran ini tidak sekadar simbolis, melainkan berdampak nyata pada aspek ekonomi dan lingkungan. Itu karena benih lokal lebih adaptif, murah, dan bisa menjaga identitas pangan setempat. Dengan demikian, perempuan bukan hanya petani, melainkan juga ekolog desa, pemegang kedaulatan benih, dan penjaga kelangsungan ekosistem pertanian lokal.
Sebuah program pelatihan penjala benih yang diinisiasi oleh IDEP Foundation di Sulawesi Tengah menunjukkan betapa besar andil perempuan dalam ketahanan pangan dan pelestarian ekologi desa pascabencana. Mereka dilibatkan dalam berbagi pengalaman, penanaman benih lokal, dan pengorganisasian masa depan benih warisan. Praktik ini memperkuat solidaritas sosial sekaligus memperkaya ketahanan komunitas terhadap ketergantungan benih dari luar dan menjaga sifat adaptif tanaman lokal. IDEP bersama Lingkar Hijau mengadakan pelatihan penyimpanan benih di enam desa di Sulawesi Tengah, yaitu Jono Oge (Kabupaten Sigi), Amal (Kabupaten Donggala), Saloya (Kabupaten Donggala), Taripa (Kabupaten Poso), Sumari (Kabupaten Donggala), dan Kumbasa (Kabupaten Donggala).
2. Ketika sains dan teknologi memperkuat peran perempuan dalam sektor pertanian

Peran perempuan dalam pertanian modern dapat diperkuat melalui integrasi sains dan teknologi. Berkat pelatihan yang memadai dan akses terhadap inovasi pertanian berkelanjutan, perempuan mampu meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan nilai jual hasil tani. Pendekatan ini sejalan dengan misi utama pemerintahan Prabowo Gibran, yaitu Asta Cita Nomor 4, yang menekankan penguatan sumber daya manusia melalui pendidikan, sains, teknologi, dan pemberdayaan peran perempuan.
Penelitian oleh Abdul Wahib Muhaimin, Dwi Retnoningsih, dan Imaniar Ilmi Pariasa (2023) yang berjudul "The role of women in sustainable agriculture practices: evidence from east java Indonesia" mengkaji peran perempuan dalam mengadopsi praktik pertanian berkelanjutan. Temuan utama menunjukkan bahwa partisipasi perempuan secara signifikan meningkatkan adopsi pupuk organik dan biopestisida meski tidak berpengaruh signifikan terhadap adopsi agroforestri. Hal ini menegaskan bahwa perempuan lebih cenderung menyadari pentingnya keberlanjutan dalam pertanian.
Di sisi lain, penelitian juga menemukan bahwa luas lahan pertanian, status kepemilikan lahan, dan partisipasi dalam kelompok tani secara signifikan memengaruhi keputusan petani untuk mengadopsi praktik pertanian berkelanjutan. Melalui pemberian pelatihan, teknologi yang tepat, dan pengakuan atas kontribusi mereka, perempuan bukan lagi sekadar pelaku pendamping. Mereka berpotensi menjadi inovator di komunitas tani, penggerak ekonomi lokal, dan pelopor pertanian masa depan.
3. Harmoni sosial dan kelembagaan untuk pelestarian plasma nutfah

Pelestarian benih lokal memerlukan harmoni sosial dan struktur kelembagaan yang mendukung. Ketika perempuan dapat berpartisipasi secara penuh dalam forum komunitas dan kelembagaan desa, mereka berperan sebagai jembatan sosial sekaligus penjaga benih yang lebih sistematis. Peran tersebut juga mendorong inklusi dan memperluas jangkauan upaya konservasi benih.
Studi oleh Matous (2023) mengkaji peran perempuan dan petani muda kakao di sebuah kabupaten di Pulau Sulawesi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dibandingkan dengan laki-laki yang lebih tua dan dianggap sebagai "pemimpin opini" dalam masyarakat, perempuan dan petani muda mampu meyakinkan hampir dua kali lipat lebih banyak rekan petani untuk mencoba teknik-teknik baru. Matous mencatat bahwa sektor pertanian di Indonesia sangat dipengaruhi oleh aspek gender. Hanya sedikit perempuan yang memegang peran penting dalam kelompok-kelompok lokal.
Kelompok-kelompok tersebut banyak berupa organisasi berbasis komunitas yang bertujuan meningkatkan penghidupan masyarakat setempat. Selain itu, kelompok ini sering menjadi penyalur dukungan dari pemerintah maupun organisasi internasional. Hal ini menegaskan nilai sosial perempuan sebagai agen perubahan. Sebagai contoh, kelompok seperti Pamong Benih Warisan (PBW) membuktikan bahwa perempuan mampu menciptakan jaringan distribusi benih secara digital dan kultural selama masa pandemik sekaligus memperkuat solidaritas serta akses benih di wilayah urban maupaun rural.
Temuan Wulandaru (2021) dalam publikasinya berjudul "Feminist Commoning of Heirloom Seeds in Indonesia" menjelaskan bahwa hubungan anggota PBW dengan benih tercipta melalui kerja reproduktif tak terlihat, seperti menanam benih, memanfaatkan hasil panen, dan membagikan kembali benih tersebut. Benih warisan memberikan kesempatan untuk merasakan kepedulian, memperoleh otonomi, akses ke makanan bergizi, dan menciptakan aktivitas ekonomi alternatif berbasis keanekaragaman hayati serta solidaritas. Pengetahuan ini diperoleh melalui pertukaran cerita, resep, dan praktik bercocok tanam.
4. Menjaga keseimbangan sosial dan lingkungan melalui praktik agribisnis berkelanjutan

Agribisnis berkelanjutan yang adil membutuhkan keseimbangan antara keuntungan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan keadilan sosial. Perempuan harus dilibatkan sebagai mitra sejajar dalam pengambilan keputusan, bukan sekadar sebagai tenaga kerja. Hal ini penting agar agribisnis dapat berjalan secara inklusif, adil, dan berorientasi pada keberlanjutan lingkungan. Di Indonesia, integrasi perempuan dalam pengelolaan sumber daya hutan melalui program social forestry yang menunjukkan bagaimana inklusi gender dapat mendukung konservasi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.
Mengutip Bank Dunia, program social forestry di Indonesia merupakan sistem pengelolaan hutan terpadu yang utamanya dilaksanakan oleh kelompok petani hutan dan komunitas adat. Tujuan utama program ini ialah mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan melindungi hutan dari kerusakan serta alih fungsi lahan. Program ini menyediakan lima model pengelolaan hutan berbasis komunitas, yaitu hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat, kemitraan kehutanan, dan hutan adat, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang pengelolaan social forestry (perhutanan sosial). Melalui program ini, perwakilan komunitas dapat memperoleh izin untuk mengelola hutan dalam jangka waktu tertentu.
Menurut dokumen RECOFTC pada 2012, warga dari tiga komunitas di Kabupaten Bantaeng berhasil memperoleh izin pengelolaan hutan dan hak sewa selama 35 tahun atas hutan setempat. Dengan insentif untuk menjaga sumber penghidupan mereka, warga tersebut memberikan dampak positif terhadap konservasi hutan. Keberhasilan ini kini dijadikan model rujukan untuk proyek-proyek Kementerian Kehutanan pada masa mendatang.
5. Inovasi pertanian sebagai strategi keberdayaan perempuan

Inovasi dalam pertanian menjadi jalan bagi perempuan untuk “bersinar” dan memimpin perubahan. Mulai dari pengembangan benih, metode pengolahan pascapanen, hingga pemasaran digital, perempuan memiliki potensi besar untuk menciptakan model agribisnis yang baru, berkelanjutan, dan inklusif. Memberikan ruang dan dukungan bagi inovasi perempuan berarti membuka pintu bagi keberlanjutan pangan sekaligus keadilan sosial. Ketika perempuan diberdayakan secara inovatif, mereka mampu mengubah pertanian yang konservatif menjadi sebuah gerakan dinamis yang merekah penuh harapan.
Keberhasilan pelestarian plasma nutfah tidak bisa dilepaskan dari peran perempuan sebagai penjaga keanekaragaman hayati. Melalui dukungan sains, teknologi, dan kelembagaan yang kuat, peran ini berpotensi berkembang menjadi kekuatan strategis dalam menghadapi tantangan pangan masa depan. Pemberdayaan perempuan dalam pertanian berkelanjutan bukan hanya merupakan investasi sosial, tetapi juga investasi penting bagi masa depan Bumi. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak, baik pemerintah, akademisi, dan masyarakat, untuk memastikan perempuan mendapatkan akses penuh terhadap sumber daya, teknologi, serta pendidikan. Dengan demikian, perempuan tidak hanya menjadi penjaga plasma nutfah, tetapi juga agen perubahan yang membawa pertanian Indonesia menuju keberlanjutan yang hakiki.