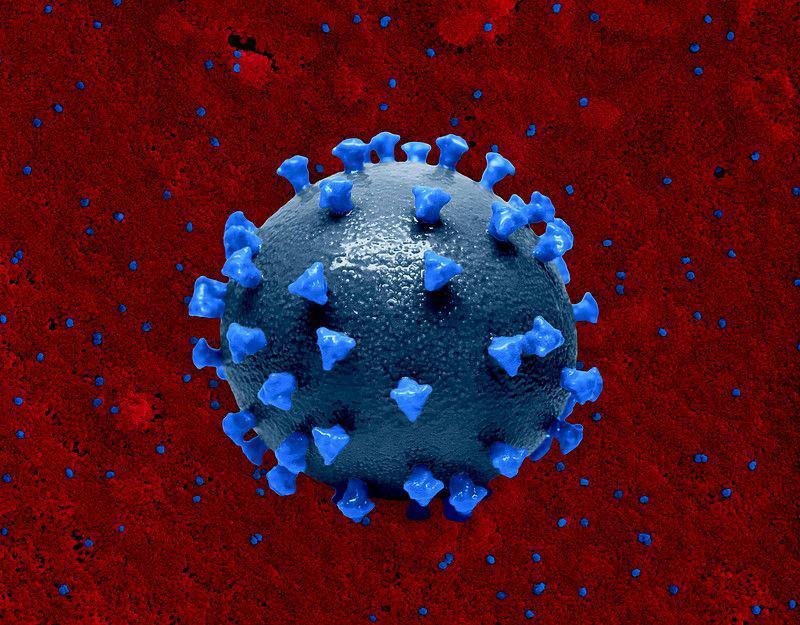"Jadi dinamika pasien gangguan jiwa memang umumnya berbeda. Kalau sakit fisik (pasien) lebih terbuka, misalnya ada luka atau nyeri di tempat tertentu. Kalau berhadapan dengan masalah psikologis sering kali aspeknya banyak," jelas dr. Nicholas saat diwawancarai oleh IDN Times.
Psikiater Kurang Cocok? Ini Tanda Kamu Perlu Second Opinion

Di balik keahlian medis dan reputasi profesional, tetap ada hal-hal yang patut diperhatikan sebelum memutuskan untuk berproses dengan seorang tenaga medis.
Berbeda dengan penyakit fisik yang umumnya lebih mudah dikenali tanda dan gejalanya, pemeriksaan kesehatan mental punya tantangan tersendiri.
Hubungan dokter dan pasien pada dasarnya adalah interaksi antar dua manusia: satu pihak butuh bantuan, sementara pihak lain berusaha menolong. Agar relasi ini efektif, keduanya perlu memiliki kesamaan persepsi mengenai apa yang ingin dicapai.
Mencari bantuan ke psikiater adalah salah satu langkah penting dalam perjalanan seseorang dalam merawat kesehatan mentalnya. Sama seperti saat mencari dokter untuk masalah fisik, pengalaman dengan psikiater pun bisa berbeda-beda bagi setiap orang.
Ada pasien yang merasa sangat terbantu, mendapat arahan yang jelas, dan merasa lebih ringan setelah sesi. Namun, tidak sedikit pula yang justru meninggalkan ruangan dengan rasa bingung atau bahkan kurang nyaman.
Di balik keahlian medis dan reputasi profesional, tetap ada hal-hal yang patut diperhatikan sebelum memutuskan untuk berproses dengan seorang psikiater. Memahami tanda-tanda peringatan alias "red flag" atau hal yang bisa menjadi pertimbangan sejak awal akan membantu kamu sebagai pasien merasa lebih aman dan percaya diri.
Dengan melihat dari sudut pandang pasien sekaligus psikiater, kamu bisa memahami lebih dalam bagaimana hubungan unik ini seharusnya terjalin.
1. Pemeriksaan kesehatan mental lebih tricky dibanding penyakit fisik
Berbeda dengan penyakit fisik yang umumnya lebih mudah dikenali tanda dan gejalanya, pemeriksaan kesehatan mental punya tantangan tersendiri. Menurut dr. Nicholas Hardi, Sp.KJ, spesialis kesehatan jiwa di Rumah Sakit Atma Jaya, dinamika pasien dengan gangguan jiwa biasanya lebih kompleks.
Aspek sosial, pengalaman masa lalu, hingga hal-hal personal yang dianggap tabu atau terlalu intim untuk dibicarakan sering kali ikut memengaruhi kondisi pasien. Situasi inilah yang membuat psikiater dituntut lebih peka dalam memahami pasien yang berada di posisi rentan. Tak heran, pemeriksaan mental bisa menjadi jauh lebih tricky dibanding pemeriksaan fisik biasa.
Di tengah kompleksitas itu, masalah batasan atau boundaries antara dokter dan pasien juga bisa muncul dan memengaruhi jalannya terapi.
"Secara tidak sadar, hubungan terapeutik yang tadi sudah kita bangun itu bisa bergeser secara fluid, secara cair. Bisa bergeser ke sana kemari, bisa menuju ke arah senang, ataupun merasa tidak suka," tambah dr. Nicholas.
2. Beberapa psikiater kerap terburu-buru
Hubungan antara pasien dan psikiater adalah fondasi utama keberhasilan terapi. Tanpa adanya rasa percaya dan komunikasi yang baik, sesi konsultasi bisa terasa kosong, meski dilakukan secara rutin.
Hal itu pernah dialami Dina (28 tahun), seorang pasien dengan gangguan kepribadian ambang atau borderline personality disorder (BPD). Ia mengaku sempat merasa tidak cocok dengan psikiater pertamanya.
"Pada tiga bulan pertama saya berobat saya memutuskan untuk ganti psikiater karena saya merasa konsultasinya tidak efektif. Saya merasa selama konsultasi dengannya, tidak ada observasi yang cukup mendalam sehingga setelah selesai sesi, saya masih questioning tentang perasaan dan gejala yang saya alami," ungkapnya kepada IDN Times.
Menurut Dina, psikiater pertamanya itu sering tampak terburu-buru. Pertanyaan yang diajukan pun cenderung sama pada setiap sesi, tanpa ada evaluasi lebih mendalam.
Meski ia memahami bahwa psikiater itu menangani banyak pasien, tetapi Dina akhirnya memutuskan untuk mencari opini kedua. Keputusan tersebut terbukti tepat. Bersama psikiater yang baru, ia merasa lebih diperhatikan dan benar-benar didengarkan, hingga kondisinya berangsur membaik.
"Saat ini saya telah ditangani oleh psikiater yang tepat dan merasa jauh lebih baik. Tak hanya memberi obat, psikiater saya juga memberi ruang bercerita yang banyak dan aman," ia menambahkan.
3. Pendekatan harus disesuaikan dengan kebutuhan pasien

Dalam terapi kesehatan mental, komunikasi yang baik adalah kunci utama agar tujuan pengobatan tercapai. Psikiater yang terburu-buru, seperti yang dialami Dina, justru bisa berisiko bagi pasien.
Menurut dr. Nicholas, hubungan dokter dan pasien pada dasarnya adalah interaksi antar dua manusia: satu pihak membutuhkan bantuan, sementara pihak lain berusaha menolong. Agar relasi ini efektif, keduanya perlu memiliki kesamaan persepsi mengenai apa yang ingin dicapai.
Dalam konteks psikiatri, hal ini berarti psikiater harus mampu menangkap tujuan spesifik yang dibutuhkan pasien.
"Contohnya kalau dia (pasien) merasa sedih, dia sulit untuk mengontrol emosi sedihnya, atau sulit mengontrol perasaan cemasnya, berarti targetnya adalah mengurangi cemasnya atau mengatasi kesedihannya," jelas dr. Nicholas.
Dari titik itu, psikiater akan menyesuaikan pendekatan dengan melihat latar belakang biopsikososial pasien, mulai dari faktor biologis, kondisi psikologis, hingga pengaruh lingkungan sosialnya.
Dengan dasar komunikasi yang terbuka dan saling memahami, barulah psikiater dapat menentukan langkah yang tepat, apakah melalui pemberian obat, psikoterapi, atau konseling.
4. Pentingnya diagnosis akurat
Dari sisi pasien, proses diagnosis dalam psikiatri seharusnya tidak dilakukan secara terburu-buru.
Iklas (26 tahun) sudah tujuh tahun terakhir rutin berobat ke psikiater karena sering dilanda rasa gelisah. Dalam perjalanannya, ia mendapati bagaimana setiap dokter bisa memberi diagnosis berbeda, mulai dari ADHD, bipolar psikosis, hingga sekadar gangguan kecemasan biasa.
"Beberapa dokter banyak yang tergesa-gesa dalam memberikan diagnosis, padahal belum tentu itu diagnosisnya, jadi banyak yang langsung meresepkan obat," Iklas bercerita kepada IDN Times.
Ia menuturkan, obat yang diresepkan pun tidak selalu tepat. Bukannya merasa lebih baik, efek samping yang muncul justru membuat aktivitas sehari-hari terganggu. Salah satu pengalaman terberat adalah ketika ia didiagnosis bipolar psikosis dan diberi obat antipsikotik golongan atipikal 400 mg. Obat itu membuatnya tidur lebih dari 12 jam, hingga sulit bekerja.
"Saya pribadi itu mau ganti psikiater karena obat yang diberikan itu alih-alih membuat saya menjadi lebih baik, malah membuat saya menjadi malas," kenangnya.
Kisah Iklas menjadi pengingat bahwa observasi mendalam sangat penting sebelum diagnosis ditegakkan dan terapi diberikan. Bagi pasien, ketika psikiater terlalu cepat menarik kesimpulan dan langsung meresepkan obat tanpa evaluasi menyeluruh, ini bisa menjadi tanda peringatan. Dalam kondisi seperti ini, tidak ada salahnya jika pasien mencari opini kedua atau mempertimbangkan psikiater lain jika merasa tidak nyaman.
5. Pasien harus menyampaikan keluhan secara terbuka
Tidak semua metode yang disarankan oleh psikiater akan langsung terasa cocok bagi pasien. Menurut dr. Nicholas, ini wajar karena setiap individu memiliki preferensi dan respons yang berbeda terhadap terapi.
Ada pasien yang lebih nyaman dengan psikoterapi dibanding obat, ada pula yang membutuhkan kombinasi keduanya. Dalam situasi ini, kuncinya adalah berdiskusi secara terbuka dengan psikiater.
"Kalau memang ada disarankan intervensi tertentu, terus kok kayaknya nggak cocok, mungkin kita perlu mencoba diskusi, kira-kira apa sih yang membuat dia berpikir ini kurang pas, dan bagaimana reaksi dari dokternya," jelas dr. Nicholas.
Melalui diskusi, pasien dapat memahami alasan di balik rekomendasi dokter, termasuk apakah metode tersebut terbukti membantu pasien lain dengan kondisi serupa. Namun, jika setelah berdiskusi pasien tetap merasa tidak cocok, atau psikiater mengakui kasus tersebut berada di luar keahliannya, mencari opini kedua adalah pilihan yang sah.
"Didiskusikan pertimbangannya apa dokter itu memberikan suatu saran, atau misalnya pasien punya pertimbangan tertentu. Sehingga kalau misalnya ada yang nggak cocok di antara kedua belah pihak, ya mungkin kita bisa cari opini lain yang mungkin cocok sama kita," tambahnya.
6. Kapan harus mempertimbangkan untuk ganti psikiater?

Mencari psikiater yang tepat bukan hanya soal keahlian medis, tetapi juga tentang bagaimana hubungan terapeutik atau therapeutic alliance terbentuk.
Menurut dr. Nicholas, hubungan ini idealnya ditopang oleh prinsip active listening, empati, serta menjaga kerahasiaan pasien. Jika hal-hal dasar ini berjalan baik, pasien akan merasa aman untuk terbuka dan percaya pada proses terapi.
Lalu bagaimana jika psikiater justru terlihat tidak mendengarkan? Dr. Nicholas menekankan pentingnya melihat pola. Jika hanya terjadi sekali, masih bisa dimaklumi dan layak didiskusikan. Namun, bila sikap tersebut berulang hingga membuat pasien merasa diabaikan, itu bisa menjadi sinyal serius untuk mencari psikiater lain.
"Apa yang membuat dokternya tidak mendengarkan? Atau dokternya kok kayaknya bosan? Nah, itu juga akan menjadi kunci," ujarnya.
Dengan kata lain, red flag yang perlu diwaspadai adalah ketika psikiater gagal mendengarkan secara aktif, tidak menunjukkan empati, dan membuat pasien kehilangan rasa percaya.
Pada titik itu, mengganti psikiater bisa menjadi langkah terbaik agar perjalanan terapi tetap sehat dan produktif. Sebab, memilih psikiater yang pas itu kadang tidak mudah, mungkin sederhananya seperti mencari sepatu yang pas yang tidak selalu cocok pada percobaan pertama. Namun, ini merupakan bagian penting dari perjalanan panjang dalam mengelola dan menjaga kesehatan mental.
Mengenali red flag sejak awal akan membantu kamu sebagai pasien terhindar dari pengalaman yang merugikan. Pada akhirnya, hubungan antara dokter dan pasien harus dilandasi kepercayaan. Jika kepercayaan hilang, pasien berhak mencari dokter lain demi mendapatkan pengobatan yang optimal.




























![[QUIZ] Mau Tahu Jenis Kronotipe Tidur Kamu? Jawab 12 Pertanyaan Ini](https://image.idntimes.com/post/20260126/1000054766_c0f5ed84-85ef-4693-a992-5103340228d4.jpg)





![[QUIZ] Seberapa Jeli Matamu Menebak Takjil Buka Puasa Ini?](https://image.idntimes.com/post/20250314/small-es-timun-serut-a-typical-indonesian-drink-made-from-shaved-cucumber-with-syrup-lime-and-basil-seeds-popular-during-ramadan-7361933a8320c4c5b17b61fdb8f980c5-c47af2949aa151d1fdeff389cb4e87ae.JPG)


![[QUIZ] Seberapa Jeli Matamu Menebak Menu Buka Puasa Ini?](https://image.idntimes.com/post/20240317/22-ed4afaeeaece5897553acd75abadb7a7.jpg)



![[QUIZ] Bisakah Kamu Mengenali Tanda Depresi pada Orang Terdekat?](https://image.idntimes.com/post/20260207/pexels-liza-summer-6383164-1_1d664b73-962c-456c-b634-3a2c9b7c92de.jpg)