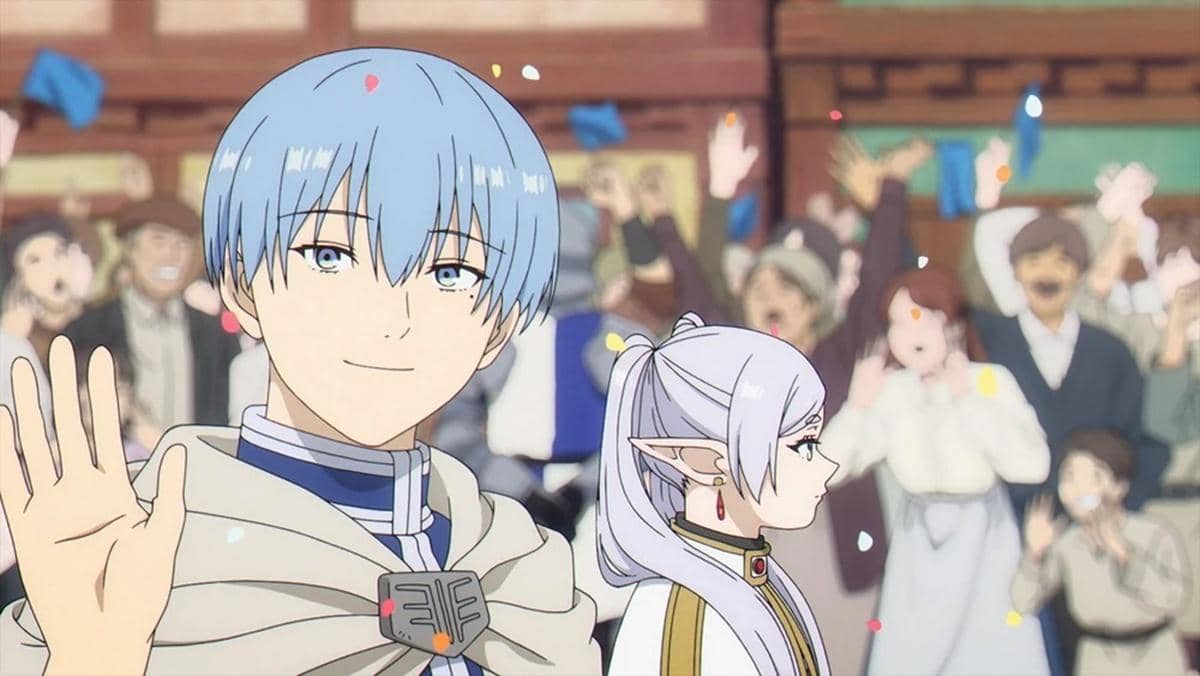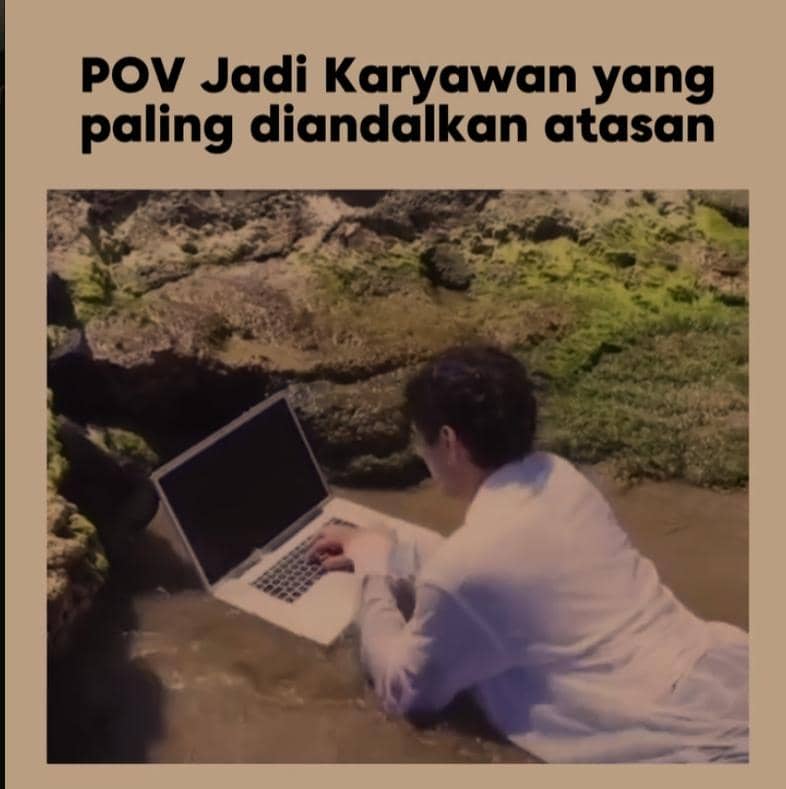Kenapa Istilah Sinefil Kini Berkonotasi Negatif?

- Sinefil sering terlibat dalam kultur performatif di media sosial, seperti Instagram dan TikTok.
- Orang sering lupa bahwa selera dalam film adalah subjektif dan merendahkan karya sinematik populer.
- Kesenjangan akses terhadap film menyebabkan perbedaan wawasan perfilman orang berdasarkan status ekonomi.
Sinefil adalah sebuah istilah serapan bahasa Inggris yang diciptakan untuk menjuluki para pencinta film. Dalam bahasa Inggris, para penikmat film ini kerap pula disebut movie buff yang artinya sama, yakni seseorang yang punya ketertarikan lebih terhadap sinema atau film. Istilah ini awalnya gak problematik, tetapi seiring berjalannya waktu, ia jadi semacam subkultur baru.
Media sosial sampai platform streaming adalah beberapa katalisnya. Kini akses terhadap beragam film dan informasinya seputarnya jadi lebih mudah dan melimpah. Konsumsi film pun meningkat dan makin banyak orang yang melabeli diri sebagai sinefil. Ironis, seiring kenaikan popularitas istilah sinefil, konotasi negatif terhadapnya pun ikut meningkat. Mengapa? Apa pula yang bikin sinefil sering dicap menyebalkan?
1. Lekat dengan kultur performatif

Salah satu alasan sinefil jadi berkonotasi negatif adalah kedekatannya dengan kultur performatif. Media sosial lagi-lagi jadi salah satu biang keroknya. Selain Instagram, TikTok, penikmat film pasti gak asing dengan Letterboxd. Aplikasi ini bak buku harian untuk para pencinta film, tempat di mana kamu bisa merekam dan menilai film-film yang sudah atau baru ditonton beserta ulasannya (bila berkenan menulis). Tentunya tujuannya awalnya hiburan belaka, seperti Facebook, Instagram, dan X (Twitter) yang dahulu dipakai orang sebagai “buku harian” daring.
Namun, lama kelamaan media sosial berevolusi seiring perkembangan penggunanya dan dorongan kapitalisme. Facebook kini menjelma jadi marketplace, Instagram jadi tempat membangun personal branding, dan X pun kini tak luput dari monetisasi. Mengutip kalimatnya Helene von Bismarck dari The Guardian dalam artikelnya soal evolusi Twitter(X), “tidak ada orang yang imun dari narsisme yang didorong media sosial.” Ini yang terjadi pula pada para pengguna media sosial yang kebetulan punya kesukaan lebih terhadap film.
Media sosial bukan lagi buku harian personal, tetapi sesuatu yang ingin mereka pamerkan, seperti jumlah film yang ditonton dalam sebulan, film eksentrik apa saja yang sudah ditonton, film populer mana yang layak dihujat dan lain sebagainya. Ini membuktikan teorinya Pierre Bourdieu soal selera dalam buku berjudul Distinction: A Social Critique and the Judgement of Taste (1984). Selera sering dipakai untuk mengkategorikan manusia dalam strata sosial tertentu. Dalam konteks film, mungkin tak sedikit yang berpikir kalau makin edgy film yang ditonton, makin tinggi selera dan status sosialnya.
2. Orang sering lupa kalau karya seni itu subjektif

Perkawinan selera dengan status sosial itulah yang kadang bikin orang lupa diri. Padahal, selera adalah sesuatu yang subjektif alias tidak hitam putih. Alhasil, banyak sinefil yang tanpa berpikir panjang merendahkan karya-karya sinematik yang secara luas dapat penerimaan positif. Sentimen terhadap film dan sutradara populer sampai genre tertentu adalah fenomena yang umum terjadi di kalangan sinefil.
Belum lagi praktik memasukkan film-film edgy nan langka ke dalam daftar sinema favorit yang kemudian dilihat orang sebagai kesengajaan. Sengaja atau tidaknya bisa jadi perdebatan, tetapi gara-gara kecenderungan pengaku sinefil merendahkan karya populer, menyebut film underrated dalam percakapan pun bisa jadi sumber konflik. Padahal, film underrated yang disebut tadi bisa saja membuka cakrawala khalayak luas terhadap katalog film baru.
3. Ada kesenjangan akses terhadap film

Hal lain yang mungkin bisa bikin kamu lebih berempati ketika melabeli diri sebagai sinefil adalah kesadaran bahwa kesenjangan akses itu nyata. Tidak semua orang bisa menjangkau film dengan mudah dan legal. Sebagian dari kita mungkin punya surplus pendapatan untuk pergi ke bioskop, berlangganan platform streaming atau VPN untuk mengakses film legal yang hanya tayang di region tertentu.
Sebagian lainnya tak punya akses bioskop yang lengkap dan responsif terhadap tren. Faktanya, banyak yang tidak punya akses itu sama sekali dan harus puas dengan katalog yang relatif terbatas. Mau tak mau, wawasan perfilman orang pun ditentukan oleh status ekonominya. Ini revelasi pahit yang mirisnya tak bisa diingkari.
Ada banyak peluang yang bisa kamu manfaatkan dengan jadi sinefil, baik secara profesional atau personal. Namun, itu harus diimbangi dengan komitmen untuk jadi sinefil yang gak menyebalkan. Ingatkan diri kalau tidak semua orang harus setuju dengan pendapatmu dan gak semua orang pula punya akses film yang sama denganmu.