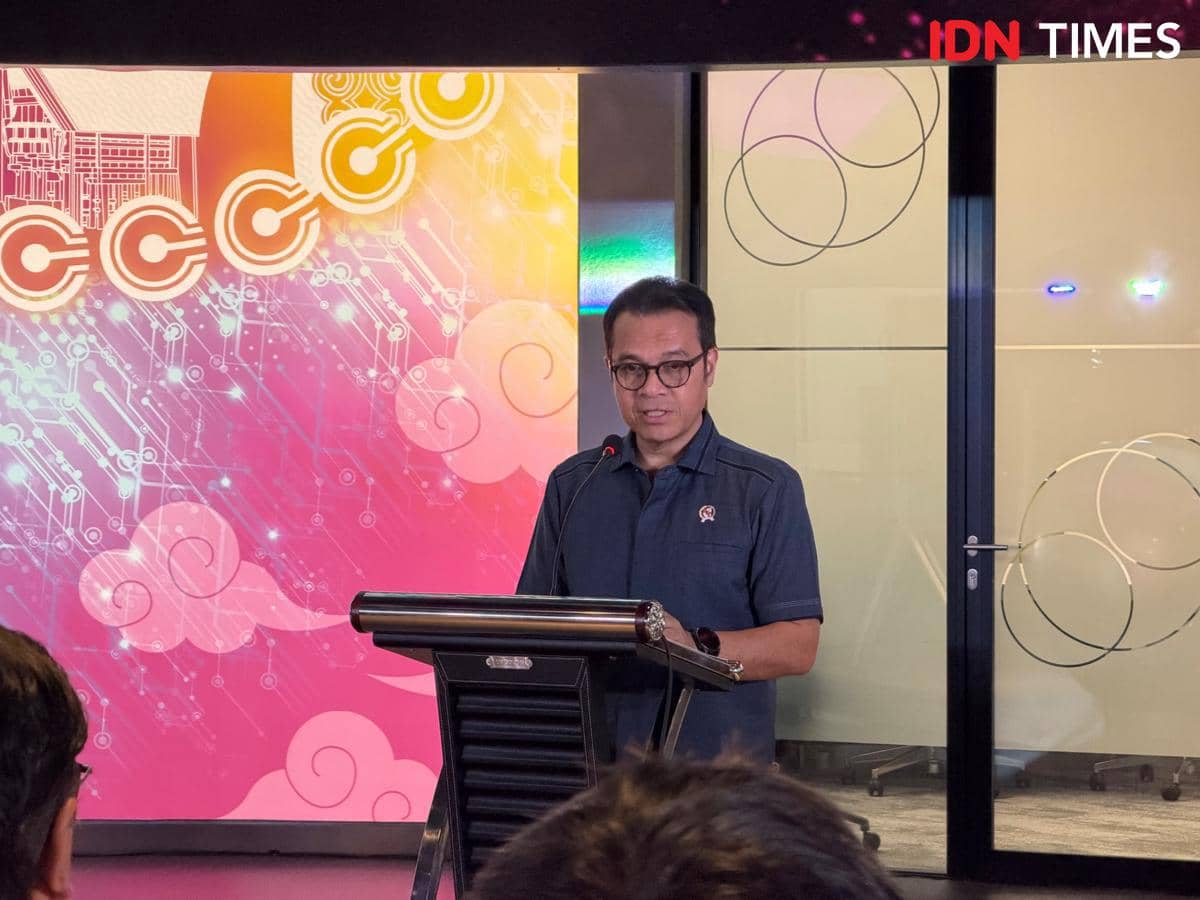Dilema Ghiblifikasi, Estetika Viral atau Perampasan Kreativitas?

- Fenomena Ghiblifikasi menyebar di dunia maya, menggunakan AI untuk mengubah foto menjadi ilustrasi ala Studio Ghibli yang viral di berbagai platform.
- CEO OpenAI meminta warganet untuk menahan diri karena lonjakan permintaan fitur "Ghiblifying" membuat tim kewalahan dan membatasi penggunaan fitur pembuatan gambar.
- Kekosongan hukum di Jepang tentang hak cipta membuka celah eksploitasi kreatif tanpa izin, menimbulkan dilema besar mengenai keadilan dalam penghargaan dan kompensasi terhadap seni.
Sepanjang minggu ini, dunia internet dibanjiri oleh foto-foto hasil rekayasa AI dengan gaya animasi tertentu. Salah satu yang paling ramai dibicarakan adalah replikasi gaya 'Studio Ghibli". Gaya ini menangkap ciri khas artistik dari karya sineas legendaris Hayao Miyazaki. Gaya ini menjadi viral setelah CEO OpenAI, Sam Altman, memperkenalkan kemampuan GPT-4o untuk mengubah foto apa pun menjadi berbagai gaya visual.
Namun, entah bagaimana, tren "Ghiblifikasi" (sebutan proses mengubah foto biasa menjadi ilustrasi ala Studio Ghibli) meledak luar biasa. Banyak orang termasuk tokoh politik dunia menggunakannya dengan cara yang tidak sepantasnya. Implementasi ghiblifikasi ini seringkali mengaburkan batas antara kreativitas yang menyenangkan dan eksploitasi karya tanpa izin. Hayao Miyazaki sendiri merasa jijik akan fenomena ini. Ia membenci kenyataan bahwa karya kerasnya selama bertahun-tahun telah direduksi menjadi sesuatu yang menurutnya hanya sebatas filter Snapchat yang membosankan.
Miyazaki selalu mengekspresikan ketidaksukaannya terhadap AI. Baginya, seni sejati berakar pada rasa empati, kemanusiaan, dan semangat yang memprioritaskan kehidupan, rasa ingin tahu, serta perjuangan kaum tertindas. Lantas, apakah fenomena Ghiblifikasi ini hanya sekadar tren estetika viral atau sudah mengarah ke bentuk perampasan kreativitas? Simak sudut pandangnya berikut ini!
1. Sam Altman secara terbuka meminta warganet untuk menahan diri
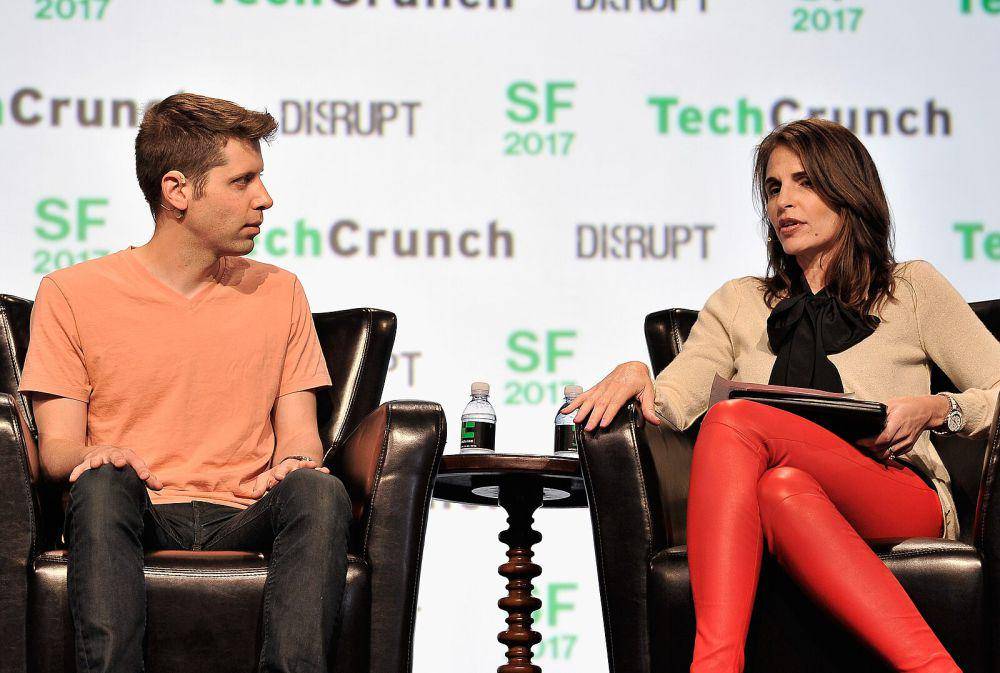
Dikutip dari NDTV, fitur baru ChatGPT yang dapat menghasilkan gambar bergaya Studio Ghibli kini tengah menjadi tren viral di dunia maya. Namun, lonjakan permintaan yang tinggi justru membuat tim OpenAI kewalahan. CEO OpenAI, Sam Altman, bahkan secara terbuka meminta warganet untuk menahan diri. Tak heran jika estetika Ghibli kini dapat ditemui di berbagai platform. Mulai dari stories Instagram, foto profil, hingga meme.
“Bisakah kalian sedikit bersabar pakai fitur gambar ini? Tolong jangan ghibli terus. Ini benar-benar gila, tim kami butuh tidur,” tulis Altman di platform X, 30 Maret 2025.
Permintaan tersebut disampaikan setelah penggunaan fitur "Ghiblifying" melonjak tajam, yang memungkinkan pengguna membuat ilustrasi bergaya anime seperti dalam Spirited Away hanya mengetikkan prompt. Saat ada yang menyindir, "Jika terus dibatasi (nerf), nanti orang akan berhenti menggunakannya,". Kemudian, Altman lantas menjawab.
“Kami justru akan melakukan kebalikannya dari nerf. Tapi ya... tetap tolong bersabar.” tulis Sam Altman di X, 30 Maret 2025.
Seorang pengguna lain mencuit bernada sarkastik dan menyarankan agar Altman “memecat timnya dan merekrut tim baru.” Altman kemudian membela mereka:
“Tidak, terima kasih. Selain sedang membangun AGI, tim ini hampir berhasil menciptakan situs terbesar di dunia hanya dalam waktu 2,33 tahun. Ini tim terbaik di dunia, meskipun memang cukup berat,” jawab Sam Altman di X pada 30 Maret 2025.
Untuk mengatasi lonjakan permintaan, OpenAI kini membatasi pembuatan gambar. Pengguna berbayar tetap bisa mengaksesnya, sementara pengguna gratis kini hanya dapat menghasilkan tiga gambar per hari. Ketika ditanya mengenai timeline AGI, Altman menjawab, "AGI akan datang lebih cepat jika kalian berhenti menggunakan GPU kami untuk membuat gambar," tulis Sam Altman di X pada 30 Maret 2025.
OpenAI membatasi sementara penggunaan fitur pembuatan gambar karena "GPU perusahaan meleleh", yang berarti bahwa beban pemrosesan data untuk menghasilkan gambar sangat berat sehingga menyebabkan sistem bekerja terlalu keras. Tim OpenAI sedang berupaya meningkatkan efisiensi alat tersebut agar pembatasan tidak berlangsung lama. Meskipun banyak pengguna yang antusias, peluncuran fitur ini menghadapi beberapa tantangan, termasuk penundaan akses bagi pengguna gratis dan adanya bug (kesalahan teknis) yang mengganggu proses pembuatan gambar.
Perusahaan menyebut GPT-4o sebagai "generator gambar paling canggih," yang mengusung peningkatan akurasi dan realisme. GPT-4o membuat gambar langkah demi langkah. Ini berbeda dari DALL-E yang langsung menghasilkan gambar. Sebelum pengumuman pembatasan, Altman bercanda tentang pengembangan kecerdasan supernya hanya untuk terbangun dengan ratusan pesan yang menunjukkan gambar dirinya dalam gaya Ghibli. Meski demikian, Altman tetap ikut merayakan tren tersebut dengan mengganti foto profilnya menjadi potret dirinya dalam gaya Ghibli.
2. Ghiblifikasi jelas mencederai jiwa seniman atau para pekerja kreatif di dunia digital

Fenomena Ghiblifikasi (proses mengubah foto selfie menjadi potret bergaya anime yang terinspirasi oleh estetika Studio Ghibli) telah menjadi sensasi di dunia maya. Berbekal alat AI terbaru dari OpenAI, siapa pun kini dapat menciptakan ilustrasi bergaya Ghibli hanya dalam hitungan detik. Sudah lengkap dipadukan latar belakang cat air lembut, mata ekspresif, dan nuansa magis yang mengingatkan pada film-film legendaris seperti Spirited Away dan My Neighbor Totoro. Keberhasilan viral fitur ini menegaskan betapa kuat daya tarik visual Studio Ghibli, tidak hanya bagi penggemar anime, tetapi juga mereka yang baru mengenalnya.
Namun, di balik euforia digital ini, terselip ironi pahit yang tak bisa diabaikan. Fenomena yang merambah hampir setiap sudut internet ini bukan hanya mereduksi seni, tetapi juga mencederai jiwa para seniman dan pekerja kreatif, terutama di dunia digital. Alih-alih sebagai bentuk apresiasi seni, fenomena ini justru menggerus nilai artistik dan kerja keras para seniman. Apa yang seharusnya menjadi bentuk apresiasi terhadap keindahan seni justru berubah menjadi eksploitasi instan berbasis algoritma.
Yang membuat fenomena ini semakin mengganggu bukan sekadar keberadaannya. Tetapi, fakta bahwa ini terjadi pada karya seorang seniman yang sangat dihormati di dunia seni yaitu Hayao Miyazaki. Maestro animasi ini dikenal akan animasi buatan tangan dan pendekatan artistiknya yang sangat manusiawi. Miyazaki bahkan pernah secara terbuka menentang kecerdasan buatan. Miyazaki mengungkapkan rasa ketidaksukaannya dan menyebutnya sebagai “insult to life itself”. Baginya, seni bukan sekadar hasil mekanik, melainkan ekspresi kompleks yang merayakan kekayaan pengalaman manusia dengan segala ketidaksempurnaan, kekacauan, dan keindahannya.
Ironisnya, karya seorang seniman yang menolak dominasi teknologi kini justru direduksi menjadi sekadar data dalam algoritma. Seni yang penuh keunikan dan emosi kini hanya menjadi bahan mentah yang dapat diproses mesin dalam hitungan detik. Ghiblifikasi bukan hanya mencerminkan ketidakpedulian terhadap kerja keras artistik, tetapi juga merendahkan makna asli dari sebuah karya seni.
Bagi pekerja kreatif digital, fenomena ini menandakan ancaman besar terhadap nilai keaslian dan penghargaan terhadap proses kreatif. Di era serbacepat, di mana segala sesuatu dapat dihasilkan dalam sekejap, keterlibatan emosional dan nilai seni yang autentik kian terpinggirkan. Mesin mungkin bisa menciptakan gambar begitu cepat, tetapi mereka tidak dapat menggantikan sentuhan manusia yang penuh perasaan.
Ghiblifikasi bukan sekadar tren atau eksperimen estetika. Ia adalah pengingat bahwa kita harus berhati-hati dalam merayakan teknologi yang kita ciptakan. Jika seni terus direduksi menjadi sekadar output algoritma, kita mungkin akan kehilangan esensi dari apa yang membuatnya berharga. Hubungan manusiawi yang mendalam sejatinya merupakan sesuatu yang tak bisa digantikan dan tergantikan oleh kecerdasan buatan.
3. Telaah undang-undang di negara asal Studio Ghibli terkait ghiblifikasi dan dilema tersandungnya hak cipta

Fenomena ghiblifikasi tentunya sarat akan kontroversi terkait hak cipta. Apalagi dalam konteks produk hukum di Jepang, negara asal Studio Ghibli. Meski OpenAI sebagai pengembang teknologi AI tidak sepenuhnya lepas dari tanggung jawab, masalah utamanya justru terletak pada kebijakan hak cipta di Jepang yang secara mengejutkan kurang sepenuhnya melindungi para pencipta atau kreator.
Pada Mei 2023, Badan Urusan Kebudayaan Jepang mengeluarkan penafsiran baru atas undang-undang hak cipta yang mengizinkan penggunaan karya berhak cipta tanpa izin untuk tujuan pelatihan AI. Berdasarkan interpretasi ini, AI dapat "melatih" dirinya menggunakan materi berhak cipta selama tujuannya bukan untuk "keuntungan langsung" (non-enjoyment). Artinya, AI boleh menggunakan karya seni yang dilindungi hak cipta untuk melatih dirinya, asalkan tidak meniru ide, perasaan, karakter, atau adegan spesifik dari karya tersebut.
Kekosongan hukum ini memunculkan celah hukum yang membingungkan. Selama AI tidak menggunakan karya tersebut untuk keuntungan komersial atau tujuan langsung yang menguntungkan, maka tidak ada yang salah jika seluruh karya seorang seniman dimanfaatkan tanpa izin atau kompensasi. Pasal 30-4 dalam Undang-Undang Hak Cipta Jepang memberikan pengecualian untuk "tujuan non-enjoyment," yang pada gilirannya membuka peluang untuk memanfaatkan karya-karya kreatif secara bebas. Ini termasuk juga untuk tujuan seperti "ghiblifikasi" (pengubahan atau replikasi karya seni dalam gaya) khususnya pada foto pribadi tanpa melanggar hak cipta.
Pengecualian ini memungkinkan siapa saja mengubah foto mereka menjadi ilustrasi bergaya Ghibli tanpa dianggap melanggar hak cipta Hayao Miyazaki. Selama gambar yang dihasilkan tidak mereproduksi karakter atau adegan dari karya Ghibli yang asli. Misalnya, AI dapat menciptakan ilustrasi seseorang menyerupai gaya Ghibli, asalkan tidak memasukkan elemen langsung dari film seperti Spirited Away atau karakter seperti Totoro.
Namun, kebijakan ini tidak hanya membuka celah eksploitasi kreatif tanpa izin. Lebih jauh, ini mencerminkan disonansi kebijakan Jepang, negara yang telah membangun kekuatan budaya global melalui seni, terutama anime dan manga. Jepang yang selama ini melindungi hak cipta seniman manusia dari salinan langsung justru membiarkan AI mempelajari dan mereplikasi karya mereka. Hal ini menimbulkan dilema besar mengenai keadilan dalam penghargaan dan kompensasi terhadap seni.
Undang-undang hak cipta Jepang telah membuka jalan bagi "ghiblifikasi." yang mana mirip seperti karya Studio Ghibli melalui teknologi seperti AI. Meskipun demikian, muncul pertanyaan apakah perkembangan teknologi ini mengabaikan hak cipta para seniman asli yang karyanya digunakan sebagai referensi atau model? Tentunya, perlu ada kebijakan yang bijaksana sehingga dapat melindungi hak cipta seniman tanpa menghambat kemajuan teknologi. Sangat penting untuk menemukan keseimbangan antara menjaga hak cipta dan mendukung inovasi teknologi agar keduanya bisa berkembang secara harmonis.
4. Ancaman eksistensial terhadap inovasi artistik menyusul adanya fenomena ghiblifikasi

Ancaman eksistensial terhadap inovasi artistik semakin nyata di tengah fenomena "ghiblifikasi" yang kian populer. Berkat kemajuan teknologi, terutama dalam kecerdasan buatan (AI), kita menyaksikan bagaimana teknologi dapat mereplikasi gaya seni ikonik, seperti estetika Studio Ghibli yang diproses secara instan. Namun, di balik kemudahan ini, terdapat potensi yang merugikan bagi perkembangan seni dan inovasi kreatif.
Beberapa orang berpendapat bahwa ketika seorang seniman meniru atau mengimitasi karya seniman lain, itu adalah bentuk penghormatan atau penghargaan. Mereka beranggapan bahwa seniman memang selalu dipengaruhi oleh karya yang lebih dulu ada. Tentu, hal ini sudah menjadi bagian dari tradisi panjang dalam dunia seni, di mana setiap seniman belajar dari karya orang lain.
Sayangnya, argumen ini mengabaikan perbedaan mendasar antara pengaruh artistik alami dan replikasi instan oleh AI. Seorang seniman yang mempelajari teknik Miyazaki (seperti dalam karya Studio Ghibli) tidak hanya meniru saja, tetapi menyerap, menginternalisasi, dan mentransformasikan pengaruh tersebut melalui pengalaman pribadi dan visi kreatif mereka. Hasilnya adalah karya yang unik dan baru sebagai representasi evolusi seni. Sebaliknya, AI hanya melakukan replikasi instan yaitu meniru gaya seni yang ada tanpa diselipkan pemahaman atau kreativitas yang mendalam sehingga berujung pada praktik duplikasi.
Sebaliknya, AI tidak mengalami proses kreatif seperti manusia. Teknologi ini hanya memodelkan pola statistik dan mereproduksi gaya dengan variasi. Tidak ada perjalanan artistik, perjuangan, atau eksplorasi visi pribadi. Akibatnya, keberagaman seni terancam karena gaya baru bisa langsung ditiru dan diproduksi massal begitu muncul.
Bagi kamu yang masih baru dalam dunia seni, situasi ini tentu menimbulkan dilema. Mengapa menghabiskan waktu bertahun-tahun mengembangkan gaya unik jika AI bisa menirunya dalam semalam? Mengapa mendorong batasan kreatif jika algoritma dapat segera mengasimilasi setiap inovasi? Jika algoritma bisa langsung meniru setiap inovasi dan terobosan seni, seniman menjadi tidak dihargai sebagaimana mestinya. Karya mereka bisa segera diproduksi massal oleh AI tanpa ada penghargaan terhadap proses kreatif atau perjuangan yang mereka lakukan. Hal ini berisiko menyebabkan demotivasi atau berkurangnya motivasi untuk berinovasi karena seniman takut karya mereka akan segera ditiru oleh teknologi tanpa ada imbalan atau pengakuan.
Fenomena ini mengancam keberlanjutan inovasi artistik yang sejati. Jika teknologi terus menggantikan peran seniman dalam menciptakan dan mengembangkan gaya seni baru, kita berisiko kehilangan proses evolusi artistik yang berakar pada pengalaman manusia dan perjalanan emosional yang mendalam. Inovasi seni akan menjadi hal yang langka, terhenti, atau bahkan terhambat oleh kemampuan AI untuk meniru dengan sangat cepat dan murah. Ini menjadi tantangan besar bagi masa depan dunia seni.
5. Ghiblifikasi mengajak kita untuk merenung lebih dalam tentang arti dari sebuah kreativitas seni
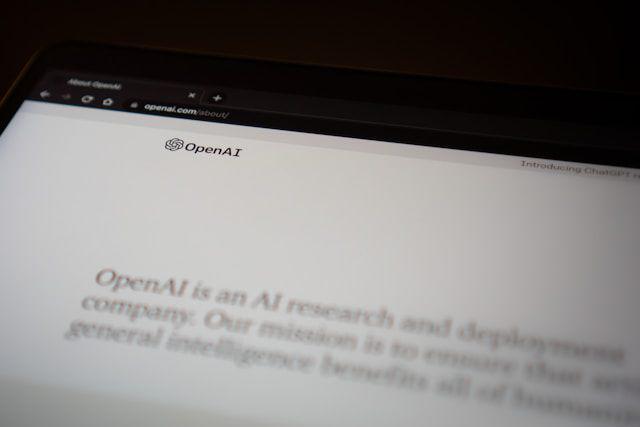
Dilema "Ghiblifikasi" ini memaksa kita merenung lebih dalam tentang makna sejati dari sebuah kreativitas. Di satu sisi, kita dihadapkan pada kecanggihan teknologi yang memudahkan kita menikmati estetika viral melalui cara yang luar biasa. Namun, di sisi lain, kita perlu mempertanyakan apakah kenyamanan ini justru mengorbankan perjalanan panjang seni yang autentik? Ketika karya seni dapat direplikasi secara instan, kita harus bertanya. Apakah kita masih menghargai proses kreatif itu sendiri, atau justru terjebak dalam kecanduan kemudahan yang meniadakan usaha dan orisinalitasnya? Inilah titik temu antara kemajuan teknologi dan keberlanjutan kreativitas manusia yang membutuhkan refleksi mendalam untuk menjaga keseimbangan.
Refleksi ini penting agar masyarakat awam tidak hanya mengagumi hasil tanpa memahami proses di baliknya. Seni bukan sekadar tampilan visual yang indah, melainkan perjalanan penuh eksplorasi, pergulatan ide, dan ekspresi personal yang mendalam. Jika kita hanya terpaku pada produk akhir tanpa menghargai perjalanan kreatifnya, maka tanpa sadar kita turut berkontribusi pada erosi nilai orisinalitas.
Lebih dari itu, fenomena ini menuntut kita untuk lebih kritis terhadap peran teknologi dalam dunia seni. Apakah AI seharusnya menjadi alat bantu bagi seniman atau malah berpotensi menggantikan peran mereka? Bagaimana kita memastikan bahwa inovasi teknologi tidak merusak gairah dan dedikasi dalam berkarya?
Pada akhirnya, dilema ini bukan hanya soal seni, tetapi juga bagaimana sebagai masyarakat mampu mendefinisikan makna kreativitas di era digital. Jika tidak berhati-hati, kita mungkin akan hidup di dunia yang penuh gambar indah, namun tanpa keterlibatan jiwa di dalamnya. Semoga fenomena ini mengajarkan kita untuk lebih menghargai proses kreatif yang sesungguhnya. Kreativitas lahir dari proses panjang, bukan sekadar replikasi instan yang menghilangkan esensi dari sebuah karya seni.