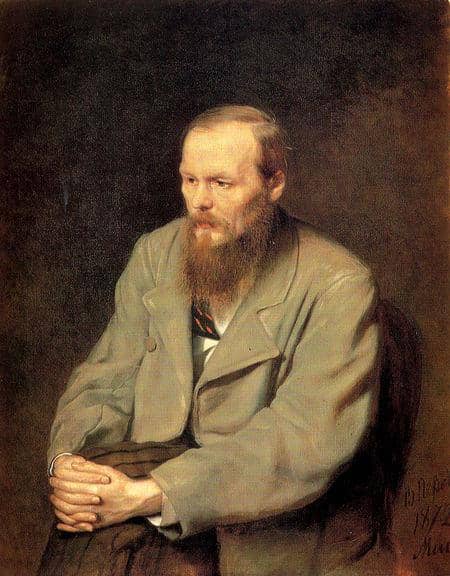5 Kebiasaan Toxic Productivity yang Berkedok Profesionalisme

- Selalu siap 24/7, seolah waktu pribadi gak pentingBekerja tanpa henti mengikis batas sehat antara kehidupan pribadi dan pekerjaan. Profesionalisme bukan berarti harus standby terus menerus.
- Meromantisasi lembur dan kurang tidurLembur dan kurang tidur sering dipandang sebagai bentuk dedikasi, padahal bisa fatal jika jadi kebiasaan. Tidur adalah kebutuhan dasar yang penting.
- Merasa bersalah saat gak sibukRasa bersalah saat istirahat menandakan pola pikir sudah tercemar toxic productivity. Istirahat juga bagian dari produktivitas yang sehat.
Dalam dunia kerja yang serba cepat, profesionalisme sering jadi topeng yang dipakai untuk membenarkan kebiasaan kerja yang ternyata gak sehat. Produktif itu bagus, tapi ketika seseorang mulai mengukur nilai diri dari seberapa sibuk dirinya, ada sinyal bahaya yang layak diperhatikan. Sayangnya, kebiasaan ini sering dianggap normal, bahkan dipuji. Padahal, di balik pujian itu, tersembunyi tekanan yang bisa bikin mental runtuh pelan-pelan.
Toxic productivity adalah kondisi di mana seseorang terdorong terus-menerus untuk menghasilkan sesuatu, bahkan saat tubuh dan pikirannya butuh jeda. Ironisnya, kebiasaan ini justru tumbuh subur di lingkungan kerja yang katanya profesional. Banyak yang terjebak dalam ilusi bahwa kerja keras tanpa henti adalah satu-satunya jalan menuju sukses. Padahal, batas antara dedikasi dan penghancuran diri itu sangat tipis.
1. Selalu siap 24/7, seolah waktu pribadi gak penting

Banyak yang bangga bisa langsung membalas email atau chat kerja jam 11 malam, seakan itu tanda loyalitas dan profesionalisme tinggi. Padahal, sikap selalu tersedia ini justru mengikis batas sehat antara kehidupan pribadi dan pekerjaan. Lama-lama, waktu istirahat jadi korban, dan burnout tinggal hitungan hari. Kerja gak berhenti bukan berarti produktif, kadang justru sebaliknya.
Profesionalisme bukan berarti harus standby terus menerus, apalagi mengorbankan waktu untuk diri sendiri atau keluarga. Kalau tiap detik hidup cuma diisi kerjaan, kapan bisa napas? Tubuh dan pikiran juga butuh ruang untuk rehat biar bisa bekerja lebih optimal. Jadi, gak perlu merasa bersalah kalau sesekali mematikan notifikasi dan memilih untuk benar-benar off.
2. Meromantisasi lembur dan kurang tidur

Lembur sering dipandang sebagai bentuk dedikasi, bahkan jadi bahan pamer, "Tadi malam tidur cuma 3 jam karena ngerjain proyek." Kedengerannya heroik, padahal efeknya bisa fatal kalau jadi kebiasaan. Kurang tidur bikin fokus berantakan, suasana hati labil, dan performa justru menurun drastis. Tapi karena dikemas dalam balutan profesionalisme, banyak yang tetap melakukannya.
Tidur bukan kemewahan, tapi kebutuhan dasar. Melewatkan waktu tidur demi produktivitas adalah investasi buruk yang hasilnya cuma kelelahan dan stres. Kerja keras itu perlu, tapi kalau tubuh gak diajak kompromi, hasil akhirnya gak akan maksimal. Profesional sejati tahu kapan harus push dan kapan harus istirahat.
3. Merasa bersalah saat gak sibuk

Ada rasa bersalah yang muncul saat lagi santai, seolah waktu luang adalah sesuatu yang harus dihindari. Ini bahaya banget, karena bikin seseorang terus menerus mencari kerjaan biar terlihat produktif. Padahal, jeda itu penting buat recharge energi dan menyegarkan pikiran. Gak semua waktu harus diisi dengan hal yang “bermanfaat” secara kasat mata.
Produktif bukan berarti harus terus bergerak tanpa henti. Kadang diam, rebahan, atau melakukan hal yang kelihatannya sepele justru bisa jadi momen reflektif yang berharga. Rasa bersalah karena istirahat adalah tanda bahwa pola pikir sudah tercemar toxic productivity. Waktunya balik ke mindset sehat, istirahat juga bagian dari produktivitas.
4. Multitasking berlebihan demi efisiensi palsu

Multitasking sering dipuji sebagai kemampuan spesial, tapi dalam praktiknya lebih sering bikin hasil kerja jadi setengah-setengah. Fokus terbagi ke banyak hal bikin kualitas kerja menurun, dan otak pun gampang lelah. Tapi karena dianggap efisien dan profesional, banyak yang tetap ngotot menjalankannya. Padahal, hasil akhirnya gak sebanding dengan energi yang dikeluarkan.
Daripada melakukan lima hal sekaligus tanpa selesai dengan baik, lebih baik fokus satu-satu dengan maksimal. Bekerja cerdas lebih penting daripada sekadar terlihat sibuk. Multitasking berlebihan hanya bikin otak terus terjaga dalam mode siaga, tanpa jeda, yang pada akhirnya bikin performa menurun dan stres meningkat. Profesionalisme bukan soal seberapa banyak yang bisa dilakukan, tapi seberapa baik hasilnya.
5. Menolak minta bantuan karena takut dinilai lemah

Ada anggapan bahwa profesional sejati harus bisa mengatasi segalanya sendiri. Minta bantuan kadang dianggap tanda kelemahan, padahal justru sebaliknya, kolaborasi itu bagian penting dari kerja profesional. Menanggung beban sendiri terus-menerus cuma bikin beban mental makin berat. Akibatnya, produktivitas yang katanya tinggi justru jadi jebakan.
Mengakui keterbatasan dan meminta bantuan itu bukan kelemahan, tapi keberanian untuk menjaga diri tetap waras. Gak ada manusia yang bisa menanggung semuanya sendirian, dan kerja tim ada justru untuk saling menopang. Profesional yang sehat tahu kapan harus maju sendiri, dan kapan perlu gandeng tangan orang lain.
Produktif itu bagus, tapi kalau sudah sampai mengorbankan kesehatan fisik dan mental, harus mulai dipertanyakan. Profesionalisme seharusnya mencerminkan keseimbangan, bukan tekanan yang diam-diam mematikan. Mulai sekarang, mari lebih jujur pada diri sendiri dan berani menantang standar kerja yang gak manusiawi.