5 Tekanan dari Tren 'Healing' yang Justru Bikin Gen Z Gak Tenang

Istilah healing kini menjadi bagian dari percakapan sehari-hari, terutama di kalangan Gen Z. Di media sosial, healing sering digambarkan melalui momen santai di kafe, liburan ke tempat tenang, atau rutinitas self-care yang tampak sempurna. Namun, di balik visual yang menenangkan itu, muncul tekanan baru yang justru membuat banyak anak muda merasa semakin tertekan.
Alih-alih merasa pulih, sebagian Gen Z justru merasa tertinggal jika belum bisa healing dengan cara yang terlihat ideal. Harapan untuk selalu merasa damai dan produktif terkadang berubah menjadi beban yang tak terlihat. Berikut lima tekanan dari tren healing yang justru membuat Gen Z tidak tenang.
1. Adanya tekanan untuk selalu tampak bahagia

Di media sosial, healing sering ditampilkan dengan ekspresi bahagia atau menjelajahi tempat-tempat indah. Hal itu membuat banyak Gen Z merasa harus selalu tampak ceria agar dianggap sudah pulih. Padahal, proses pemulihan tidak selalu tampil dalam bentuk senyuman.
Perasaan sedih, bingung, atau lelah justru sering menjadi bagian penting dalam proses healing yang jujur. Ketika emosi negatif ditekan demi bisa tampil bahagia, yang muncul nantinya hanya kepalsuan. Alih-alih merasa sembuh, justru mereka semakin merasa jauh dari diri sendiri.
2. Adanya standar finansial untuk bisa healing

Healing kini kerap diasosiasikan dengan liburan mahal, staycation, atau belanja barang-barang untuk ritual self-care. Hal itu secara tidak langsung menciptakan standar finansial yang tinggi untuk bisa merasa layak beristirahat. Banyak Gen Z akhirnya merasa belum pantas healing kalau belum mengeluarkan biaya besar.
Padahal, istirahat mental bisa dilakukan dengan cara sederhana dan gratis, seperti tidur cukup atau jalan santai. Tekanan untuk membayar mahal demi merasa 'pantas pulih' justru menambah stres. Healing seharusnya bisa memerdekakan, bukan membebani.
3. Adanya tuntutan untuk cepat pulih

Ada harapan tidak tertulis bahwa proses healing harus cepat selesai agar bisa kembali produktif. Hal itu cenderung membuat Gen Z merasa terburu-buru dalam proses yang seharusnya bersifat personal dan tak bisa disamaratakan. Akibatnya, banyak yang merasa bersalah jika masih merasa lelah atau belum sepenuhnya move on.
Pemulihan emosional sejatinya tidak memiliki tenggat waktu yang tetap. Memaksakan diri untuk cepat sembuh justru hanya akan memperlambat proses itu sendiri. Sehingga sudah semestinya healing dinikmati sebagai perjalanan, alih-alih sebuah perlombaan.
4. Adanya kompetisi diam-diam dalam proses healing
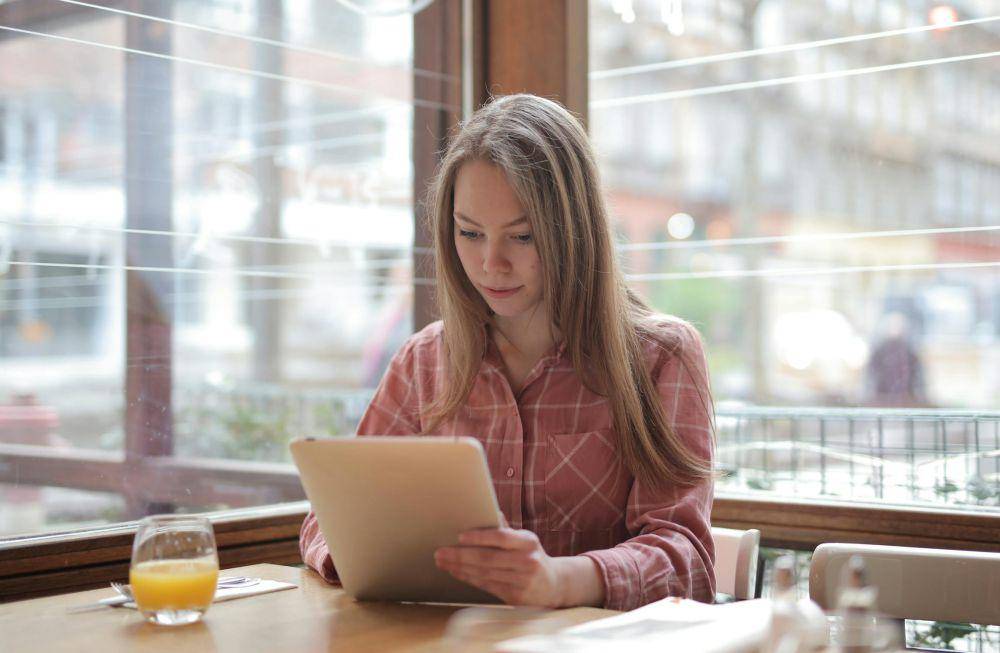
Fenomena healing di media sosial sering berubah menjadi ajang perbandingan. Siapa yang healing-nya paling estetis, paling mahal, atau paling menyentuh, cenderung lebih disorot. Hal itu membuat healing kehilangan makna personalnya dan berubah menjadi kompetisi secara tidak langsung.
Alih-alih menjadi tempat rehat, proses pemulihan justru menjadi ajang validasi. Gen Z bisa merasa gagal hanya karena proses healing-nya terkesan tidak semenarik milik orang lain. Padahal, yang paling penting adalah kenyamanan pribadi, bukan pengakuan dari luar.
5. Adanya harapan untuk selalu produktif setelah healing

Banyak narasi di kalangan Gen Z yang menyebutkan bahwa setelah healing seseorang harus kembali lebih produktif dan semangat. Hal demikian tentu menciptakan beban bahwa hasil dari healing harus bisa dibuktikan. Apabila tidak ada perubahan yang signifikan, maka proses healing dianggap gagal.
Padahal, proses penyembuhan tidak selalu membawa hasil yang langsung terlihat. Terkadang healing hanya membuat seseorang merasa sedikit lebih tenang atau mampu menjalani hari tanpa beban berat. Itu pun sudah merupakan bentuk kemajuan yang layak dihargai.
Fenomena healing seharusnya menjadi ruang untuk istirahat dan pemulihan diri, bukan ajang pembuktian sosial. Alih-alih terpaku pada standar ideal, lebih baik fokus pada apa yang benar-benar membantu secara personal. Gen Z perlu menyadari bahwa setiap orang memiliki cara dan waktu sendiri untuk sembuh.










































![[QUIZ] Pilih Lagu Upin Ipin, Kamu Kuat Berhitung atau Menghafal?](https://image.idntimes.com/post/20251113/img_20251113_075916_b46460b1-96a6-47a4-b147-6151d03d5757.jpg)



