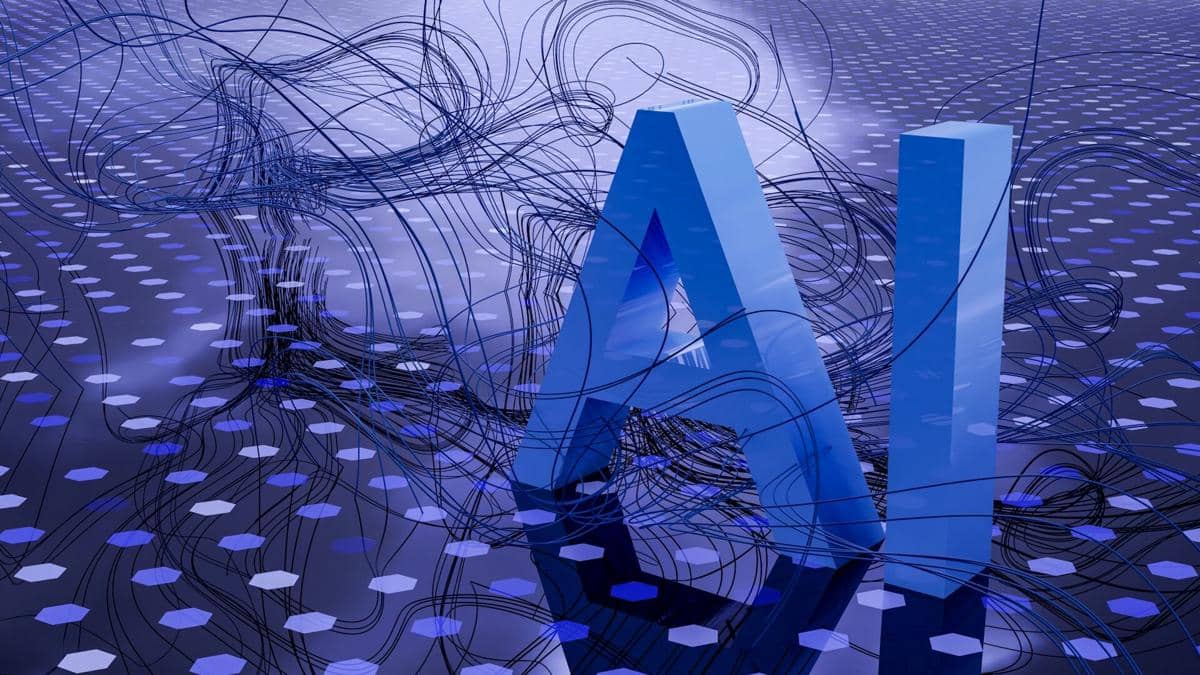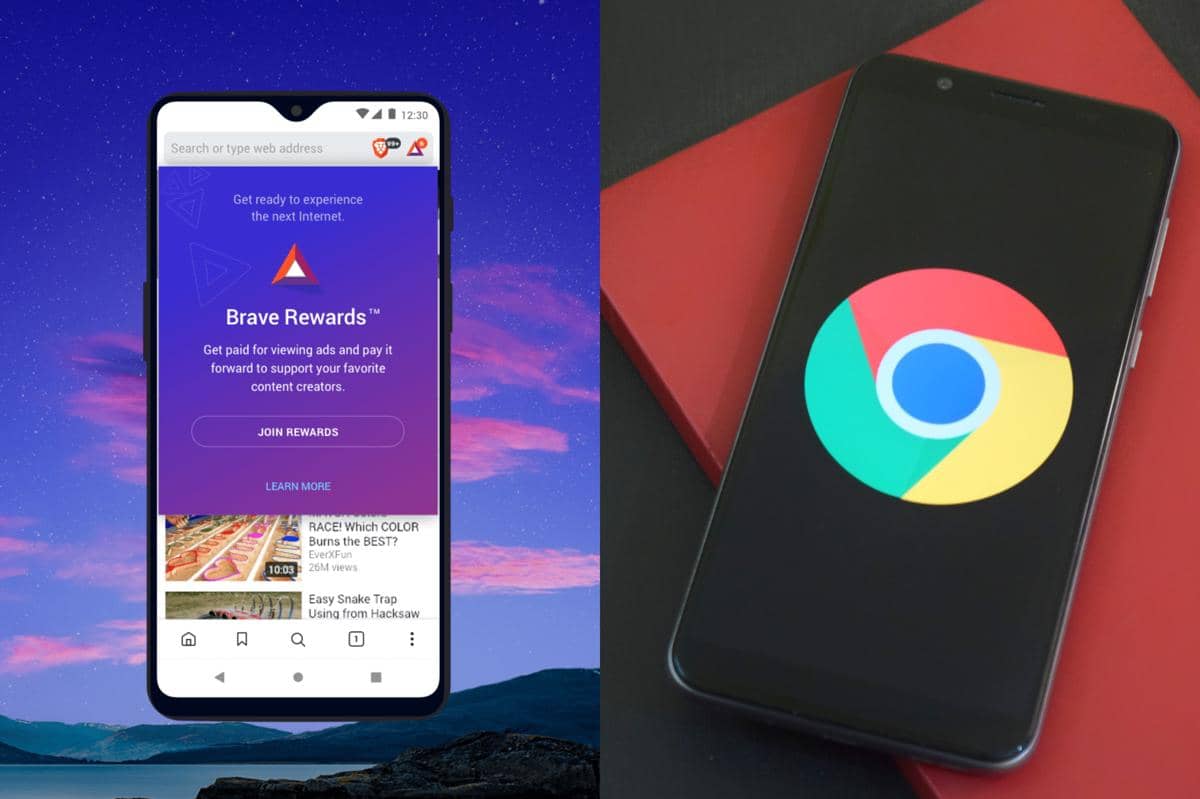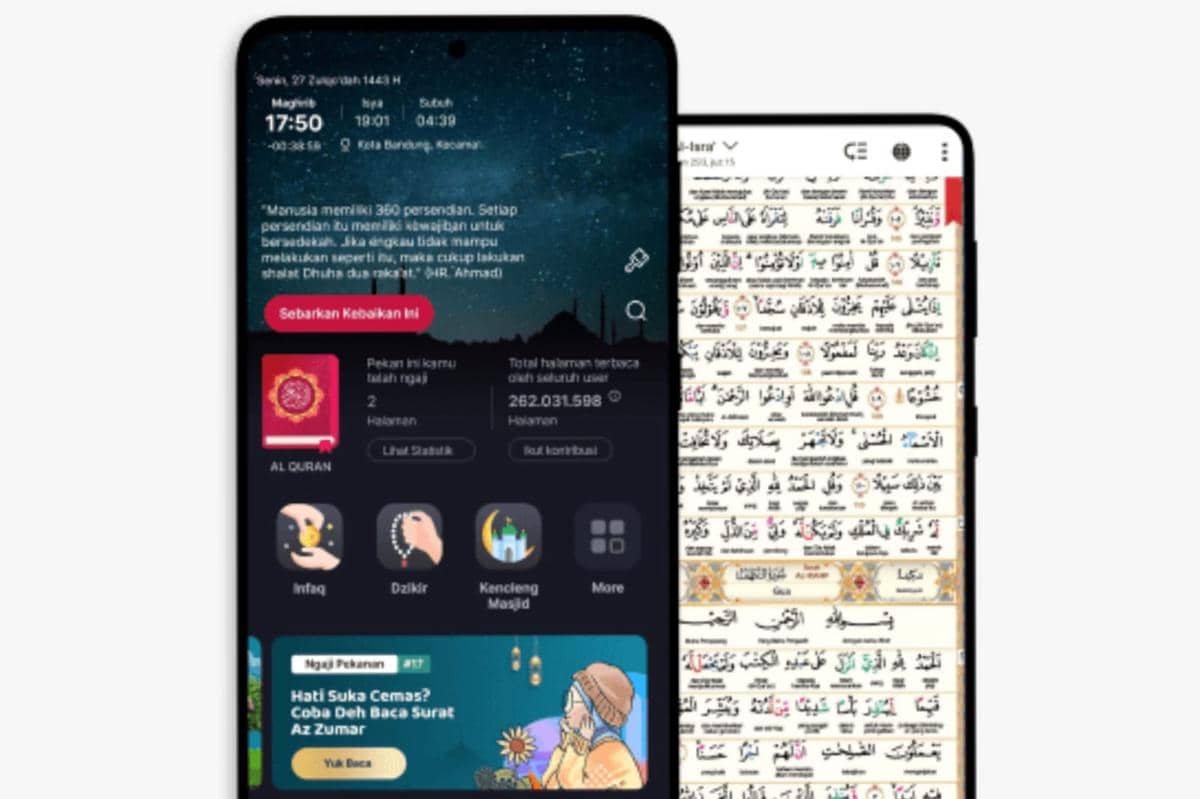Game Bukan Musuh, Justru Bullying yang Membunuh

- Game sebagai kambing hitam: Penelitian menunjukkan game tidak menyebabkan perilaku agresif, namun stigma negatif terhadap game masih kuat.
- Fokus utama pada realitas perundungan: Perilaku bullying di sekolah mengakar dan berdampak serius terhadap kesehatan mental remaja.
- Sekolah yang terlalu sibuk mengajar sampai lupa mendengar: Sistem pendampingan psikologis di sekolah lemah, perlunya memperkuat literasi empati di dunia maya.
Jumat, (7/11/2025) lalu, insiden ledakan terjadi di SMAN 72 Jakarta. Menanggapi peristiwa tersebut, Presiden RI Prabowo Subianto kemudian meminta sekolah untuk mewaspadai pengaruh game online dan perundungan di kalangan siswa. Uniknya, salah satu genre game online yang dinilai memberikan efek atas timbulnya kekerasan adalah PUBG Mobile.
Usai rapat terbatas bersama sejumlah menteri dan pejabat negara di kediaman Presiden, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden memberikan arahan untuk membatasi serta mencari solusi atas dampak negatif dari game online. Selain itu, Presiden juga mendorong penguatan nilai-nilai sosial melalui kegiatan karang taruna dan pramuka agar generasi muda lebih aktif dalam kehidupan bermasyarakat. "Jadi, tadi beliau juga menyampaikan bahwa kita memang perlu menumbuhkan kembali kepedulian sosial, menghidupkan kembali kehidupan bermasyarakat kita, beliau juga tadi membahas bagaimana karang taruna harus aktif kembali, Pramuka harus aktif kembali," ujar Prasetyo di kediaman Prabowo, mengutip IDN Times, Senin (10/11/2025).
Namun, ada persoalan yang jauh lebih mendasar dibandingkan sorotan tentang game online, yaitu perilaku bullying di lingkungan sekolah yang tampak mengakar. Banyak anak tumbuh dalam sistem yang mengagungkan prestasi akademik, tetapi gagal menumbuhkan empati dan kesadaran sosial. Saat tekanan sosial dan ejekan menjadi hal biasa, remaja yang rentan bisa kehilangan arah hingga berujung pada tindakan ekstrem.
Game justru lebih sering menjadi pelarian dari tekanan sosial. Sayangnya, hal ini sering disalahartikan oleh publik sehingga stigma negatif terhadap game makin menguat. Lantas, apakah pantas jika game online menjadi pemicu atas buntut insiden ledakan yang terjadi di SMAN 72 Jakarta ini? Yuk, saling berbagi sudut pandang.
1. Game sebagai kambing hitam

Ketika berita tentang kekerasan remaja mulai mencuat, game online kerap dijadikan kambing hitam yang dianggap memicu perilaku agresif. Narasi ini sudah muncul sejak 1990-an di Amerika Serikat, terutama ketika game seperti Mortal Kombat dan Grand Theft Auto kian populer. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa tuduhan tersebut tidak memiliki dasar ilmiah yang konsisten.
Pada 2015, Task Force on Violent Media dari American Psychological Association (APA) meninjau 31 studi yang dipublikasikan sejak 2009. Laporan itu menyebut adanya keterkaitan antara permainan video kekerasan dan peningkatan perilaku agresif, pikiran agresif, serta penurunan empati dan perilaku prososial. Namun, hubungan tersebut bersifat korelasional sehingga tidak bisa disimpulkan bahwa game menjadi penyebab langsung perilaku kekerasan.
Sebaliknya, sejumlah penelitian justru menemukan hasil berbeda. Salah satunya dilakukan oleh Andrew Przybylski dan Netta Weinstein dari University of Oxford pada 2019 yang melibatkan lebih dari 1.000 remaja di Inggris. Dalam studi tersebut, para pengasuh remaja diminta menilai seberapa sering anak bermain game kekerasan dan seberapa agresif perilaku mereka selama sebulan terakhir. Hasilnya menunjukkan tidak ada korelasi signifikan antara durasi bermain game kekerasan terhadap tingkat agresivitas pemain.
Temuan serupa juga diungkap oleh Juveriya M. Mistry dan Vidyadayini Shetty pada 2020 dalam jurnal International Journal of Creative Research Thoughts (IJCRT). Mereka menyimpulkan tidak terdapat perbedaan signifikan dalam skor agresivitas antara kelompok pemain dan non-pemain game kekerasan. Bertolak belakang dengan anggapan umum, hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa bermain game kekerasan tidak berkorelasi dengan perilaku agresif di kalangan remaja. Jadi, dapat disimpulkan bahwa game hanyalah medium ekspresi, bukan pembentuk perilaku destruktif. Ketika pejabat publik tergesa-gesa menyalahkan game tanpa memahami konteks riset secara global, mereka justru menghidupkan kembali stigma lama yang telah terbantahkan oleh data ilmiah.
2. Fokus utamanya adalah realitas perundungan yang telah lama terjadi di sistem pendidikan

Alih-alih memahami persoalan secara menyeluruh, pemerintah tampak terburu-buru dan hanya melihat bahwa bermain game menyebabkan kecanduan. Padahal, fokus yang sebenarnya perlu disoroti bukan pada genre gamenya, melainkan pada realitas bullying yang selama ini menggerogoti sistem pendidikan Indonesia. Berdasarkan laporan Programme for International Student Assessment (PISA) 2018 yang dikompilasi oleh UNICEF tahun 2020, sekitar 41 persen siswa Indonesia mengaku pernah mengalami perundungan setidaknya beberapa kali dalam sebulan. Bentuknya beragam mulai dari ejekan verbal, kekerasan fisik, hingga pengucilan sosial di lingkungan sekolah.
Yang lebih mengkhawatirkan, angka sebenarnya kemungkinan jauh lebih tinggi karena banyak korban memilih untuk diam. Faktor rasa takut, rasa malu, hingga ketidakpercayaan terhadap sistem sekolah membuat sebagian besar kasus bullying tidak pernah dilaporkan. Akibatnya, data perundungan di Indonesia sulit dipastikan secara akurat. Dalam konteks ini, menyalahkan game online sebagai pemicu kekerasan jelas menyesatkan karena justru ada persoalan psikososial yang jauh lebih serius di baliknya.
Penelitian yang diterbitkan di The Lancet Psychiatry pada 2015 menunjukkan bahwa anak-anak yang menjadi korban bullying memiliki risiko lima kali lebih tinggi mengalami kecemasan dan hampir dua kali lebih besar mengalami depresi atau melakukan tindakan menyakiti diri sendiri pada usia 18 tahun dibandingkan anak yang mengalami kekerasan di rumah. Hasil studi tersebut menegaskan bahwa perundungan di masa sekolah berdampak lebih parah terhadap kesehatan mental remaja dibandingkan perlakuan salah dari orang tua. Banyak korban bullying kemudian kehilangan rasa percaya diri dan menarik diri dari lingkungan sosial.
Dalam banyak kasus, dunia game justru menjadi ruang aman bagi mereka untuk merasa diterima. Dunia digital memungkinkan remaja membangun identitas baru tanpa adanya tekanan sosial yang mereka hadapi di dunia nyata. Karena itu, apabila menyalahkan game berarti menutup mata terhadap fungsi terapeutik dan sosial yang sebenarnya dimiliki ruang digital bagi sebagian anak muda.
3. Sekolah yang terlalu sibuk mengajar sampai lupa mendengar

Setelah memahami akar sosialnya, penting juga melihat bagaimana sistem sekolah berperan dalam memerparah atau justru mencegah kekerasan tersebut. Salah satu akar persoalan dari krisis ini terletak pada lemahnya sistem pendampingan psikologis di sekolah. Berdasarkan Risalah Kebijakan Pusat Studi Kebijakan dan Pendidikan (PSKP) Kemendikbud (sekarang Kemendikdasmen) tahun 2022, disebutkan bahwa tidak semua sekolah di Indonesia memiliki guru bimbingan dan konseling (BK).
Secara nasional, jumlah guru BK hanya sekitar 33.000 orang untuk melayani sekitar 18,8 juta siswa atau setara 1 : 570. Jumlah ini menunjukkan bahwa peran guru BK belum berjalan optimal karena beban tanggung jawab yang terlalu besar. Rasio tersebut bahkan jauh dari standar The American School Counselor Association (ASCA) yang merekomendasikan 1 konselor untuk tiap 250 siswa. Kondisi ini menyebabkan banyak pelajar tidak memiliki ruang aman untuk menyalurkan tekanan emosional maupun masalah pribadi yang mereka alami. Akibatnya, mereka cenderung memendam emosi tanpa pendampingan yang memadai.
Lembaga pendidikan memiliki kewajiban untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan anak selama proses belajar. Karena itu, ketika guru atau pihak sekolah tidak menindaklanjuti kasus perundungan, hal tersebut dapat dianggap sebagai bentuk pengabaian terhadap tanggung jawab hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 54 ayat (1) menegaskan bahwa anak di dalam maupun di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, maupun tindakan pelanggaran lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, atau pihak lain.
Dalam praktiknya, tidak semua siswa menunjukkan perilaku yang positif. Ada pula yang bersikap nakal atau melanggar tata tertib sekolah. Karena itu, guru memiliki peran penting untuk mendidik, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, serta mengevaluasi peserta didik secara menyeluruh. Tugas tersebut juga mencakup kewenangan memberikan penghargaan maupun sanksi secara proporsional agar proses pendidikan tidak hanya mencerdaskan secara intelektual, tetapi juga membentuk karakter dan tanggung jawab moral siswa.
Lebih memprihatinkan lagi, sebagian sekolah masih cenderung menilai perilaku siswa secara dangkal. Anak yang murung sering dianggap malas, sementara ketika siswa menunjukkan gelagat agresif langsung dicap nakal tanpa memahami kondisi psikologis yang mendasarinya. Pola pikir seperti ini kian memperlebar gap emosional antara guru dan siswa sehingga membuat komunikasi di lingkungan sekolah menjadi dingin. Dalam situasi semacam ini, potensi munculnya kekerasan psikologis bisa meningkat karena tidak ada sistem deteksi dini terhadap perubahan perilaku ekstrem. Pada hakikatnya, sekolah seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai tempat mengajar dan menilai prestasi siswa, tetapi juga menjadi ruang yang aman bagi siswa untuk merasa didengar.
4. Pendekatan yang paling efektif adalah memperkuat literasi empati di dunia maya

Jika Presiden benar-benar ingin menekan angka kekerasan di kalangan pelajar, pendekatan yang paling efektif bukanlah membatasi game online itu sendiri. Literasi empati dan dukungan sosial di sekolah juga perlu dibangun. Salah satu model yang bisa dijadikan rujukan adalah program Social Emotional Learning (SEL) yang diterapkan di Finlandia.
Finlandia menempatkan kesejahteraan siswa sebagai bagian dari mandat hukum pendidikan dasar. Dari kerangka itulah, tim Psikologi Pendidikan Universitas Turku mengembangkan program KiVa (Kiusaamista Vastaan) yang berarti “melawan perundungan.” Program ini lahir berkat dukungan penuh dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Finlandia yang dimulai dari uji coba pada 2007–2009, kemudian diluncurkan secara nasional. Kini, KiVa menjadi salah satu program anti-bullying paling sering dievaluasi dan diadaptasi di dunia.
Penelitian dari University of California 2016 terhadap hampir 7.000 siswa kelas 4–6 di sekitar 80 sekolah dasar Finlandia menunjukkan hasil signifikan. Sekitar separuh sekolah yang menerapkan KiVa mencatat penurunan tajam kasus bullying dibanding sekolah tanpa intervensi serupa. Lebih jauh, penelitian ini menemukan bahwa KiVa berhasil mengurangi tingkat depresi pada sekitar 4 persen siswa kelas enam yang paling sering menjadi korban bullying dan meningkatkan rasa percaya diri di kalangan 15 persen siswa lain yang pernah mengalami perundungan beberapa kali per bulan. Analisis lanjutan yang mencakup 53 program anti-bullying di seluruh dunia juga menunjukkan bahwa peluang seorang siswa menjadi korban bullying hampir dua kali lebih tinggi di sekolah tanpa KiVa dibanding sekolah yang mengimplementasikannya.
Menurut Jaana Juvonen, profesor psikologi di UCLA yang telah meneliti bullying selama lebih dari dua dekade, keunggulan KiVa terletak pada pendekatan komuniternya. “Biasanya, anak-anak dengan masalah kesehatan mental ditangani secara individual. Tapi, keindahan program ini adalah efektivitasnya pada tingkat sekolah secara menyeluruh, terutama bagi mereka yang paling membutuhkan dukungan,” ujarnya melalui situs UCLA. Peneliti menemukan bahwa KiVa tidak hanya menekan angka kekerasan di sekolah, tetapi juga memperbaiki persepsi siswa terhadap lingkungan belajar mereka dan meningkatkan kesehatan mental secara umum.
Di Indonesia, pemerintah bisa meniru semangat yang sama dengan memperluas peran psikolog sekolah serta menciptakan kanal pelaporan rahasia bagi korban bullying. Selain itu, pendidikan mengenai “digital empathy” juga penting agar anak-anak belajar berinteraksi secara sehat di dunia maya. Dunia digital tidak perlu dianggap musuh, melainkan ruang baru yang harus dipahami dan dikelola dengan empati. Saat remaja diberi ruang aman untuk berekspresi dan bercerita, mereka akan memiliki mekanisme yang lebih sehat untuk mengelola emosi dan tekanan sosial. Hal ini jauh lebih efektif daripada sekadar membatasi akses bermain game.
Menyalahkan game atas tindakan kekerasan di kalangan pelajar adalah refleksi dari kegagalan melihat akar persoalan yang sebenarnya. Kekerasan tidak lahir dari layar gawai, melainkan dari lingkungan sosial yang membiarkan bullying tumbuh subur. Selama sistem sekolah tidak membangun budaya empati dan pendampingan psikologis yang kuat, tragedi serupa berpotensi akan terus berulang dengan bentuk berbeda.
Jadi, daripada sibuk mencari kambing hitam dari dunia digital, mengapa tidak mulai menyembuhkan luka sosial yang selama ini terabaikan? Banyak anak menemukan ketenangan di dunia game karena dunia nyata terlalu keras bagi mereka. Tugasnya bukan mengambil pelarian itu, tetapi menghadirkan ruang aman di dunia nyata agar mereka tak perlu terus bersembunyi di balik layar. Tanpa intervensi psikososial yang serius, tiap wacana pembatasan game hanya menjadi solusi semu yang "meninabobokan" nurani publik. Mungkin, sudah waktunya berhenti menyalahkan permainan dan mulai bertanya: Apa yang salah dengan cara mendidik dan mencintai anak-anak kita?