Era AI, Mengapa Sentuhan Tangan Manusia Tetap Tak Tergantikan?

Memahami perbedaan AI Generated dan AI Assistant: Content creator menggunakan AI sebagai assistant untuk merangkai kata, mengedit video, dan membuat caption. Skill prompt writing menjadi keterampilan baru yang penting.
Prompt: skill wajib baru pekerja industri kreatif: Industri kreatif membutuhkan prompt writer yang mampu membuat instruksi yang bisa diterjemahkan mesin dengan akurat. Keterampilan ini menjadi pondasi penting bagi pekerja kreatif.
Banjir data latih AI: tumpang tindih hak cipta di zona abu-abu: Model Generative AI dilatih menggunakan data dari internet tanpa izin pemiliknya. Masalah hak cipta pada musik, gambar, teks, dan merek juga muncul dalam penggunaan AI.
Jakarta, IDN Times - “Penghasilanku sudah turun 50 persen... aku masuk final talent tapi klien lebih milih suara AI… aku pasang harga belasan juta, AI cuma 500 ribu.” ucap Jati Andito yang menggantungkan seluruh hidupnya sebagai voice over talent.
Dalam industri komersial, kreativitas kini bukan lagi pertarungan orisinalitas, tetapi efektivitas per detik, per prompt, dan per rupiah.
Hal ini paling terasa di panggung audio dan musik. Jati Andito, voice over talent sekaligus musisi independen, menjadi saksi pergeseran ekonomi kreatif secara langsung yang mengharuskan Jati untuk berdamai dengan kenyataan bahwa suaranya kini bersaing dengan mesin. "Aku nggak kaget, sudah tahu sesuatu yang kita takutkan akan terjadi," katanya.
Jati Andito menambahkan, dalam bermusik menggunakan Generative AI seperti Suno bisa menghasilkan lagu dengan lirik yang sama, tetapi dalam tiga aliran musik yang berbeda dalam waktu kurang dari satu menit. Secara produksi ini adalah sebuah revolusi besar. Namun secara esensi, apakah lagu tersebut memiliki jiwa yang sama dengan lagu yang digarap selama berbulan-bulan di studio rekaman?
Secara teori, AI membuat seni lebih mudah diakses oleh semua orang. Tetapi secara praktik, AI justru melahirkan kompetisi yang tidak adil - antara manusia dengan jiwanya dan mesin dengan algoritmanya.
Angka yang ditawarkan AI per menitnya bahkan lebih murah dari tarif parkir bebas di kota besar.
Perubahan dalam industri kreatif bukan lagi isu masa depan. Ini sudah terjadi sekarang, senyap namun massif. Kini kecerdasan buatan seperti Eleven Labs, Descript, Murf.ai, Suno.ai bukan lagi sekadar alat bantu, tetapi berevolusi menjadi alat pencipta ide dan suara yang dapat bergerak lebih cepat dari ritme kerja manusia itu sendiri.
Efisiensi biaya menjadi alasan utama mengapa agensi dan klien mulai melirik AI. Seperti kasus yang dialami Jati, perbedaan antara belasan juta dan Rp500 ribu adalah angka yang sangat signifikan bagi neraca keuangan perusahaan.
Studi internasional yang dilakukan CISAC (International Confederation of Societies of Authors and Composers) memperkirakan, pekerja musik bisa kehilangan hampir 25 persen pendapatannya dalam empat tahun ke depan, dan sektor audiovisual juga diperkirakan menurun lebih dari 20 persen pendapatan karena perkembangan Generative AI.
Di sisi lain, kehadiran AI generator visual membantu para content creator menghasilkan content yang lebih menarik dan berwarna. Dari gambar, AI mampu menghasilkan footage sinematik yang terlihat sangat realistis, baik dari ekspresi wajah seseorang hingga pencahayaan yang dramatis.
1. Memahami perbedaan AI Generated dan AI Assistant

Memahami perbedaan antara AI Generated dan AI Assistant adalah kunci untuk memposisikan diri di industri kreatif. Content creator Dianti Elma menggunakan AI sebagai assistant. Ia memberikan ide dasar, lalu AI membantu merangkai kata, dan Elma melakukan penyesuaian (adjusting) agar tetap memiliki sentuhan personal.
"Storytelling kita yang membuat konten tetap mempunyai emotional attachment," ujarnya.
Sebaliknya, AI Generated adalah proses di mana manusia hanya memberikan perintah singkat dan membiarkan mesin melakukan seluruh pekerjaan tanpa ada revisi atau koreksi kreatif lebih lanjut.
Elma memulai karier kontennya pada 2018 tanpa membayangkan bahwa tujuh tahun kemudian, AI akan menjadi bagian penting dari proses kreatifnya. Pada 2025, dengan sebuah prompt ia dapat menghasilkan footage sesuai kebutuhan, sesuatu yang dulu memakan waktu dan tenaga. Bagi Elma, kemajuan ini menandai babak baru di mana kreativitas dan teknologi berjalan beriringan.
“Jujur aku sendiri sangat terbantu menggunakan AI, karena bisa mempersingkat waktu 60-70 persen waktu kerja untuk buat satu video sebagai content creator,” ujarnya tanpa ragu.
Google Gemini membantunya menyusun storyline.
ChatGPT merapikan caption dan copywriting.
Cap Cut mempercepat proses editing.
Meski dirinya mengaku menggunakan AI setiap hari, ia hanya membayar dan berlangganan platform AI yang ditawarkan CapCut sebesar Rp 130.000 per bulan.
Menurutnya, dulu dalam membuat satu video membutuhkan waktu 1-2 hari penuh, kini dengan AI dirinya bisa menghemat waktu cukup banyak dan bisa melakukan pekerjaan lain di hari yang bersamaan. Ia juga menyadari, seiring cepatnya produksi video ternyata sejalan dengan meningkatnya tuntutan pekerjaan.
“Kadang klien pengennya lebih banyak footage, jadi biasanya kalo kehabisan ide dan stok video aku minta AI yang buatin, tapi promptnya tetap dari aku,” tuturnya.
Elma mengaku, fitur AI yang diberikan CapCut membuat videonya lebih disukai klien karena selalu lebih variatif, mulai dari angle pengambilan video hingga editannya yang selalu terlihat menarik.
Elma sendiri selain bekerja sebagai content creator, ia juga seorang social media specialist di sebuah perusahaan yang terletak di bilangan Kota Jakarta Barat.
“AI juga bantu aku untuk pantau engagement, terus juga untuk bantu tulis caption postingan di sosmed, sisanya aku masih bisa bikin sendiri dengan kreatifitasku.” ucapnya menceritakan.
Profesi seperti social media specialist dan content creator sering dianggap glamor bagi publik, karena pekerjaan mereka terlihat seperti berfoto, tersenyum, memegang produk, mengedit video, posting, lalu dibayar. Namun pada kenyataannya, profesi ini membutuhkan fokus riset audiens, revisi berkali-kali, ide yang tiba-tiba harus diganti, algoritma yang berubah tanpa peringatan, deadline yang datang beruntun, dan brand yang ingin semuanya ‘serba cepat’.
“AI bikin kita harus adaptif dan kreatif pastinya,” ucapnya.
2. Prompt: skill wajib baru pekerja industri kreatif

Industri kreatif saat ini mengalami pergeseran skill yang cukup signifikan. Jika dulu kemampuan teknis seperti desain grafis, fotografi, komposer, atau editing video menjadi modal utama, kini muncul satu keterampilan baru yang diam-diam menjadi pondasi penting pekerja kreatif, yaitu keterampilan membuat prompt.
Prompt Writer diprediksi akan menjadi salah satu pekerjaan paling menguntungkan di masa depan. Menulis perintah yang mampu diterjemahkan mesin dengan sangat akurat bukanlah hal mudah. Ia membutuhkan pemahaman mendalam tentang struktur bahasa, konteks visual, dan logika algoritma. Jati Andito bahkan menyebutkan bahwa seorang prompt writer bisa memiliki kapasitas setara dengan satu rumah produksi kecil.
Secara sederhana, prompt adalah perintah atau instruksi teks yang diberikan pengguna AI kepada model Generative AI seperti ChatGPT, Google Gemini, dan SUNO untuk menghasilkan output tertentu, seperti gambar, musik, ide, atau teks.
Elma meyakini bahwa menguasai prompt menjadi skill wajib bagi pekerja industri kreatif saat ini. Ia melihat prompt kini bukan sekadar instruksi teknis, melainkan prompt menjadi penerjemah imajinasi yang sulit dijelaskan oleh sebagian orang. “Kalau mau survive, harus bisa bikin prompt yang benar, tinggal tulis ide yang muncul di kepala kita, dan AI akan membantu menjelaskannya lebih mudah,” ujarnya.
Pelukis abstrak Indonesia yang dikenal dengan nama “Shuxxi Art” melihat munculnya fenomena ‘AI Artist’. Meskipun ia merasa bingung dan cenderung tidak setuju menyebut mereka sebagai seniman, ia mengakui bahwa menulis prompt yang sangat spesifik juga membutuhkan skill berpikir kritis dan kreativitas tinggi. Namun, ia tetap pada pendiriannya bahwa karena AI mengambil aset orang lain, ia menganggapnya bukan seni sejati.
Berkutat di dunia desain grafis membuat Sharone Alexandra tidak menutup mata dari kemajuan teknologi bernama AI (Akal Imitasi). Bagi Sharone, prompt adalah ujung penanya dalam menggambar. Bukan membuat dari awal, hanya sebagai penyempurna karya yang dibuatnya.
“Biasanya AI (Dreamina, Google Gemini) dipakai untuk mempercantik visual design sih, jadi misalnya konsep awalnya sudah ada gitu, tinggal digabungin sama prompt kira-kira perlu ditambahin apa gitu atau mungkin bagian mana yang harus diubah atau diganti.” ucap Sharone menjelaskan.
Ia juga menambahkan, pekerja kreatif saat ini tidak lagi dinilai dari kemampuan teknis semata. Karena yang akan bertahan adalah mereka yang mampu menggabungkan skill kreatif dengan skill prompt engineering, “kita harus belajar menguasai prompt sih, karena tidak sedikit klien hire orang di bidang kreatif yang bisa pakai AI dengan baik,” katanya.
Namun, Edo Tirtadarma, dosen di sebuah universitas swasta di Kota Tangerang Selatan, mengingatkan bahwa keahlian menyusun prompt AI tidak bisa menggantikan ilmu dasar seni. "Basic knowledge tentang warna, visual, dan desain tetap harus ada agar kita bisa mentranslasikannya menjadi kata-kata (prompt)," jelas Edo.
Dari semua ini, lahir sebuah pertanyaan:
Jika seni adalah rasa, bisakah rasa direkayasa AI?
Jika kreativitas adalah proses, bisakah proses itu dilewati?
Atno Setiawan, pelukis jalanan di sekitaran Blok M Square mengatakan, “seni itu rasa, emosi. Kalau saya lagi senang pasti lukisannya terlihat bagus. Tapi kalau saya lagi sedih lukisannya terlihat biasa-biasa saja,” ucapnya sembari melanjutkan melukis pesanan pelanggannya.
Meski memiliki keterbatasan fisik yang membuatnya hanya mampu beraktivitas dengan satu tangan saja, tidak serta membuatnya merasa tersisihkan dengan kehadiran AI saat ini, “Iya tahu memang ada itu (Generated AI) di HP, saya juga pernah coba pakai, tapi ya namanya lukisan pasti orang tahu mana yang buatan tangan (manusia) dan mana yang bukan, gitu. Jadi saya tidak merasa terancam, saya anggapnya sebagai hiburan, tapi kembali ke orang-orangnya,” tuturnya.
Hal serupa diucapkan juga oleh seorang ilustrator, comic & concept artist yang telah berkarya di ranah internasional, Ario Anindito, “Seni itu melibatkan intuisi dan emosi… seniman dengan gaya yang sama, ketika dia memiliki perasaan yang berbeda maka hasilnya sudah pasti akan berbeda juga,” ujarnya.
Komikus asal Bandung ini mengaku tidak pernah menggunakan AI di setiap proses kerjanya. Menurutnya, proses kreativitas manusia jauh lebih baik dibanding melibatkan Generative AI. “Selama proses mengerjakan Comic Marvel, DC Comic, Star Wars Comic, saya tidak ingin proses kerja saya dicampuri oleh orang lain bahkan oleh AI. Karena bagi seorang seniman disitulah tantangannya, yaitu menemukan ide dan saya hanya ingin proses mencari ide itu murni keluar dari kepala saya sendiri,” ujarnya.
Meski begitu, ia tetap mengakses AI untuk melihat karya-karya yang dihasilkannya, tetapi berupaya untuk tidak bergantung pada kecerdasan buatan tersebut. Baginya, hal itu penting untuk menunjukkan bahwa karya manusia masih memiliki nilai dan kualitas yang melampaui kinerja AI.
Dari dua pertanyaan di atas mengenai seni dan proses kreativitas, dapat disimpulkan bahwa jawabannya adalah ‘Tidak’.
Akal Imitasi (AI) tidak bisa merekayasa rasa atau perasaan dari seni, juga tidak bisa melewati proses kreativitas itu sendiri. Karena seni dan proses kreativitas itu hanya bisa dilakukan oleh manusia. Kehadiran AI seperti Google Gemini dan ChatGPT hanya sebatas membantu mengurai ide-ide yang muncul di kepala manusia, ketika ide tersebut sulit dijabarkan dengan kalimat.
Di sisi lain, Edo Tirtadharma mengingatkan bahwa efisiensi AI bisa menjadi boomerang jika penggunanya menjadi malas. Ia melihat ada tren mahasiswa yang menggunakan AI bahkan untuk menulis kata pengantar laporan. Hal ini menunjukkan bahwa efisiensi biaya dan waktu yang ditawarkan AI bisa menggerus kemampuan seseorang dalam berpikir kritis jika tidak dikelola dengan bijak.
Ario Anindito memperingatkan juga bahwa ketergantungan pada Generative AI mencerminkan krisis budaya di mana efisiensi lebih dihargai daripada ekspresi. Baginya, seni adalah tentang proses dan perasaan yang tidak bisa direplikasi oleh mesin yang hanya melakukan kompilasi data secara mekanis.
Sementara itu, Jati Andito yakin AI bisa memberikan kesempatan yang sama bagi siapa saja. Teknologi ini bisa menjadi ‘tangan kanan’ bagi teman-teman disabilitas dalam mengakses informasi sekaligus tetap produktif dalam berkarya. Dalam konteks ini, AI adalah alat yang mulia. Namun ketika AI digunakan perusahaan besar untuk menggantikan ribuan pekerja demi profit semata, disitulah masalahnya bermula.
3. Banjir data latih AI: tumpang tindih hak cipta di zona abu-abu

Model Generative AI dilatih menggunakan miliaran data dari internet, mulai dari teks, gambar, audio, audio-visual, hingga karya seni lainnya. Masalahnya, tidak semua data tersebut dikumpulkan dengan persetujuan pemiliknya.
Ari Juliano Gema, seorang praktisi hukum dan eks pejabat di Badan Ekonomi Kreatif, melihat fenomena ini sebagai tantangan redistribusi nilai. Menurutnya, ketika biaya produksi turun drastis karena AI, seharusnya ada mekanisme kompensasi bagi mereka yang datanya digunakan untuk melatih AI tersebut. Tanpa itu, kekayaan hanya akan menumpuk di pemilik platform.
“Kenapa data latih AI di dunia internasional bermasalah? Ya karena tidak ada izin, tidak ada kredit atas karya yang dipakai, dan tidak adanya kompensasi bagi pencipta karya tersebut. Consent, Credit, and Compensation sebutannya,” ucap Ari Juliano menjelaskan.
Guruh Riyanto dari Serikat Sindikasi juga menyoroti hal serupa. Ia menekankan bahwa AI hadir sebagai ancaman karena berada di tangan pemilik modal tanpa perlindungan hukum yang kuat bagi pekerja. "Pekerjaannya makin produktif karena AI, tapi nggak lantas nilai ekonominya tambah tinggi, justru diturunkan karena AI menurunkan nilai kerjanya," jelas Guruh.
Ari Juliano menjelaskan bahwa secara umum, dunia internasional sedang berdiskusi mengenai status karya hasil AI. Indonesia sendiri, melalui UU Hak Cipta Pasal 34, memberikan celah untuk menilai orisinalitas sebuah karya. "Prinsipnya, manusialah yang memegang peran penting sebagai subjek hukum pemilik hak cipta," jelas Ari.
Namun, masalah muncul ketika AI belajar dari data yang memiliki hak cipta. Jati Andito mempertanyakan bagaimana mekanisme kompensasi jika suaranya atau lagu-lagunya dicomot tanpa izin untuk melatih algoritma. Baginya, ini adalah bentuk eksploitasi modern di mana karya manusia dikapitalisasi oleh pemilik platform tanpa memberikan bagi hasil yang adil kepada pencipta aslinya.
Ari Juliano memperkenalkan konsep "Uji Empat Langkah" untuk menentukan apakah karya AI bisa dilindungi hak cipta:
Apakah prompt atau instruksi dibuat sendiri?
Apakah ada koreksi atau revisi manusia pada karya yang dihasilkan Generative AI?
Apakah karyanya termasuk karya yang dilindungi hak cipta?
Apakah karya yang dihasilkan Generative AI memiliki atau menunjukkan sifat khas pribadi si pencipta?
Jika keempatnya terpenuhi, maka karya tersebut bisa diklaim sebagai milik si pencipta.
Ari Juliano Gema melihat prompt sebagai bukti kepemilikan. Jika seseorang bisa membuktikan bahwa ia merancang prompt yang kompleks dan personal untuk menghasilkan sebuah karya, maka ia memiliki posisi tawar yang lebih kuat untuk mengklaim hak cipta atas karya tersebut. Prompt adalah bentuk kontribusi manusia di tahap input.
Ario Anindito tetap pada pendiriannya, bahwa AI yang mencuri gaya gambar ilustrator tidak layak disebut sebagai pencipta. “Tidak mungkin AI menciptakan sesuatu yang baru tanpa mengambil atau menjiplak gaya gambar ilustratornya,” tegas Ario. Baginya, hukum hak cipta harus lebih tegas dalam mengatur penggunaan dataset yang tidak berizin.
Masalah lain muncul pada penggunaan suara dan wajah. Ari Juliano menekankan bahwa suara adalah data pribadi yang bersifat khusus, begitu juga dengan wajah yang memiliki data retina yang spesifik. Meniru suara seseorang tanpa izin, seperti yang dialami oleh banyak penyanyi saat ini, bisa dikategorikan sebagai pelanggaran hak privasi dan publisitas. Namun, regulasi di Indonesia masih tertatih-tatih mengejar kecepatan teknologi ini.
Ignatius Igas, seniman tradisional di Bali, merasa hak cipta karya manualnya tetap aman secara identitas karena ia memiliki rekam jejak fisik. Namun, ia setuju bahwa bagi perupa pemula, AI bisa mengaburkan kreativitas dan identitas jika mereka tidak hati-hati dalam menjaga orisinalitas gaya mereka di tengah gempuran referensi AI.
Hukum hak cipta saat ini ibarat labirin yang belum selesai dibangun. Semua pihak sedang mencari jalan keluar agar teknologi tetap berkembang tanpa mengorbankan hak-hak dasar para seniman. Tantangan terbesarnya adalah membuktikan sejauh mana "sentuhan manusia" hadir dalam sebuah karya yang keluar dari mesin algoritma.
Permasalahan hak cipta pada musik memiliki kompleksitas tersendiri. Jati Andito menyoroti tren vocal cloning di mana suara penyanyi yang sudah meninggal bisa digunakan untuk menyanyikan lagu baru. Secara etis, hal ini memerlukan izin keluarga. Namun secara hukum, suara sebagai data pribadi masih menjadi area yang sangat abu-abu di banyak negara, termasuk Indonesia.
Jika sebuah lagu dihasilkan sepenuhnya oleh AI menggunakan suara orang lain tanpa izin, hal itu bisa digugat sebagai pelanggaran hak publisitas. Namun, pembuktian di pengadilan Indonesia akan sangat menantang karena belum memiliki preseden hukum yang kuat untuk kasus-kasus berbasis AI.
Pada karya gambar, masalah utama adalah scraping data. Banyak ilustrator merasa keberatan jika gaya unik mereka direplikasi oleh AI. Ari Juliano menyarankan pembentukan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) untuk seniman rupa dan ilustrator, serupa dengan yang ada di industri musik. LMK ini nantinya bisa menegosiasikan lisensi dengan pengembang AI sehingga seniman mendapatkan kompensasi.
Teks juga tidak luput dari masalah. ChatGPT belajar dari jutaan artikel di internet. Jika teks yang dihasilkan AI terlalu mirip dengan karya asli seseorang, maka unsur "sifat khas dan pribadi" dari penulis asli telah dilanggar. Namun, seringkali AI menyamarkan sumbernya sehingga sulit bagi penulis asli untuk mengklaim hak mereka.
Masalah "Merek" juga muncul, seperti dalam kasus Studio Ghibli. Jika seseorang menggunakan nama Ghibli dalam prompt untuk menghasilkan gambar dan mengomersialkannya dengan membawa-bawa nama tersebut, itu adalah pelanggaran merek. "Ghibli itu adalah merek. Kalau kamu ngomong ‘saya punya lukisan kayak Ghibli’, itu sudah pelanggaran merek," tegas Ari Juliano.
Ari juga menyarankan agar setiap platform AI yang beroperasi di Indonesia wajib mendaftarkan diri di KomDigi dan menjelaskan secara transparan penggunaan dataset mereka. Jika mereka tidak bisa membuktikan telah mendapatkan izin dari para pemegang hak cipta, platform tersebut seharusnya dilarang beroperasi. Ini adalah bentuk proteksi negara terhadap warga yang bekerja di industri kreatif.
Serikat Sindikasi melalui Guruh Riyanto mencatat juga adanya keresahan anggota mengenai pencurian hak cipta di internet. Nilai waktu kerja yang dicurahkan seniman untuk menciptakan sebuah karya seolah hilang begitu saja saat algoritma scraping mengambil karya tersebut untuk pelatihan mesin. Ini bukan hanya masalah hukum perdata, tapi masalah nilai ekonomi yang dirampas.
Di Uni Eropa, sudah ada EU AI Act yang mulai mengatur penggunaan AI secara ketat. Indonesia saat ini baru memiliki "Roadmap" atau peta jalan, namun belum sampai pada regulasi teknis yang mengikat. Ari memperingatkan bahwa tanpa aturan yang tegas, pada tahun 2029 (tahun politik) kita mungkin akan melihat kekacauan besar akibat deepfake dan manipulasi informasi berbasis AI.
Masalah hak cipta juga menyentuh aspek durasi. Hak cipta berlaku hingga 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Ahli waris berhak mengomersialkan karya tersebut. Jika AI menggunakan karya tersebut sebagai data latih tanpa izin ahli waris, maka ini adalah pelanggaran hukum yang nyata.
Regulasi di masa depan harus mampu membedakan antara mesin yang sekadar mengambil inspirasi dan mesin yang meniru karya secara langsung. Jika batasannya tidak jelas, aturan hak cipta bisa menjadi tidak berarti, karena siapa pun dapat mengaku sebagai pencipta hanya dengan menekan satu tombol.
Bagi seniman tradisional seperti Ignatius Igas, pada akhirnya orang akan mulai merindukan tekstur nyata, bau cat, dan goresan tangan yang tidak bisa diproduksi oleh printer atau layar monitor. “Pecinta seni tahu kok mana yang mereka inginkan, real panting,” ucapnya dengan nada tegas.
Shuxxi Art juga mengatakan, bahwa di masa depan seniman tradisional mungkin akan lebih dihargai karena ‘ketidaksempurnaan’ mereka. Generated AI menghasilkan karya yang terlalu rapi, sempurna, dan dingin, sementara manusia menghasilkan karya yang ‘hidup’ karena ada kesalahan-kesalahan alami di dalamnya.




























![[OPINI] Menakar Kelayakan Thomas Djiwandono Jadi Deputi BI](https://image.idntimes.com/post/20250115/sesi-1-sal02498-7b8580309183379b3c8eba91d7bc3c5b-273b07c328eb87f261cb80b9e2a0fd07_watermarked_idntimes-1.JPG)
![[OPINI] Apakah Perubahan Kemasan Produk Menjadi Saset Tanda Resesi?](https://image.idntimes.com/post/20260208/perubahan-ukuran-sachet-resesi-ekonomi_57b6ce7b-02bb-459b-b0d3-ce678054e335.JPG)
![[OPINI] Kenapa Tulisan yang Ditulis Sendiri Sering Dibilang Buatan AI?](https://image.idntimes.com/post/20260123/alasan-gak-semua-hal-layak-ditulis-menulis-berlebihan_d71a7bb9-f249-48fb-be75-26f38e13ac2f.jpeg)

![[OPINI] Relasi Epstein-Chomsky, dan Integritas Intelektual Kiri](https://image.idntimes.com/post/20260204/efta00003652-0_3909c293-079d-4870-ba54-8c60af9ef07b.jpg)
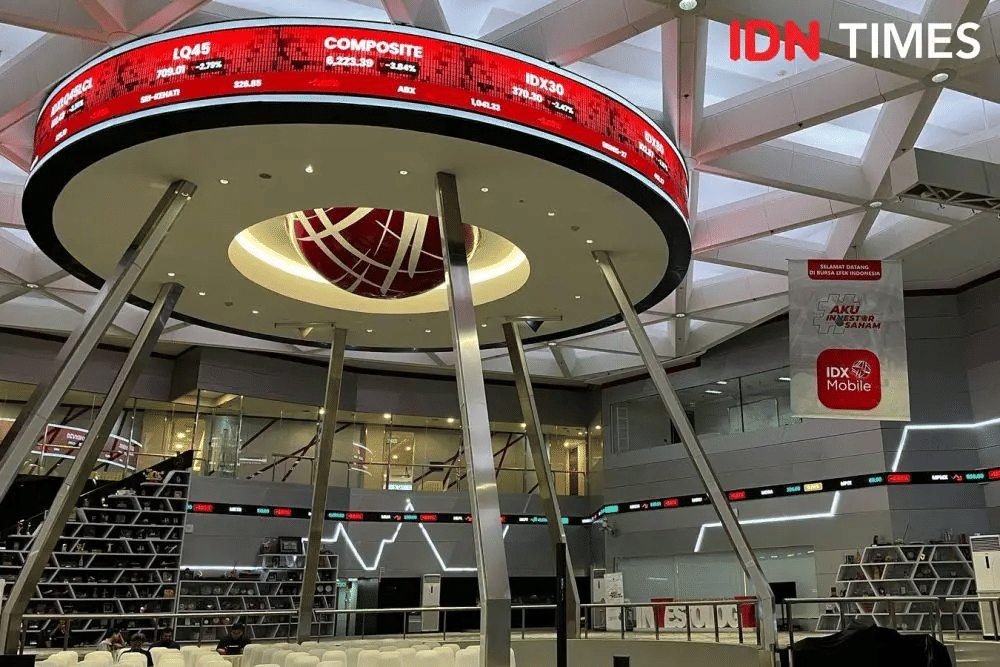


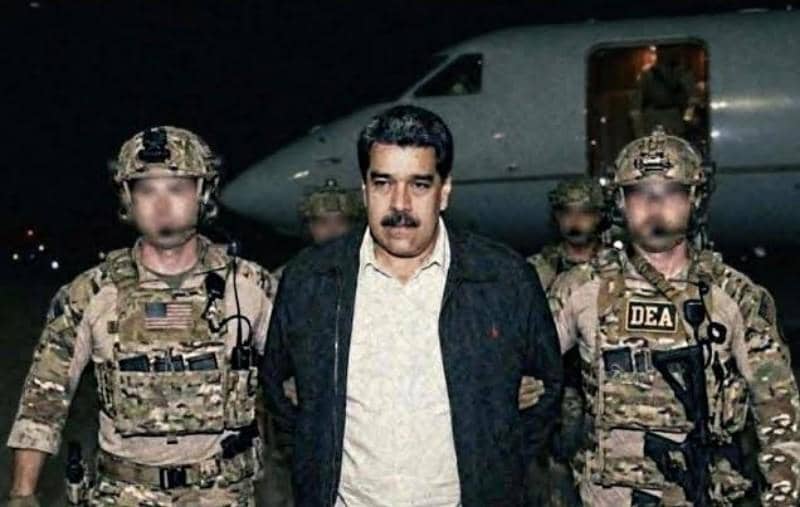


![[OPINI] Berhenti Berlindung di Balik Kalimat “Aku Orangnya Emang Begini”](https://image.idntimes.com/post/20251018/pexels-kampus-7555858_e0f0519c-fde0-4ab4-8965-0e12dabbd0b7.jpg)
![[OPINI] Peran Perempuan dalam Wujudkan Harmoni Sosial dan Lingkungan](https://image.idntimes.com/post/20250802/pexels-julia-m-cameron-8841582_4f4cbb51-bd42-46f6-ba78-fa42532e55a6.jpg)

![[OPINI] Setelah Chavez dan Castro: Ujian Revolusi Bolivarian](https://image.idntimes.com/post/20260108/upload_dd95bcd42f154a2960cdda3ed70e7109_4c8d29e1-0272-4459-9dbd-c40eeccc46c8.jpg)
![[OPINI] Nikah Muda: Alasan Kenapa Gak Semua Cerita Cinta Bisa Ditiru](https://image.idntimes.com/post/20260103/pexels-danu-hidayatur-rahman-1412074-2852135_2f19e731-6a9c-4db9-8adb-4642e15915d2.jpg)

