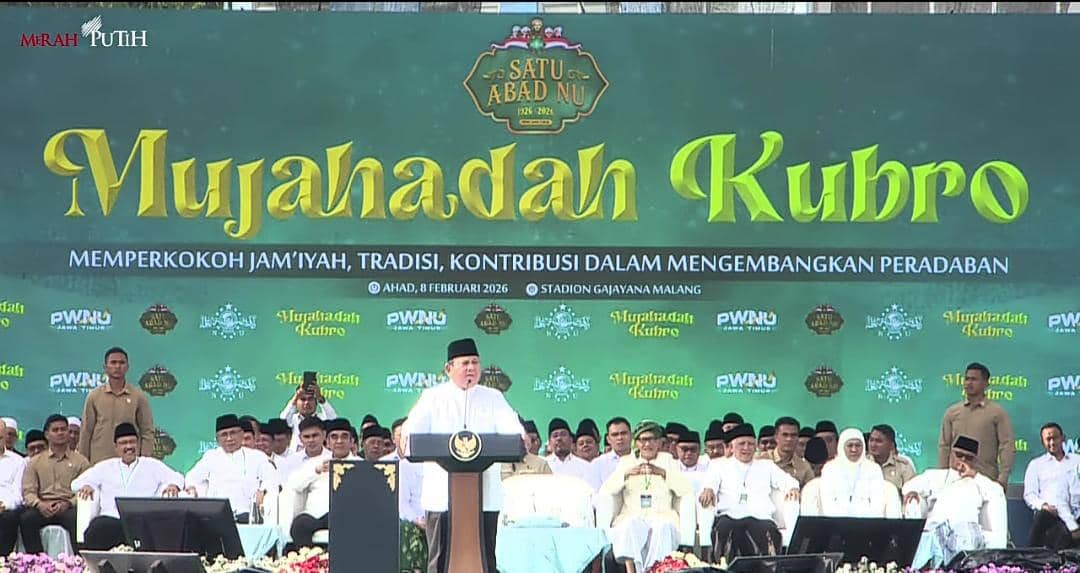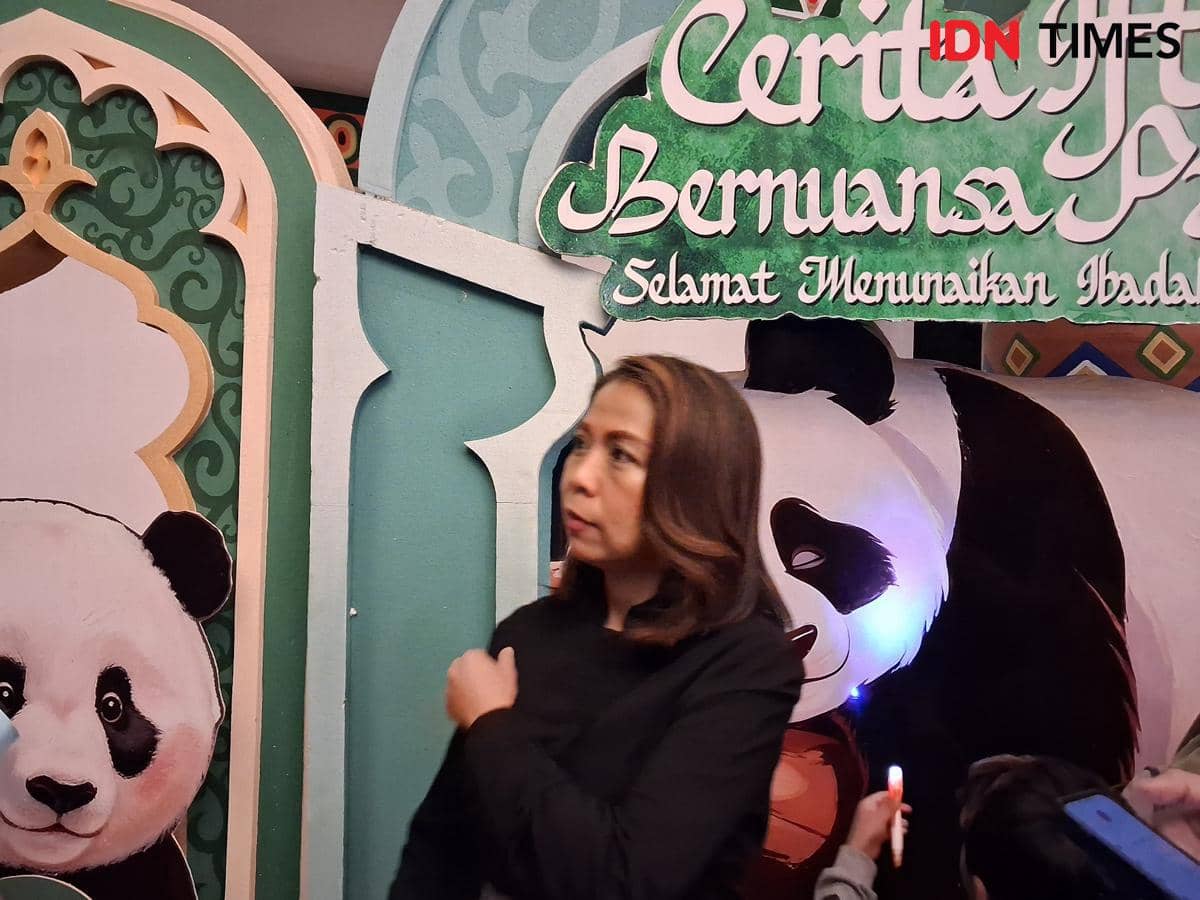Politik Identitas: Kendaraan Minoritas untuk Menggalang Dukungan

Jakarta, IDN Times - Politik identitas selalu muncul menjelang pemilihan umum (pemilu). Secara umum di Indonesia, frasa ini cenderung dianggap sebagai konotasi negatif.
Menjelang Pemilu 2024, politik identitas kembali ramai ketika para calon presiden atau koalisi menyambangi golongan tertentu untuk menggalang dukungan.
Lantas, apa itu politik identitas? Yuk Gen Z, simak penjelasannya di bawah ini!
1. Politik identitas dimaknai sebagai kendaraan ideologi politik

Menurut Guru Besar Ilmu Politik Hukum Islam, UIN Jakarata, Arskal Salim, politik identitas dalam bidang ilmu sosial dan humaniora dimaknai sebagai kendaraan yang membawa aspirasi, tuntutan kepentingan politik, dan ideologi politik.
Politik identitas, kata dia, menstimulasi bahkan menggerakkan aksi-aksi untuk meraih tujuan politik tertentu. Politik identitas juga dinilai mengkapitalisasi ras, suku bangsa, bahasa, adat, gender hingga agama sebagai mereknya.
“Politik identitas biasanya dimanfaatkan oleh kelompok minoritas maupun marjinal dalam upaya melawan ketidakadilan atau ketimpangan sistem. Dalam menyuarakan aspirasi kelompok pengusung politik identitas, distingsi seperti kesukuan, gender dan agama ditunjukkan secara eksplisit dan intensif,” kata Arskal dalam tulisannya di laman uinjkt.ac.id dikutip IDN Times, Minggu (7/4/2023).
2. Politik identitas dimanfaatkan untuk memperlihatkan posisi sebagai korban

Arskal menjelaskan, politik identitas tidak lazim dimainkan oleh kelompok mayoritas yang sebenarnya memiliki akses lebih atau privilege dibandingkan kaum minoritas.
Politik identitas oleh kelompok minoritas kerap dimanfaatkan untuk memperlihatkan posisi sebagai korban (playing victim) dari sistem represif yang dijalankan oleh kelompok mayoritas.
“Bagaimana mungkin kelompok mayoritas dengan privilege, kemudian mem-frame diri sebagai korban?” kata dia.
Arskal menegaskan, politik identitas berbeda dengan politik kebangsaan. Menurut dia, politik kebangsaan memahami keberadaan kelompok mayoritas dan minoritas.
Namun, haluan politik ini bertujuan untuk mengakomodasi agar kedua kelompok menjadi inklusif. Hal ini berbeda dengan politik identitas yang salah satu kelompoknya menuntut hak ekslusif.
Dalam kacamata politik kebangsaan, ujar Arskal, keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia di atas segalanya.
"Setiap warga dari latar belakang sosial, kultural, agama apapun memiliki hak dan kewajiban yang setara untuk berpartisipasi dalam politik," kata dia.
Sebaliknya, dalam perspektif politik identitas, pemenuhan hak satu kelompok yang menjadi tujuan utama. Hal itu, kata Arskal, justru bisa menimbulkan ketegangan atau bahkan perpecahan antar kelompok.
Meski demikian, politik praktis belum tentu membawa politik identitas. Menurut dia, pelaku politik praktis adalah anggota masyarakat dengan kesamaan identitas tertentu. Misalnya adanya kesamaan visi misi politik, geografis hingga kesamaan agama.
“Namun, hal ini tidak serta-merta menjadikan setiap praktik politik sebagai gerakan politik identitas,” kata Arskal.
Menurut Arskal, sebuah politik praktis menjadi gerakan politik identitas adalah ketika afiliasi kesukuan, keagamaan atau ras dijadikan komoditas untuk memobilisasi pengaruh perilaku pemilih.
Preferensi objektif terhadap calon pemimpin yang memiliki kapasitas mumpuni pun disebutnya menjadi terdistorsi oleh sentimen kesukuan atau keagamaan itu.
Contohnya adalah calon pemimpin yang tidak kompeten tetapi memiliki keyakinan agama yang sama akan lebih dipilih daripada calon pemimpin yang kompeten tapi berbeda keyakinan.
"Acapkali, politik identitas memanipulasi doktrin agama untuk mendiskriminasi dan menyudutkan pemilih seagama yang menyalurkan aspirasi politik yang berbeda," ujar dia.
3. Politik identitas memiliki tujuan eksklusif untuk kelompoknya sendiri

Arskal menyimpulkan, politik identitas sering disalahpahami sebagai bagian dari politik praktis atau bahkan merupakan politik kebangsaan.
"Memang, kesamaan identitas menjadi pemersatu bagi anggota suatu kelompok (in group unity)," katanya.
Namun, dalam konteks kebangsaan Indonesia yang majemuk, kata dia, menonjolkan identitas kelompok secara dominan justru dapat menjadi potensi ancaman bagi persatuan dan kesatuan bangsa (nation unity).
“Di sinilah pembeda antara politik identitas dengan politik kebangsaan, sebab yang satu ingin meraih tujuan eksklusif kelompoknya sendiri, sedangkan yang lain bertujuan untuk meraih tujuan inklusif bagi kehidupan bersama,” ujar Arskal.
Baca berita terbaru terkait Pemilu 2024, Pilpres 2024, Pilkada 2024, Pileg 2024 di Gen Z Memilih IDN Times. Jangan lupa sampaikan pertanyaanmu di kanal Tanya Jawab, ada hadiah uang tunai tiap bulan untuk 10 pemenang.