Pahit Manis Idul Fitri, Jadi Minoritas di Keluarga Mayoritas Muslim

- Mengalami tantangan sebagai minoritas di keluarga muslim
- Tidak bisa pulang kampung saat Idul Fitri karena tuntutan pekerjaan sebagai jurnalis
Jakarta, IDN Times - Menjadi pemeluk agama minoritas di keluarga besar muslim punya warna tersendiri. Ya, agama saya Katolik, sementara keluarga besar mayoritas memeluk agama Islam.
Orangtua dan keluarga besar selalu mengajarkan saya sedari kecil, sejatinya agama hanya bagaimana cara kita berkomunikasi dengan Sang Khalik. Tak ada kepercayaan mana yang paling salah atau bahkan si paling benar.
"Bagimu agamamu, bagiku kau saudaraku," begitu kira-kira slogan keluarga besar kami sehingga bisa berdampingan satu sama lain.
1. Kenangan besar di kota kecil

Selama hidup 27 tahun, bisa dihitung jari saya tidak mudik dan memeriahkan bagaimana hangatnya perayaan Idul Fitri di kampung halaman tercinta, Kutoarjo, Jawa Tengah (Jateng). Sebuah kota kecil dengan kehangatan di setiap sudutnya.
Bagi saya, lagi-lagi sejak kecil sudah menganggap, setidaknya dalam satu tahun ada dua perayaan besar keagamaan yang dinantikan, yaitu Idul Fitri dan Natal. Bukan cuma amplop tunjang hari raya (THR) yang dinanti keluar dari saku saudara, tapi kehangatan dan kebersamaan keluarga yang paling utama.
Saya beranggapan, manisnya Idul Fitri sudah bisa dikecap sejak memasuki bulan puasa. Rasanya di lidah sudah membayangkan bagaimana nikmatnya opor ayam dipadu dengan sambal krecek, khas buatan orang kampung. Setiap gigitannya mengandung kehangatan serta tawa dan canda keluarga besar yang hanya bisa kumpul setahun sekali.
Belum lagi agenda wajib keluarga besar saya, kulineran, membeli makanan khas kampung halaman untuk disantap sesudah opor dan sambal krecek habis tak tersisa.
Kami juga terbiasa nyekar ke makam keluarga dan sungkem meminta maaf sekaligus berkat ke mbah. Dari empat mbah saya, dua di antaranya beragama Katolik, dua lainnya beragama Islam.
Saat ini, hanya satu mbah yang tersisa, yakni nenek dari ibu. Mbah Hadi namanya, keluarga kami menjulukinya sebagai Neli yang merupakan akronim Nenek Lincah. Maklum, di umurnya yang sudah hampir satu abad, dia masih sat-set, bahkan ingat jelas kapan tanggal lahir anak, cucu, hingga buyutnya.
2. Quarter life crisis ala milenial dan Gen Z

Tapi sialnya, kehangatan dan keseruan itu semakin ke sini, agaknya sulit saya rasakan lagi. Kalau milenial dan Gen Z bilang, quarter life crisis, fase krisis yang dialami oleh seseorang pada usia 20-an sampai awal 30-an. Saya harus bertanggungjawab dengan tuntutan pekerjaan.
Sebagai jurnalis dan pemeluk agama nasrani yang tidak merayakan Idul Fitri, saya tidak mungkin mengambil libur dan cuti untuk pulang kampung. Saya harus standby di Ibu Kota, menjadi cadangan alias backup rekan kerja lainnya yang ingin merayakan Idul Fitri dan berjaga sewaktu ada arahan untuk meliput peristiwa. Toh, rekan kerja muslim saya melakukan hal serupa, ketika saya mengambil jatah libur perayaan Natal dan tahun baru.
Sudah tiga kali Idul Fitri saya tak bisa pulang kampung ke Kutoarjo. Cuma bisa merasakan kuah opor dan sambal krecek secara virtual. Silaturahmi serta sungkem juga dilakukan sembari menatap layar gawai yang kadang-kadang permohonan maaf belum tersampaikan, tetapi sambungannya sudah terputus akibat keterbatasan sinyal.
Tak jarang saat saya liputan, rasanya ingin bergabung saat melihat keluarga lain yang dengan hangat bisa berkumpul. Selama libur Idul Fitri, keluarga inti saya yang cuma berjumlah empat orang yakni ayah, ibu, dan adik pulang kampung. Alhasil, saya harus menahan kangen gurihnya kuah opor dari rumah di Jakarta.
3. Terkadang sebait kata-kata bisa jadi penenang

Tapi tak masalah, saya menenangkan rasa itu dengan prinsip hidup yang didapat dari beberapa tokoh favorit. Saya ingat betul pesan budayawan favorit sekaligus tokoh intelektual muslim, Emha Ainun Nadjib alias Cak Nun. Di sela-sela acara Kenduri Cinta, ia menjelaskan makna falsafah Jawa, urip iku mung mampir ngombe (hidup itu cuma mampir minum).
Ada lagi dalam buku Kawruh Jiwa, filsuf Jawa, Ki Ageng Suryomentaram mengajarkan Ing kene, ngene, saiki, aku gelem (di sini, seperti ini, sekarang, aku menerima semuanya).
Kedua kutipan itu mengajarkan, hidup itu cuma singgah sebentar untuk minum. Mirip seperti rasa senang atau sedih, cuma sementara kita rasakan. Bahwa ada posisi di mana sudah saatnya kita merasa sedih, atau sudah waktunya harus merasakan senang. Sebagai manusia, tak perlu larut dalam rasa, yang penting bagaimana cara mengolah yang memang sudah jadi ketentuan Dia, Yang Maha Ada, Al Qadir, Al Mu'akhir, Al Muqtadir, Al Kariim, Al Muhaymin, dan segala maha lainnya.




























![[OPINI] Menakar Kelayakan Thomas Djiwandono Jadi Deputi BI](https://image.idntimes.com/post/20250115/sesi-1-sal02498-7b8580309183379b3c8eba91d7bc3c5b-273b07c328eb87f261cb80b9e2a0fd07_watermarked_idntimes-1.JPG)
![[OPINI] Apakah Perubahan Kemasan Produk Menjadi Saset Tanda Resesi?](https://image.idntimes.com/post/20260208/perubahan-ukuran-sachet-resesi-ekonomi_57b6ce7b-02bb-459b-b0d3-ce678054e335.JPG)
![[OPINI] Kenapa Tulisan yang Ditulis Sendiri Sering Dibilang Buatan AI?](https://image.idntimes.com/post/20260123/alasan-gak-semua-hal-layak-ditulis-menulis-berlebihan_d71a7bb9-f249-48fb-be75-26f38e13ac2f.jpeg)

![[OPINI] Relasi Epstein-Chomsky, dan Integritas Intelektual Kiri](https://image.idntimes.com/post/20260204/efta00003652-0_3909c293-079d-4870-ba54-8c60af9ef07b.jpg)
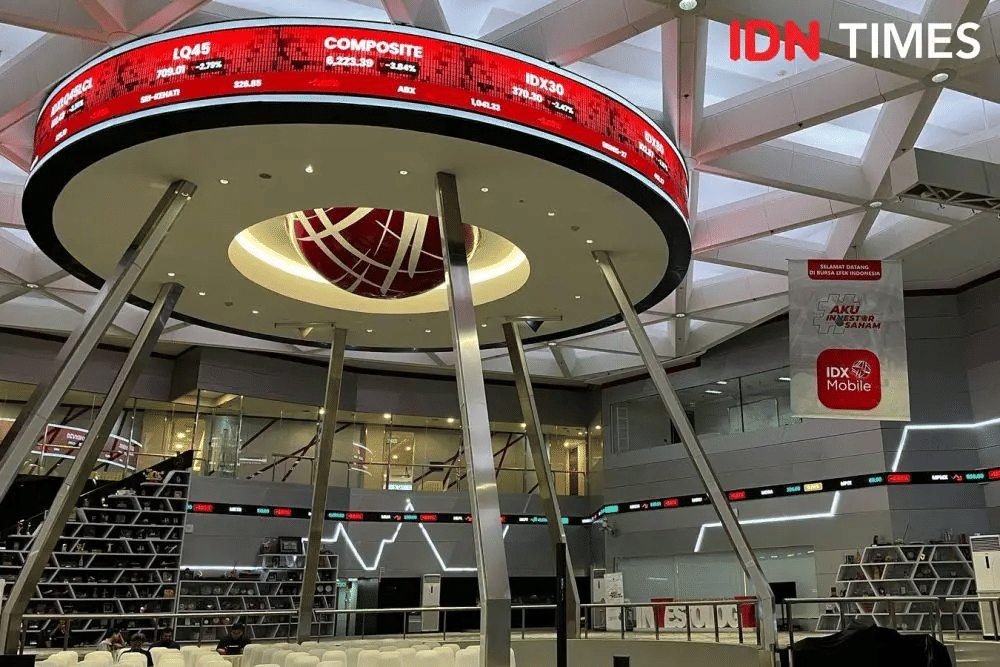


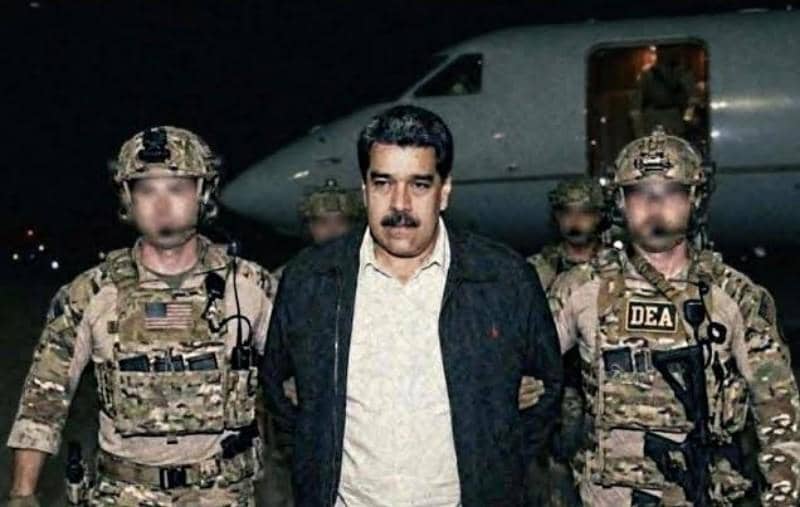


![[OPINI] Berhenti Berlindung di Balik Kalimat “Aku Orangnya Emang Begini”](https://image.idntimes.com/post/20251018/pexels-kampus-7555858_e0f0519c-fde0-4ab4-8965-0e12dabbd0b7.jpg)
![[OPINI] Peran Perempuan dalam Wujudkan Harmoni Sosial dan Lingkungan](https://image.idntimes.com/post/20250802/pexels-julia-m-cameron-8841582_4f4cbb51-bd42-46f6-ba78-fa42532e55a6.jpg)

![[OPINI] Setelah Chavez dan Castro: Ujian Revolusi Bolivarian](https://image.idntimes.com/post/20260108/upload_dd95bcd42f154a2960cdda3ed70e7109_4c8d29e1-0272-4459-9dbd-c40eeccc46c8.jpg)
![[OPINI] Nikah Muda: Alasan Kenapa Gak Semua Cerita Cinta Bisa Ditiru](https://image.idntimes.com/post/20260103/pexels-danu-hidayatur-rahman-1412074-2852135_2f19e731-6a9c-4db9-8adb-4642e15915d2.jpg)


