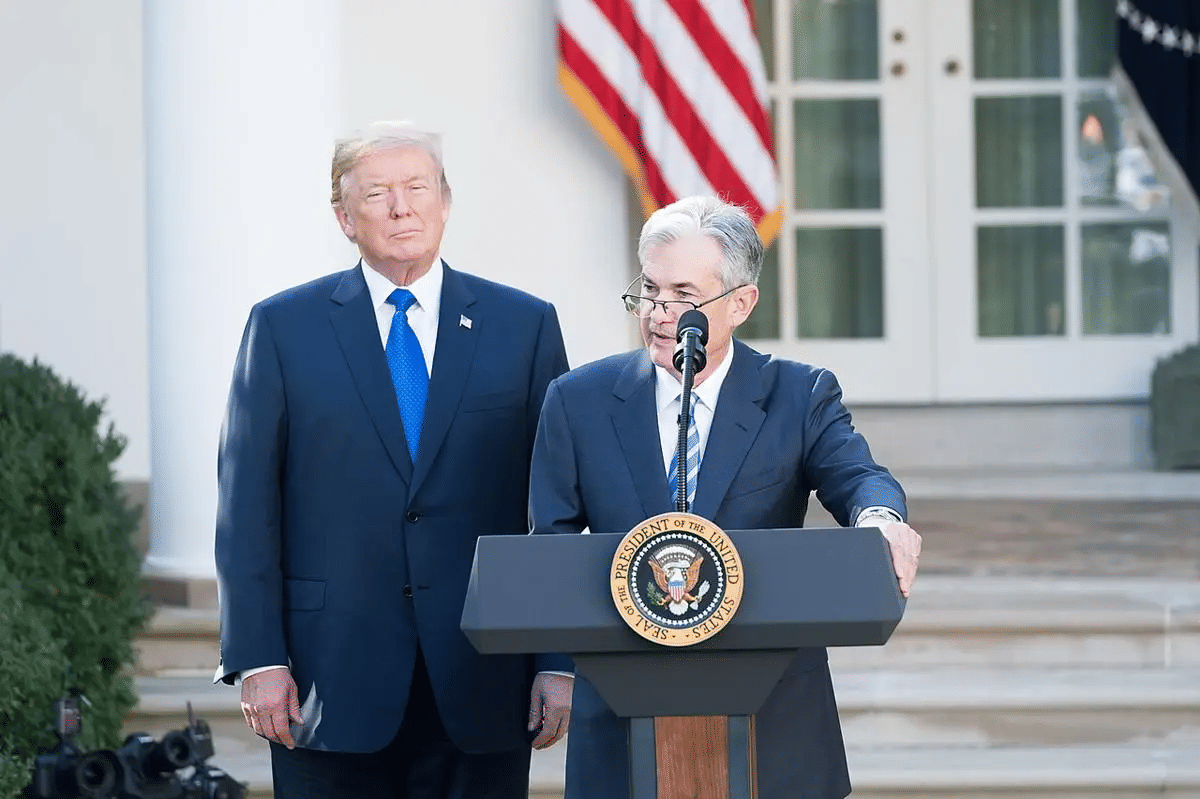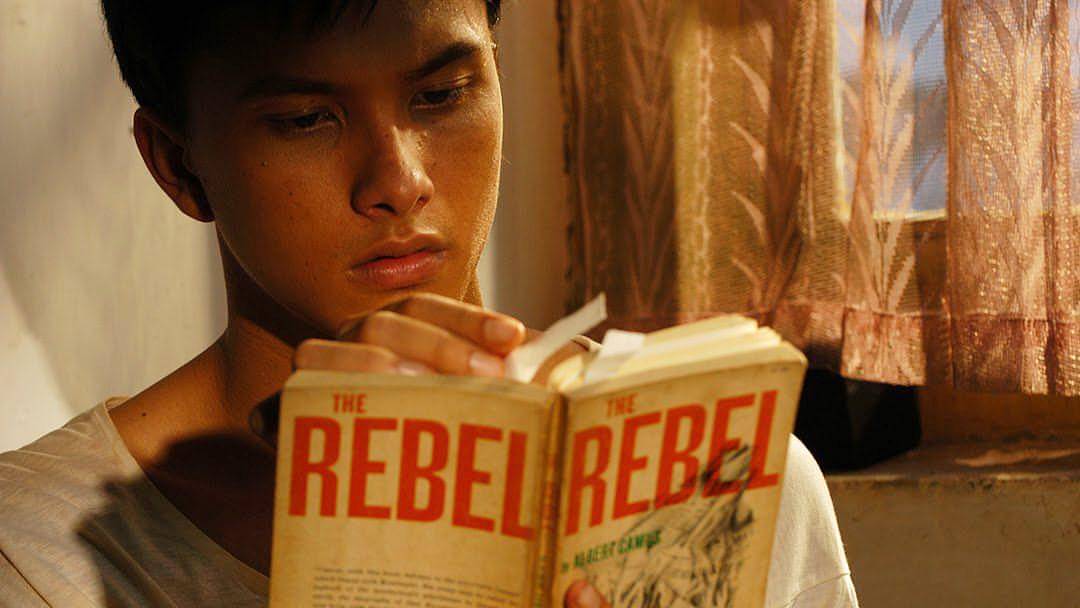Semuanya Berubah Sampai Ibuku Terpapar Corona

“Mas, Ibu udah gak bisa nyium lagi,” keluh ibuku pada suatu malam. Sudah satu minggu sejak batuk dan flu yang dirasakan tak kunjung membaik.
Sebab tak menunjukkan gejala demam, aku masih tak ambil pusing dengan keluhannya. Dalam benak, aku berharap bahwa virus yang bersarang di tubuhnya bukanlah corona. Karena masih penasaran, aku meminta ibu untuk mencium aroma kopi Gayo yang baru saja kuseduh dengan metode V60.
“Gak ada wanginya, Mas,” sahut ibuku. Aku panggil adik perempuan yang saat itu hendak menunaikan salat Isya.
“Dek, coba cium wanginya deh. Ada aromanya gak?” pintaku.
“Ini kecium banget kok aromanya,” jawab dia.
Sejak saat itulah aku sudah menyiapkan sedikit ruang dalam hati jika COVID-19 benar-benar menyerang ibuku.
“Ya udah besok coba tes COVID aja Bu,” saranku.
“Mas, Ibu takut,” gelisahnya. Ibuku adalah seorang komorbid dengan penyakit paru-paru. Usianya saat ini 55 tahun. Dia adalah tipe orang yang sangat sulit menelan obat. Jika rasa pahit dari obat saja sedikit terasa, saat itu pula dia bisa memuntahkan seluruh isi perutnya. Aku pun pusing. Tidak bisa membayangkan bagaimana jadinya bila ibu harus diisolasi terpisah dari keluarga.
“Justru yang bahaya kalau gak ketahuan corona, terus malah nularin aku, ke ayah, ibu, sama adek, terus penanganannya terlambat,” imbuhku.
Ketika itu, aku sangat yakin bahwa kunci penanganan corona adalah deteksi dini. Malam-malam sebelumnya, aku menyimak pemaparan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Doni Monardo dalam acara Indonesia Lawyer Club. Dia mengatakan bahwa tidak ada penderita corona yang meninggal setelah terdeteksi dan mendapatkan perawatan sejak awal.
Pernyataan Doni kala itu aku sampaikan kepada ibuku. Meyakinkan dia bahwa testing adalah langkah utama untuk menyelamatkan bukan saja nyawanya, tapi nyawa seluruh anggota keluarga.
Keesokan harinya, di pagi hari, ternyata ibuku sudah pergi ke rumah sakit. Kata ayah, ibu langsung dites dengan metode PCR, karena adanya gejala seperti flu, batuk, dan kehilangan indra penciuman. Masa itu, Oktober 2020, butuh waktu satu hari untuk memperoleh hasil uji laboratorium.
Singkat cerita, keesokan harinya, ibuku menerima telepon dari rumah sakit. Mengabarkan bahwa hasil tesnya adalah positif COVID-19. Adikku bergegas membangunkanku. Kantukku seketika hilang ketika dia berkata, “Mas, Ibu kena corona.”
Saat aku ke luar dari kamar, menuruni tangga dari lantai dua, aku sudah melihat ayah dan ibu duduk di meja makan. Saling berseberangan. Ibu mengenakan masker. Raut wajahnya terlihat memelas.
“Mas, Ibu kena COVID,” katanya mengabarkan kepadaku. Untuk sesaat, suasana siang itu begitu sunyi. Ungkapan ini mungkin saja berlebihan, tapi waktu serasa berhenti untuk sejenak. Kami sekeluarga bingung untuk menentukan apa tindakan yang harus dilakukan.
Ibu merupakan seorang extrovert, bukan tipikal yang cocok untuk menjalani isolasi mandiri. Apalagi di daerah yang tak familiar. Seperti wisma atau ruang ICU. Siang itu, kami hanya memiliki waktu satu jam untuk memutuskan, apakah ibu harus dirawat di rumah sakit atau isolasi mandiri di rumah.
Setelah menerima saran dari kolega yang seorang dokter, kami akhirnya memutuskan ibu dirawat di rumah sakit.
Di rumah sakit yang jaraknya sekitar 850 meter dari rumah, di situlah untuk pertama kalinya aku benar-benar takut dengan corona. Aku diminta menandatangani surat pernyataan bahwa kondisi ibuku sepenuhnya diserahkan kepada rumah sakit.
Bila nanti ibu meninggal, maka jenazah harus disemayamkan dengan pemulasaran COVID-19. Kami juga tidak boleh mengunjungi pasien.
Lalu WhatsApp dari dari ibuku masuk. Dia meminta untuk dibelikan makanan. Belum ada di antara kami yang sempat santap malam, bahkan sejak siang hari. Saya belikan dia dimsum dengan wedang jahe, dan satu liter air kemasan.
Terbesit dalam benak, bahwa malam itu adalah kali terakhir aku melihat ibuku secara langsung.
“Ibu kalau ada apa-apa kabarin. Boleh pake hape kok, kalau kangen telepon aja,” kataku, meyakinkan ibu bahwa dia bisa melewati ujian ini.
Singkat cerita, pada hari kelima, kondisi ibuku cukup mengkhawatirkan. Meski masih sadar, dia harus memperoleh alat bantu pernapasan. “Ibu sulit napas, Mas,” keluhnya.
“Ibu juga susah minum obat. Setiap hari ibu harus minum 18 obat,” katanya dengan lirih.
Sulit membayangkan. Betapa beratnya seseorang yang tidak terbiasa meminum obat, harus menenggak 18 butir obat.
Setiap hari aku bersama adikku mengantarkan makanan kepada ibu. Supaya dia rutin makan. Yang lebih penting lagi adalah supaya dia memperoleh perhatian dari anak-anaknya. Kami sempat beberapa kali video call. Hanya itu yang bisa kami lakukan dari kejauhan.
Singkat cerita, memasuki hari ke-12, dokter sudah mengizinkan ibuku pulang. Meski hasil tes terakhir masih menunjukkan positif, tapi ibu sudah melewati fase kritis. Dia sudah diizinkan untuk menjalani isolasi mandiri.
Sebenarnya, protokol rumah sakit tidak mengizinkan hal seperti itu. Namun, ada banyak pasien corona yang mengantre untuk memperoleh perawatan lebih intensif.
Melalui cerita ini, saya ingin menyampaikan, corona tidak akan benar-benar menjadi perhatian hingga orang terkasih dan terdekat kita terpapar virus tersebut. Sekalipun kita yakin mampu menjaga diri dengan baik, belum tentu orang-orang yang tinggal di rumah kita mampu melakukan hal serupa.
Corona benar-benar mengubah segalanya.
Malam demi malam aku lewati dengan gelisah. Meski melalui pesan atau telepon aku selalu meyakinkan ibu, sebenarnya aku juga menguatkan diriku sendiri, bahwa dia pasti bisa melewati ini semua.
Corona benar-benar mengubah segalanya. Sampai kita sadar bahwa mawas diri adalah satu-satunya cara terbaik untuk melindungi diri.
#SatuTahunPandemik adalah refleksi dari personel IDN Times soal satu tahun virus corona menghantam kehidupan di Indonesia. Baca semua opini mereka di sini.