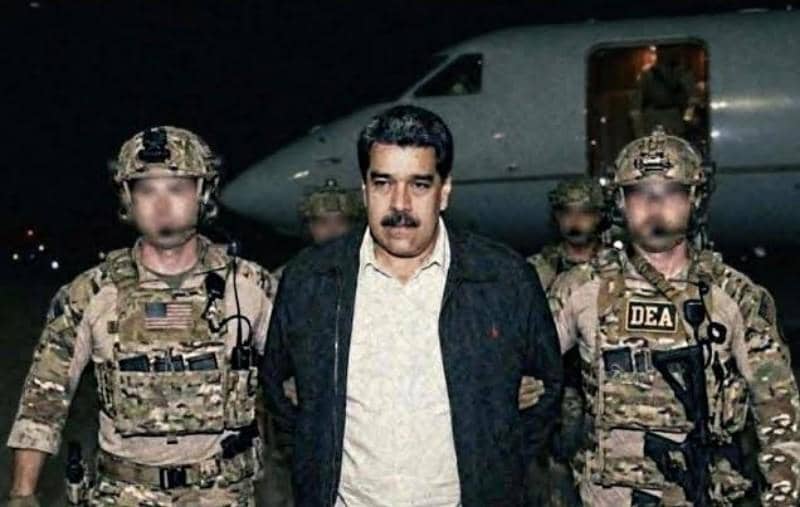[OPINI] Apa yang Tersisa dari Film Istirahatlah Kata-Kata?

- Film Istirahatlah Kata-Kata disutradarai oleh Yosep Anggi Noen, mengangkat kisah pelarian Wiji Thukul di Pontianak dan peristiwa Kudatuli.
- Puisi-puisi Wiji Thukul yang merekam kegelisahan kemanusiaan dan pengalaman sosial-politik kurang diperkenalkan secara sistematis kepada generasi muda.
- Penetapan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional menimbulkan pertanyaan etis dan pedagogis terhadap cara negara memaknai masa lalu.
Dalam tiga semester terakhir, saya selalu menugaskan para mahasiswa di kelas-kelas yang saya ampu untuk menonton film Istirahatlah Kata-Kata. Setelah itu, mereka diminta menganalisis film tersebut dengan menggunakan perspektif sila kedua Pancasila, yakni Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Pendekatan ini saya pilih agar film tidak hanya dibaca sebagai karya seni atau dokumen sejarah, tetapi juga sebagai refleksi etis kebangsaan.
Film Istirahatlah Kata-Kata disutradarai oleh Yosep Anggi Noen, sineas yang dikenal melalui karya-karyanya yang kerap menyoroti pengalaman manusia dalam situasi sosial dan politik yang menekan. Film ini bukan film biografi konvensional, melainkan potret yang minim dialog tentang ketakutan, kesepian, dan keberanian—yang justru membuatnya relevan dibaca melalui perspektif kemanusiaan.
Biasanya, setelah sekitar tiga puluh menit menonton, saya mengajukan pertanyaan sederhana kepada mahasiswa: “Bagaimana, filmnya bagus atau tidak?” Sebagian besar menjawab bahwa film tersebut bagus, tetapi dengan nada yang datar, tidak antusias seperti setelah menonton film drama atau film laga.
Ada pula mahasiswa yang dengan jujur mengatakan, “Bosan, Pak. Alurnya kurang kami mengerti.” Terus terang, saya justru lebih menghargai jawaban yang jujur, meskipun terasa pahit. Jawaban-jawaban itu menjadi pintu masuk yang penting untuk memahami jarak generasi muda dengan film ini, bahkan dengan konteks sejarah yang melingkupinya.
Film ini berkisah tentang masa pelarian Wiji Thukul di Pontianak, ketika ia berusaha menghindari kejaran aparat Orde Baru setelah peristiwa Kudatuli—Kerusuhan 27 Juli 1996. Kudatuli merupakan penyerbuan terhadap kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di Jakarta yang saat itu diduduki oleh massa PDI pendukung Megawati Soekarnoputri. Mereka menolak kebijakan Orde Baru yang mendukung Soerjadi sebagai Ketua Umum PDI, meskipun Megawati sebelumnya terpilih secara demokratis melalui kongres partai. Peristiwa ini menjadi salah satu titik penting dalam sejarah represi politik menjelang runtuhnya Orde Baru.
Dalam film tersebut, beberapa puisi Wiji Thukul—penyair, Ketua Jaringan Kerja Kebudayaan Rakyat, sekaligus anggota Partai Rakyat Demokratik—dibacakan dalam sejumlah adegan. Puisi-puisi seperti Para Penyair Adalah Pertapa Agung dan Kuterima Kabar dari Kampung hadir sebagai penanda penting. Namun demikian, bagi sebagian besar mahasiswa, sosok Wiji Thukul tetap terasa asing, demikian pula puisi-puisinya.
Mengapa hal ini terjadi?
Jawabannya sesungguhnya cukup sederhana: Wiji Thukul dan karya-karyanya nyaris tidak diperkenalkan secara sistematis kepada para siswa dan mahasiswa. Berbeda dengan puisi-puisi Chairil Anwar yang akrab melalui buku-buku pelajaran sekolah, puisi-puisi Wiji Thukul hampir tidak pernah mendapatkan ruang dalam kurikulum formal. Padahal, secara historis dan tematis, puisi-puisi Thukul merekam kegelisahan kemanusiaan dan pengalaman sosial-politik yang penting dalam perjalanan bangsa ini.
Ironisnya, kondisi tersebut tetap terjadi meskipun salah satu rekan Wiji Thukul, Hilmar Farid, pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Kebudayaan. Setahu saya, salah satu kebijakan penting pada masa itu adalah penayangan film Istirahatlah Kata-Kata di TVRI melalui program Belajar dari Rumah yang bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pada 16 Juni 2020. Namun, ketika saya menanyakan hal ini kepada mahasiswa—yang sebagian besar lahir setelah tahun 2000—hampir semuanya menyatakan belum pernah menonton film tersebut.
Situasi ini menunjukkan bahwa jarak generasi muda dengan Wiji Thukul bukan semata soal minat, melainkan juga soal pewarisan ingatan. Tanpa pengenalan yang memadai, karya-karya yang lahir dari pergulatan kemanusiaan—seperti puisi-puisi Wiji Thukul—berisiko terputus dari generasi berikutnya. Di titik inilah, film Istirahatlah Kata-Kata menjadi penting, bukan hanya sebagai karya sinema, tetapi sebagai medium pembelajaran nilai kemanusiaan dalam sila kedua Pancasila—nilai yang seharusnya terus hidup dalam ruang pendidikan dan kesadaran publik.
Namun, upaya pewarisan ingatan tersebut tidak berlangsung dalam ruang hampa. Ia berhadapan dengan realitas politik yang turut membentuk cara negara dan masyarakat memaknai masa lalu. Penetapan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional oleh pemerintahan Prabowo, misalnya, menjadi konteks yang tidak bisa diabaikan. Keputusan negara tersebut sah secara administratif, tetapi pada saat yang sama menimbulkan pertanyaan etis dan pedagogis.
Bagaimana puisi-puisi Wiji Thukul—yang lahir dari perlawanan terhadap ketidakadilan dan represi pada masa Orde Baru—dapat diajarkan secara jujur kepada generasi muda, ketika penguasa pada masa itu kini diangkat sebagai pahlawan nasional?
Saya selalu mengajukan pertanyaan kepada mahasiswa setelah mereka selesai mempresentasikan analisis film Istirahatlah Kata-Kata: apakah penculikan aktivis dan penghilangan orang secara paksa sejalan dengan sila kedua Pancasila? Mereka hampir selalu menjawab tidak. Dari sana, saya melanjutkan dengan pertanyaan berikutnya: bagaimana pandangan kalian terhadap sikap pemerintah Indonesia saat ini yang menetapkan Soeharto, Presiden pada masa Orde Baru, sebagai pahlawan nasional?
Pertanyaan-pertanyaan itu tidak dimaksudkan untuk memberi jawaban tunggal, melainkan untuk menjaga agar ruang pendidikan tetap menjadi tempat yang memungkinkan dialog kritis tentang kemanusiaan, keadilan, dan ingatan kolektif bangsa.
Pada akhirnya, pertanyaan tentang apa yang tersisa dari film Istirahatlah Kata-Kata bukan hanya soal ingatan terhadap Wiji Thukul atau sejarah Orde Baru. Ia juga berkaitan dengan cara kita, sebagai bangsa, menerapkan nilai kemanusiaan dalam pendidikan dan kebijakan publik. Apakah nilai kemanusiaan yang adil dan beradab hanya berhenti sebagai rumusan normatif—sekadar kata-kata indah—atau sungguh-sungguh dihidupkan melalui keberanian merawat ingatan, termasuk ingatan yang tidak selalu nyaman bagi negara maupun masyarakat.