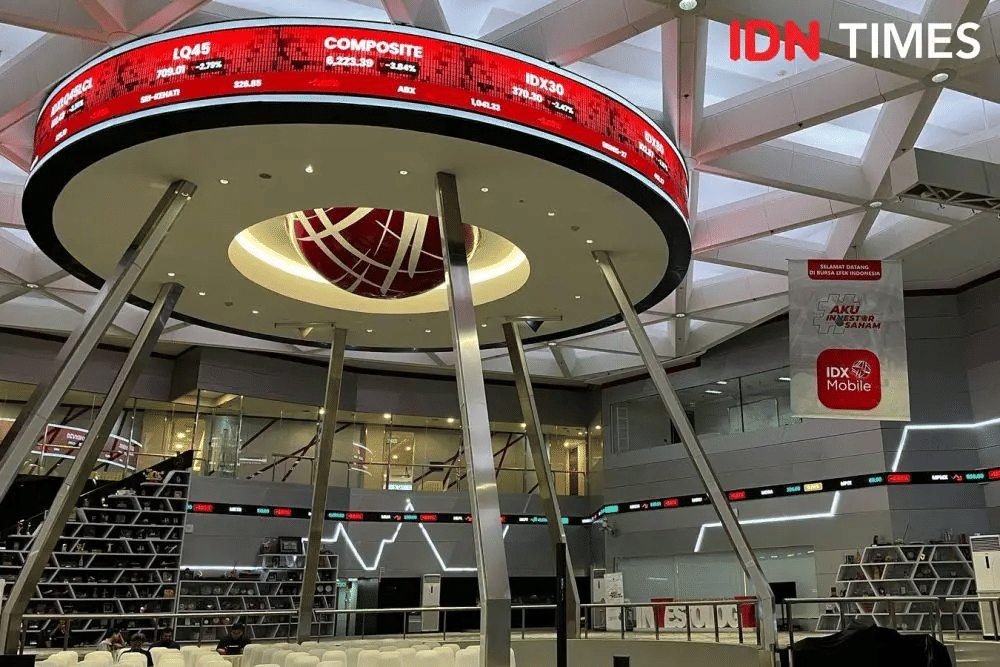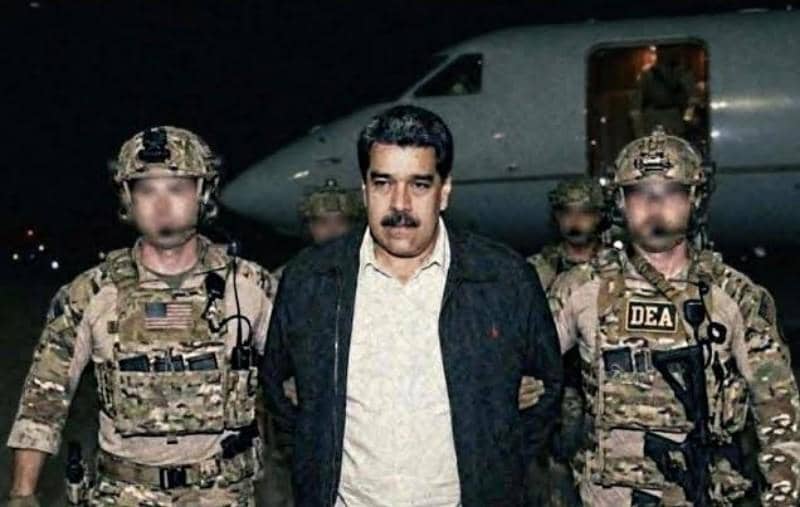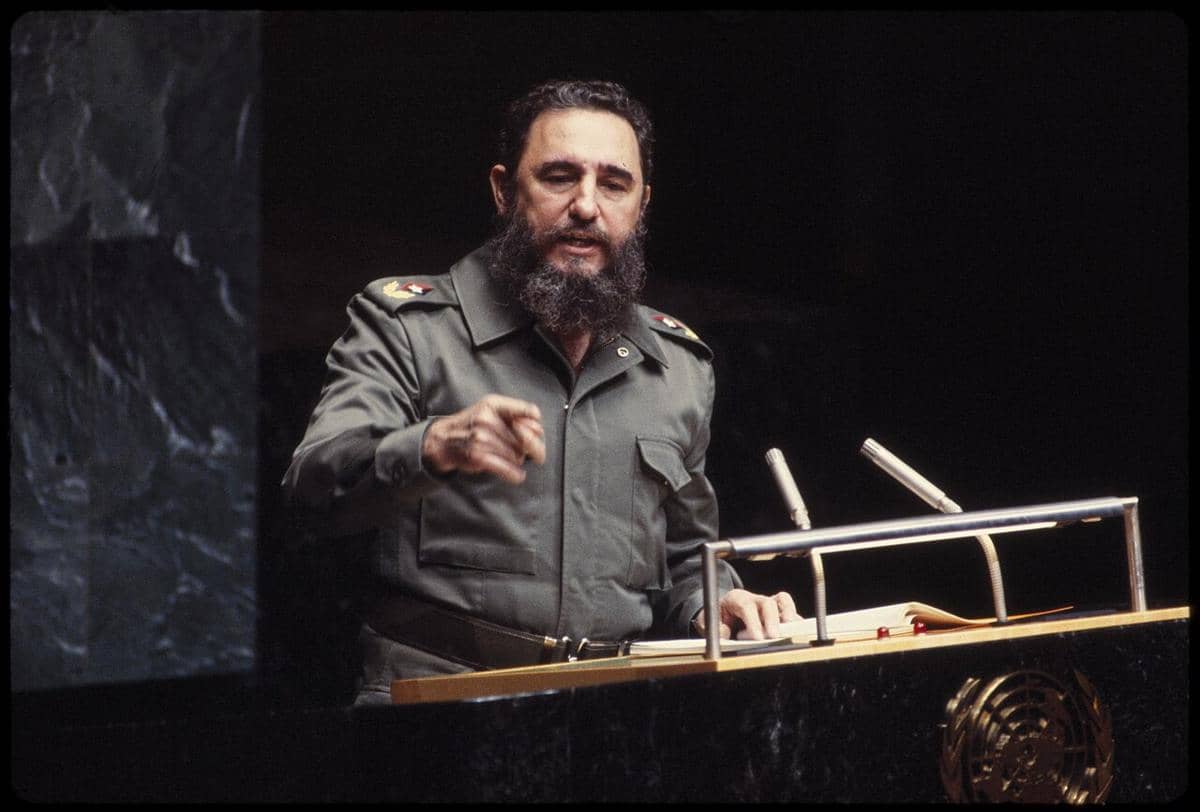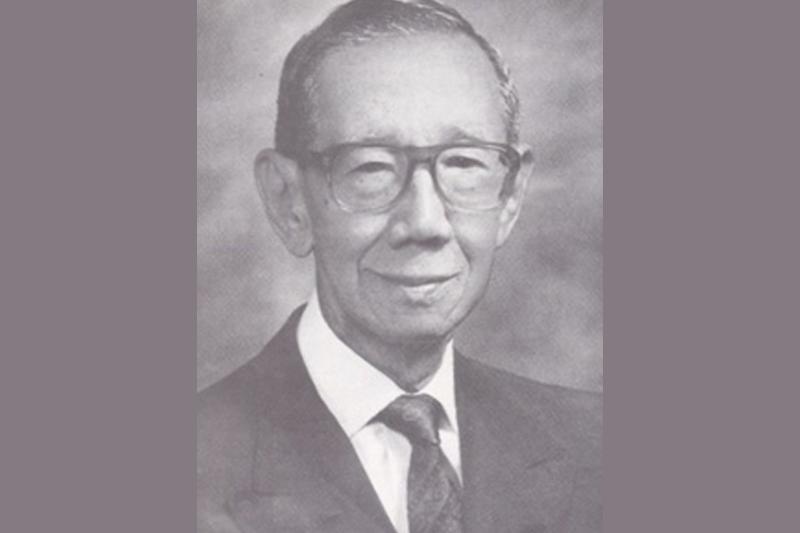[OPINI] Healing Ala Gen Z: Kebutuhan Emosional atau Sekadar Tren?

- Media sosial membentuk standar healing yang ideal, membuat tekanan FOMO dan menggeser makna healing.
- Healing bukan cuma soal liburan, tapi pemulihan diri; tidak selalu butuh biaya besar dan lebih tentang memberi jeda dari stres dan rutinitas.
- Gen Z lebih terbuka soal emosi, tapi mudah burnout; tekanan hidup datang dari berbagai arah, sering dijadikan pelarian cepat.
Kata "healing" sekarang sudah seperti mantra yang muncul di mana-mana. Entah itu staycation, nonton konser, nongkrong di coffee shop, sampai-sampai, sekadar beli es kopi susu, semuanya kini bisa diberi label “healing”. Budaya healing ala Gen Z memang menarik. Di satu sisi, ini menunjukkan generasi sekarang semakin sadar pentingnya kesehatan mental. Tapi di sisi lain, makna healing terasa makin sempit dan kadang kehilangan esensinya. Yuk, kita coba ulik lebih dalam fenomena ini, kapan healing benar-benar dibutuhkan, dan kapan cuma jadi gaya hidup kekinian.
1. Media sosial membentuk standar healing yang ideal

Di Instagram atau TikTok sering kali menggambarkan healing sebagai momen estetik nan mewah. Akibatnya, banyak yang berpikir kalau healing itu harus fancy biar sah. Padahal, setiap orang punya cara yang berbeda-beda buat merasa lebih baik. Sayangnya, tekanan FOMO membuat healing menjadi ajang pembuktian sosial, bukan kebutuhan diri. Ini yang membuat makna healing mulai bergeser.
2. Healing bukan cuma soal liburan, tapi pemulihan diri

Bagi para Gen Z, healing tidak melulu harus kabur ke Bali atau nginep di glamping estetik. Kadang, rebahan sambil nonton film favorit sudah cukup untuk menyegarkan pikiran. Intinya, healing lebih tentang memberi jeda dari stres dan rutinitas yang padat. Namun, beberapa orang masih menganggap healing sebagai aktivitas yang butuh biaya besar. Padahal, pemulihan mental tidak selalu harus mahal.
3. Gen Z lebih terbuka soal emosi, tapi mudah burnout

Generasi ini memang lebih berani terbuka soal perasaan. Mereka tidak sungkan bilang kalau sedang capek, butuh waktu sendiri, atau sekadar ingin istirahat. Kesadaran soal kesehatan mental memang semakin tinggi. Tapi di sisi lain, tekanan hidup datang dari berbagai arah, mulai tugas kuliah, pekerjaan, sampai ekspektasi sosial. Jadi, wajar saja kalau healing sering dijadikan pelarian cepat, meski efeknya kadang hanya sementara.
4. Tren healing juga dimanfaatkan jadi peluang bisnis

Fenomena healing kini sudah merambah ke dunia bisnis. Mulai dari tempat wisata, coffee shop, sampai produk skincare, semuanya berlomba-lomba menawarkan pengalaman “healing” yang katanya bisa bikin tenang. Di satu sisi, hal ini membantu orang semakin sadar pentingnya self-care. Namun di sisi lain, healing jadi terlihat seperti sesuatu yang harus dibeli, padahal esensinya tak selalu soal materi.
5. Ikut tren healing sah-sah saja, asal tahu batasnya

Healing bukan hal yang salah, apalagi jika memang dibutuhkan. Tapi kalau hanya demi tampil keren di media sosial, ada baiknya dipikirkan lagi. Tidak semua hal harus dibagikan ke publik, dan tidak semua healing harus terlihat sempurna. Yang terpenting, kamu tahu kapan perlu jeda dan apa yang benar-benar membuatmu pulih. Selama kamu jujur pada diri sendiri, cara healing apa pun bisa diterima.
Fenomena healing yang sedang populer di kalangan Gen Z sebenarnya menjadi tanda yang positif bahwa generasi ini semakin peduli pada kesehatan mental. Namun, penting untuk selalu ingat bahwa healing sebaiknya dilakukan dengan niat yang tulus dan dari hati, bukan sekadar ikut-ikutan tren. Kalau dilakukan dengan benar, proses healing bisa memberi dampak nyata dan membantu meningkatkan kesejahteraan pribadi.