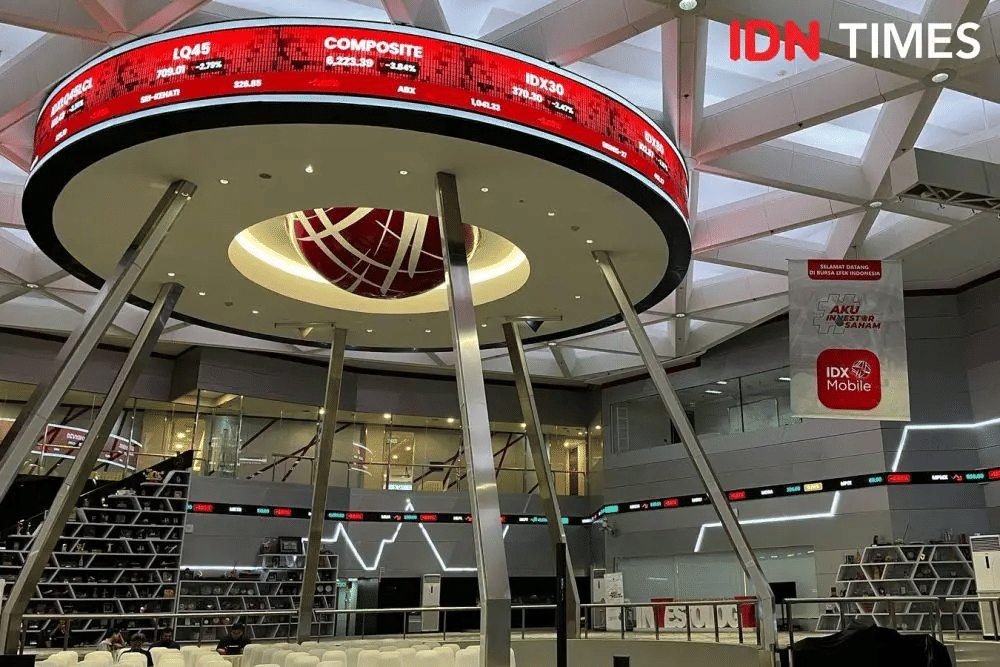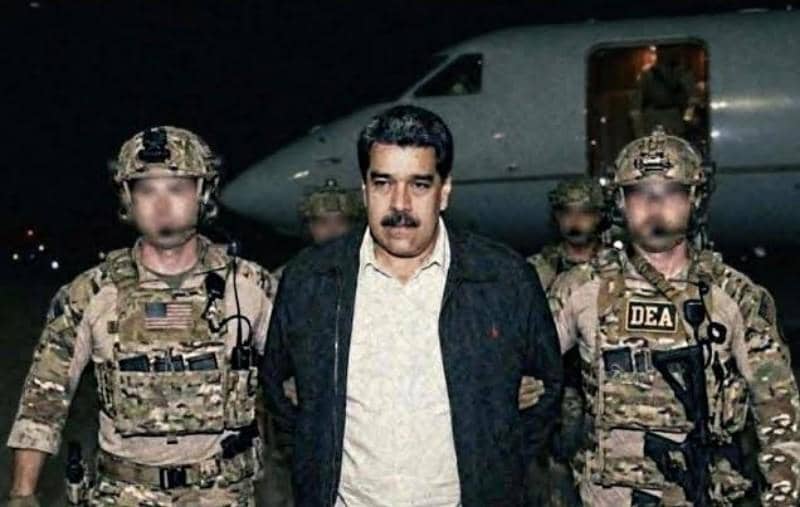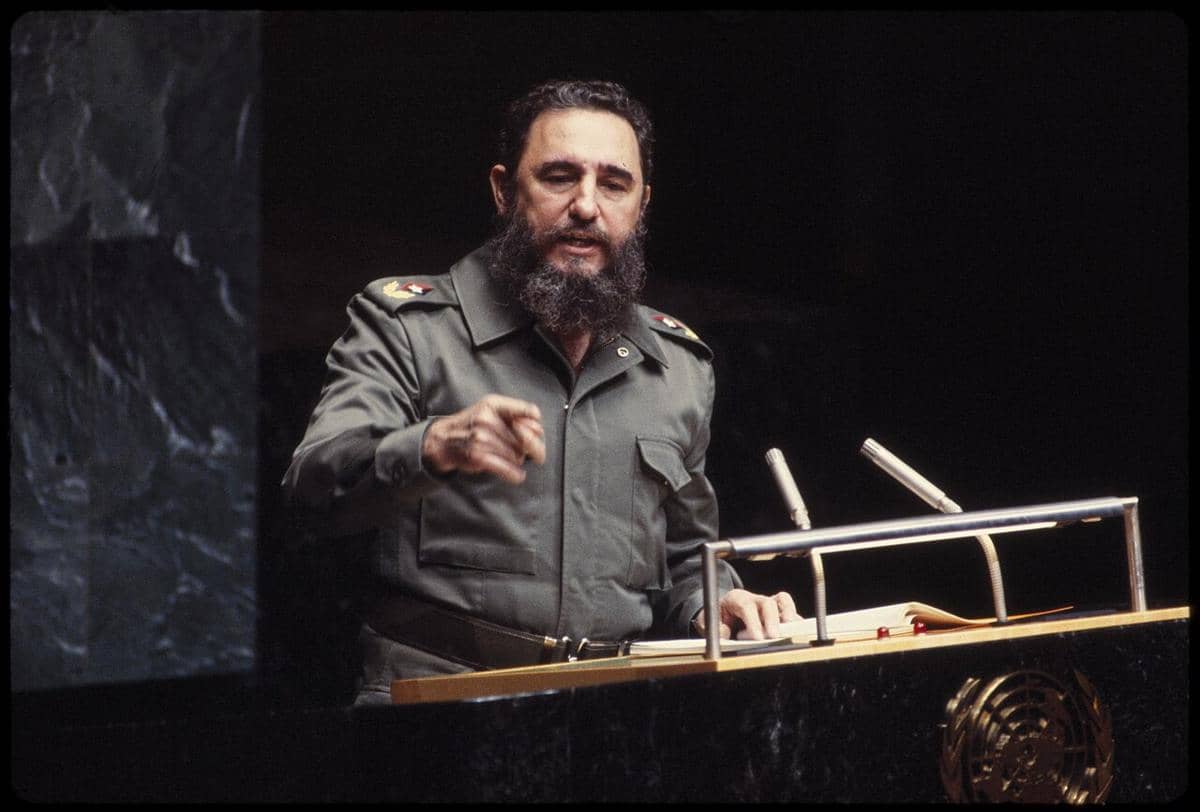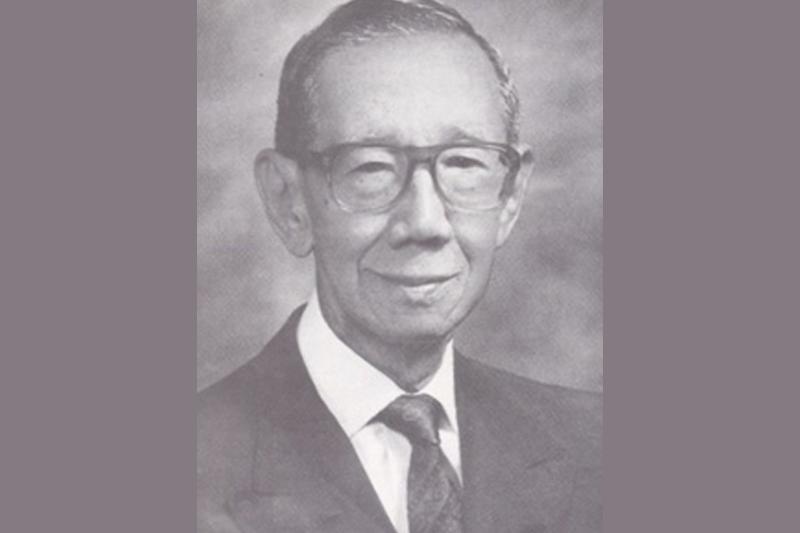[OPINI] Kenapa Masih Ada Orang Tone Deaf saat Negara sedang Kacau?

- Privilese membentuk distorsi pengalaman sosial
- Individualisme menjadi konsekuensi modernisasi ekonomi
- Media sosial mengonstruksi distraksi dan disonansi kognitif
Indonesia sedang menghadapi situasi negara yang jauh dari kata stabil. Skandal kekuasaan, kegagalan kebijakan, dan aparat yang semakin represif seharusnya cukup membuat publik bersatu melawan ketidakadilan yang pada akhirnya membuat rakyat resah dan turun ke jalan. Namun, di tengah kekacauan itu, masih ada orang tone deaf saat negara sedang kacau alias mereka memilih bersikap seolah tidak terjadi apa-apa.
Mereka sibuk dengan urusan pribadi, bahkan menganggap protes rakyat hanya sekadar gangguan lalu lintas. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan yang mengusik tentang bagaimana mungkin masih banyak orang tone deaf saat negara jelas-jelas sedang kacau? Berikut beberapa alasan yang dapat menjelaskan sikap tersebut.
1. Privilese membentuk distorsi pengalaman sosial

Teori Pierre Bourdieu tentang modal sosial dan modal ekonomi menjelaskan bagaimana privilese membentuk habitus seseorang. Orang dengan sumber daya ekonomi tinggi memiliki jaringan dan akses yang melindungi mereka dari risiko sosial. Maka tidak heran jika kenaikan harga, ketidakpastian kerja, atau pelayanan publik yang buruk hanya menjadi wacana jauh, bukan ancaman nyata.
Distorsi pengalaman ini membuat kelompok dengan privilese gagal memahami penderitaan mayoritas. Mereka hidup dalam ruang aman yang membentuk ilusi stabilitas, meskipun di luar sana rakyat berhadapan dengan kekacauan. Privilese tidak hanya melindungi tubuh, tetapi juga membius kesadaran. Dari sinilah lahir sikap tone deaf yakni sebuah ketidakmampuan melihat krisis sebagai sesuatu yang mendesak karena pengalaman hidup mereka tidak pernah disentuh langsung oleh krisis itu.
2. Individualisme menjadi konsekuensi modernisasi ekonomi

Modernisasi dan liberalisasi ekonomi di Indonesia sejak era 1990-an membawa dampak kultural yang kuat dengan lahirnya masyarakat individualistik. Logika “survival of the fittest” meresap ke dalam cara pandang sehari-hari masyarakat Indonesia. Keberhasilan dipandang sebagai capaian pribadi, sementara kegagalan dianggap kelemahan individu. Dalam kerangka ini, penderitaan kolektif cenderung didegradasi menjadi masalah personal.
Fenomena tone deaf kemudian berkembang sebagai implikasi logis dari individualisme. Jika orang melihat segala persoalan sebagai tanggung jawab pribadi, maka wajar bila mereka menilai demonstrasi atau kritik sosial sebagai “drama” yang tidak relevan. Padahal, masalah struktural di Indonesia seperti korupsi, ketidakadilan hukum, hingga represi politik di negara ini tidak bisa dipecahkan dengan solusi individual. Kegagalan memahami dimensi kolektif inilah yang melahirkan sikap abai di tengah krisis.
3. Media sosial mengonstruksi distraksi dan disonansi kognitif

Shoshana Zuboff dalam teorinya tentang surveillance capitalism pun telah menjelaskan tentang bagaimana algoritma media digital yang tidak netral. Platform media sosial memang dirancang untuk mempertahankan atensi pengguna selama mungkin dengan cara menyajikan konten yang paling menghibur, paling ringan, atau bahkan paling memicu sensasi. Dalam konteks krisis, algoritma semacam ini justru menyingkirkan berita-berita kritis dan menggantikannya dengan hiburan instan.
Akibatnya, lahir masyarakat yang hidup dalam disonansi kognitif. Mereka mengetahui ada masalah besar di luar sana, tetapi perhatian mereka terus diarahkan pada hal-hal trivial. Orang lebih mengingat perdebatan selebritas ketimbang nama korban yang tewas di jalanan saat demonstrasi. Distraksi digital inilah yang memperkuat tone deaf yakni sebuah sikap “tahu tapi pura-pura tidak tahu” karena lebih nyaman menenggelamkan diri dalam hiburan.
4. Hegemoni narasi politik mengendalikan kesadaran publik

Antonio Gramsci menyebut konsep hegemoni untuk menjelaskan bagaimana kekuasaan bertahan bukan hanya melalui represi, tetapi juga melalui pengendalian narasi. Di Indonesia, hal ini tampak jelas ketika pejabat publik menyederhanakan keresahan rakyat menjadi sekadar “kegaduhan”, atau menjustifikasi tindakan represif dengan dalih stabilitas nasional. Narasi seperti ini bukan sekadar retorika, tetapi instrumen untuk membentuk persepsi masyarakat.
Orang-orang di Indonesia yang memilih menjadi tone deaf kerap menjadi corong pasif dari narasi hegemoni ini. Mereka meniru pernyataan elite tanpa mempertanyakan validitasnya. Bahkan ketika data dan fakta di lapangan jelas menunjukkan kebalikannya, narasi kekuasaan tetap lebih dipercaya. Hegemoni berhasil menumpulkan daya kritis, sehingga banyak orang merasa nyaman hidup dalam ilusi bahwa semua terkendali.
5. Politik ketakutan melahirkan budaya diam

Michel Foucault menekankan bagaimana kekuasaan bekerja bukan hanya dengan hukuman fisik, tetapi juga melalui disiplin yang membatasi ruang bicara. Di Indonesia, politik ketakutan ini hadir dalam berbagai bentuk ancaman hukum bagi pengkritik pemerintah, stigma terhadap aktivis, hingga tekanan sosial di lingkungan kerja. Ketakutan membuat orang memilih diam, dan lama-lama diam berubah menjadi sikap abai.
Budaya diam ini kemudian menormalisasi tone deaf. Banyak orang lebih memilih aman ketimbang kritis, bahkan ketika hak-hak dasar dilanggar. Ketakutan membuat solidaritas melemah, dan melemahnya solidaritas membuka jalan bagi penguasa untuk bertindak sewenang-wenang. Dalam jangka panjang, tone deaf bukan sekadar masalah moral, tetapi ancaman serius bagi demokrasi di Indonesia itu sendiri.
Apa yang terjadi di Indonesia hari ini jelas memperlihatkan jurang yang begitu dalam antara mereka yang peduli dan mereka yang memilih zona nyaman dengan menjadi tone deaf. Menjadi orang tone deaf saat negara sedang kacau bukanlah sikap netral, tetapi bentuk keberpihakan pada status quo yang menindas. Selama masih banyak orang yang nyaman dalam privilese dan pura-pura 'tuli', krisis akan terus berulang, dan korban baru akan terus berjatuhan tanpa pernah ada perubahan nyata.
Referensi:
""Bourdieu on social capital – theory of capital". Tristan Claridge. Diakses pada Agustus 2025.
"Cultural Capital Theory Of Pierre Bourdieu". Simply Psychology. Diakses pada Agustus 2025.
"Survival of the fittest". Britannica. Diakses pada Agustus 2025.
"Shoshana Zuboff: ‘Surveillance capitalism is an assault on human autonomy’". The Guardian. Diakses pada Agustus 2025.
"Gramsci and the Theory of Hegemony" Bates, Thomas R. Diakses pada Agustus 2025
"Foucault's theory of power" Lynch, Richard A. Diakses pada Agustus 2025