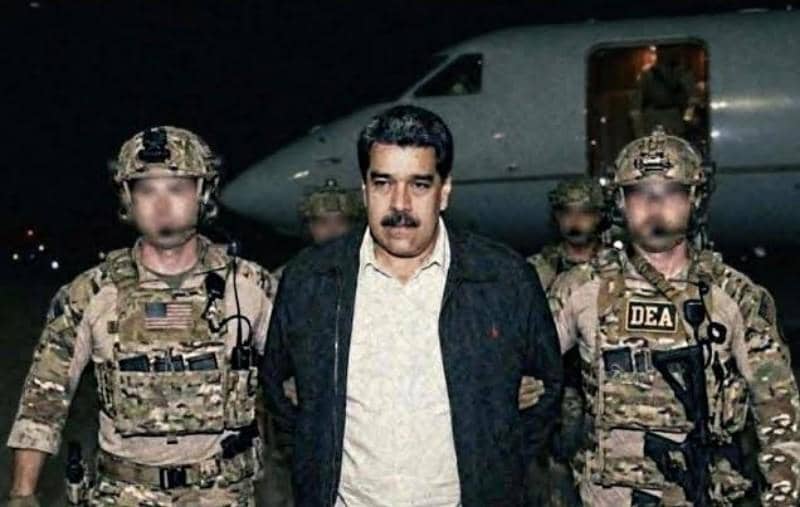Mengapa Topik Kesetaraan Gender yang Dibahas Laki-Laki Selalu Sama?

- Laki-laki memahami gender dari perspektif perbandingan fisik
- Pendidikan gender jarang menyentuh pembahasaan laki-laki sejak dini
- Norma sosial membentuk persepsi maskulinitas yang tidak fleksibel
Kesetaraan gender masih sering dipahami secara sempit, terutama ketika laki-laki ikut serta dalam membahasnya. Bukan berarti kontribusi mereka tidak penting, hanya saja topik yang diangkat sering kali terbatas pada persoalan fisik atau peran rumah tangga, seolah-olah inti dari kesetaraan hanya berkutat pada hal-hal itu saja. Ketika perempuan bicara soal hak reproduksi, kekerasan seksual, atau kemandirian ekonomi, tanggapannya sering direspons dengan pertanyaan sinis yang tidak relevan, bahkan terkesan mengalihkan fokus dari isu utama.
Diskursus publik di media sosial memperlihatkan kecenderungan laki-laki untuk mereduksi kesetaraan gender menjadi bahan candaan atau tantangan fisik. Padahal, wacana kesetaraan tidak sekadar soal siapa kuat dan siapa lemah, tapi bagaimana semua orang bisa hidup adil tanpa terkekang peran tradisional yang membatasi pilihan. Untuk memahami kenapa topik yang mereka bahas cenderung stagnan, perlu dilihat lebih jauh dari sisi pendidikan, budaya populer, sampai pengaruh norma sosial yang membentuk cara pandang tersebut. Berikut lima hal yang bisa menjelaskan mengapa pembahasan laki-laki tentang kesetaraan gender sering kali berputar di tempat yang sama.
1. Laki-laki memahami gender dari perspektif perbandingan fisik

Banyak laki-laki mengenal isu kesetaraan gender lewat perbandingan yang bersifat fisik. Contohnya, ketika perempuan menuntut kesetaraan, respons yang muncul sering berupa pertanyaan seperti “berarti angkat galon sendiri dong?” atau “boleh dong kami mukul balik?” Seolah-olah inti dari kesetaraan hanya soal siapa yang lebih kuat, bukan soal akses, hak, atau tanggung jawab sosial yang setara.
Pendekatan ini muncul karena mereka dibesarkan dalam pola pikir kompetitif, bukan kolaboratif. Kesetaraan dipahami sebagai ajang pembuktian bahwa dua pihak harus bisa melakukan hal yang sama dalam bentuk dan intensitas yang identik. Padahal, kesetaraan itu soal akses yang adil, bukan hasil yang sama. Sayangnya, ketika pendekatan yang digunakan adalah fisik, maka diskusinya pun akan selalu berhenti pada soal tenaga dan kerja kasar.
2. Pendidikan gender jarang sekali menyentuh pembahasaan laki-laki sejak dini

Pendidikan soal kesetaraan gender lebih banyak ditujukan pada perempuan, seolah mereka yang harus paham dan sadar lebih dulu. Akibatnya, laki-laki tumbuh tanpa pemahaman yang utuh tentang makna kesetaraan yang sebenarnya. Mereka tahu tentang feminisme, tapi hanya di permukaan sebab hal yang banyak terdengar hanya potongan-potongan narasi dari media sosial tanpa konteks lengkap.
Saat laki-laki tidak dilibatkan sejak dini dalam diskusi yang sehat dan mendalam tentang gender, maka wajar jika saat dewasa mereka hanya bisa merespons dari sudut pandang terbatas. Mereka tidak tahu bagaimana kesenjangan gender memengaruhi pendidikan, pekerjaan, atau perlindungan hukum perempuan. Akibatnya, ketika ikut bersuara, pembahasannya pun mentok di wilayah yang dangkal dan sering kali salah arah.
3. Norma sosial membentuk persepsi maskulinitas yang tidak fleksibel

Dalam banyak budaya di dunia, laki-laki selalu diharapkan untuk tampil kuat, logis, dan juga dominan. Konsep maskulinitas ini membuat mereka sulit menerima narasi yang memberi ruang pada kerentanan, empati, atau kerja sama lintas gender. Ketika perempuan menuntut haknya, laki-laki yang memegang norma maskulin kaku akan merasa seolah-olah sedang kehilangan wilayah kekuasaan.
Karena tekanan untuk selalu tampil kuat, mereka cenderung menyederhanakan isu kesetaraan menjadi tantangan, bukan kolaborasi. Diskusi yang harusnya membuka ruang bagi pemahaman, malah berubah jadi adu argumen soal “siapa lebih berat bebannya”. Norma sosial semacam ini perlu dibongkar perlahan agar laki-laki bisa melihat bahwa kesetaraan gender tidak mengancam identitas mereka, tapi justru membebaskan mereka dari beban peran tradisional.
4. Media populer sering mempromosikan stereotip kesetaraan gender yang salah

Televisi, film, dan konten digital punya peran besar dalam membentuk cara berpikir masyarakat, termasuk tentang gender. Sayangnya, representasi laki-laki dalam media populer juga masih banyak sekali yang masih mempertahankan stereotip lama. Laki-laki digambarkan sebagai pencari nafkah utama, pengambil keputusan, dan jarang menunjukkan emosi. Sementara perempuan diperlihatkan sebagai pengurus rumah atau pelengkap cerita.
Ketika laki-laki melihat representasi semacam ini terus-menerus, mereka tumbuh dengan bayangan bahwa struktur sosial saat ini sudah adil, karena sesuai dengan gambaran media. Maka tak heran jika mereka bingung ketika mendengar tuntutan kesetaraan. Media tidak hanya membentuk ekspektasi publik, tapi juga membatasi cakupan pemahaman laki-laki tentang bagaimana relasi gender bisa lebih adil dan manusiawi.
5. Ruang aman diskusi gender masih terlalu terbatas bagi laki-laki

Tidak semua laki-laki nyaman untuk ikut serta dalam diskusi tentang kesetaraan gender karena takut salah ucap, dikritik, atau dianggap tidak cukup paham. Akibatnya, mereka hanya berani berbicara di ruang-ruang yang tidak kritis, yang justru memperkuat miskonsepsi. Lingkungan yang tidak memberi ruang belajar dan bertanya tanpa takut dihakimi membuat laki-laki terjebak dalam pemahaman yang keliru tapi tetap mereka anggap benar.
Supaya laki-laki bisa ikut berbicara dengan cara yang konstruktif, dibutuhkan ruang yang bisa menampung kesalahan sekaligus membimbing mereka memahami lebih dalam. Edukasi tidak cukup berhenti di poster kampanye atau seminar sehari. Butuh pembiasaan, diskusi yang jujur, dan kurikulum pendidikan yang menyentuh akar persoalan gender secara adil. Ketika ruang aman dibuka, pembahasan laki-laki tentang kesetaraan tidak akan lagi itu-itu saja.
Kesetaraan gender tidak akan bisa dicapai jika hanya dibahas sepihak, tapi juga tidak akan berkembang kalau diskusinya stagnan. Laki-laki punya peran penting dalam menyuarakan isu ini, tapi perlu pemahaman yang lebih luas dari sekadar perbandingan fisik dan peran rumah tangga. Untuk bisa benar-benar setara, semua pihak perlu belajar ulang, membuka ruang bicara, dan mendengarkan lebih dalam tanpa defensif.