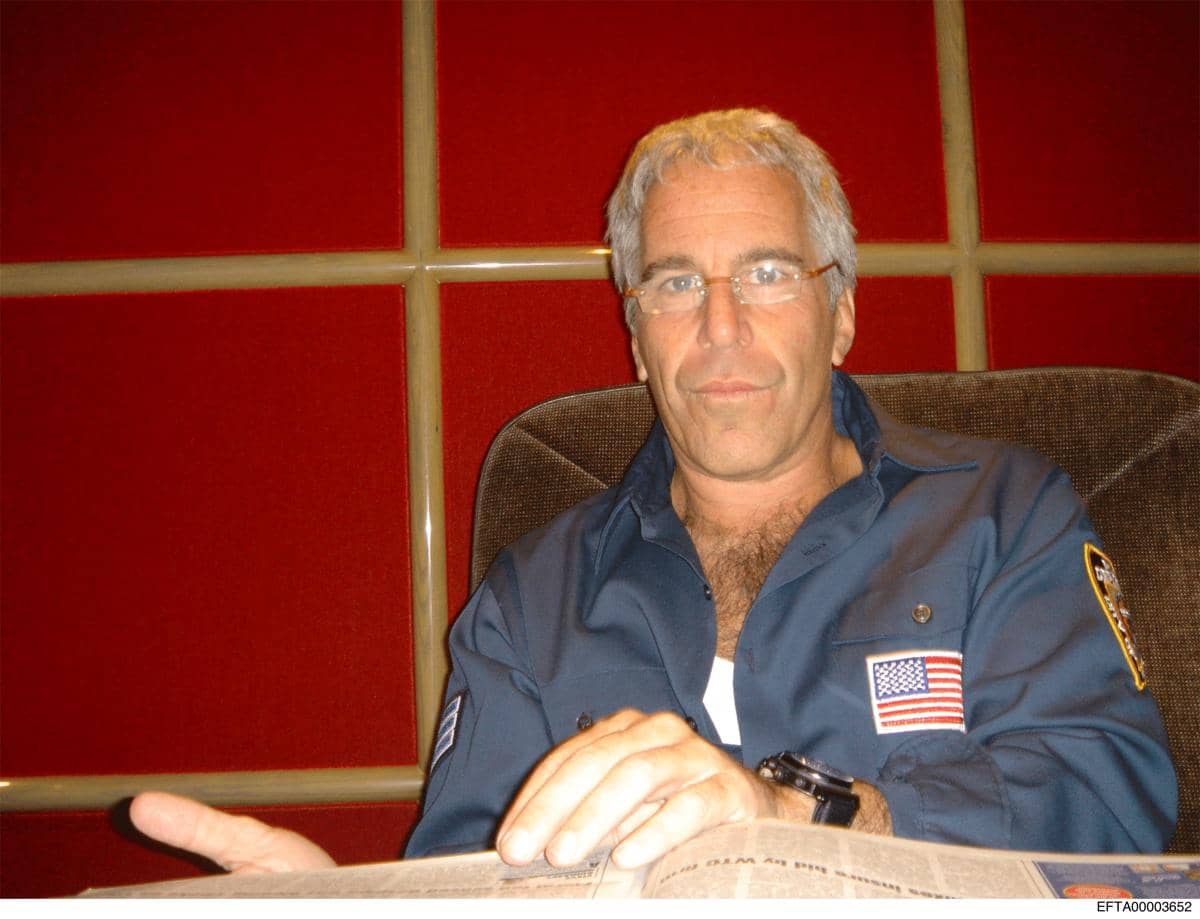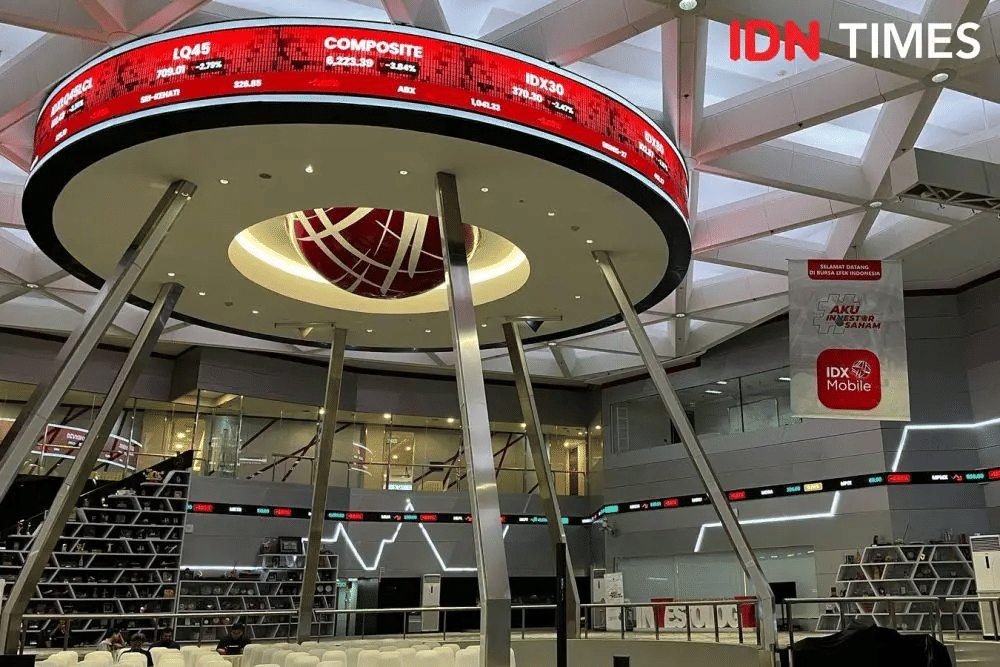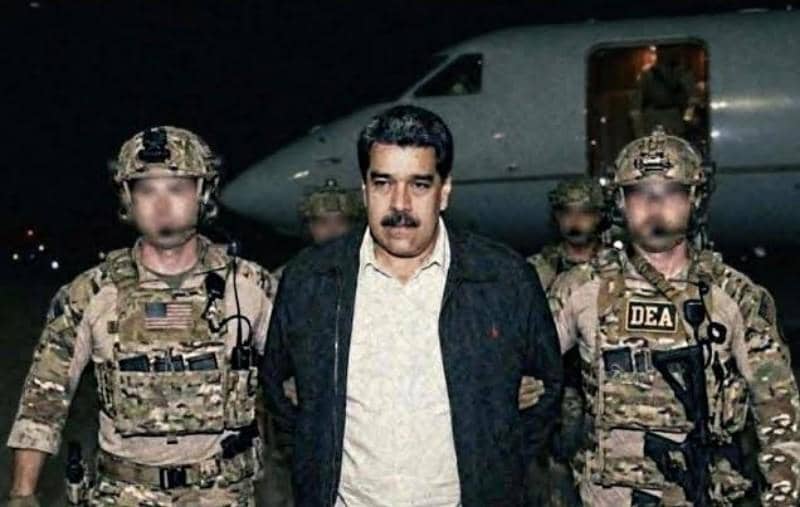[OPINI] Minimalisme: Gaya Hidup atau Sekadar Pelarian?

Ketika promosi belanja hadir hampir setiap hari, iklan digital menghantui layar, dan media sosial penuh dengan gaya hidup glamor, justru muncul tren baru yang seolah berseberangan: gaya hidup minimalis. Esensinya sangat sederhana memiliki lebih sedikit barang, mengurangi distraksi, namun meraih kehidupan yang lebih bermakna. Tapi pertanyaannya, apakah ini sekadar gaya hidup kekinian yang tampak estetis di Instagram, atau benar-benar menjadi alternatif hidup yang patut dijalani di era serba konsumtif seperti sekarang?
Ketertarikan pada konsep minimalisme mulai tumbuh sejak pandemi melanda. Ketika aktivitas di luar terbatas, muncul banyak waktu untuk merenung: begitu banyak barang di rumah yang ternyata tidak pernah digunakan. Lemari penuh pakaian yang jarang dipakai, buku-buku yang hanya jadi pajangan, hingga kosmetik yang sudah kedaluwarsa. Semua itu menimbulkan pertanyaan: apakah selama ini belanja dilakukan karena kebutuhan, atau hanya ikut-ikutan?
Gaya hidup konsumtif sudah mengakar dalam masyarakat. Sering kali muncul dorongan untuk membeli sesuatu agar terlihat relevan, sukses, atau bahagia. Padahal, kebahagiaan dari barang-barang itu seringkali hanya sesaat. Di sinilah minimalisme hadir sebagai alternatif: hidup dengan kesadaran bahwa “cukup” bisa jauh lebih membahagiakan daripada berlebihan.
Meski begitu, menjalani hidup minimalis bukan tanpa tantangan. Di tengah masyarakat yang gemar memamerkan kemewahan, hidup sederhana bisa dianggap “tidak keren”. Tekanan sosial membuat banyak orang merasa tertinggal jika tidak mengikuti tren terbaru baik dalam urusan gadget, fashion, maupun gaya hidup.
Namun, tren minimalisme kini justru mulai mendapat tempat, terutama di kalangan generasi muda perkotaan. Banyak kreator digital berbagi tentang cara merapikan rumah dengan metode Marie Kondo, membuat lemari kapsul, hingga menerapkan gaya hidup bebas sampah. Mereka menunjukkan bahwa minimalisme bukan soal kekurangan, tapi tentang hidup dengan pilihan yang lebih sadar dan bermakna.
Gaya hidup ini juga menjadi bentuk perlawanan terhadap pola konsumsi berlebihan yang merusak lingkungan. Dengan mengurangi pembelian, secara otomatis limbah, polusi, dan eksploitasi alam juga berkurang. Dampaknya sangat luas: pengeluaran lebih terkontrol, ruang tinggal lebih rapi, pikiran lebih tenang, dan lingkungan menjadi lebih terjaga.
Namun penting untuk memahami bahwa minimalisme bukan berarti hidup dalam kekurangan dan membuang semua yang dimiliki. Ini bukan soal asketisme. Minimalisme sejatinya adalah seni membuat pilihan secara sadar memilah mana yang esensial dan mana yang bisa dilepaskan. Menikmati teknologi, fashion, atau liburan tetap mungkin dilakukan, selama tidak dijadikan tolok ukur kebahagiaan.
Setiap orang punya definisi yang berbeda soal hidup minimalis. Tak perlu membatasi diri hanya dengan 30 barang seperti ekstremis minimalis di luar negeri. Bagi ibu rumah tangga, bisa berarti lebih sering memasak sendiri daripada membeli makanan di luar. Bagi mahasiswa, bisa berarti lebih bijak dalam membeli barang dan lebih fokus pada pengalaman yang bernilai.
Di tengah dunia yang semakin bising oleh informasi dan ajakan untuk terus membeli, gaya hidup minimalis menawarkan ruang untuk hening dan refleksi. Gaya hidup ini membantu menyadari perbedaan antara keinginan dan kebutuhan, antara pencitraan dan kejujuran. Minimalisme bukan sekadar tren sesaat. Ia merupakan respons dari kelelahan kolektif akibat hidup yang dipenuhi oleh tuntutan materi. Semakin banyak orang yang menyadari hal ini, semakin besar peluang untuk membangun kehidupan yang lebih berkelanjutan baik untuk diri sendiri maupun untuk bumi yang menjadi rumah bersama.