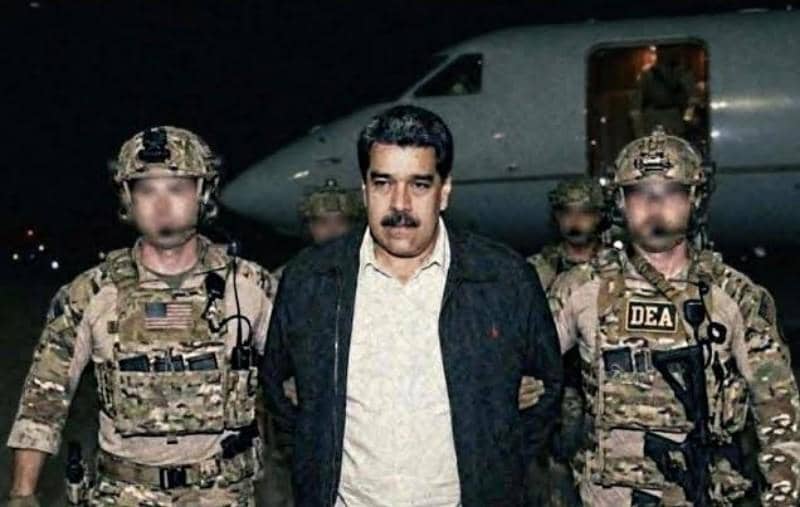[OPINI] Rio Haryanto dan Mental Inlander

JIKA tak salah ingat akhir 1986, saya pertama kali masuk bioskop dan menonton bersama bapak. Judul filmnya Doea Tanda Mata, dibintangi Alex Komang dan Yenny Rahman, aktor dan aktris yang pada waktu itu, setidaknya menurut bapak saya, selain paling terkenal juga paling berwatak mainnya.
Film ini sebenarnya untuk dewasa, 17 tahun ke atas sebagaimana tertera pada posternya. Tapi saya tetap bisa masuk. Harap maklum sajalah, namanya juga bioskop pinggiran. Terletak di Praya, ibukota Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Selain perkara aturan yang sungguh longgar, film-film yang diputar di sini pun rata-rata merupakan produksi tahun sebelumnya, bahkan dua atau tiga tahun sebelumnya, meski saat diumumkan keliling kota dan kampung dengan pengeras suara yang dipasang di atap cidomo (sejenis andong atau cikar) dan pikap colt diesel, tetap saja disebut sebagai film baru.
Dari film inilah untuk kali pertama pula saya mendapati kalimat, yang walau cuma terlihat sekilas, kemudian mendekam lama dalam ingatan: “anjing dan inlander dilarang masoek!”
Verboden vor Honden en Inlander, omong londonya. Kata bapak saya, kalimat ini adalah penghinaan luar biasa. Bangsa kita, kok, disamakan dengan anjing. Terlalu, kata beliau menirukan Haji Oma.
Sampai lama setelah hari itu saya terus terpengaruh oleh kegeraman bapak, dan bertekad akan senantiasa menempatkan kompeni sebagai musuh terbesar keempat setelah iblis laknatullah, Abu Jahal, dan Abu Lahab.
Saya pernah menangis dan merasa sangat terpukul dan tidak bisa tidur siang selama tak kurang satu pekan setelah pada partai final Piala Eropa 1988, Belanda menang atas Uni Soviet.
Sesungguhnya ini pilihan yang sama-sama tidak menyenangkan. Yang satu kompeni yang satu komunis. Jika pun kemudian saya memilih condong ke Uni Soviet, percayalah, itu semata-mata lantaran pertimbangan komunis tidak pernah menyetarakan bangsa ini dengan anjing. Mereka, konon, cuma memberontak.
Kebencian pada kompeni baru agak surut saat saya duduk di bangku SMA, tepatnya, ketika satu hari tanpa sengaja saya bertemu Pramoedya Ananta Toer. Tentu saja bukan pertemuan fisik. Saat itu saya sudah pindah ke Lubukpakam, satu kota kecil di Sumatera Utara, sedangkan Pram masih terkurung nun jauh di Pulau Buru.
Saya bertemu Pram lewat “Bumi Manusia”, satu di antara tetraloginya yang melegenda. Saya begitu takjub melihat tetangga saya, seorang mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara, membaca buku berjudul Ilmu Taksonomi dengan amat tekunnya. Apakah isi buku itu memang sedemikian menarik?
Ternyata, dia tidak membaca Ilmu Taksonomi. Buku ini hanya dia pinjam sampulnya, untuk menyamarkan buku Pram yang dinyatakan terlarang oleh rezim Orde Baru.
Paparan-paparan Pram sesungguhnya tak terlalu banyak mengubah pandangan saya terhadap kompeni. Toh, Pram juga tidak memaksudkan demikian. Tahun 1990 di Italia, saat Marco Van Basten, Ruud Gullit, dan Frank Rijkaard tampil loyo dan Belanda kehilangan ketajaman sampai akhirnya terhenti di babak perdelapan final Piala Dunia usai digilas Jerman Barat (1-2), saya girang bukan kepalang.
Namun di lain sisi saya mulai paham bahwa sebutan inlander, terutama dalam kalimat Verboden vor Honden en Inlander, bukan sepenuhnya merupakan bentuk keangkuhan mereka sebagai kolonialis yang lalim, rasis, dan merasa memiliki derajat lebih tinggi sebagai manusia. Pada Pasal 131 dan Pasal 163 Indsiche Staatsregeling (I.S.), Pemerintah Kolonial memang membagi golongan masyarakat di Hindia Belanda menjadi tiga strata dan pribumi menempati peringkat terbawah. Di atasnya adalah kelompok orang-orang Eropa diikuti kelompok Timur Asing yang terdiri dari China, Arab, dan lainnya. Meski demikian, doktrinisasi ini saya kira tidak akan berjalan apabila pada diri tidak ada bibit-bibit inferioritas. Bibit pecundang: tak pernah yakin pada kemampuan, pesimistis, rendah diri, lebih suka jadi kacung.
Sekarang kita sudah merdeka. Pram telah wafat dan tak ada lagi mahasiswa yang mau repot-repot membaca bukunya dengan terlebih dahulu mengganti sampulnya dengan sampul buku Ilmu Taksonomi. Buku-buku Pram kini dicetak ulang dan dijual bebas, dipajang di rak mengkilap di toko-toko buku yang sejuk dan berbau harum. Media-media sosial semacam Facebook, Twitter, Path, dan Instagram, mencatat negeri ini sebagai pasar terbesar mereka. Dan saat ini, boleh dikata sudah hampir tak ada yang menyebut nama Belanda dengan disertai rasa benci. Beberapa tahun terakhir, mereka bahkan jadi olok-olok yang kelewat riang berkat jasa seorang lelaki uzur berwajah sombong bernama Louis van Gaal.
Akan tetapi, setelah sekian lama, ternyata, ada yang tak berubah sama sekali. Mental inlander tadi. Setelah sekian lama, kita, atau lebih persisnya sebagian besar kita, masih juga tak yakin pada kemampuan, masih pesimistis, rendah diri, dan lebih suka jadi kacung.
Bagaimana bangsa ini menyikapi keberadaan Rio Haryanto di lintasan Formula One, menjadi representasi sahih mental itu.
Siapalah Rio dibanding Lewis Hamilton, memang, sudah pasti kalah. Maka alangkah sia-sianya dana milaran yang digelontorkan untuk dirinya. Jika dibelikan beras bisa untuk makan orang berapa kampung? Berapa banyak anak putus sekolah yang bisa sekolah lagi? Berapa banyak orang sakit yang tak perlu menderita lantaran harus bergantung pada BPJS?
Maka Rio Haryanto pun dihantam dengan perisakan-perisakan yang dahsyat. Bukan cuma Rio. Pemerintah Indonesia dan pihak-pihak lain yang membantu dan mendukung kiprahnya juga ikut diserang. Ribut-ribut yang makin kencang dari seri ke seri balapan ini baru berhenti setelah Manor Racing memutuskan mendepak Rio Haryanto dari kursi tunggal jet darat itu pada pertengahan musim.
Ajaibnya, pendepakan justru disambut dengan suka cita yang gegap gempita. Di kolom komentar beberapa media dalam jaringan (daring) yang memuat berita pendepakan Rio, banyak yang menuliskan bahwa Formula One memang belum pantas bagi orang Indonesia. Itu olahraga yang terlalu mewah dan eksklusif. Terlalu tinggi dan terlalu mahal dan karenanya tak terjangkau. Jangan memaksakan diri kalau memang tak mampu. Maka kembalilah ke kampung, Rio, tulis mereka, lomba balap karung saja.
Reaksi serupa belakangan muncul lagi pascamencuat kabar bahwa Rio Haryanto berpeluang kembali ke lintasan Formula One di musim 2018. Meski belum ada kepastian, serangan sudah gencar dilancarkan. Dan lagi-lagi, tolok ukur ketidaksepakatan tak jauh-jauh dari asumsi bahwa Indonesia terlalu miskin dan terlalu ndeso untuk berada di lingkungan balapan paling gemerlap di kolong jagat tersebut.
Betapa menyedihkan! Betapa ketika dunia telah bergerak jauh di abad millenials, kita masih betah menjadi kaum inlander, yang makin ke sini makin menyedihkan karena meski nyinyir dan pemarah ternyata tetap saja pesimistis dan minderan, yang sudah merasa cukup puas dengan idola sekelas Young Lex, Awkarin, dan Ayu Ting Ting.