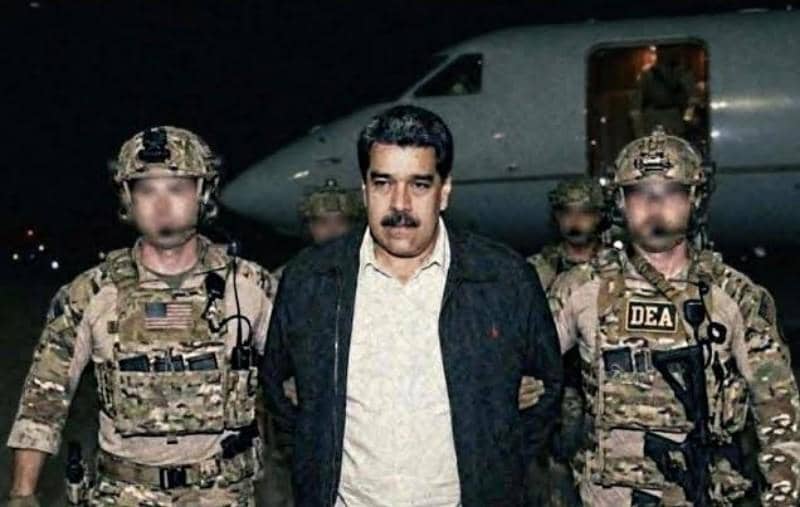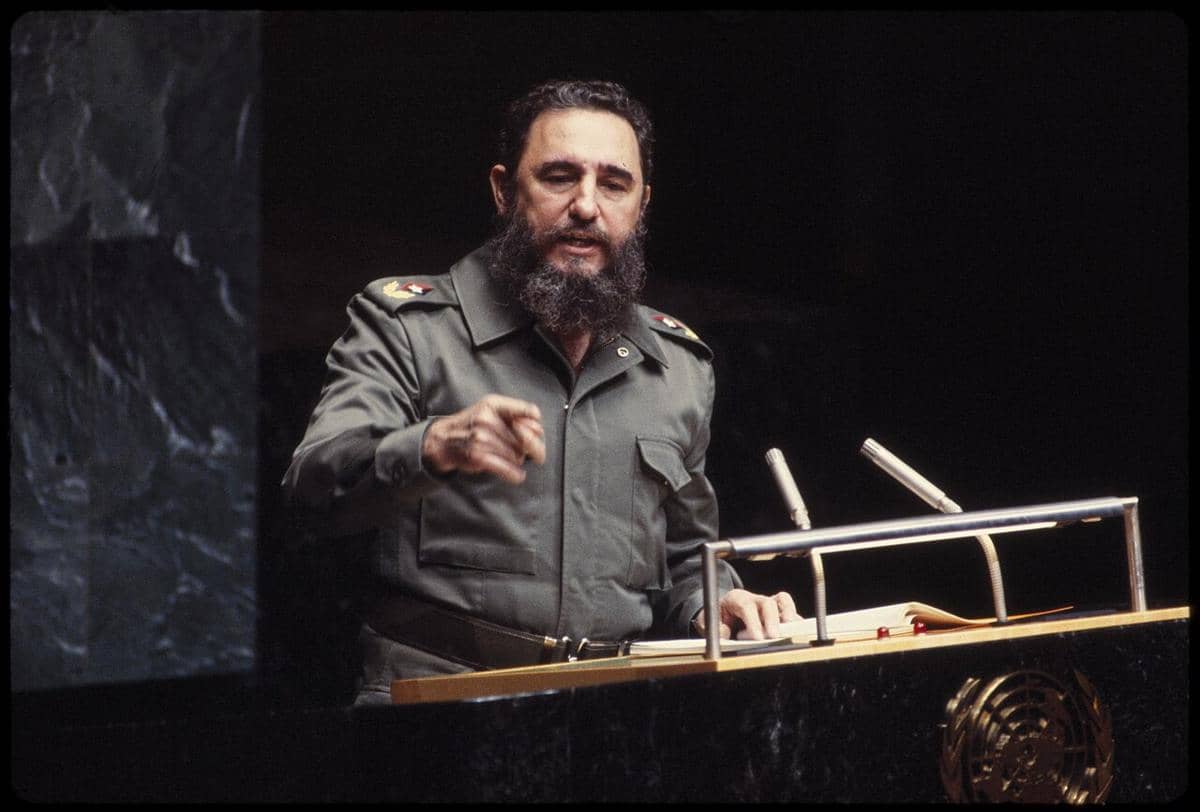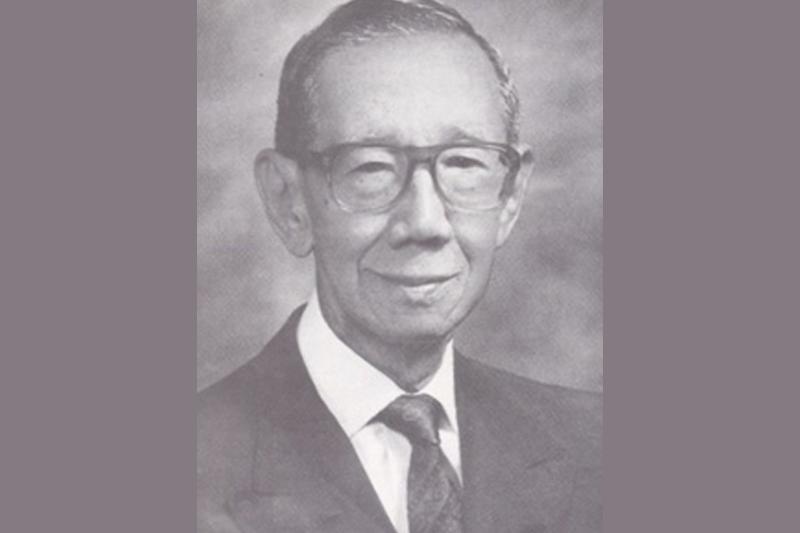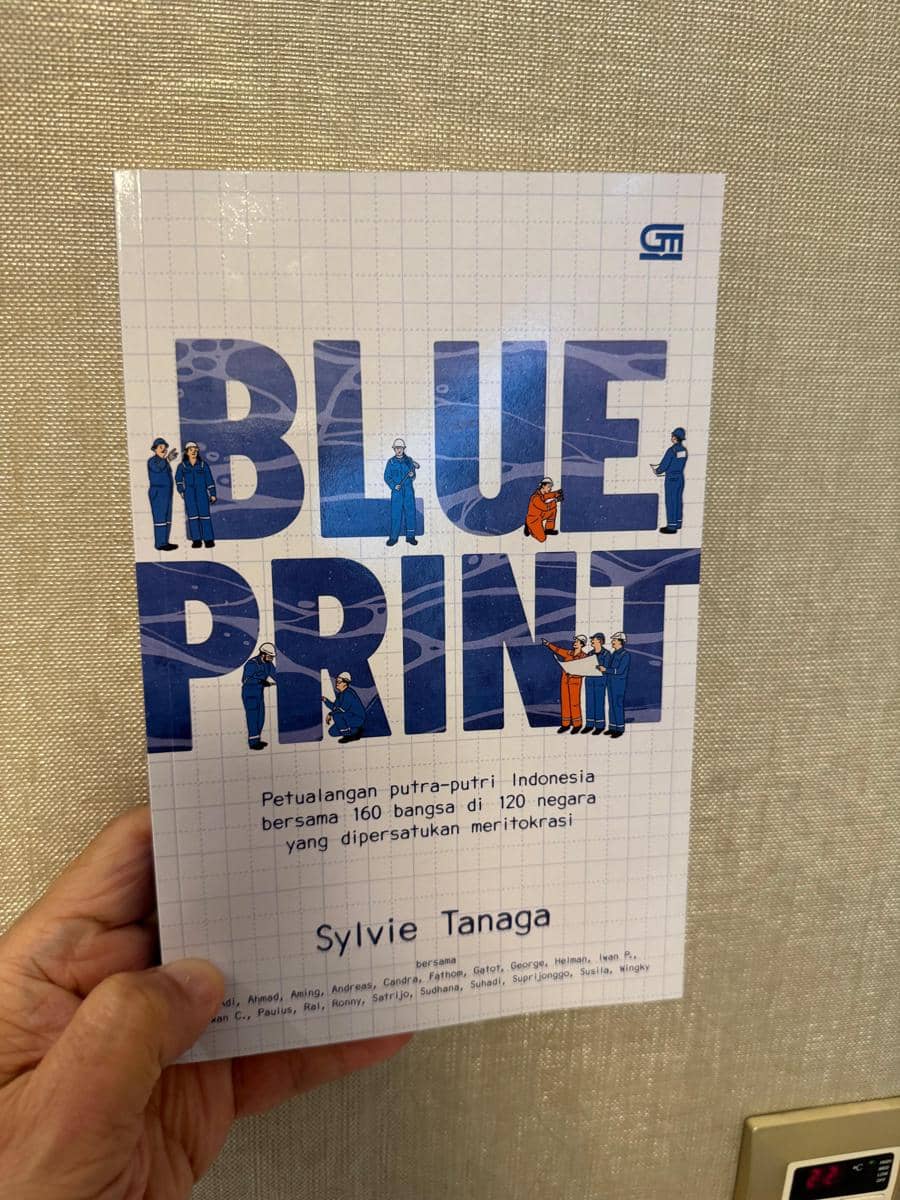[OPINI] Natalius Pigai yang Absen di Jam Tergelap

- Indonesia kembali belajar alfabet krisis: aksi, bentrok, cedera, dan kematian.
- Komnas HAM mencatat pola mengkhawatirkan dalam penanganan massa di Jakarta.
- Natalius Pigai absen dalam penanganan tragedi, menimbulkan kebutuhan akan standar penanganan yang mencegah tragedi itu sejak awal.
Di jalanan yang berbau gas air mata, suara sirene bersahutan dengan teriakan yang pecah-pecah. Sepanjang pekan terakhir Agustus hingga awal September, Indonesia kembali belajar alfabet krisis: A untuk “aksi”, B untuk “bentrok”, C untuk “cedera”, dan paling getir, K untuk “kematian”. Sejumlah media nasional mencatat sedikitnya tujuh sampai delapan orang tewas, ratusan luka-luka, dan tak sedikit bangunan serta fasilitas umum rusak. Angka-angka itu bukan sekadar statistik; ia adalah nama, umur, dan alamat, yang tiba-tiba berhenti bertambah usia.
Di antara nama-nama itu, Affan Kurniawan, 21 tahun, pengemudi ojek online, mungkin adalah cermin paling retak dari carut-marut penanganan massa. Affan bukan demonstran; ia sedang mengantar pesanan ketika kendaraan taktis Brimob melindas tubuhnya di kawasan Pejompongan, 28 Agustus. Ia sempat dilarikan ke rumah sakit, tapi nyawanya tak tertolong. Kasus ini kini disorot Kompolnas, namun yang kita perlukan bukan hanya perhatian setelah tragedi, melainkan standar penanganan yang mencegah tragedi itu sejak awal.
Data dari pemantauan Komnas HAM pada aksi 28-30 Agustus di Jakarta menunjukkan pola mengkhawatirkan: 351 orang ditangkap pada 25 Agustus dan sekitar 600 orang pada 28 Agustus, sebagian besar di Jakarta, sementara ribuan lainnya dibubarkan dengan kekuatan yang diduga berlebihan.
Komnas HAM membuka posko pengaduan dan melakukan pemantauan lapangan, menandakan situasi bukan sekadar “ketertiban umum” yang terganggu, melainkan potensi pelanggaran HAM yang sistemik. Amnesty International menambahkan sinyal bahaya: penggunaan kekuatan berlebihan kembali berulang di banyak kota. Negara boleh bicara stabilitas, tetapi hukum hak asasi menuntut akuntabilitas.
Di mana Natalius Pigai?
Dalam gejolak itu, kita mencari sosok yang seharusnya paling lantang: Menteri Hak Asasi Manusia. Kabinet Merah Putih membelah Kemenkumham menjadi tiga: Hukum; Hak Asasi Manusia; dan Imigrasi & Pemasyarakatan. Pos HAM diisi Natalius Pigai, seorang aktivis yang lama bersuara untuk korban.
Tapi pada saat korban jatuh, penangkapan massal terjadi, dan kepercayaan publik ambruk, publik nyaris tak melihat langkah luar biasa dari kementerian yang khusus mengurus HAM di republik ini. Di momen yang menuntut kehadiran, kita justru mendengar gema pernyataan yang terasa “template”: minta damai, minta proporsional.
Padahal kerangka hukumnya jelas. UU No. 9/1998 menegaskan kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum; penanganan aksi harus menjunjung asas proporsionalitas dan kepastian hukum. UU No. 39/1999 menempatkan hak untuk hidup dan hak untuk tidak disiksa sebagai hak yang tak bisa dikurangi dalam keadaan apa pun.
Dalam standar hak asasi, yang dilarang bukan demo, melainkan ekses kekuasaan tanpa akuntabilitas. Ketika aparat mengerahkan kekuatan mematikan atau membahayakan jiwa, pemerintah–terutama Menteri HAM–wajib memimpin audit menyeluruh: SOP, komando, pelatihan, hingga rantai pertanggungjawaban pidana dan etiknya.
Lalu apa yang kita dengar sebagai kebijakan konkret? Kita belum melihat tim investigasi independen lintas-kementerian yang dipimpin Menteri HAM, dengan mandat, tenggat, dan publikasi temuan yang dapat diuji publik. Kita belum melihat protokol nasional pengendalian massa yang direvisi berbasis prinsip “minimum force”, serta moratorium taktis atas penggunaan rantis di koridor sipil sempit.
Kita juga belum melihat komitmen anggaran darurat untuk layanan pemulihan korban: bantuan medikolegal, kompensasi, dan trauma healing komunitas. Ketiadaan ini menjelaskan kenapa kampus-kampus, lembaga profesi hukum, dan organisasi masyarakat sipil lebih dulu mengeluarkan sikap, sementara kementerian yang khusus menjaga martabat manusia terasa berjalan dalam mode “press release”.
Bahkan dari kacamata pragmatis, absen dalam krisis adalah kelalaian politik. Pemerintah menghadapi kerugian ekonomi yang dihitung mencapai puluhan miliar rupiah selama hari-hari kerusuhan; ini bukan sekadar soal citra, melainkan biaya sosial yang terus menggelembung.
Dalam demokrasi manapun, “law and order” tanpa penghormatan HAM hanya menanam bibit krisis berikutnya. Tugas Menteri HAM bukan menjadi juru damai yang netral-netral saja, tetapi arsitek kebijakan yang memastikan kepolisian bekerja dalam pagar hukum dan standar hak asasi, serta berani menuntut pertanggungjawaban ketika pagar itu dilompati.
Apa yang seharusnya terjadi?
Pertama, deklarasi darurat akuntabilitas HAM: pengumuman resmi pembentukan tim independen dengan keikutsertaan Komnas HAM, Kompolnas, ahli forensik, dan organisasi sipil; semua temuan berupa rekaman bodycam, rantai komando, perintah lapangan, dibuka sejauh hukum memungkinkan. Kedua, pembaruan SOP pengendalian massa: pelarangan penggunaan kendaraan taktis untuk mendorong massa di ruang padat, eskalasi bertahap yang rigourous, dan kewajiban de-escalation training.
Ketiga, skema reparasi: santunan negara yang layak bagi keluarga korban, beasiswa bagi adik-kakak atau anak korban, dan layanan pemulihan psikososial. Keempat, pemisahan tegas proses etik-internal dan pidana, agar publik melihat hukum bukan hanya tajam ke rakyat, tapi juga ke pemegang senjata.
Bagi penulis tentu rakyat tidak meminta yang muluk. Hanya meminta Menteri HAM hadir sungguh-sungguh: bukan sekadar imbauan damai, melainkan kebijakan yang menyentuh luka. Dalam narasi negara, demonstran sering dituduh “mengganggu ketertiban”; tapi ketertiban yang menutup mata pada nyawa manusia adalah ketertiban yang cacat sejak kalimat pertama.
Indonesia memang butuh ketertiban: ketertiban yang lahir dari keadilan. Dan keadilan tak akan datang dari kementerian yang lebih sibuk menata struktur dan jargon, ketimbang menatap mata keluarga Affan dan berkata: “Negara salah. Ini cara kami memperbaikinya.”
Terakhir, mari kita ingat: konstitusi memberi rakyat hak bersuara; undang-undang mengikat negara untuk melindungi. Di jalanan yang masih menyisakan bau mesiu, negara diuji apakah berani berdiri di pihak warga yang haknya dilanggar atau sekadar berdiri di podium, membaca kalimat-kalimat tanpa risiko. Menteri HAM, panggungnya menunggu, lampunya menyala terang. Yang kita butuhkan sekarang bukan aktor pembaca naskah, melainkan pemimpin yang menulis ulang adegannya dengan pena kebijakan dan tinta akuntabilitas.