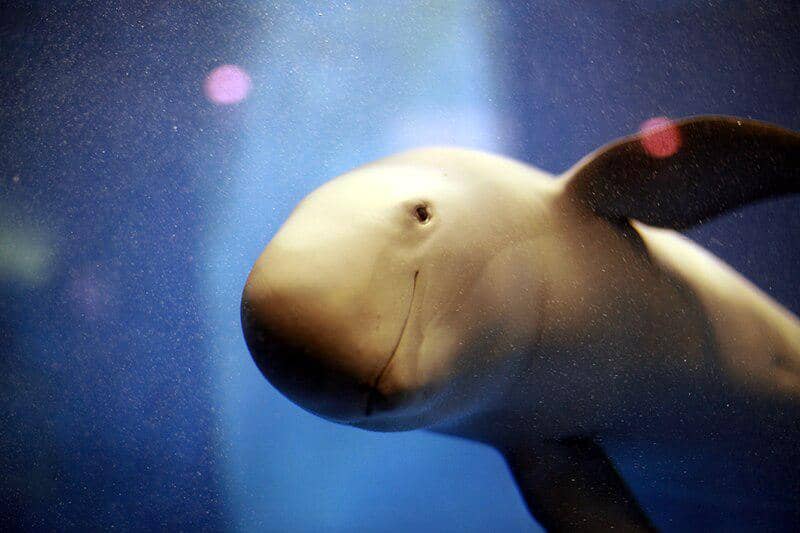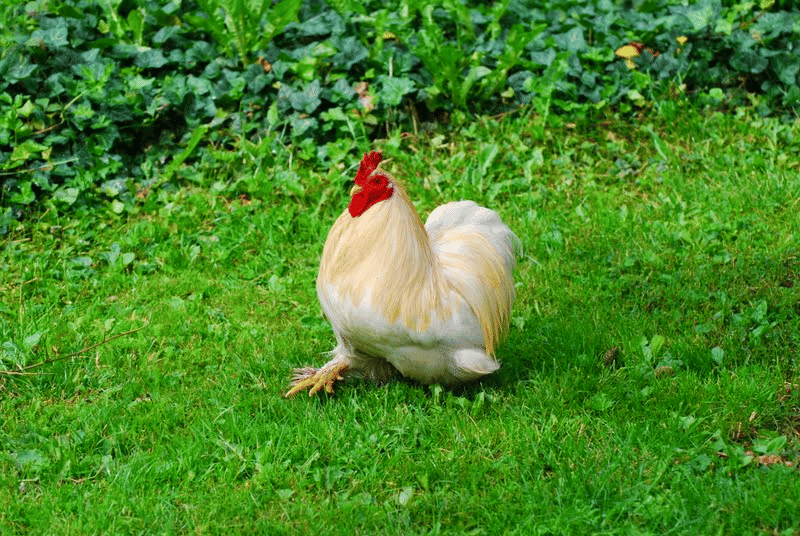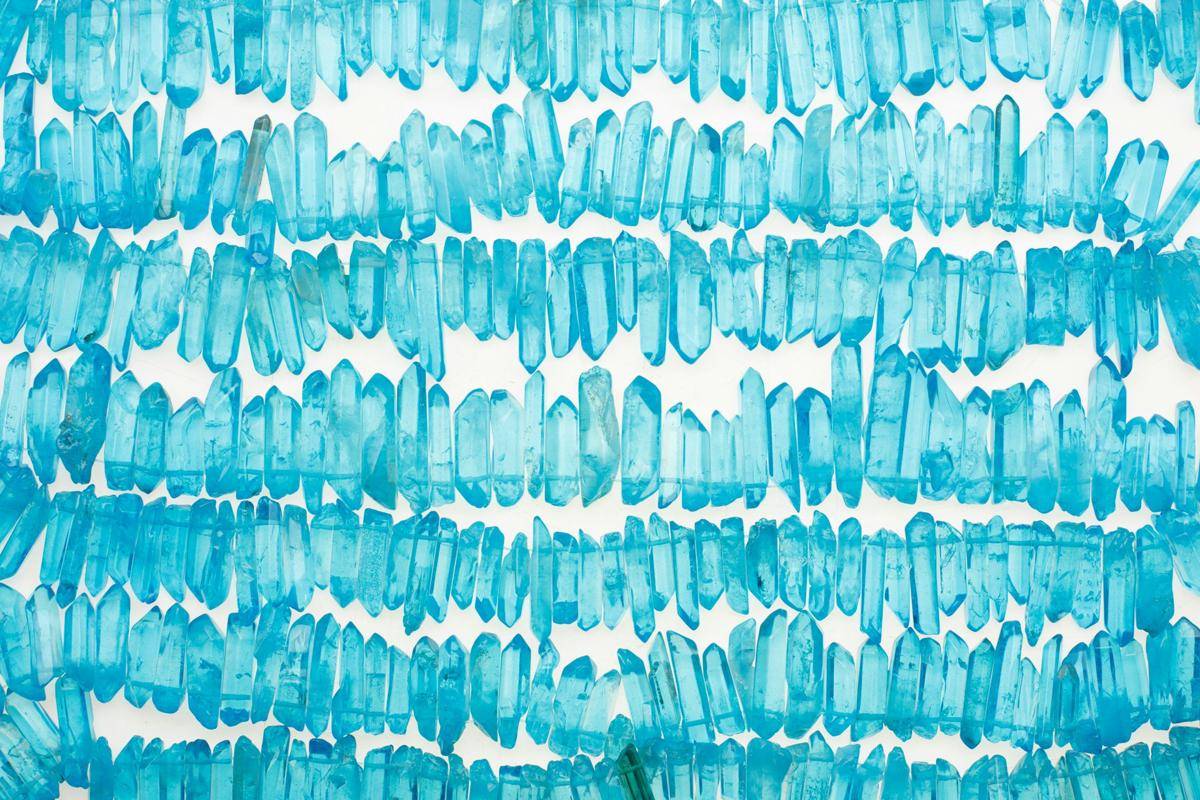"Climate Change and Habitat Loss Are Big Factors in Frog Pandemic". Diakses pada September 2025. The University of Texas at Austin.
Schwenk, Kurt, and Jackson R. Phillips. “Circumventing Surface Tension: Tadpoles Suck Bubbles to Breathe Air.” Proceedings of the Royal Society B Biological Sciences 287, no. 1921 (February 19, 2020).
"How Do Frogs Breathe?". Diakses pada September 2025. Britannica.
"How do frogs breathe and drink through their skin?". Diakses pada September 2025. Live Science.
Bagaimana Kodok Bisa Bernapas dan Minum Menggunakan Kulit?

- Kodok bernapas melalui kulit dengan mekanisme respirasi kutaneus
- Berudu menciptakan gelembung udara sendiri untuk bernapas
- Kulit kodok juga digunakan untuk minum dan rentan terhadap polutan
Saat seekor kodok terdiam di pinggir kolam atau danau, banyak orang tidak menyadari bahwa ia sedang melakukan sesuatu yang sangat kompleks, yaitu bernapas dan "minum" menggunakan kulit mereka yang lembab.
Kodok memiliki cara hidup yang berbeda dari manusia. Mereka tidak hanya mengandalkan paru-paru untuk bernapas, tetapi juga menggunakan kulit sebagai jalur pertukaran oksigen. Kulit mereka tipis, dipenuhi kelenjar yang menghasilkan lendir agar tetap lembap, dan memiliki pori-pori yang memungkinkan molekul udara masuk.
Dengan struktur ini, oksigen bisa masuk ke tubuh melalui kulit, sementara air juga dapat langsung diserap. Yuk, pahami lebih lanjut tentang mekanisme kodok bernapas dan minum menggunakan kulit.
1. Respirasi kutaneus pada kodok
Kodok memiliki kemampuan bernapas melalui kulit dengan mekanisme yang disebut respirasi kutaneus. Tepat di bawah permukaan kulitnya terdapat jaringan pembuluh darah kecil yang dapat menyerap oksigen langsung dari air atau udara, sekaligus mengeluarkan karbon dioksida.
Proses ini bekerja hampir sama seperti paru-paru, hanya saja terjadi di permukaan tubuh. Meskipun kodok juga menggunakan paru-paru dan lapisan mulut untuk bernapas, respirasi kutaneus memberi keunggulan penting karena memungkinkan mereka bertahan hidup di dalam air maupun saat hibernasi panjang.
Selama kulit tetap lembap berkat lendir yang diproduksi kelenjar, pertukaran gas dan air akan berlangsung secara otomatis, meski tidak semua jenis kodok bergantung penuh pada mekanisme ini.
2. Berudu menggunakan gelembung udara
Kodok yang masih dalam bentuk berudu belum memiliki insang yang berkembang sempurna sehingga tetap membutuhkan udara untuk bernapas. Namun, saat baru menetas, tubuh mereka terlalu kecil untuk menembus tegangan permukaan air.
Untuk mengatasinya, berudu menciptakan gelembung udara sendiri. Studi pada 2020 mencatat berudu berenang tepat di bawah permukaan, lalu dengan cepat mengisap udara hingga terbentuk gelembung. Gelembung ini kemudian didorong masuk ke paru-paru sehingga mereka bisa tetap bertahan hidup meski belum mampu muncul langsung ke permukaan air.
3. Kulit sebagai organ untuk minum

Selain bernapas, kodok juga menggunakan kulit untuk minum. Air meresap melalui pori-pori kulit, masuk ke ruang-ruang kecil di jaringan, lalu diserap melintasi membran sel hingga mencapai aliran darah. Banyak spesies kodok memiliki bagian kulit khusus yang kaya pembuluh darah, disebut drinking patch, yang memungkinkan mereka menyerap air dalam jumlah besar.
Adaptasi ini sangat penting bagi kodok yang hidup di daerah kering, seperti trilling frog dan water-holding frog di gurun Australia, yang bergantung pada kemampuan menyerap air secara cepat selama musim hujan. Air cadangan tersebut bisa disimpang dan terkadang digunakan untuk menambahkan lapisan lendir ekstra di kulit.
4. Kulit kodok rentan akan polutan
Kulit kodok yang berpori memberi manfaat besar, tetapi juga membawa risiko. Permeabilitas kulit membuat mereka sangat rentan terhadap polutan dan perubahan iklim. Penelitian menunjukkan bahwa kulit kodok mudah terpapar bahan kimia komersial maupun mikroplastik dari lingkungan.
Selain itu, kebutuhan untuk menjaga kelembapan kulit menjadikan mereka sangat tergantung pada kondisi habitat yang basah.
Dengan semakin seringnya kekeringan dan meningkatnya suhu akibat perubahan iklim, area hutan hujan seperti Amazon serta hutan Atlantik di Brasil, Argentina, dan Paraguay terancam menyusut, yang berarti ruang hidup kodok juga ikut berkurang.
5. Hilangnya kodok menjadi indikasi perubahan iklim
Kodok sering menjadi kelompok hewan pertama yang menunjukkan tanda penurunan populasi atau bahkan hilang sama sekali ketika lingkungan mulai terganggu. Kondisi ini menjadikan mereka indikator penting bagi kesehatan ekosistem.
Hilangnya kodok tidak hanya berarti berkurangnya satu jenis hewan, tetapi juga memicu perubahan besar dalam rantai makanan. Kodok berperan menjaga populasi serangga agar tetap terkendali, sehingga mengurangi risiko ledakan hama yang dapat merusak tanaman atau menularkan penyakit.
Di sisi lain, banyak predator seperti ular dan burung bergantung pada kodok sebagai sumber makanan utama. Jika kodok menghilang, keseimbangan antara pemangsa dan mangsa akan terganggu, yang pada akhirnya berdampak pada stabilitas ekosistem secara keseluruhan.
6. Tantangan adaptasi terhadap iklim

Perubahan iklim menimbulkan pertanyaan serius tentang kemampuan kodok untuk beradaptasi dengan cepat. Kodok, seperti banyak spesies lain, memiliki keterbatasan biologis dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan suhu, pola hujan, dan kekeringan yang semakin ekstrem.
Para ahli menilai laju perubahan iklim terjadi jauh lebih cepat dibandingkan kemampuan hewan untuk berevolusi atau mengubah perilaku mereka. Beberapa spesies mungkin memiliki peluang untuk bertahan dengan menyesuaikan pola hidup atau habitat, tetapi sebagian besar kemungkinan tidak mampu mengikuti kecepatan perubahan ini.
Hal ini menempatkan banyak populasi kodok dalam posisi rentan, terutama yang hidup di lingkungan dengan kondisi khusus seperti hutan hujan yang bergantung pada kelembapan stabil untuk kelangsungan hidup mereka.
Kulit kodok memberi mereka cara unik untuk bernapas dan minum, tetapi juga menjadikan mereka rentan terhadap perubahan lingkungan. Peran penting mereka dalam ekosistem membuat keberlangsungan hidup kodok bukan hanya soal satu spesies, melainkan keseimbangan alam secara keseluruhan.
Referensi