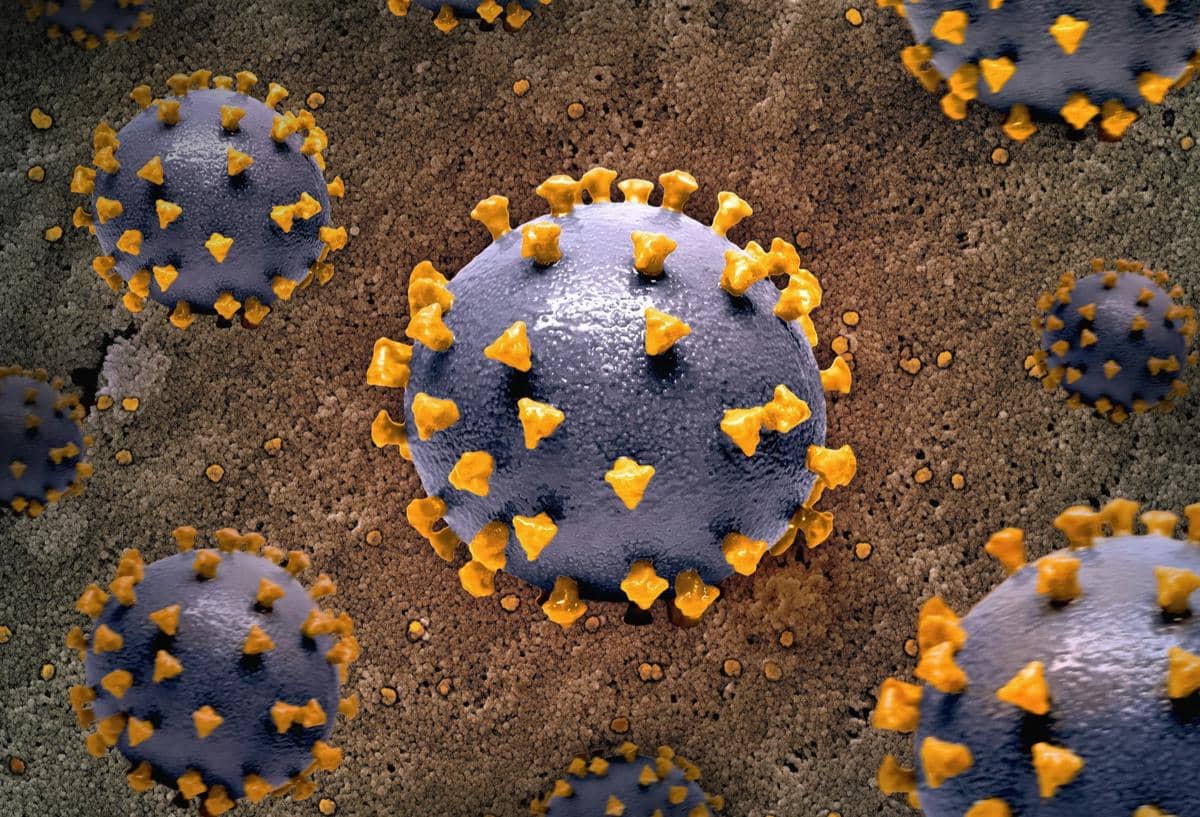Koalisi Sipil Tolak Usul Pilkada Dipilih DPRD, Ini Alasannya

- Usulan pilkada tidak langsung menunjukkan sikap nirempati terhadap rakyat yang sedang menghadapi situasi sulit.
- Tingginya ongkos politik bukan disebabkan oleh mekanisme pilkada langsung, melainkan pada tata kelola pemilu yang belum serius dibenahi negara.
- Pilkada langsung telah menjadi instrumen sirkulasi dan regenerasi kepemimpinan nasional, menghapusnya dapat menciptakan otoritarianisme baru.
Jakarta, IDN Times - Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Koalisi untuk Kodifikasi UU Pemilu, menolak keras usulan pilkada digelar secara tertutup. Di mana kepala daerah tak dipilih langsung oleh rakyat, namun diwakili DPRD.
Hal itu disampaikan koalisi sipil menanggapi usul Presiden RI, Prabowo Subianto dan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia soal pilkada tidak langsung. Keduanya beralasan, pilkada langsung menimbulkan ongkos politik yang tinggi, sehingga pemilihan melalui DPRD dinilai sebagai solusi yang lebih murah dan praktis.
1. Nirempati terhadap kondisi rakyat yang sedang sulit

Peneliti Perludem, Haykal menegaskan gagasan tersebut tidak hanya salah arah secara substansial, tetapi juga memperlihatkan sikap nirempati terhadap rakyat yang sedang menghadapi situasi sulit. Ia secara khusus menyoroti masyarakat di berbagai daerah yang sedang dihadapi bencana.
Usulan itu disampaikan di tengah situasi seperti saat ini.
Menurutnya, ketika publik membutuhkan kepastian perlindungan dan kehadiran negara dalam penanganan bencana, para elite justru sibuk mendiskusikan rekayasa politik yang berpotensi mengerdilkan hak-hak demokratis rakyat.
2. Persoalan utama ada di tata kelola pilkada langsung

Haykal menilai, persoalan utama bukan pada mekanisme pilkada langsungnya, melainkan pada tata kelola pemilu yang belum serius dibenahi negara. Jika dicermati, tingginya ongkos politik bukan disebabkan oleh mekanisme pilkada langsung, melainkan biaya kampanye yang tidak terkendali, termasuk praktik politik uang seperti jual beli suara maupun jual beli kandidasi.
"Riset menunjukkan bahwa sekitar 25 sampai 33 persen pemilih pada Pemilu 2014 terpapar politik uang. Angka ini sangat mungkin meningkat pada Pemilu 2019, Pemilu 2024, hingga Pilkada 2024. Fakta ini memperlihatkan bahwa politik uang berlangsung masif di seluruh arena elektoral di Indonesia, termasuk pilkada," ucap Haykal.
Selain itu, salah satu faktor yang membuat ongkos politik semakin mahal adalah tingginya biaya kandidasi, yakni seluruh biaya yang harus dikeluarkan bakal calon sejak tahap pencalonan. Biaya ini mencakup konsolidasi dukungan politik sejak dini, mulai dari mahar politik kepada partai, pembiayaan survei elektabilitas, hingga belanja komunikasi dan jaringan politik.
"Karena tidak seluruh biaya tersebut diatur dalam skema dana kampanye resmi, praktik pendanaan kandidasi sering berlangsung tanpa transparansi dan memperbesar ketergantungan calon pada pemodal tertentu," tuturnya.
Dengan demikian, tingginya ongkos pilkada bukanlah disebabkan mekanisme pemilihan secara langsung, melainkan proses pencalonan yang transaksional dan tidak akuntabel.
Menyelesaikan persoalan tersebut dengan menghapus pilkada langsung dianggap sebagai langkah keliru dan tidak menyentuh akar masalah. Bila logika ini dipakai secara konsisten, maka pemilu-pemilu lain pun berpotensi dihapus hanya karena tingginya praktik politik uang.
Padahal, kata dia, pilkada langsung merupakan capaian penting dalam konsolidasi demokrasi Indonesia pasca reformasi, yang memperluas ruang akuntabilitas, membuka partisipasi publik, dan mendorong kompetisi yang lebih terbuka.
3. Wacana penghapusan pilkada langsung bukanlah hal yang baru

Haykal lantas menerangkan, wacana penghapusan pilkada langsung bukanlah hal yang baru. Pada penghujung masa pemerintahannya, Presiden Keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pernah menghadapi situasi politik yang serupa dengan konteks saat ini, ketika DPR mengesahkan perubahan Undang-Undang Pilkada yang menghapus mekanisme pemilihan langsung dan mengembalikan pemilihan kepala daerah ke DPRD.
Namun, SBY menilai langkah tersebut sebagai kemunduran demokrasi, karena justru membuka ruang transaksi politik yang lebih gelap di balik pintu tertutup parlemen daerah, serta mengurangi hak rakyat untuk menentukan secara langsung siapa yang memimpin mereka.
Selain itu, kata Haykal, pilkada langsung selama ini telah menjadi instrumen sirkulasi dan regenerasi kepemimpinan nasional. Telah banyak sosok dan figur pemimpin yang lahir dari proses pilkada langsung dan secara berjenjang mengisi ruang politik di tingkat nasional.
Jika mengembalikan pilkada menjadi tidak langsung, maka rantai sirkulasi dan regenerasi kepemimpinan akan dapat dipastikan terganggu, nepotisme merajalela dan menciptakan otoritarianisme baru.
Haykal menyebut, ketimbang menghidupkan kembali wacana pilkada tidak langsung, pembentuk undang-undang seharusnya fokus memperbaiki tata aturan kepemiluan untuk menjawab persoalan politik uang.
"Langkah-langkah itu dapat dilakukan, antara lain, dengan memperkuat pengaturan dana kampanye, meningkatkan efektivitas penegakan hukum, memperbaiki sistem audit, memperkuat transparansi pendanaan politik dan mendorong pelembagaan partai politik yang lebih demokratis," beber dia menegaskan.
"Kami juga menegaskan bahwa mekanisme tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional, mereduksi kedaulatan rakyat, dan membuka ruang transaksi politik yang lebih gelap di balik pintu tertutup DPRD," lanjut dia.