Ketidakseimbangan Akses Pendidikan dan Politik dalam Kehidupan

Politik berperan dalam mengatur regulasi, menciptakan sistem yang inklusif agar pendidikan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa adanya diskriminasi
Pentingnya pemahaman maupun penanaman nilai keadilan mengenai ketidakseimbangan akses pendidikan dan politik sejak dini agar tercipta rasa kemanusiaan dan rasa saling menghargai dalam lingkungan sosial
Ketidakseimbangan akses pendidikan dan politik masih menjadi persoalan nyata di Indonesia. Pendidikan dan politik merupakan dua aspek fundamental dalam pembangunan bangsa, pendidikan berperan penting dalam meningkatkan kecerdasan, mengembangkan diri, dan seseorang akan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan guna meningkatkan kualitas dan memenuhi kebutuhan hidupnya.
Sementara itu, politik menjadi arena pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan publik, menentukan arah dan kualitas penyelenggaraan pendidikan nasional. Politik berperan dalam mengatur regulasi, dan menciptakan sistem yang inklusif agar pendidikan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa adanya diskriminasi. Ketimpangan dalam memperoleh akses pendidikan dan keterlibatan politik menimbulkan perasaan tertinggal atau terpinggirkan bagi sebagian masyarakat, hal ini menyebabkan siklus ketidakadilan sosial menjadi sulit diputus.
Pentingnya pemahaman maupun penanaman nilai keadilan mengenai ketidakseimbangan akses pendidikan dan politik sejak dini agar tercipta rasa kemanusiaan dan rasa saling menghargai dalam lingkungan sosial, khususnya di lingkungan sekolah. Namun, pada kenyataannya, pemerataan pendidikan masih sulit dijangkau di berbagai daerah akibat faktor geografis, infrastruktur, dan kebijakan yang belum sepenuhnya berpihak pada kelompok marginal. Hal ini turut berdampak pada akses politik, di mana kelompok yang kurang teredukasi atau kurang memiliki kesadaran atas kondisi politik tertentu cenderung tidak memiliki kekuatan dan ambisi untuk memperjuangkan hak-haknya dalam proses politik.
Oleh karena itu, sebagai seorang pelajar, sudah saatnya tidak menutup mata terhadap permasalahan ketimpangan yang terjadi. Diperlukan upaya sosialisasi, penelitian, dan penguatan pemahaman mengenai pentingnya akses pendidikan dan politik yang setara agar seluruh lapisan masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional dan mencapai kehidupan demokratis yang adil.
Hasil Kegiatan
Adanya ketidakseimbangan dalam mengakses pendidikan juga pengetahuan politik di berbagai strata masyarakat masih menjadi permasalahan yang tak kunjung ditemukan penyelesaiannya membawa kekhawatiran kepada kami. Sebagai mahasiswa yang mendapat kesempatan untuk menuntut pendidikan secara formal, kami memiliki urgensi untuk membantu pemerintah dalam menyebarkan pengetahuan dimulai dari teman-teman sekolah yang masih menuntut pendidikan wajib 12 tahun, misalnya siswa SMP. Melihat bagaimana kondisi ketimpangan yang masih terjadi hingga sekarang, kami berusaha membagikan ilmu pengetahuan dan kesadaran mengenai bagaimana keadaan realitas ketidakseimbangan akses pendidikan dan politik di Indonesia.
Kami, kelompok 5, melaksanakan sosialisasi turun lapangan ke SMP Negeri 1 Malang sebagai bentuk pemenuhan urgensi yang sudah disebutkan diatas. Kami membentuk sistem pembelajaran yang terbuka dan juga interaktif, karena kami mengerti kesadaran mengenai hal ini di kalangan siswa siswi SMP masih menjadi hal yang belum disoroti. Maka dari itu kami berusaha mengemas pembahasan kami dalam bentuk yang menyenangkan agar siswa bisa menangkap pentingnya sikap mentoleransi sekitar mereka mengenai keadaan serta kesempatan untuk menuntut pendidikan formal yang tidak setara. Kami menyusun pemaparan materi kami dengan melaksanakan quiz, pengenalan singkat terhadap lingkungan politik, juga bermain permainan yang dapat menarik antusiasme para siswa dan kami juga menyiapkan berbagai hadiah untuk mengapresiasi segala usaha siswa dalam proses memahami materi yang kami sampaikan.
Kegiatan sosialisasi yang telah kami laksanakan di SMP Negeri 1 Malang berjalan tanpa hambatan dan mendapatkan antusiasme tinggi dari para siswa. Dalam kegiatan ini, kami memilih untuk melakukan sosialisasi kepada siswa siswi kelas 8. Melalui sosialisasi ini, kami memberikan pemahaman mengenai pentingnya akses pendidikan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat, kami turut memberikan pengenalan dan pemahaman singkat mengenai akses politik, serta bagaimana ketidakseimbangan kedua akses tersebut memiliki hubungan dan pengaruhnya masing-masing. Materi yang kami sampaikan menekankan bahwa pendidikan yang tidak merata, terutama di wilayah terpencil, menyebabkan hilangnya kesempatan anak-anak maupun remaja untuk mendapatkan pendidikan yang memadai.
Hal ini akan mempengaruhi kemampuan mereka dalam memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara dan terbatasnya partisipasi dalam urusan politik. Melalui metode pembelajaran yang interaktif, seperti tanya jawab, diskusi kelompok, serta menggunakan PowerPoint menarik yang menggambarkan kondisi ketidakseimbangan pendidikan di Indonesia, yang dapat mendorong kesadaran para siswa akan pentingnya pemerataan pendidikan sebagai pondasi demokrasi yang sehat. Selain itu, kegiatan ini akan menumbuhkan motivasi para siswa untuk berperan aktif dalam mengatasi permasalahan ketimpangan yang ada, misalnya dengan mengadakan kegiatan kampanye kesadaran di lingkungan sekolah atau masyarakat sekitar.
Maka dari itu, kegiatan sosialisasi ini tidak hanya meningkatkan wawasan para siswa mengenai isu sosial, tetapi juga membentuk sikap simpati, empati, dan tanggung jawab yang kuat, sehingga diharapkan para siswa dapat menjadi generasi penerus yang lebih peduli dan turut berkontribusi dalam mencapai akses pendidikan dan politik yang lebih adil di masa depan.
Pengenalan Akses Pendidikan dan Politik
Pendidikan merupakan sebuah proses yang berisi interaksi antara pendidik dengan peserta didik, yang terkonsolidasi; membentuk sebuah sistem yang saling berkaitan. Pendidikan merupakan sebuah kewajiban bagi masyarakat Indonesia karena pendidikan menjadi suatu hal yang sangat esensial dalam proses pemanusiaan dalam masyarakat berbudaya (Hakim, 2016). Pendidikan berfungsi untuk meningkatkan kecerdasan intelektual masyarakat, mengembangkan keterampilan, serta membangun karakter guna memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Pendidikan juga sebagai bekal, sehingga nantinya masyarakat dapat berkontribusi dalam membangun peradaban maju (Alawiyah, 2012), karena dasar pembangunan yang strategis adalah pendidikan (Hakim, 2016).
Pendidikan harus diterapkan pada segenap rakyat Indonesia, bukan hanya untuk golongan tertentu saja, sehingga dalam hal ini, negara berperan penting dalam mengatur segala urusan pendidikan guna pencerdasan bangsa. Adapun salah satu jenjang pada pendidikan formal; pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi menjadi sebuah solusi bagi pertumbuhan dan pengembangan bangsa seiring dengan berkembangnya zaman, hal ini ditujukan untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat menjadi anggota masyarakat dengan kemampuan akademik atau profesional yang dapat menerapkan ataupun menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sebagainya (Markum dalam Alawiyah, 2012). Pendidikan tinggi menjadi sarana pencetak sumber daya manusia (SDM), sebagai pengelola tempat mendidik SDM yang memiliki kemampuan tinggi, penghasil SDM dengan pemikiran yang tajam, handal, dan penghasil pakar yang menjadi pelaku pembangunan (Surakhmad dalam Alawiyah, 2012).
Hasil studi intensif mengenai hubungan antara SDM dengan pembangunan yang telah dilakukan sekitar 40 tahun silam menyatakan bahwa terdapat korelasi positif antara pendidikan tinggi dengan keberhasilan pembangunan (Surakhmad dalam Alawiyah, 2012). Dalam mencapai hal tersebut, negara memiliki peran sentral dalam membuka dan memperluas akses pendidikan melalui kebijakan, pembiayaan, maupun pengelolaan sistem pendidikan guna menghasilkan SDM yang berkualitas, berdaya saing, serta siap menghadapi tantangan pembangunan nasional.
Akses pendidikan merupakan kemudahan dan kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk memperoleh pendidikan yang layak. Akses pendidikan turut menjadi pondasi utama dalam mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan dan kemajuan bangsa secara keseluruhan. Pemerataan pendidikan memang masih sulit menjangkau daerah-daerah terpencil karena kondisi tipologis daratan dan perairan Indonesia yang rumit, serta adanya pembangunan infrastruktur yang tidak merata. Namun, hal ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memberhentikan pemerataan akses pendidikan. Pendidikan merupakan elemen dasar dari hak asasi manusia yang mutlak demi terpenuhinya hak-hak lain, karena di dalam hak atas pendidikan juga terkandung elemen lainnya seperti hak ekonomi, sosial, budaya, hak sipil, dan politik (Hakim, 2016).
Akses pendidikan merujuk pada kesempatan seseorang untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan adil tanpa memperdulikan di mana tempat tinggalnya, siapa orang tuanya, apakah laki-laki atau perempuan, dan apakah memiliki kekurangan fisik atau tidak. Dengan adanya akses pendidikan yang baik, seseorang dapat mempelajari hal-hal baru, dapat memiliki kesempatan yang lebih baik di masa depan khususnya dalam konteks pekerjaan, serta dapat memajukan negara, karena orang-orang yang terdidik akan tumbuh menjadi warga negara yang peduli dan bertanggung jawab. Selain itu, hak atas pendidikan sebagai bagian dari HAM tidak sekedar hak moral, melainkan juga hak konstitusional yang mana tercantum dalam UUD
1945 Pasal 28 C ayat (1). Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk mengembangkan diri, memperoleh pendidikan, dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan guna meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan masyarakat. Pasal 31 ayat (2), (3), dan (4) turut menegaskan bahwa setiap warga negara harus mengikuti pendidikan dasar, sedangkan pemerintah wajib membiayai dan mengusahakan penyelenggaraan pengajaran nasional dengan memprioritaskan anggaran sekitar 20 persen dari Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Hakim, 2016).
Peran negara dalam mengatur dan menjamin akses pendidikan yang merata tentu tidak lepas dari dinamika politik yang berlangsung di Indonesia. Politik menjadi arena pengambilan keputusan dan kebijakan publik, hal ini menjadi faktor kunci dalam menentukan arah dan kualitas penyelenggaraan pendidikan nasional. Politik berperan dalam mengalokasikan anggaran pendidikan, mengatur regulasi, dan menciptakan sistem yang inklusif agar pendidikan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa adanya diskriminasi. Politik merupakan kunci untuk memahami lingkungan (Aristoteles dalam Bakesbang, 2023).
Sedangkan KBRI mendefinisikan politik ke dalam tiga pengertian: 1) pengetahuan tentang ketatanegaraan atau pemerintahan negara, 2) semua masalah dan tindakan yang mempengaruhi pemerintahan suatu negara atau negara lainnya (kebijakan, taktik, dll), dan 3) bagaimana cara bersikap dalam menangani atau menghadapi suatu masalah (Rusfiana & Nurdin dalam Harahap, 2022). Sehingga, dapat dikatakan bahwa politik merupakan sebuah usaha dalam menetapkan aturan-aturan yang dapat diterima oleh mayoritas masyarakat untuk mencapai kehidupan harmonis, di mana pemerintah menjadi otoritas yang terorganisir, dan menekankan pelembagaan kepemimpinan, serta alokasi nilai-nilai secara resmi (Anggara dalam Harahap, 2022).
Dengan demikian, akses politik juga dibutuhkan karena memungkinkan setiap warga negara dapat berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat, serta arah kebijakan publik (Santo, 2024).
Akses politik adalah kesempatan yang setara bagi setiap warga negara untuk terlibat dalam proses politik, baik sebagai pemilih, pembuat kebijakan, maupun sebagai pengawas jalannya pemerintahan. Akses politik dapat membantu mengurangi ketidakseimbangan politik dengan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok marginal; untuk terlibat dan memperjuangkan kepentingannya. Akses politik turut menjadi pondasi bagi terciptanya pemerintahan yang responsif, demokratis, dan berkeadilan.
Selain itu, akses politik yang luas dan merata akan mendorong akuntabilitas, transparansi, kinerja pemerintah, dan kebebasan masyarakat dalam menyuarakan pendapat, sehingga dapat meningkatkan legitimasi dan stabilitas politik. Namun, di Indonesia masih terdapat perbedaan aksesibilitas pendidikan maupun kesenjangan politik. Ketidakseimbangan akses pendidikan menciptakan kesenjangan dalam kualitas dan kesempatan belajar yang turut berdampak pada ketidakseimbangan akses politik. Di sisi lain, akses politik yang tidak merata akan memperburuk ketimpangan pendidikan, karena kebijakan dan alokasi sumber daya cenderung menguntungkan kelompok yang telah memiliki kekuatan politik. Hal ini menyebabkan masyarakat yang tidak memiliki kekuatan politik cenderung kurang mampu menyuarakan kepentingan dan memperjuangkan hak-haknya, dan berakhir kuatnya siklus ketidakadilan dan marginalisasi.
Contoh Ketidakseimbangan Akses Pendidikan dan Politik
Ketidakseimbangan dalam bidang pendidikan merupakan salah satu tantangan yang masih menjadi hal yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia. Meskipun pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan untuk menjamin pemerataan akses dan kualitas pendidikan, kenyataan yang ada masih terdapat perbedaan yang signifikan antar wilayah. Ketidakseimbangan tidak selalu mencerminkan ketidakadilan secara langsung, tetapi lebih pada kondisi yang tidak proporsional dalam penyediaan sumber daya pendidikan.
Salah satu bentuk nyata dari ketidakseimbangan tersebut adalah distribusi tenaga pendidik yang tidak merata antar wilayah perkotaan dengan daerah 3T (Tertinggal, Terluar, Terpencil), yang pada akhirnya hal tersebut memengaruhi mutu pendidikan yang diterima oleh peserta didik. Provinsi Papua menjadi contoh konkret dari permasalahan ini. Papua menghadapi tantangan serius dalam distribusi tenaga pendidik, terutama di wilayah-wilayah kecil yang sulit dijangkau. Salah satu faktor penyebab utama dari ketidakseimbangan ini adalah minimnya jumlah pelamar dalam proses rekrutmen guru di daerah 3T.
Berdasarkan pernyataan Sekretaris Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud, Nunuk Suryani, selama pelaksanaan seleksi guru dan PPPK, daerah-daerah 3T, termasuk Papua, menunjukkan tingkat partisipasi pelamar yang sangat rendah. Padahal, kebutuhan tenaga pengajar di wilayah tersebut sangat tinggi,mencapai sekitar 179.769 formasi. Di beberapa daerah, bahkan tidak ada satu pun pelamar yang mendaftar. Hal ini menyebabkan kekosongan posisi guru di berbagai sekolah dan berdampak serius terhadap proses pembelajaran.
Ketidakseimbangan pendidikan menjadi semakin lebar karena siswa di daerah 3T mengalami keterlambatan dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan pengembangan diri yang seharusnya setara dengan wilayah lain di Indonesia (Tutukansa & Tuffahati, 2022). Perbandingan dengan wilayah lain menunjukkan perbedaan yang signifikan. Berdasarkan data rekrutmen CASN tahun 2023, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjadi instansi dengan jumlah pelamar PPPK guru terbanyak, yaitu mencapai 1.796 orang dalam satu periode pendaftaran (Dike Rani Feirisa, 2023).
Angka ini sangat kontras jika dibandingkan dengan Provinsi Papua, di mana formasi guru yang tersedia cukup banyak namun minim peminat, bahkan di sejumlah daerah sama sekali tidak ada pelamar. Ketidakseimbangan ini mencerminkan rendahnya minat tenaga pendidik untuk ditempatkan di daerah 3T, seperti Papua, yang dipengaruhi oleh faktor geografis, aksesibilitas, fasilitas pendidikan yang terbatas, serta persepsi tentang kondisi kerja yang kurang mendukung. Sementara itu, Jawa Timur yang memiliki infrastruktur lebih baik, akses pelatihan yang luas serta fasilitas memadai, cenderung lebih diminati oleh para pencari kerja di sektor pendidikan.
Permasalahan distribusi tenaga pendidik di daerah 3T tidak dapat dilepaskan dari kondisi sarana dan prasarana pendidikan yang belum memadai. Sarana dan prasarana, seperti bangunan sekolah, buku pelajaran, serta fasilitas pendukung lainnya, merupakan komponen penting dalam menunjang proses belajar mengajar. Banyak wilayah 3T di Indonesia masih menghadapi keterbatasan dalam hal penyediaan fasilitas pendidikan. Di Provinsi Papua, misalnya, kurangnya pemerataan pembangunan berdampak langsung pada kelengkapan infrastruktur pendidikan.
Salah satu contoh nyata dapat dilihat di Kabupaten Jayawijaya. Berdasarkan data dalam publikasi ilmiah, wilayah ini memiliki total 62 sekolah yang tersebar dari tingkat TK hingga SMA, yang terdiri atas 1 SMA negeri, 1 SMA swasta , 2 SMP negeri, 10 SMP swasta, 21 Sd negeri, 9 SD swasta, dan 18 TK atau PAUD. Meskipun jumlah tersebut mencerminkan adanya upaya pembangunan pendidikan, ketersediaan sarana dan prasarana di sekolah-sekolah tersebut masih belum layak. Beberapa sekolah, salah satunya yaitu terjadi di SD Inpres Megapura, di mana harus menghadapi kekurangan buku pelajaran, bahkan dalam satu kelas, satu buku digunakan bersama oleh lima siswa. selain itu, di SMP 2 Wamena, sebagian besar buku di perpustakaan masih menggunakan standar kurikulum lama yang tidak relevan dengan kebutuhan pendidikan saat ini (Tutukansa & Tuffahati, 2022).
Sementara itu, jika dilihat data dari Provinsi Jawa Timur yang dapat diakses melalui laman resmi, terlihat jelas kesenjangan dalam jumlah dan kualitas sarana prasarana. Kabupaten Jember misalnya, memiliki hampir 3.500 sekolah dengan lebih dari 18 ribu ruang kelas, sekiar 1.300 laboratorium, serta perpustakaan yang dilengkapi dengan buku-buku yang sesuai dengan kurikulum terkini (Dapodik Jatim, 2025). Perbandingan ini menunjukkan bahwa akses terhadap sarana pendidikan tidak merata, dan menunjukkan bahwa daerah-daerah maju di Jawa lebih cepat berkembang dalam hal pembangunan infrastruktur pendidikan. Berbanding terbalik dengan daerah 3T seperti Jayawijaya masih tertinggal dan membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah.
Persoalan serupa juga tercermin dalam bidang politik. Ketidakseimbangan akses politik menjadi salah satu hambatan besar dalam mewujudkan sistem demokrasi yang inklusi di Indonesia. Akses politik yang ideal seharusnya menjamin bahwa setiap warga negara, tanpa memandang latar belakang sosial, geografis, maupun budaya, memiliki peluang yang sama untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan public. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa kelompok-kelompok tertentu, khususnya masyarakat di wilayah 3T seperti Papua, masih mengalami berbagai hambatan dalam mengakses ruang politik.
Salah satu contoh nyata ketidakseimbangan akses politik dapat dilihat dari rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu di wilayah Papua, khususnya di Distrik Jayapura Selatan. Pada pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, dari total 82.765 pemilih, hanya sekitar 49% atau 40.630 orang yang menggunakan hak pilihnya. Persentase ini menunjukkan penurunan yang signifikan dan mencerminkan minimnya kesadaran politik masyarakat setempat.
Minimnya partisipasi ini dipengaruhi oleh kurangnya distribusi informasi politik ke seluruh lapisan masyarakat. Banyak warga yang tidak mengetahui secara jelas jadwal maupun ketentuan teknis pemilu akibat lemahnya sosialisasi dari penyelenggara pemilu (Fonataba, 2017). Peran media massa yang seharusnya menjadi sarana utama untuk menyebarkan informasi politik secara luas belum maksimal dijalankan. Hal ini sangat disayangkan mengingat media memiliki fungsi strategis dalam memberikan pendidikan politik dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menggunakan hak suara. Rendahnya intensitas kampanye serta kurangnya pemberitaan mengenai proses dan tahapan pemilu menyebabkan informasi politik tidak menjangkau masyarakat secara menyeluruh. Kondisi ini berdampak pada tingginya angka golput dan lemahnya partisipasi politik warga. Sebagai perbandingan dengan wilayah Papua, tingkat partisipasi politik masyarakat di Kota Mojokerto menunjukkan angka yang cukup tinggi.
Pada Pemilu 2014, partisipasi pemilih di kota tersebut mencapai 81,66%, jauh di atas rata-rata partisipasi di wilayah tertinggal seperti Distrik Jayapura Selatan. Masyarakat Mojokerto terlihat lebih siap dalam menentukan pilihan politiknya, terutama dalam pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Hasil riset menunjukkan bahwa sekitar 42,44% warga telah mengenal baik calon yang akan mereka pilih (Chalik, 2015).
Ketidakseimbangan akses pendidikan dan ketidakseimbangan akses politik adalah dua persoalan yang berkaitan erat dan saling memperkuat satu sama lain. Pendidikan yang tidak merata, seperti yang terjadi di daerah 3T termasuk Papua, menyebabkan rendahnya kualitas sumber daya manusia, terutama dalam hal kemampuan literasi, pemahaman terhadap hak-hak warga negara, dan kesadaran terhadap proses politik. Ketika akses pendidikan terbatas, masyarakat tidak mendapatkan informasi dan pemahaman yang cukup untuk berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi, seperti pemilu. Hal ini terlihat dari rendahnya partisipasi politik di Distrik Jayapura Selatan, yang salah satunya disebabkan oleh kurangnya informasi mengenai proses dan jadwal pemilihan umum.
Di lain hal, ketidakseimbangan dalam akses politik seperti minimnya partisipasi masyarakat dalam pemilu, dapat memperlambat upaya untuk pemerataan pendidikan. Rendahnya keterlibatan masyarakat dalam ruang politik membuat aspirasi mengenai perbaikan infrastruktur pendidikan atau distribusi tenaga pengajar menjadi kurang terdengar oleh para pengambil kebijakan. Dapat disimpulkan bahwa keterbatasan dalam pendidikan menghambat partisipasi politik dan keterbatasan partisipasi politik berpotensi memperburuk kondisi pendidikan. Oleh karena itu, kedua isu ini harus ditangani secara bersamaan untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan, agar masyarakat di seluruh wilayah Indonesia dapat menikmati hak-haknya secara setara, baik dalam pendidikan maupun politik.
Dampak Ketidakseimbangan Akses Pendidikan dan Politik
Pendidikan merupakan hak seluruh umat manusia. Sebagaimana disebutkan dalam ikrar yang dikumandangkan oleh Majelis Umum PBB pada 1948. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya pendidikan untuk dijadikan hal yang harus dipenuhi oleh setiap negara. Berkaca dari bagaimana Indonesia berkedudukan di kancah global, Indonesia menempati posisi 67 (detikEdu, 2025) yang berarti menunjukkan bahwa pendidikan merupakan sektor yang menjadi catatan penting bagi pemerintah indonesia untuk terus dibenahi agar bisa mencapai posisi pendidikan yang layak dan juga adil bagi masyarakatnya. Ketidakmerataan pendidikan menjadi salah satu hal yang masih bermasalah sampai sekarang.
Menurut ucapan Nurhuda (2022), permasalahan tidak meratanya pendidikan di Indonesia masih menjadi tantangan yang serius dan diakari oleh kurangnya koordinasi efektif antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan antara proses pendidikan dengan politik yang harus dibenahi. Pembenahan sektor pendidikan ini bukan sekedar memperbaiki dan memperbarui fasilitasnya, tetapi juga memberikan akses yang mudah serta kualitas pendidik yang setara baik didesa maupun dikota sehingga menciptakan kesempatan belajar yang setara bagi setiap warga Indonesia.
Pembenahan diperlukan karena pendidikan merupakan akar dari sumber pengetahuan yang membawa masyarakat menjadi kelompok manusia yang paham dan “melek” akan keadaan politik di negaranya. Pendidikan berperan menjadi bekal bagi setiap individu untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik, dari menentukan kebijakan publik hingga menentukan pemimpin negara. Dari sini kita dapat memahami bahwa pendidikan dan juga politik memegang hubungan erat yang saling mendukung satu sama lain. Dalam pendidikan, politik diperlukan untuk mengatur, menentukan arah, serta menjamin keadilan serta pemerataan. Begitu juga sebaliknya, dalam politik diperlukan adanya pendidikan sebagai bentuk pendoman dan juga pemahaman mengenai etika juga struktur dari negara. Namun melihat keadaan pendidikan di Indonesia yang masih tidak merata dan masih dapat dikatakan berkualitas rendah dalam berbagai aspeknya, menjadikannya sebagai akar permasalahan ketimpangan sosial yang kompleks. Ketidakhadiran pemerintah dalam menanggulangi permasalahan ini secara serius juga menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan tidak kunjung usainya permasalahan ini dari tahun ke tahun.
Permasalahan pendidikan yang tidak merata di Indonesia akan terus menjadi siklus berkelanjutan apabila tidak segera diselesaikan. Pendidikan bisa dikatakan berperan sebagai pondasi dari setiap aspek kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang akan memicu siklus tersebut untuk terus berputar, dimulai dari minimnya pendidikan berlanjut ke minimnya pengetahuan mengenai kewarganegaraan, minimnya kesempatan bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan dan membangun kehidupan yang layak, dan akan berlanjut kepada minimnya partisipasi mereka sebagai warga negara Indonesia dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Dari rentetan siklus ini dampak yang dirasakan oleh negara bukan sekedar kehilangan jumlah suara masyarakat saat pemilihan pemimpin, terhambatnya pembangunan negara yang inklusif dan berkeadilan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat juga akan mengalami keterlambatan. Hal ini dapat memicu kemunduran sebuah negara dalam kedudukannya di kancah internasional.
Solusi dalam Mengatasi Ketidakseimbangan Akses Pendidikan dan Politik
Dalam permasalahan ketidakseimbangan akses pendidikan dan politik, tentu sangat diperlukan solusi dan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan tersebut. Beberapa solusi berikut dapat menjadi langkah-langkah dalam mengatasi ketidakseimbangan akses pendidikan, yaitu:
1. Pemerataan fasilitas pendidikan
Dengan luasnya wilayah Indonesia, banyak wilayah-wilayah yang belum difasilitasi akses pendidikan yang cukup dan memadai, terutama bagi wilayah-wilayah pedesaan dan daerah-daerah terpencil yang jauh dari perkotaan. Kurangnya fasilitas seperti bangunan sekolah yang jarang, sehingga para pelajar perlu menempuh jarak jauh untuk mencapai sekolah. Lalu kurangnya fasilitas buku dan pembelajaran, bahkan kurangnya sumberdaya manusia pengajar atau guru. Sehingga pemerataan fasilitas pendidikan hingga ke daerah-daerah pelosok perlu diperhatikan lebih dalam, terutama oleh pemerintah. Agar lebih memperhatikan peningkatan dan pemerataan fasilitas pendidikan di seluruh penjuru daerah di Indonesia.
2. Bantuan pendidikan
Pendidikan menjadi salah satu cara untuk mengatasi kemiskinan. Dan tingginya biaya pendidikan membuat beberapa masyarakat, terutama masyarakat yang berada di garis kemiskinan, menjadi kesulitan untuk mengakses pendidikan. Sehingga pemerintah perlu untuk lebih memberikan perhatian terhadap akses pemerataan pendidikan dengan cara memberikan bantuan-bantuan kepada kalangan masyarakat yang kurang mampu. Bantuan dalam bentuk beasiswa, biaya, subsidi buku maupun seragam. Perlu adanya program beasiswa dan bantuan biaya pendidikan, ataupun pendidikan gratis bagi kalangan masyarakat yang kurang mampu. Sehingga masyarakat kalangan kurang mampu juga dapat mengakses pendidikan seperti kalangan masyarakat yang lain.
3. Pemerataan akses informasi dan teknologi
Di era digital ini, akses informasi dan teknologi menjadi salah satu sarana dalam memperoleh dan melaksanakan pendidikan. Karena dengan internet dan teknologi, tidak hanya pendidikan dan pembelajaran sekolah yang bisa diperoleh. Terdapat berbagai macam ilmu dan pengetahuan yang bisa diperoleh. Penggunaan internet dan teknologi juga dapat mempermudah 17
penyampaian dan peroleh ilmu pendidikan, baik bagi pengajar ataupun peserta didik. Dengan tidak meratanya akses internet dan teknologi ke daerah-daerah pelosok Indonesia, dapat menghambat masyarakat yang hidup di daerah-daerah tersebut untuk memperoleh informasi dan pengetahuan. Sehingga pemerataan akses internet dan teknologi ke daerah-daerah pelosok Indonesia juga perlu menjadi perhatian utama pemerintah.
4. Penyediaan sekolah dan pendidikan inklusif
Pemerataan akses pendidikan juga sangat diperlukan bagi kalangan penyandang disabilitas. Ketidakseimbangan akses pendidikan bagi kalangan penyandang disabilitas dapat terjadi karena adanya stigma dan pandangan buruk dari masyarakat. Pandangan buruk yang ada pada masyarakat membuat adanya eksklusifitas dalam lingkungan pendidikan, yang membuat anak anak-anak berkebutuhan khusus semakin kesulitan untuk menjangkau akses pendidikan (Jauhari, 2017). Sehingga pemerintah harus sangat memperhatikan pemerataan akses pendidikan bagi kalangan penyandang disabilitas, agar mereka tetap mendapatkan hak dan akses yang sama dalam pendidikan. Dan dalam perwujudan pemerataan akses pendidikan bagi penyandang disabilitas, diperlukannya sekolah atau pendidikan yang bersifat inklusif. Sekolah inklusif yang aman dan nyaman, sumber daya pengajar dan pendamping, fasilitas pembelajaran yang mendukung, lingkungan pendidikan dan aman, nyaman, dan ramah bagi kalangan penyandang disabilitas. Menurut Jauhari (2017), ada empat karakteristik dari pendidikan inklusif, yaitu:
a. pemberian kurikulum yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas
b. pendekatan pembelajaran yang fleksibel dan mudah dipahami
c. pembelajaran yang ramah dan nyaman
d. sistem penilaian yang fleksibel, memperhatikan kebutuhan dan kemampuan dari penyandang disabilitas.
Tim Penulis
Annisa Ananta Widodo
Farah Dila Safitri
Khansa Fithaniyah
Syafira Audia Pinkan
Anindya Naura




























![[OPINI] Menakar Kelayakan Thomas Djiwandono Jadi Deputi BI](https://image.idntimes.com/post/20250115/sesi-1-sal02498-7b8580309183379b3c8eba91d7bc3c5b-273b07c328eb87f261cb80b9e2a0fd07_watermarked_idntimes-1.JPG)
![[OPINI] Apakah Perubahan Kemasan Produk Menjadi Saset Tanda Resesi?](https://image.idntimes.com/post/20260208/perubahan-ukuran-sachet-resesi-ekonomi_57b6ce7b-02bb-459b-b0d3-ce678054e335.JPG)
![[OPINI] Kenapa Tulisan yang Ditulis Sendiri Sering Dibilang Buatan AI?](https://image.idntimes.com/post/20260123/alasan-gak-semua-hal-layak-ditulis-menulis-berlebihan_d71a7bb9-f249-48fb-be75-26f38e13ac2f.jpeg)

![[OPINI] Relasi Epstein-Chomsky, dan Integritas Intelektual Kiri](https://image.idntimes.com/post/20260204/efta00003652-0_3909c293-079d-4870-ba54-8c60af9ef07b.jpg)
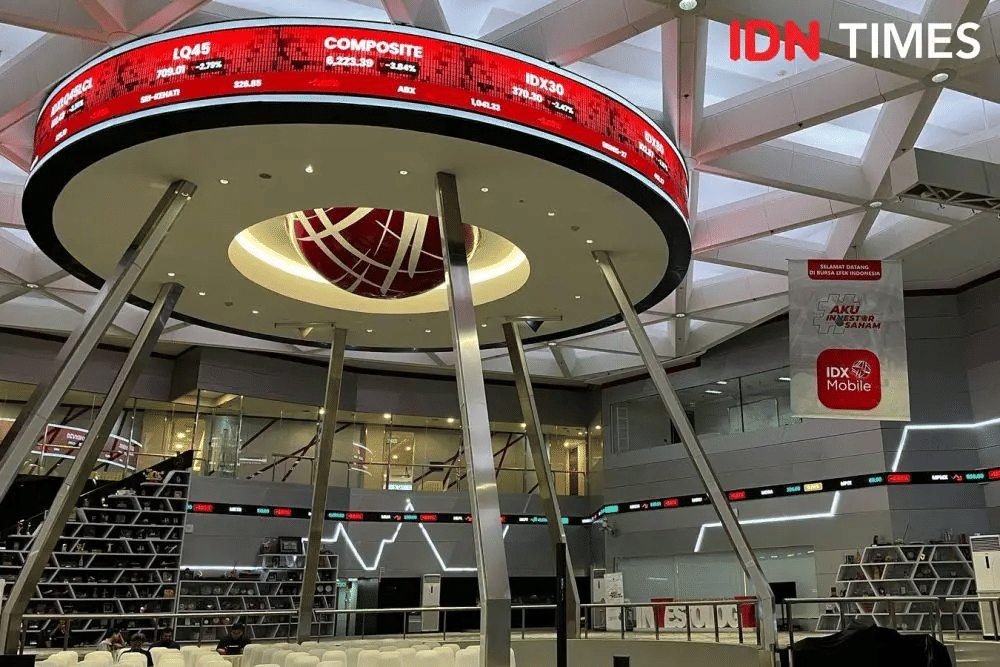


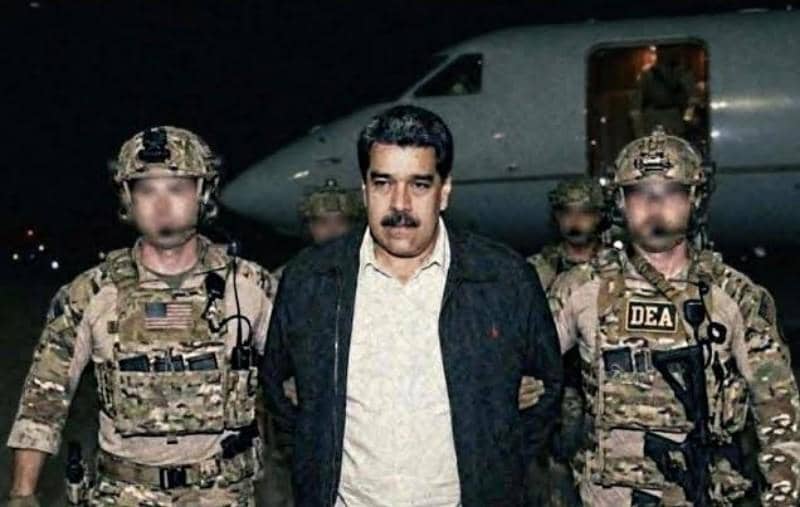


![[OPINI] Berhenti Berlindung di Balik Kalimat “Aku Orangnya Emang Begini”](https://image.idntimes.com/post/20251018/pexels-kampus-7555858_e0f0519c-fde0-4ab4-8965-0e12dabbd0b7.jpg)
![[OPINI] Peran Perempuan dalam Wujudkan Harmoni Sosial dan Lingkungan](https://image.idntimes.com/post/20250802/pexels-julia-m-cameron-8841582_4f4cbb51-bd42-46f6-ba78-fa42532e55a6.jpg)

![[OPINI] Setelah Chavez dan Castro: Ujian Revolusi Bolivarian](https://image.idntimes.com/post/20260108/upload_dd95bcd42f154a2960cdda3ed70e7109_4c8d29e1-0272-4459-9dbd-c40eeccc46c8.jpg)
![[OPINI] Nikah Muda: Alasan Kenapa Gak Semua Cerita Cinta Bisa Ditiru](https://image.idntimes.com/post/20260103/pexels-danu-hidayatur-rahman-1412074-2852135_2f19e731-6a9c-4db9-8adb-4642e15915d2.jpg)


