[NOVEL] Redum-BAB 2
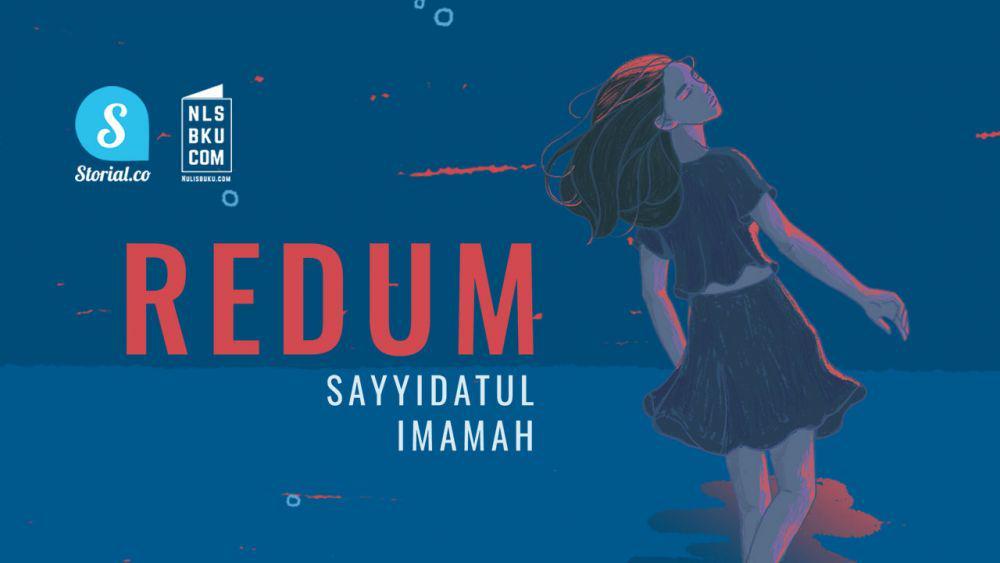
Anna mimisan lagi pagi ini, di meja makan. Ibu terlihat sangat panik sampai rasanya seluruh meja makan bisa jadi alat untuk menghentikan mimisan Anna. Ayah mencoba membantu dengan berdiri di samping mereka berdua, sedangkan Anna tersenyum ke arahku di sela-sela tangan Ibu yang mengusap darah di hidungnya.
Dia sudah sering mimisan. Sering yang aku maksud adalah seperti kegiatan rutin bulanan. Terkadang, aku pikir Anna adalah kumpulan bunga layu yang punya darah dan daging. Dia begitu mudah sakit, terkena memar, dan pusing. Kami hanya membawa Anna ke puskesmas dan dokter bilang Anna mungkin harus diperiksa di rumah sakit karena peralatan di puskesmas yang kurang memadai. Namun, Ayah sedang sibuk dengan pekerjaannya. Dia hampir naik jabatan kalau rajin datang ke kantor, sedangkan Ibu selalu menuruti kata Anna. Kalau Anna tidak mau ke rumah sakit, maka Ibu tidak akan membawanya. Apalagi, Anna selalu bilang, "Ini hanya mimisan biasa." Atau, "Ini hanya sakit biasa."
Aku tidak mau masuk ke dalam dunia Anna yang sakit dan lemah. Aku ada di dunianya yang penuh musik, cerita, dan keceriaan. Maka, aku tidak pernah mau ikut campur dalam hal itu. Ketika Ayah sudah punya waktu untuk ke rumah sakit, mereka kadang melupakannya karena Anna sudah kelihatan sehat. Namun, hari ini, Anna mimisan lagi dan tentu saja itu mengingatkan mereka untuk pergi ke rumah sakit.
"Kami bisa terlambat nanti," kata Anna. "Lagian, ini hanya mimisan."
Biasa.
Ibu memejamkan matanya rapat-rapat, lalu melirikku. "Nora hari ini berangkat sendiri saja-"
"Buuu."
Cara Anna merengek selalu seperti itu, memanjangkan huruf vokal dengan bibir mengerut. Dengan cara itu juga dia selalu bisa meluluhkan hati Ibu. Ayah adalah penentu keputusan di keluarga kami. Dan, dia memutuskan kalau Anna akan sekolah. Ketika semua drama itu selesai, kami akhirnya berangkat ke sekolah bersama. Aku dan Anna berjalan berdampingan di trotoar, membicarakan tentang tahun terakhirku di sekolah dan universitas impianku.
"Kenapa harus di luar kota?" Anna mendahuluiku, lalu berbalik badan dan melangkah mundur. Itu juga salah satu kebiasaannya.
"Karena kota ini mirip sehelai kertas."
"Artinya?"
"Artinya, aku sudah membaca semua hal yang ada di sehelai kertas itu dan aku harus membalik kertas lain untuk membacanya juga."
Anna mengerutkan dahi. "Kalau begitu, aku akan kuliah di luar kota juga."
"Kalau untuk mengikutiku saja, tidak usah."
Dia menggeleng. "Itu karena aku sudah tahu kalau kota ini hanya sehelai kertas."
Aku ikut berjalan mundur di sampingnya. Kalau ada tiang atau seseorang yang berjalan ke arah kami, sudah pasti kami akan menabraknya.
"Boleh aku ikut makan dengan kalian di meja pojok nanti?" tanyanya.
Meja pojok adalah tempatku dan Rena selalu makan. "Tidak."
Bukannya aku ingin memisahkan Anna dari Rena. Hanya saja, kali terakhir Rena berbicara dengan Anna adalah dengan memberi tahu Anna kalau 5-MeO-MiPT adalah obat psikedelik yang bertindak cepat. Sebelum aku menghentikannya, Rena menambahkan, "Itu membuat akalmu menyimpang tanpa efek visual."
Yang paling membuatku malas membuat mereka berdekatan adalah: karena Rena menjadi semakin liar ketika bersama Anna. Dia merasa bisa menyuntikkan keliaran itu pada Anna karena menurutnya itu lucu, sedangkan Anna berpikir kalau Rena adalah orang yang tepat untuk menghunjamkan segala rasa penasarannya.
"Kenapa?" Kaki Anna terantuk retakan yang timbul di trotoar. Dia hampir jatuh, tapi aku menahan tangannya. Aku berjongkok untuk memeriksa kakinya, tetapi Anna malah ikut berjongkok. "Kamu selalu memisahkan kami berdua."
"Bukan begitu. Nanti, kami tidak makan di meja pojok."
Anna memicingkan matanya, sama seperti ketika dia memergokiku membohongi Ayah tentang nilaiku.
"Jadi, kalian tidak makan di sana saat aku ingin makan bersama kalian?" Aku berdiri dan mencoba untuk mencari topik pembicaraan lain, tetapi Anna tahu trik itu dan langsung berkata, "Kinan tidak masuk. Dia sedang ke rumah neneknya. Itu artinya nanti aku tidak punya teman untuk makan di kantin dan kamu tahu kalau aku benci makan sendirian. Apalagi, dengan-"
"Anna-"
"-dengan segala hal yang terjadi di kantin."
Aku menatap mata cokelatnya yang mirip tanah di bawah air. "Oke, tapi hanya saat makan siang. Kamu tidak boleh mengikuti kami ke kelas."
"Yeah!" Dia melompat girang lalu berjalan zig-zag di depanku.
Aku harap Rena sedikit mabuk pagi ini agar dia tidak punya tenaga untuk berbicara dengan Anna.
***
Rena tidak mabuk.
Namun, dia lesu.
Dia menaruh kepalanya di meja ketika aku sampai di kelas dan aku hanya duduk di sampingnya tanpa menyapa. Rena tidak mengangkat kepalanya ketika guru masuk. Aku menaruh buku di depannya seperti sebelum-sebelumnya. Namun, Bu Nani sudah muak dengan trik itu. Dia menghampiri meja Rena dan membangunkannya. Awalnya, hanya dengan teguran. Ketika Rena tidak merespons, guru itu menggoyang-goyangkan tubuh Rena.
Rena mengangkat kepalanya dan membuat seisi kelas memekik kaget ketika melihat mata kiri Rena yang lebam dan sudut bibirnya yang pecah. Aku langsung menutupi wajah Rena dengan buku, lagi. Bu Nani mendelik ke arahku lalu menatap prihatin pada Rena.
"Ikut saya ke UKS, Direna."
Rena memutar bola matanya. "Tidak mau."
"Ajak dia, Nora."
Guru-guru selalu memanfaatkan aku untuk membuat Rena jinak. Seharusnya, itu membuatku kesal, tetapi itu malah membuatku merasa berguna. Aku menarik tangan Rena tanpa mengatakan apa pun dan Rena tidak menolak tarikan itu.
Guru yang bertugas di UKS mendesis prihatin pada keadaan Rena. "Kenapa bisa sampai seperti ini?" tanyanya.
Rena menjawab dengan malas. "Kepentok pintu saat lampu mati."
Bu Nani berdiri dengan tegap di samping ranjang. Dia lebih banyak melirikku daripada Rena. Walaupun ini baru kali ketiga Rena berulah di sekolah, tetapi aku tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku akan duduk di ruang kepala sekolah, menceritakan dengan wajah polos bahwa aku tidak tahu apa pun yang terjadi pada Rena. Walaupun, sebenarnya, aku tahu apa yang terjadi tanpa diberi tahu oleh Rena.
Tadi malam, sebelum aku berenang di danau sendirian, Rena bilang bahwa dia berharap menjadi buta.
Aku tahu, dia tidak mungkin melakukan itu sendiri. Dia menyulut api pada orang yang salah.
***
Setelah membuat kepala sekolah dan guru konseling di sekolah menyerah menanyaiku, aku kembali ke kelas untuk mengambil tas Rena dan menemui gadis itu di UKS. Rena tergelak ketika melihatku memasuki ruangan. Meskipun di sana masih ada Bu Nani, dia mengeraskan tawanya. Seandainya aku bisa memberi tahu Bu Nani kalau tawa Rena hanya bisa dimengerti jika sudah bersamanya selama bertahun-tahun, mungkin aku tidak perlu menatap ekspresi kebingungan Bu Nani.
"Apa yang mereka katakan?" tanya Rena di sela tawanya. "Mereka tanya apakah ayahku sialan?"
Sebenarnya, orang tua Rena sudah meninggal karena kecelakaan dan semua guru tahu itu.
Aku mengangkat bahu. "Kurang lebih begitu."
Bu Nani menatap kami berdua dengan lelah. Matanya mengingatkanku pada Ibu saat melihat aku dan Anna bertengkar tentang hal konyol. "Kalian akan Ibu tinggalkan di sini, tapi nanti akan ada guru yang akan datang. Jangan berani-berani kabur," kata Bu Nani. "Rena, kakakmu akan dipanggil."
Raut wajah Rena berubah. Wajahku mungkin juga begitu.
Luan akan ke sini untuk kali kedua. Bukan kabar baik.
"Bu, ayolah, Bu. Saya benaran kejedot pintu, kok. Tadi malam, lampu di rumah saya mati. Saya kebelet pipis, sampai nggak tahu kalau pintu masih ditutup. Jadinya kejedot, deh."
"Rena, kamu sudah dewasa. Dan, kamu tahu kalau sekolah ini tidak akan membiarkan kekerasan jenis apa pun terjadi-"
"Ini bukan kekerasan, kok, Bu. Sumpah."
Bu Nani menggeleng sedih. "Kami akan membantu, Rena. Kamu harus tahu itu. Kami di sini dan akan membantumu. Kalau kamu mau berterus terang tentang apa yang terjadi di rumah ...." Guru itu menggantung kata-katanya di udara, membuatku mengisi kalimat lanjutannya.
Kamu bisa menceritakannya pada kami.
Rena melirikku, ada sirat kegelian di sana. "Itu urusan saya, bukan urusan sekolah."
"Kamu merupakan siswa di sekolah ini dan itu artinya kamu menjadi tanggung jawab kami."
Rena membasahi bibirnya. Itu adalah usahanya untuk menahan agar tidak berkata kasar. "Terserah, deh, Bu."
Bu Nani keluar dengan wajah penuh kemenangan.
Aku membiarkan suasana aneh tadi menjauh dengan mengatakan, "Mereka masih mencurigai Luan."
"Memang seharusnya begitu."
Rena sangat membenci Luan. Dia sering bilang bahwa Luan adalah manusia dengan IQ nol yang bertahan hidup hanya dengan memelas.
Aku juga tidak terlalu menyukai Luan, tetapi aku tidak membencinya. Dia pernah membiarkanku menangis tanpa memelukku. Dia juga tidak pernah dengan sengaja menyenggol payudaraku ketika kami duduk bersama-tidak seperti lelaki lainnya. Dia baik. Rena hanya bersikap defensif terhadap keadaan yang menimpanya selama ini, lalu dia melampiaskan segalanya pada Luan.
"Dia tidak bersalah, Ren."
Rena melotot. "Dia bersalah!"
"Kevin melukaimu lagi," kataku. "Kalian bertengkar lagi."
Rena memunggungiku. "Dia hanya kelepasan. Dia selalu seperti itu. Dia hanya memukulku sekali, lalu menangis."
Aku ingin mengatakan kalau hubungan Rena dengan Kevin tidak sehat, tetapi itu pasti akan membuat Rena murka. Dia jatuh cinta setengah mati pada lelaki itu. Lelaki yang pernah membenturkan kepala Rena ke dinding, lelaki yang memakinya lebih sering dari siapa pun, lelaki yang menjerumuskannya pada dunia sialan.
"Kami akan pindah." Kalimat itu mengejutkanku. Rena membalikkan badan untuk menghadapku lagi. "Satu bulan lagi, ketika Kevin sudah bisa membayar utangnya. Kami akan hidup bersama, Ra. Di luar kota, jauh dari sini. Kami akan bahagia."
Aku menahan diri untuk tidak menarik kepala Rena lalu mengguncangnya untuk membuat seluruh isi otaknya yang gila keluar, sehingga hanya menyisakan yang waras saja.
"Kalian akan pergi," kataku.
"Kami akan pergi."
"Ke mana tepatnya?"
"Ke rumah Kevin."
"Dan, kamu pikir di sana tidak ada orang tuanya?"
Rena terkikik. "Kevin bilang, dia akan membunuh mereka."
"Ren."
"Bercanda, kok. Orang tua Kevin itu orang kampung dan mereka akan menerimaku. Kevin sudah janji."
"Lalu, kenapa dia mukul kamu?"
Rena menoleh ke arahku. "Aku bertanya tentang hal yang salah."
"Apa?"
Dia membiarkan keadaan hening untuk sementara. Lalu, dia menggigit bibir. Tangan kirinya meraba pergelangan tangan kanannya-itu selalu dia lakukan ketika gugup-tempat di mana bekas luka itu berada. "Aku tanya bagaimana kalau ... aku hamil."
***
Baca ribuan cerita seru dan tuliskan ceritamu sendiri di Storial!
storial.co
Facebook: Storial
Instagram: storialco
Twitter: StorialCo
YouTube: Storial co














































