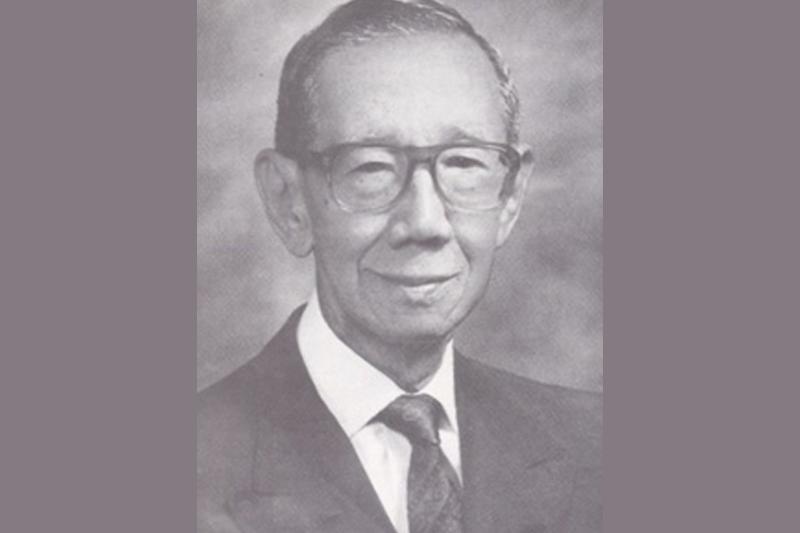JakTV, Kejaksaan, dan Pertarungan Makna dalam Demokrasi Informasi

Artikel ini ditulis oleh Cakra Mudra, Mahasiswa Pascasarjana Kajian Stratejik Intelijen,
Program Studi Ketahanan Nasional, Sekolah Kajian Stratejik dan Global, Universitas Indonesia
Memahami, bukan Membungkam: Upaya Melampaui Polarisasi dalam Kontestasi Opini Publik
Penahanan Tian Bahtiar, Direktur Pemberitaan JakTV (JAK TV), oleh Kejaksaan Agung pada April 2025 menjadi babak baru dalam dinamika relasi antara media, hukum, dan kekuasaan di Indonesia. Tian ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menerima dana ratusan juta rupiah dari dua advokat untuk menyebarkan konten pemberitaan yang menggiring opini publik dan dianggap menyudutkan Kejaksaan Agung dalam perkara ekspor CPO, tambang timah, dan impor gula.
Menurut Kejagung, konten tersebut bukanlah produk jurnalistik murni, melainkan hasil rekayasa yang ditujukan untuk membentuk persepsi negatif terhadap institusi hukum. Ketiganya kini dijerat dengan Pasal 21 UU Tipikor tentang perintangan proses penyidikan.
Langkah ini memunculkan pro dan kontra. Sebagian kalangan memujinya sebagai upaya tegas penegak hukum untuk melindungi proses peradilan dari intervensi opini. Namun tak sedikit pula yang melihat ini sebagai ancaman terhadap kebebasan pers dan ruang kritik yang sah.
Di era digital, informasi bukan sekadar data. Ia adalah kekuatan. Narasi bisa menjadi alat untuk membentuk opini, memengaruhi arah kebijakan, bahkan mengubah persepsi publik terhadap sebuah institusi. Media, yang semula berfungsi sebagai pengawas kekuasaan, kini rentan menjadi alat kekuasaan baru—terutama ketika ia beroperasi di bawah pesanan atau tekanan kepentingan tertentu.
Dalam studi strategis, hal ini dikenal sebagai influence operations—upaya sistematis untuk mengubah cara publik memandang suatu isu melalui pengelolaan informasi. Operasi semacam ini tidak hanya dilakukan oleh negara, tapi juga oleh aktor non-negara seperti firma hukum, konsultan politik, atau bahkan individu yang memiliki akses terhadap media dan ruang publik.
Dalam sistem demokrasi, kritik terhadap lembaga negara adalah hal yang wajar, bahkan penting. Pers harus diberi ruang untuk menyoroti kinerja institusi penegak hukum, termasuk Kejaksaan Agung. Namun, yang jadi soal adalah ketika kritik tersebut tidak lahir dari proses jurnalistik yang independen, melainkan dari transaksi tersembunyi yang bertujuan untuk melemahkan legitimasi hukum.
Di sinilah kita perlu bersikap jernih. Bukan untuk membungkam kritik, tetapi untuk menjaga agar kritik tetap otentik. Jika konten yang disebarkan oleh media adalah bagian dari kampanye bayaran untuk menggiring opini dan merusak proses hukum, maka ini bukan lagi soal kebebasan pers, melainkan penyalahgunaan kekuatan media.
Kritik terhadap lembaga hukum tetap harus dilindungi, tetapi kritik yang dimanipulasi untuk menghalangi keadilan patut ditelusuri secara hukum. Di titik inilah pentingnya Dewan Pers dan lembaga etik lainnya. Mereka harus diberi ruang untuk menilai apakah sebuah karya jurnalistik benar-benar layak disebut demikian, ataukah telah berubah menjadi alat propaganda terselubung.
Begitu pula dengan aparat penegak hukum. Mereka perlu berhati-hati agar tidak terjebak dalam kecenderungan represif. Penindakan terhadap pelaku penyebaran informasi harus berbasis bukti yang jelas, dan tidak menimbulkan efek ketakutan bagi jurnalis lain yang bekerja secara profesional.
Kasus JAK TV mencerminkan bagaimana demokrasi informasi menghadapi tantangan serius. Di satu sisi, kita hidup di era keterbukaan, di mana publik bisa mengakses beragam informasi. Tapi di sisi lain, keterbukaan ini juga memunculkan risiko manipulasi, hoaks, dan rekayasa persepsi.
Ketika narasi bisa dibeli, dan ketika opini publik bisa dikendalikan melalui konten yang tampaknya sah, maka ancaman terhadap demokrasi tidak lagi datang dari sensor, tapi dari banjir informasi yang tidak jujur.
Yang harus dibangun adalah ruang publik yang sehat—di mana media tetap bebas, tetapi bertanggung jawab. Di mana lembaga hukum tetap tegas, tetapi tidak sewenang-wenang. Dan di mana masyarakat punya kapasitas untuk menyaring informasi dan memahami motif di balik setiap narasi.
Kasus ini seharusnya tidak dipahami secara biner: antara “media lawan negara” atau “hukum lawan kebebasan.” Justru sebaliknya, ini adalah pengingat bahwa di era informasi, semua pihak—media, lembaga hukum, dan masyarakat—punya tanggung jawab bersama untuk menjaga integritas ruang publik.
Keadilan tidak akan tegak di ruang yang dipenuhi kebisingan narasi pesanan. Dan demokrasi tidak akan kuat jika kritik hanya dibolehkan ketika sesuai dengan kepentingan tertentu.
Dalam dunia yang makin dipenuhi kabar, narasi, dan citra, mungkin tugas kita sebagai warga bukan lagi hanya mencari kebenaran, tetapi juga menjaga makna.



























![[OPINI] Menakar Kelayakan Thomas Djiwandono Jadi Deputi BI](https://image.idntimes.com/post/20250115/sesi-1-sal02498-7b8580309183379b3c8eba91d7bc3c5b-273b07c328eb87f261cb80b9e2a0fd07_watermarked_idntimes-1.JPG)
![[OPINI] Apakah Perubahan Kemasan Produk Menjadi Saset Tanda Resesi?](https://image.idntimes.com/post/20260208/perubahan-ukuran-sachet-resesi-ekonomi_57b6ce7b-02bb-459b-b0d3-ce678054e335.JPG)
![[OPINI] Kenapa Tulisan yang Ditulis Sendiri Sering Dibilang Buatan AI?](https://image.idntimes.com/post/20260123/alasan-gak-semua-hal-layak-ditulis-menulis-berlebihan_d71a7bb9-f249-48fb-be75-26f38e13ac2f.jpeg)

![[OPINI] Relasi Epstein-Chomsky, dan Integritas Intelektual Kiri](https://image.idntimes.com/post/20260204/efta00003652-0_3909c293-079d-4870-ba54-8c60af9ef07b.jpg)
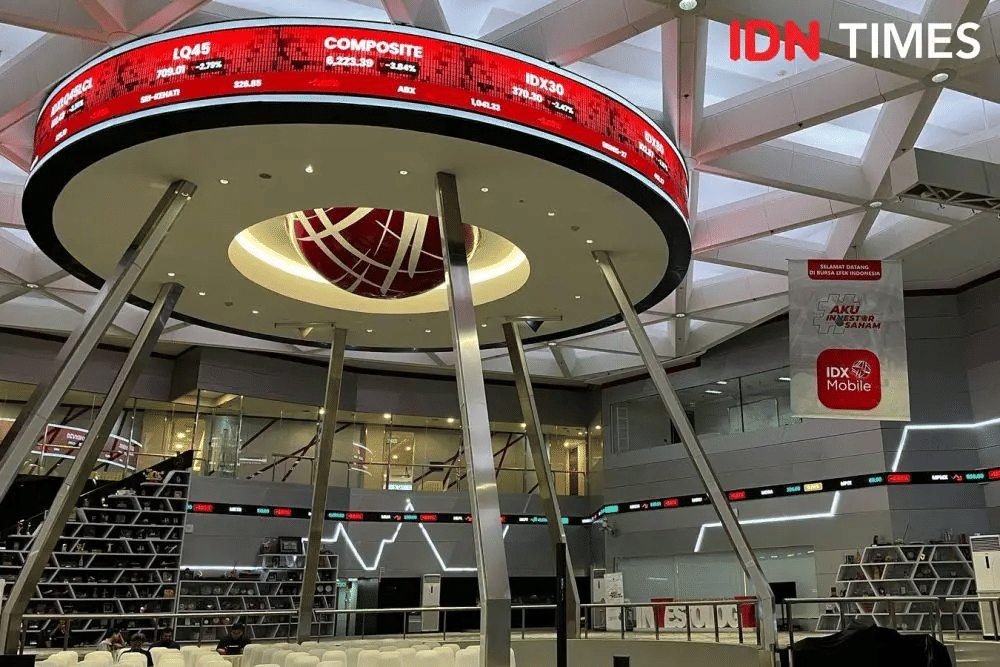


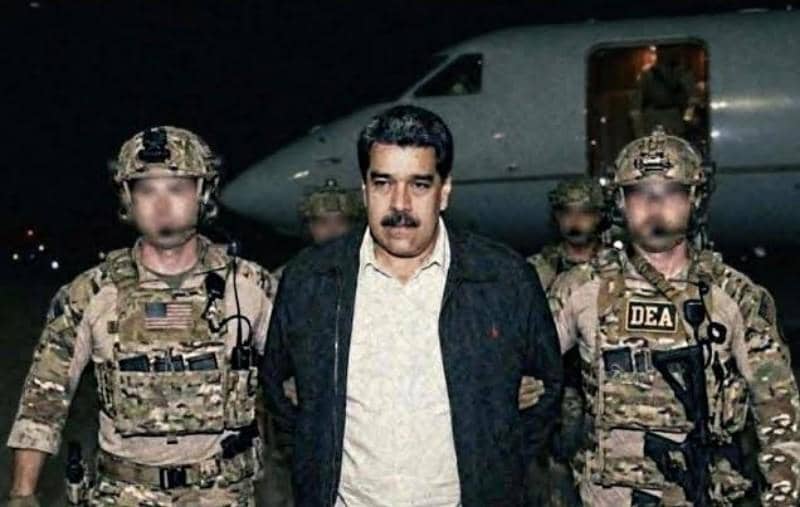


![[OPINI] Berhenti Berlindung di Balik Kalimat “Aku Orangnya Emang Begini”](https://image.idntimes.com/post/20251018/pexels-kampus-7555858_e0f0519c-fde0-4ab4-8965-0e12dabbd0b7.jpg)
![[OPINI] Peran Perempuan dalam Wujudkan Harmoni Sosial dan Lingkungan](https://image.idntimes.com/post/20250802/pexels-julia-m-cameron-8841582_4f4cbb51-bd42-46f6-ba78-fa42532e55a6.jpg)

![[OPINI] Setelah Chavez dan Castro: Ujian Revolusi Bolivarian](https://image.idntimes.com/post/20260108/upload_dd95bcd42f154a2960cdda3ed70e7109_4c8d29e1-0272-4459-9dbd-c40eeccc46c8.jpg)
![[OPINI] Nikah Muda: Alasan Kenapa Gak Semua Cerita Cinta Bisa Ditiru](https://image.idntimes.com/post/20260103/pexels-danu-hidayatur-rahman-1412074-2852135_2f19e731-6a9c-4db9-8adb-4642e15915d2.jpg)