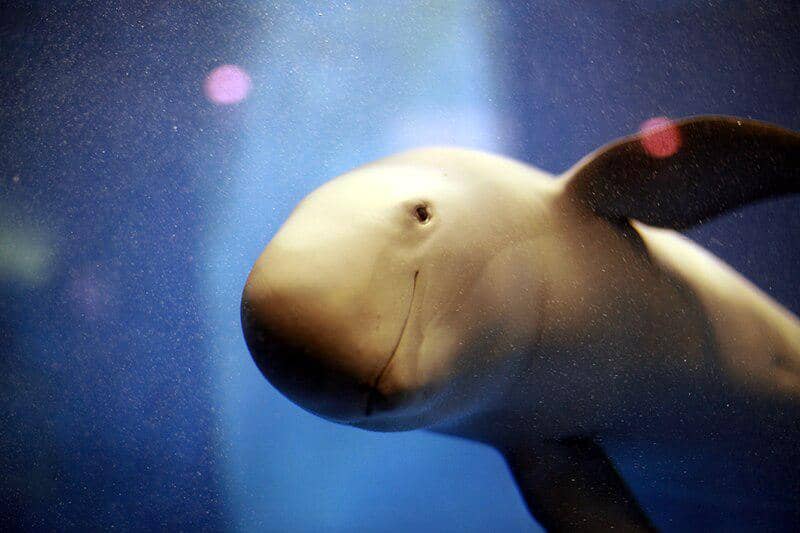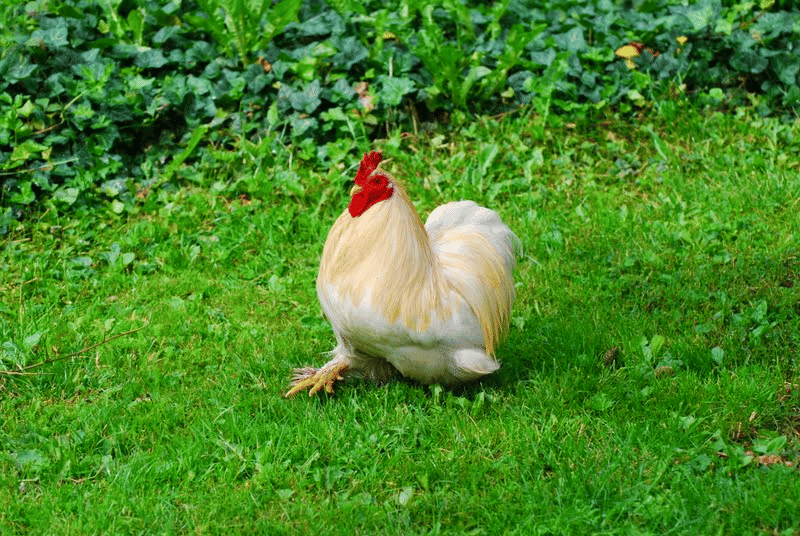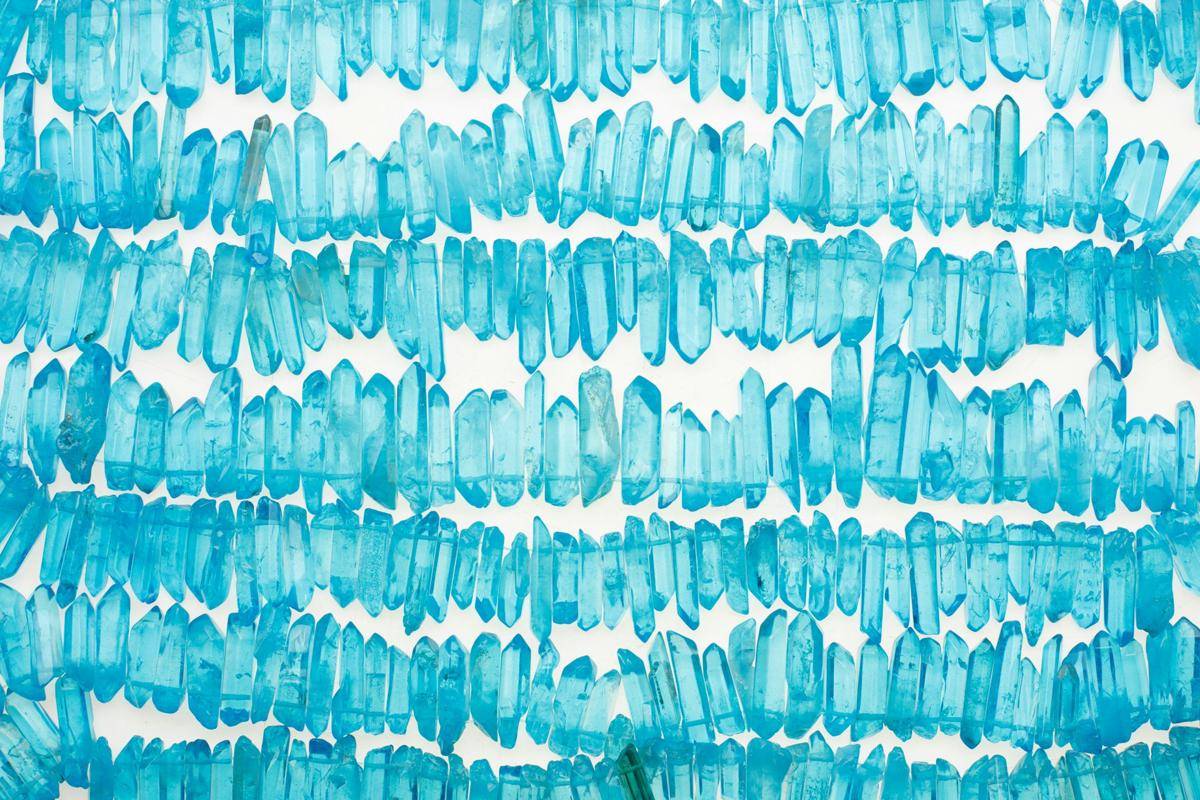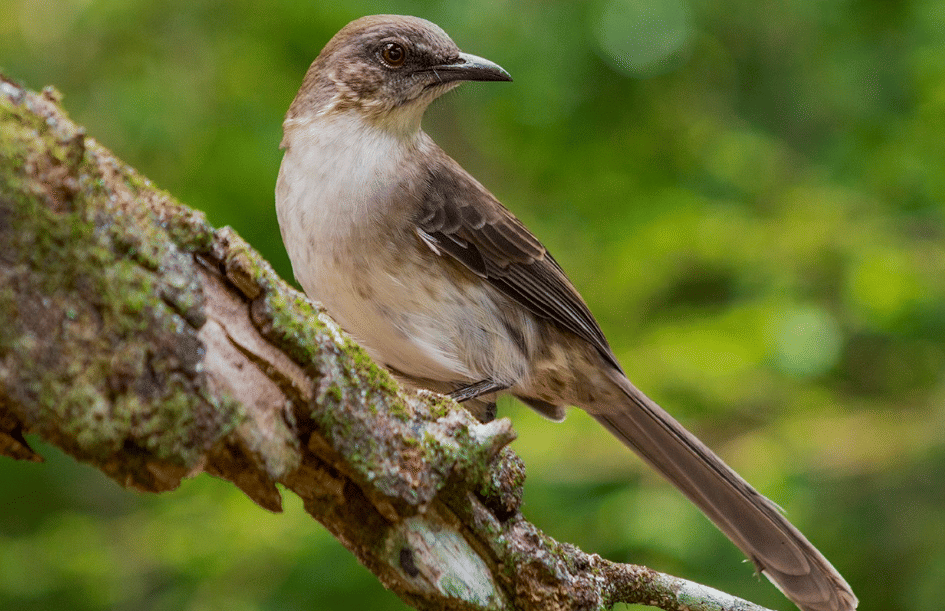Apa Itu ACAB? Ketahui Asal-usul Sentimen Antiaparat Ini

All cops are bastards (ACAB) jadi salah satu jargon yang bermunculan belakangan ini. Sesuai dengan artinya yang mempertanyakan akuntabilitas dan kejujuran polisi, ia sering naik ke permukaan tiap kali polisi melakukan blunder serta penyalahgunaan kekuasaan, terutama saat mengatasi keramaian, seperti unjuk rasa, pertandingan olahraga, konser musik, dsb. Pertanyaannya, apa itu ACAB dab dari mana asal-usulnya? Kenapa pula sentimen antiaparat di kalangan warga sipil bisa jadi masalah global?
1. Jargon ACAB populer seiring kemunculan skena musik punk dan rap

ACAB erat kaitannya dengan skena musik punk yang naik ke permukaan pada 1970-an. Merujuk buku A Dictionary of Catch Phrases yang ditulis Eric Partridge, ACAB dipopulerkan oleh jurnalis majalah New Society di Inggris yang sempat ditangkap polisi saat meliput sebuah aksi protes dan harus mendekam semalam di penjara. Di sana, ia takjub melihat berbagai grafiti bertuliskan ACAB di dinding-dinding sel tahanan. Namun, ada pula yang percaya bahwa jargon ini sudah ada sejak 1920-an dan secara umum dipakai untuk meluapkan kekesalan warga terhadap polisi maupun aparat. ACAB secara umum adalah keyakinan bahwa tidak ada polisi yang bisa dipercaya, tak peduli sebaik dan sesopan apa mereka bersikap.
Kenaikan popularitas jargon itu sepertinya didukung pula oleh kebangkitan skena musik punk dan rap. Merujuk tulisan Florian Griese yang berjudul "Lyrics of Dissident Youth Cultures and Police Misconduct in the United States" dalam The Annual Review of Criminal Justice Studies, lagu-lagu rap dan punk kerap menyenggol sentimen antipolisi. Ini tidak mengejutkan. Bila kita perhatikan, skena rap dan punk sangat erat kaitannya dengan kelas pekerja dan tuntutan-tuntutan mereka yang dianggap menggebrak status quo, contohnya ekspresi keberatan terhadap kebijakan ekonomi neoliberal Ronald Reagan di Amerika Serikat dan Margaret Thatcher di Inggris Raya. Lantas, apa kaitannya dengan polisi?
2. Menjaga keadilan dan mengatasi kriminalitas bukan tujuan awal pembentukan satuan polisi

Ada fakta menarik yang dielaborasi Aya Gruber dalam jurnal Houston Law Review berjudul "Policing and 'Bluelining'". Dalam tulisannya itu, Gruber mengungkap bahwa polisi awalnya tidak dibentuk untuk tujuan menjaga keadilan dan mengatasi kriminalitas. Satuan polisi modern mulai terbentuk pada awal abad ke-19 dan sejak awal mengakomodasi kepentingan kelas penguasa. Di Amerika Serikat, terutama di bagian selatan, anggota polisi merupakan rekonstitusi dari satuan pengamanan yang dibayar untuk menjaga budak-budak asal Afrika. Intinya, mereka adalah orang-orang yang memang bekerja atas pesanan pemilik lahan dan perkebunan.
Di bagian utara Amerika Serikat, kepentingan kelas penguasa merujuk pada imigran dari negara Eropa yang relatif miskin. Mengisi pos-pos buruh kelas bawah, kelas penguasa alias pemilik modal biasanya khawatir bila mereka mulai menuntut dan berserikat. Di sinilah, biasanya polisi diturunkan untuk mempertahankan status quo. Mereka diturunkan untuk mencegah pekerja berserikat dan membubarkan protes. Pola serupa bisa ditemukan pula di Inggris Raya.
Di Australia dan Kanada pada awal abad ke-19, tugas mereka melancarkan asimilasi warga pribumi. Meski terlihat agak berbeda, sebenarnya tujuan finalnya sama: menguasai lahan milik warga pribumi untuk kepentingan pemilik modal. Pola-pola keberpihakan tadi sampai sekarang masih sering terlihat dan diaplikasikan di berbagai tempat, termasuk di Indonesia.
3. Politisi kerap berkolaborasi dengan polisi untuk kepentingan tertentu

Selain pemilik modal, politisi adalah kolaborator setia polisi. Masih merujuk tulisan Gruber, beberapa Presiden Amerika Serikat menggunakan dalih kriminalitas sebagai salah satu cara menggaet suara saat pemilu. Richard Nixon, Ronald Reagan, sampai Trump sering menciptakan “musuh bersama”, seperti hippie, kaum minoritas, dan imigran untuk menciptakan kesan darurat keamanan di kalangan mayoritas (warga kulit putih). Ketika urgensi dan kekhawatiran terbentuk, mereka bisa dengan mudah melancarkan kebijakan-kebijakan yang nantinya menguntungkan kelompok-kelompok tertentu.
Subsidi dan jaminan sosial/ekonomi bagi kelompok rentan kerap dibatasi karena mereka dianggap kriminal dan penyebab ketidaktertiban. Sementara itu, anggaran kepolisian justru dinaikkan disertai praktik segregasi rasial dan bentuk diskriminasi lain. Tak heran, alih-alih mengamankan aksi protes di sisi massa, polisi sering bertindak sebagai tameng penguasa dengan memblokade akses menuju gedung perwakilan rakyat.
Masih merujuk Gruber, fakta di Amerika Serikat membuktikan kalau meningkatkan anggaran untuk keamanan (menambah personel dan perangkat) tidak serta-merta mengurangi angka kriminalitas. Baltimore, salah satu kota dengan rekor kekerasan dan kriminalitas tertinggi di Amerika Serikat, akhirnya memecahkan rekor penurunan angka pembunuhan serta kasus kriminal yang signifikan pada 2025. Kebijakan nirkekerasan Wali Kota Brandon Scott dipercaya sebagai pemicunya. Ia memilih melakukan pencegahan ketimbang mengatasi. Caranya dengan mengaktifkan kembali kegiatan komunitas yang berfaedah dan menyasar langsung pihak-pihak yang rentan jadi korban maupun pelaku kriminal.
Jargon ACAB alias sentimen antipolisi ternyata lekat kaitannya dengan sejarah pembentukannya. Sejak awal, polisi tidak sepenuhnya hadir untuk rakyat, melainkan lahir dari relasi patron-klien antara penguasa dan bawahan. Ada isu kelas dan kepentingan yang sulit dipisahkan dari eksistensi polisi. Tak heran bila warga sipil memilih untuk menjaga jarak dan mempertanyakan netralitas mereka.