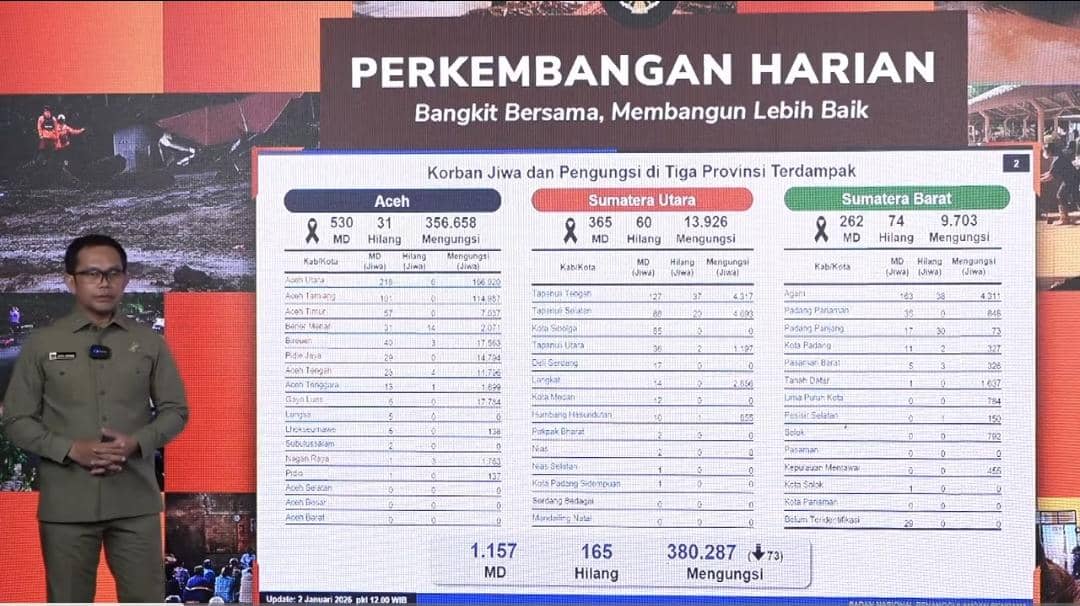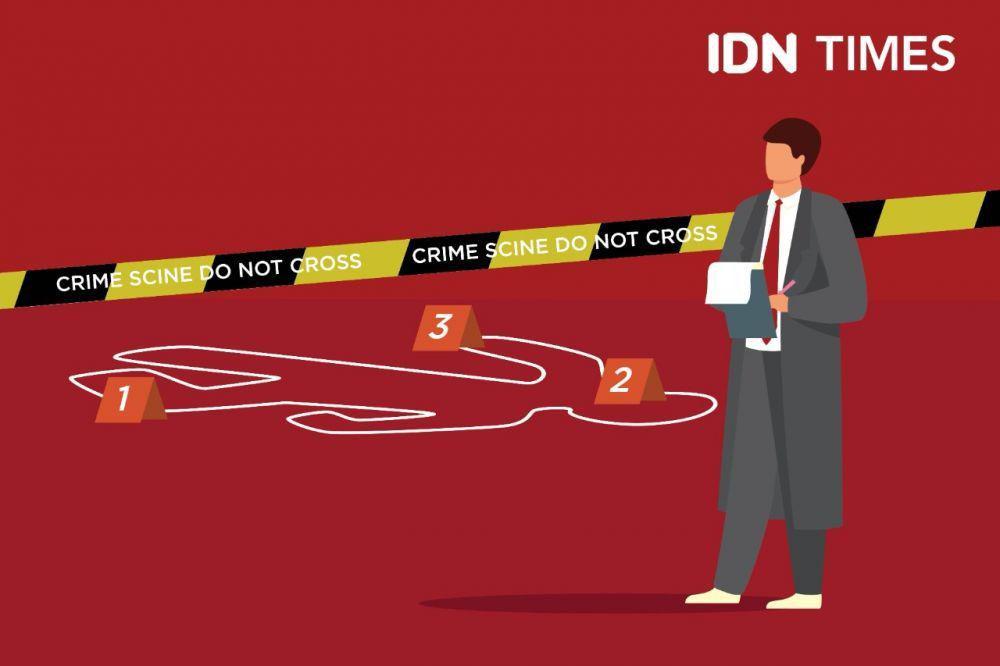RUU TNI dan Sejarah Dwifungsi ABRI, Mengancam Demokrasi?

- RUU TNI menimbulkan kekhawatiran publik karena dapat menghidupkan kembali dwifungsi ABRI era Orde Baru.
- Sejarah dwifungsi ABRI dimulai dari kebijakan Presiden Sukarno dan membawa dampak besar bagi demokrasi di Indonesia.
- Draf RUU TNI dinilai mengandung pasal bermasalah yang dapat mengembalikan Dwifungsi TNI dan menguatkan militerisme, seperti perluasan jabatan sipil bagi perwira aktif TNI.
Jakarta, IDN Times - Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) yang tengah berlangsung di DPR memicu kekhawatiran publik. Beberapa poin yang menjadi sorotan adalah perluasan peran TNI di jabatan sipil, mengatasi masalah narkotika, membantu penanganan isu keamanan siber, menyelamatkan WNI, dan kepentingan nasional di luar negeri. Poin-poin ini dikhawatirkan dapat menghidupkan kembali Dwifungsi ABRI seperti yang terjadi di era Orde Baru.
Sejarah mencatat, keterlibatan militer dalam pemerintahan sipil membawa dampak besar bagi demokrasi di Indonesia. Lantas, apa yang dimaksud dengan Dwifungsi ABRI, bagaimana sejarahnya, dan sejauh mana Revisi UU TNI mengancam kembalinya peran militer dalam kehidupan sipil? Berikut penjelasannya.
1. Sejarah dwifungsi ABRI

Mengutip ANTARA, terbentuknya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) bermula dari kebijakan Presiden Sukarno yang ingin menyatukan angkatan perang dan kepolisian dalam satu wadah. Keputusan ini tertuang dalam Tap MPRS Nomor II dan III Tahun 1960. Sejalan dengan regulasi tersebut, Keputusan Presiden (Keppres) No. 21/1960 menghapus jabatan Menteri Muda Kepolisian dan menggantikannya dengan Menteri Kepolisian Negara, yang kemudian dimasukkan dalam bidang keamanan nasional bersama angkatan perang lainnya.
Pada 19 Juni 1961, Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR) mengesahkan Undang-Undang Pokok Kepolisian No. 13/1961, yang menetapkan Polri sebagai bagian dari ABRI dengan kedudukan sejajar dengan TNI Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU). Penyatuan kekuatan ini bertujuan menyeimbangkan dinamika politik sipil yang berkembang saat itu.
Namun, menguatnya peran militer menimbulkan kekhawatiran bagi Sukarno. Untuk mengimbanginya, ia mereorganisasi undang-undang darurat perang dan menetapkan dirinya sebagai Kepala Penguasa Perang Tertinggi (PEPERTI). Di saat yang sama, ia semakin mendekat dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Sementara itu, pimpinan angkatan bersenjata, terutama Jenderal A.H. Nasution, melihat pengaruh PKI yang semakin besar sebagai ancaman bagi negara, dikutip dari jurnal Asrudin Azwar berjudul Dwifungsi TNI dari Masa ke Masa.
Puncaknya, setelah peristiwa Gerakan 30 September (G30S/PKI) dan kejatuhan Sukarno, militer menjadi kekuatan dominan dalam politik Indonesia. Sejak 1966, angkatan bersenjata menjalankan peran sosial-politik melalui konsep Dwifungsi, yang memungkinkan mereka bertugas di luar kedinasan ABRI, termasuk di sektor legislatif dan eksekutif.
Di era Orde Baru, dwifungsi ABRI semakin mengakar. Militer tidak hanya berperan sebagai alat pertahanan negara tetapi juga mengambil peran dalam pemerintahan. Pengaruhnya kian dominan pasca-peristiwa G30S, dengan dalih menstabilkan situasi dan mengisi kekosongan akibat pembersihan unsur-unsur PKI di berbagai sektor. Hal ini menjadikan militer sebagai pilar utama dalam pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto.
2. RUU TNI berpotensi menghidupkan kembali Dwifungsi ABRI

Adapun draf Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI), dikutip dari Kontras.org, dianggap mengandung sejumlah pasal bermasalah yang dinilai dapat mengembalikan Dwifungsi TNI dan menguatkan militerisme.
Salah satu yang menjadi sorotan utama adalah perluasan jabatan sipil bagi perwira aktif TNI, termasuk di Kejaksaan Agung dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Hal ini dianggap bertentangan dengan prinsip supremasi sipil dan merupakan bentuk nyata dari Dwifungsi TNI. Sebagai alat pertahanan negara, peran TNI seharusnya tidak bercampur dengan institusi penegak hukum seperti Kejaksaan.
Penempatan personel TNI aktif di KKP juga menuai kritik. Sebagai lembaga sipil, KKP seharusnya tidak diisi oleh prajurit TNI yang masih aktif berdinas. Idealnya, setiap prajurit yang menduduki jabatan di institusi sipil harus mengundurkan diri dari kedinasan militer.
Selain itu, perluasan tugas operasi militer selain perang (OMSP) dalam draf RUU TNI juga dipandang berlebihan, terutama terkait kewenangan TNI dalam penanganan narkotika. Seharusnya, upaya pemberantasan narkotika tetap berada dalam koridor sistem peradilan pidana, bukan dalam model perang yang melibatkan militer. Pelibatan TNI dalam tugas ini dinilai berisiko membuka potensi penyalahgunaan kekuasaan.
Lebih lanjut, draf RUU TNI juga menghapus kewajiban persetujuan DPR dalam pelaksanaan OMSP. Kebijakan ini berpotensi melemahkan fungsi kontrol parlemen sebagai wakil rakyat. Tanpa mekanisme pengawasan yang kuat, perluasan peran militer dalam urusan sipil dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan dengan aparat penegak hukum dan lembaga lain dalam menangani permasalahan di dalam negeri.
3. Implikasi RUU TNI terhadap demokrasi

Perluasan peran TNI di luar tugas pertahanan negara dinilai berisiko menghidupkan kembali dwifungsi ABRI, yang dapat mengancam demokrasi dan profesionalisme TNI. Mengutip ylbhi.or.id, pelibatan militer dalam penanganan narkotika berpotensi menempatkan TNI dalam ranah penegakan hukum, yang bukan merupakan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi).
Tanpa mekanisme pengawasan yang ketat, yurisdiksi peradilan militer dalam kasus pidana umum, pelanggaran HAM, atau korupsi yang melibatkan anggota TNI berisiko menghambat proses hukum yang adil. Kekhawatiran ini diperparah dengan kemungkinan militer terjebak dalam praktik bisnis ilegal, seperti yang pernah terjadi di kepolisian.
Draf RUU TNI juga memungkinkan prajurit aktif mengisi jabatan di Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung, yang dinilai dapat merusak independensi peradilan dan memperkuat impunitas di tubuh TNI. Selain itu, RUU ini memberikan wewenang bagi TNI untuk mengisi posisi di Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, yang berpotensi membuka ruang bagi intervensi militer dalam urusan politik dalam negeri, dengan alasan "keamanan negara."
Praktik ini mengingatkan pada dwifungsi ABRI di era Orde Baru dan bertentangan dengan Pasal 5 TAP MPR No. VII Tahun 2000 yang menegaskan netralitas TNI dalam politik.